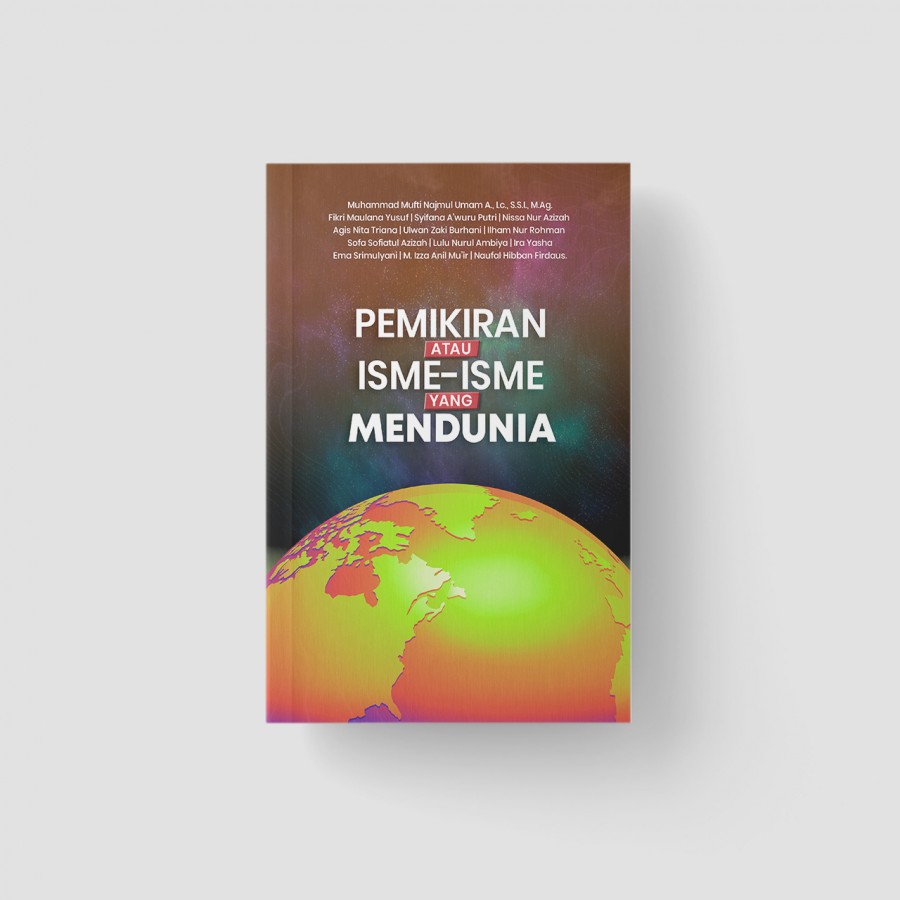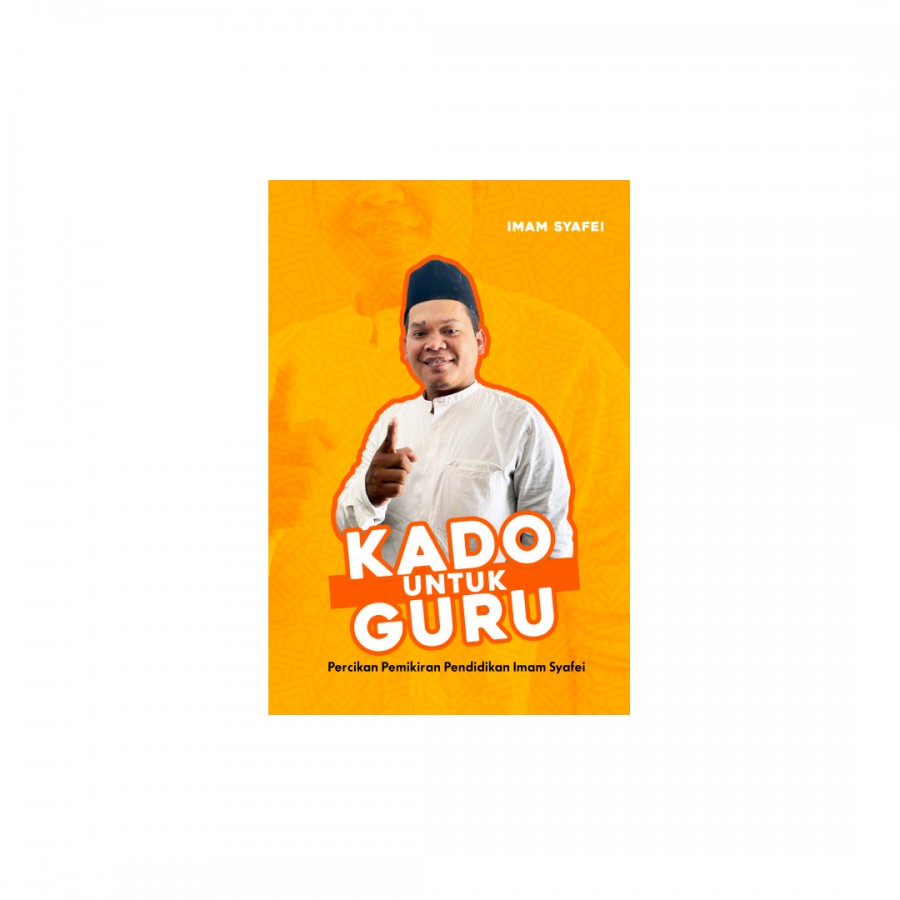Kulemparkan kulit alpaca putih itu tepat di depan wajahnya.
“Ini kulit alpaca milikku yang selalu merasa dirinya adalah milikmu, aku sudah tidak tahan melihat dirinya selalu tertuju ke arah rumahmu. Memang kuakui, rumput halaman rumahmu salah satu yang terbaik di desa ini, tapi kau yang selalu acuh dan melarangnya menikmati setiap helai rumput hijau itu membuatku muak!” Aku sedikit mengatur nafas sebelum melanjutkan perkataanku.
“Pada akhirnya, setelah merenung berhari-hari kuputuskan untuk menyembelihnya dan memberikan semua bagian tubuhnya kepadamu. Kulit putihnya dengan bulu-bulu lembut dan kecil itu bisa kau jadikan selimut atau karpet. Dagingnya di dalam kendi biru ini bisa kau jadikan masakan, jeroannya di kendi merah bisa kau jadikan makanan anjing milikmu, atau terserah kau!” kataku sambil menunjuk tumpukan barang yang kubawa ke halaman rumahnya.
Dia masih membisu seperti biasa, lagaknya terlihat santai. Sikapnya itu sering kali membuatku bertanya-tanya apakah dia seorang manusia? Kurasa tidak ada manusia yang sesantai dirinya. Namun, entah kenapa dia memiliki aura yang misterius sekaligus hangat, ditambah lagi rerumputan berkualitas tinggi di halamannya selalu membuat para alpaca memekik kegirangan.
Sepengetahuanku, sudah tiga alpaca milik pemuda desa sebelah dan di sebelahnya lagi yang datang ke tempatnya. Ketiganya bernasib sama, tertolak mentah-mentah setelah dibiarkan berkeliaran di halamannya dan mencoba rumputnya barang sesuap.
Dia memang seperti itu, alpacaku pun sama. Awalnya dia seakan mengizinkan alpaca milikku untuk menikmati rumput hijau miliknya. Dia buka pagar rumahnya sehingga alpaca putih milikku masuk dengan riang. Dia elus-elus bagian punggungnya lalu dia beri sedikit rumput segar dari halamannya.
Alpaca putih milikku yang memang tak tahu diri semakin tergila-gila. Dari binar matanya aku melihat semacam keriangan yang tiada tara. Sejak saat itu, dia tak mau kugembalakan ke tempat lain. selalu menarik dan memaksa tubuhku untuk pergi ke rumahnya. Namun sejak saat itu pula dengan kejam dia melarangnya mengunyah tanaman kecil itu.
“Apa maksudmu, aku tidak mengerti, setiap perempuan di desa ini memiliki alpaca yang didapatkan dari lelaki, hanya dirimu saja yang tidak punya. Lalu untuk apa kau biarkan alpaca milikku masuk dan menikmati sesuap rumputmu setelah itu kau campakkan?” Aku mulai naik pitam melihat tingkahnya yang masih santai.
“Asal kau tahu, beberapa waktu yang lalu sebelum kau mengundangnya ke halamanmu ini, alpaca ini sudah diterima di halaman perempuan jelita yang rumahnya melewati tiga gunung dari sini. Memang cukup jauh dan memakan waktu cukup lama untuk tiba di sana, tapi melihat perlakuannya terhadap alpaca ini, aku rela mengantarkannya ke sana,” kataku sambil menunjuk ke arah utara.
“Tapi, semua berubah saat alpaca ini mencicipi rumputmu, dia tak ingat lagi dengan wanita itu. Di pikirannya selalu terngiang kelezatan rumputmu. Rasanya tak ada rumput lain yang bisa dia makan, aku tak tahan melihatnya seperti itu.”
Setelah mendengarku berbicara panjang lebar, dia tetap tak bergeming. Ekspresinya masih datar, dia hanya melihat diriku dari teras rumahnya tanpa keinginan untuk beranjak menghampiriku.
Angin gunung bertiup, udara semakin dingin, matahari pun sudah semakin condong ke arah barat. Sinar jingga semakin membuat pemandangan sekitar semakin indah, termasuk juga rumah wanita itu.
“Ya sudah, kutinggalkan bagian-bagian tubuh alpaca ini di sini, terserah mau kau apakan. Mau kau buang, kau kubur, atau kau bakar juga terserah padamu. Tugasku sudah selesai mengurus alpaca ini. Aku bisa membeli alpaca lainnya nanti, entah yang berwarna hitam atau merah kecokelatan, yang jelas aku tidak akan membeli alpaca putih lagi. Alpaca semacam itu biasanya mudah tertipu, buktinya seonggok di depan wajahmu itu.” Aku berkata sambil merapikan barang bawaanku itu agar mudah dia angkat nanti.
“Aku berharap setelah ini kau dapat menemukan alpaca yang benar-benar bisa kau sayangi. Ingat, di desa ini hanya kaulah satu-satunya perempuan yang tidak memiliki alpaca. Sejujurnya aku tidak ingin melihatmu kesepian.” Setelah itu aku berlalu dari rumahnya.
“Terimakasih.” Kudengar suaranya samar sekali, namun tak kujawab. Kuanggap hanya angin lalu, aku terus melanjutkan langkah menjauh dari rumahnya.
Kabut malam sudah mulai turun, sebentar lagi jarak pandang akan semakin terbatas. Setelah sepuluh langkah aku berhenti, entah mengapa ada yang mengganjal dalam hatiku dan memaksa untuk menoleh kembali ke rumahnya. Hatiku bergumul dalam pilihan menoleh atau tidak.
Setelah mengambil beberapa kali nafas panjang aku putuskan untuk menoleh ke belakang. Kulihat dia sedang merapikan tumpukan kulit dan dua guci yang kutinggalkan tadi. Dia bawa satu-persatu secara perlahan.
Saat akan memasukkan barang terakhir, dia menoleh ke arahku. Dia tersenyum getir, matanya berlinang air mata, perlahan sosoknya menghilang, tertutupi kabut yang semakin pekat. Tak terasa, pipiku terasa hangat, dua aliran air kecil membasahinya.
Jember, 10 Juni 2022
Sigit Candra Lesmana, seorang pria kelahiran Jember, 12 Maret 1992. Suka menulis apa pun, mulai dari cerpen, puisi, novel, dan artikel. Sehari-hari sibuk bekerja sebagai penulis lepas. Beberapa cerpennya memenangkan lomba nasional dan diterbitkan di koran. No. WA: 085232959405/ 085695568905. Instagram: @sigitcandral