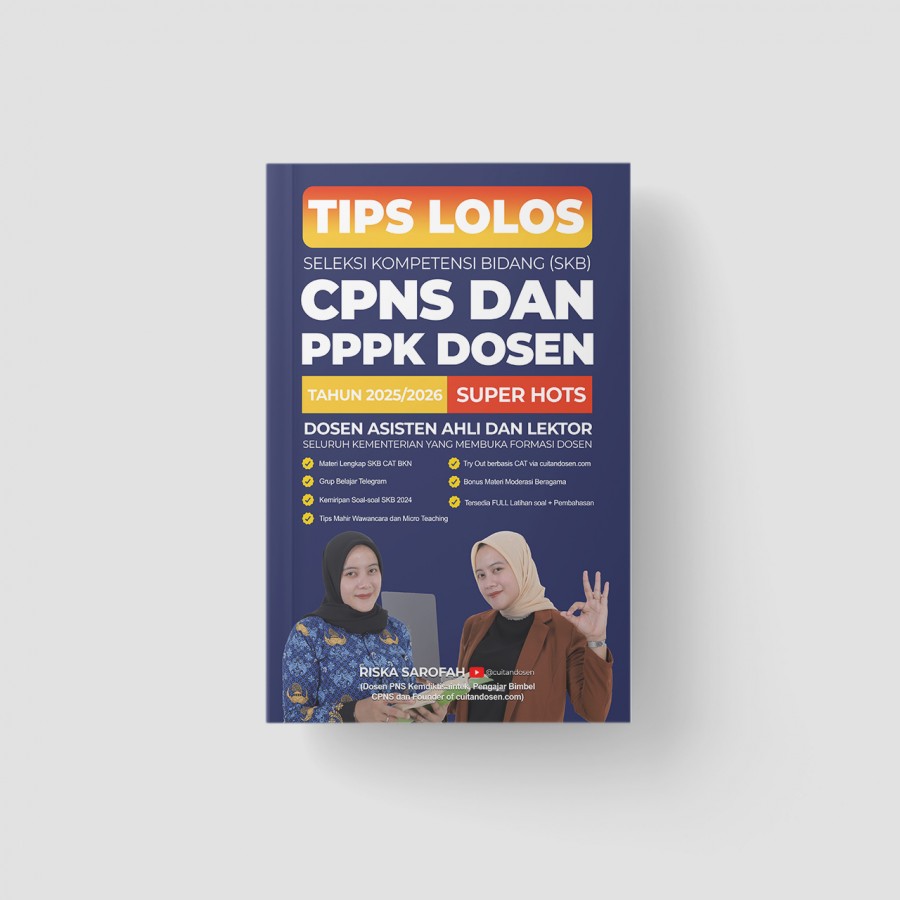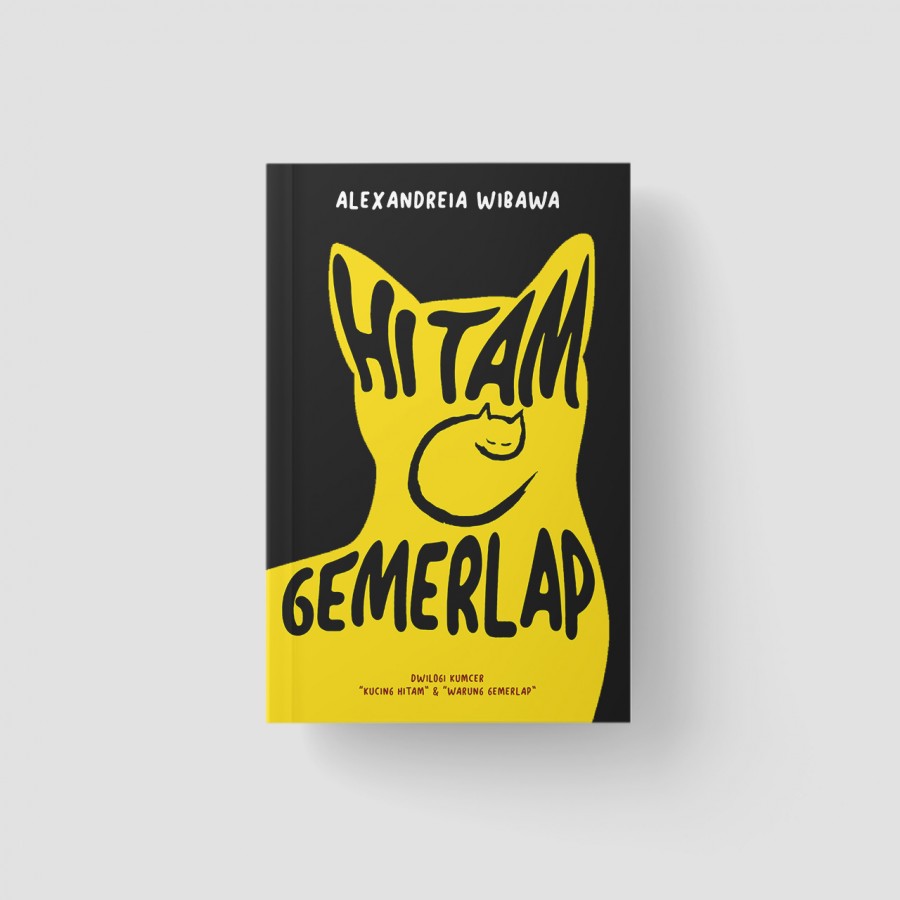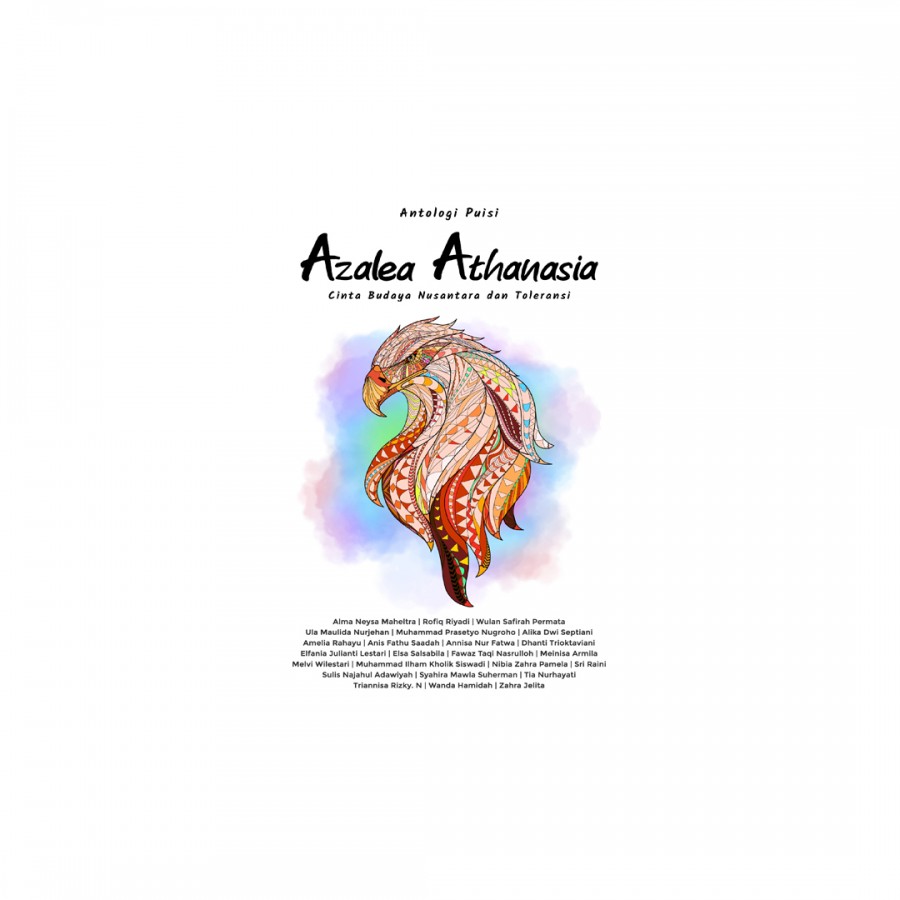Sebagai seorang anak kampung, mamak selalu ingin anaknya itu bisa mengaji. Setelah bisa mengaji, akan didaftarkan menjadi seorang muadzin. Mamak ingin mendengarkan lantunan suara anaknya dari kejauhan tiap hari. Tanpa takut ia pergi ke mana. Amir terus saja didorong oleh mamaknya. Sejak kecil saat-saat pulang sekolah, mamaknya selalu repot membereskan debu di sela-sela ketiak Amir. Mengelap hingga kinclong kembali dan di isi kembali dayanya seperti sebuah telepon genggam, agar Amir bisa berangkat mengaji.
“Setelah pulang sekolah langsung tidur. Nanti waktunya mengaji mamak bangunin.”
Amir tidak menolak. Sebab, hanya ada mamaknya di sini yang menjaga. Bapaknya entah sudah ke mana. Amir selalu menurut, sekonyong-konyong ia ingin bermain dan bernafsu bersama teman-teman. Ia lebih suka melihat mamaknya.
“Mak, kalau Amir sudah besar. Amir boleh bantu-bantu, mamak?”
“Boleh, kok. Asal saat ini belajar yang pintar. Mengaji yang rajin. Jangan lupa untuk jadi muadzin.”
Amir dan mamaknya saling pandang dengan senyuman. Mereka bagai dua sayap yang selalu ingin terbang bersama, melihat keindahan dunia lainnya tanpa takut dipandang rendah orang lain.
Setelah lamanya kesibukan mereka masing-masing. Dua sosok manusia tersebut akhirnya sudah selesai dengan urusannya. Mereka saling bertanya, lalu ke luar. Amir menuju tempat mengajinya. Mamak menjemput rejeki di lapak dagangannya.
“Kamu hati-hati, nak. Yang pinter.”
Mereka berpisah. Amir hilang di makan pepohonan yang lebih tinggi darinya. Mamaknya tetap berdiri melihat anaknya. Setelah sekian detik Amir membuat dirinya terhipnotis. Lalu dijinjingnya kembali bawaannya menuju lapak.
Dalam perjalanannya, mamak agak lama dalam melangkah. Ia perlu bertugas menyeimbangkan bawaannya agar dapat sampai dalam keadaan yang terbaik. Tidak jarang ada saja yang menegurnya, bahkan menggodanya. Saat sapaan itu mendekat kepadanya, ia balas dengan ramah. Sedangkan saat godaan menungguinya, ia bahkan tidak hiraukan lagi. Ia takut, orang lebih seenaknya jika ia ramah. Maka ia pergi saja tanpa perlu menghiraukannya.
Lapak sederhana berbentuk persegi panjang itu menetap setia menunggui dirinya. Beratap seng yang saat siang hari panasnya bisa memusingkan diri. Saat hujan, bunyinya seperti tembakan yang dilontarkan berkali-kali dan itu sangat dingin. Setiap sisi lapaknya senada berwarna putih. Di depannya bertuliskan, kue tradisional mamak Amir.
Amir sudah sampai di tempat mengajinya. Secara perlahan, Amir masih malu-malu untuk masuk. Ia baru pindah mengaji di sana. Sebelumnya berada di desa sebelah. Walaupun di desa sebelah, rumahnya lebih dekat ke sana. Karena rumah Amir persis sekali diperbatasan.
“Assalamualaikum, Ustadz.”
Ustadznya menjawab. Ia disuruh masuk. Amir menyalimi guru mengajinya itu. Lalu memberikan buku tulis untuk ditulis ustadznya. Lalu membuka Al-Quran yang akan dibacanya hari ini. Selang beberapa waktu, ustadz memanggilnya. Memberikan tugas untuk hari ini.
Amir ke belakang, mencari tempat yang nyaman. Teman-teman lainnya masih memperhatikan mereka. Senyap-senyap, mereka terdengar berbicara soal Amir. Sepertinya mereka penasaran dengan bocah baru itu.
“Kamu sangat pendiam. Mau berteman dengan kami?”
“Mau.” Amir menjawabnya.
“Sini saja kita bareng-bareng.”
“Boleh.”
Amir menuju ke mereka. Melanjutkan tugasnya hingga selesai. Dirinya masih malu-malu untuk melakukan aktifitas. Ia seperti tanaman, hidup namun pasif. Ia sangat yakin, bahwa hari ini dirinya belum terbiasa dengan teman-teman sebayanya. Mungkin nanti. Teman-temannya terus tertawa terbahak-bahak.
“Kalian, sini!” ustadz memanggil mereka.
Hanya mereka yang berkumpul jauh di pojok. Mereka semua datang dengan bawaan bermacam-macam, Al-Quran, Juz ama, atau Iqro. Mereka sama seperti barisan yang mengantri jatah makanan di rutan.
Sederet yang tadinya sebuah barisan yang panjang, secara perlahan habis di makan waktu. Sekarang menjadi setengah lingkaran yang pusatnya adalah ustadz. Saat-saat menunggu jam pulang, mereka selalu disuguhkan cerita-cerita yang dapat diambil hikmahnya. Ustadznya memang tegas, tapi saat bercerita, para muridnya selalu hanyut dalam cipratan liur yang diramu menjadi cerita dengan drama.
Ustadz secara perlahan membangun suasana cerita. Para murid mulai memasang skrup yang kencang pada kedua telinganya. Mereka buka lebar-lebar. Ustadz memerhatikan semua murid-muridnya sebelum ia melanjutkan cerita.
“Kalian kenal Nabi Ibrahim?” Ustadz menyampaikan.
“Kenal!” semua anak-anak berteriak.
“Siapa?”
“Nabi.”
Mereka saling tersenyum gembira. Ustadz menunjuk beberapa lagi muridnya untuk duduk merapat. Ada yang digeser. Satu dan dua orang dipindahkan menjauh, agar semuanya khusyuk mendengarkan.
“Pada zaman dahulu, hiduplah seorang Nabi Ibrahim. Seorang nabi yang sangat ingin memiliki seorang anak. Ia pun meminta kepada Allah SWT dan berdoa.”
Cerita itu berlanjut dengan hikmat. Ustadz tidak sulit membawa mereka ke dalam dunia yang diceritakan. Lehernya, yang tidak pernah berhenti bergerak, terus diperhatikan muridnya. Tangan yang meliuk-liuk. Bibir yang terus seperti ombak. Mereka dengarkan sangat menyenangkan, hingga sudah lewat lima belas menit.
“Pak Ustadz, pulang!” seorang anak murid berteriak. Berikutnya, semua berebut melihat jam yang ada di sana. Mereka bergegas berlari, mengambil tas. Tanpa menghimbau perkataan Ustadz. Seluruh pojok ruangan ini seperti sedang berebut perhiasan yang berserakan. Setiap orang tidak mau ketinggalan dan kehabisan.
“Kumpul lagi.” Segera Ustadz mengarahkan mereka untuk berkumpul mendekat. Berulang kali ustadz berbicara. Dalam hitungan detik, semuanya sudah rapih berbaris menunggu doa untuk pulang.
Amir duduk dengan rapih. Barang-barangnya sudah dicek, dan dibereskan kembali. Ia hanya celingak-celinguk membayangkan sekitar. Tiba-tiba salah satu temannya berteriak dan memimpin doa.
Amir menunggu giliran untuk salim. Ia tidak suka berhimpit-himpitan. Ia lebih suka menunggu habis, lalu ia salim. Tubuh kecilnya hanya membuat dirinya kesusahan jika berdekat-dekatan. Bukannya nanti ia akan bisa dahulu, mungkin saja ia akan terlempar dan terhempas.
Sudah waktunya ia maju dan salim. Pamit dari tempat mengajinya dan lalu pulang ke rumah. Selama perjalanan, Amir menikmati menuju rumah, ia ingin sekali bercerita segera apa yang ia dapatkan. Mengenai cerita nabi Ibrahim yang mengorbankan anaknya demi perintah Allah SWT.
Kepalanya menoleh ke kanan dan kiri. Melihat sekitar. Cahaya sore malu-malu pergi. Udara tertiup cukup bagi Amir. Di ujung jalan, ia melihat keramaian. Tidak satu dua orang, namun puluhan. Berwarna-warni pakaian yang digunakan. Setiap orang berteriak saling sahut. Diantara kerumunan warna, didominasi oleh warna coklat. Polisi.
Amir mempercepat langkahnya. Lama-kelamaan ia berlari. Menuju keramaian tersebut. Ia mendengar, “Angkat-angkat.” Lalu ia masuk lebih jauh, “Ada berapa korbannya?” Ia mencari-cari, lalu dirinya ditarik dari belakang.
“Jangan mendekat. Anak kecil mundur.” Seorang polisi dengan tatapan tajam membuat dirinya diam.
Suara tangisan terdengar mengelilingi tempat ini. Amir melihat-lihat dengan cepat. Badan kecilnya saat ini menguntungkan. Ia bisa meliuk-liuk bagai ular. Menjalar dari satu pohon ke pohon lainnya, yang saat ini menjelma menjadi badan.
“Anak-anak saya… Tolong… Semuanya…” seorang ibu dengan badan yang lunglai, namun suaranya terus mengeluarkan rengekan.
“Awalnya bagaimana, Bu?” bapak berseragam coklat yang tadi menarik Amir menanyakannya. Ia berbeda memperlakukan Amir dengan ibu tersebut.
Wanita yang mengaku ibu, terus saja bungkam tidak bisa bicara, atau tidak ingin bicara. Amir terus saja seperti ular yang masuk mencari celah. Ibu tersebut dikelilingi oleh beberapa orang, ditanyai secara perlahan.
Amir melihatnya. Satu, seorang anak lelaki remaja, sekitar umur lima belas tahun. Lehernya menganga lebar. Seperti tercabik-cabik. Di lengan tangannya, darah mengalir segar. Kedua, seorang wanita berumur sepuluh tahun. Wajahnya manis, lehernya hampir putus. Ketiga dan keempat, mereka memiliki luka yang sama, bajunya sobek-sobek dengan luka sayatan.
Amir yang tercengang dengan segera ia mundur. kepalanya pusing, ingin rasanya muntah.
“Anak saya, tolong…” Ibu itu meraung-raung seperti kesetanan.
Amir terbayang dengan cerita ustadz tadi. Seorang nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya lalu berubah menjadi domba.
Dari dalam rumah, terdengar gaduh suara. Seorang laki-laki dewasa, “Saya yang membunuh. Itu anak saya. Saya bermimpi, saya sudah izin ke anak-anak saya.”
Semua orang berhamburan menjauh. Beberapa laki-laki dewasa maju. Salah satunya bapak polisi. Ia mengeluarkan pistol. Menyuruh pembunuh mengangkat tangan. Ia menurut.
“Maju.” Polisi itu memaksa.
Pelaku maju secara perlahan. Ada dua orang laki-laki yang siap menangkap tangannya. Pelaku melihat dua orang itu. dengan cepat tangan yang ke atas, ia belakangi dan mengambil dua pisau di belakang dan mengarahkan ke badan mereka.
Dua laki-laki terluka. Polisi langsung mengeluarkan tembakan ke salah satu kaki pelaku. Semua orang berhamburan tanpa arah. Amir membayangkan seperti anak-anak yang pulang mengaji. Siapapun sibuk mementingkan dirinya, Amir terpanah diam menonton.
Beberapa orang menyenggolnya. Namun Amir tetap bisa menghindarinya. Seorang polisi dan pelaku beradu ketangkasan membuat dirinya terhipnotis. Tidak ada yang dapat mengganggunya.
“Amir… Amir…” Teriakan itu datang dari kejauhan. Amir tetap saja tidak mendengar. Dengan cepat, suara dan wujudnya tepat di belakang Amir. Tangan itu menarik Amir dengan kuat. Badan kecilnya saat ini seperti tidak memiliki beban sama sekali. Amir menengok ke belakang. Mamaknya.
“Mundur! kamu tidak lihat sedang bahaya.”
“Mamak ngapain ke sini?”
“Jangan banyak tanya.”
Amir ditariknya mundur menjauh. Mata Amir masih menuju mereka. Beberapa detik berikutnya pelaku terjatuh. Badannya yang mulai lunglai, lemas. Pelaku melempar salah satu pisau yang ia genggam. Pisau tersebut tepat melesat di leher polisi. Seragam coklatnya subur dengan darah.
Amir melihat kehebatan pelaku melempar pisau. Badannya yang ditarik mamak, terus saja membuat dirinya menjauh. Pelaku mencari-cari, kepalanya terus mencari korban. Entah menuju siapa. Tidak lama ia terperanjat. Ia menemukan istrinya yang sedang pingsan.
Pelaku memaksa dirinya bangkit. Ia terus maju secara perlahan. Dirinya terus memecah sisa energi yang tersisa. Membakar perapian cemburu yang ada di balik hatinya. Memutar ulang ingatan memori cemburu di kepalanya. Lambat laun, pelaku sudah di samping istrinya yang pingsan.
“Bayar pengkhianatan ini dengan nyawamu.” Pelaku berteriak dengan kencang. Lalu ia menancapkan pisau di hati istrinya. Darah menyiprat. Pelaku menariknya kembali, menusuknya berkali-kali. Tangisan mengucur tanpa henti. Kutukan demi kutukan terus diucapkan.
“Sudah!” seorang laki-laki maju.
“Diam.” Pelaku berteriak.
Pelaku berancang-ancang, lalu ia menusuk dirinya tepat di bagian ia akan mati segera. Dalam perjumpaan dengan maut, sang pelaku terus saja mengulang-ngulang, “jangan biarkan saya hidup. Saya ingin mati. Ingin bergabung bersama keluarga saya di surga. Tanpa perlu takut istri saya mendua.”
Mereka semua hening. Mengamati dari balik pohon, dinding, dan lain-lain. Suara pelaku secara cepat menurun dan menghilang. Tidak ada keributan.
Alfiansyah Bayu Wardhana, biasa dipanggil Alfian. Lulusan S1 Sastra Indonesia, Universitas Pamulang. Kesibukannya saat ini membuat konten sastra, sejarah, dan budaya di akun media sosial pribadinya dan mengelola akun Mendengarkan Ceritamu. Berkomunitas di Gerakan Berbagi, Adakopi Original, Semaan Puisi, dan Dewan Kesenian Kelurahan Serua. Karya yang sudah dipublikasi, yaitu:
(1) Cerpen, Bulan Biarlah Aku Bermimpikan Bayangan terbit di Literasi Kalbar (2024); (2) Cerpen, Sepi Sesudah Ramai terbit di Riau Sastra (2024) dan LPM Al-Mizan (2024); (3) Cerpen, Pintu Itu Diketuk terbit di Jurnal Post (2024). (4) Cerpen, Ramadan Tiba Di Jakarta di Magrib.id (2024).
IG : Hoyalfi
Tiktok : Hoyalfi