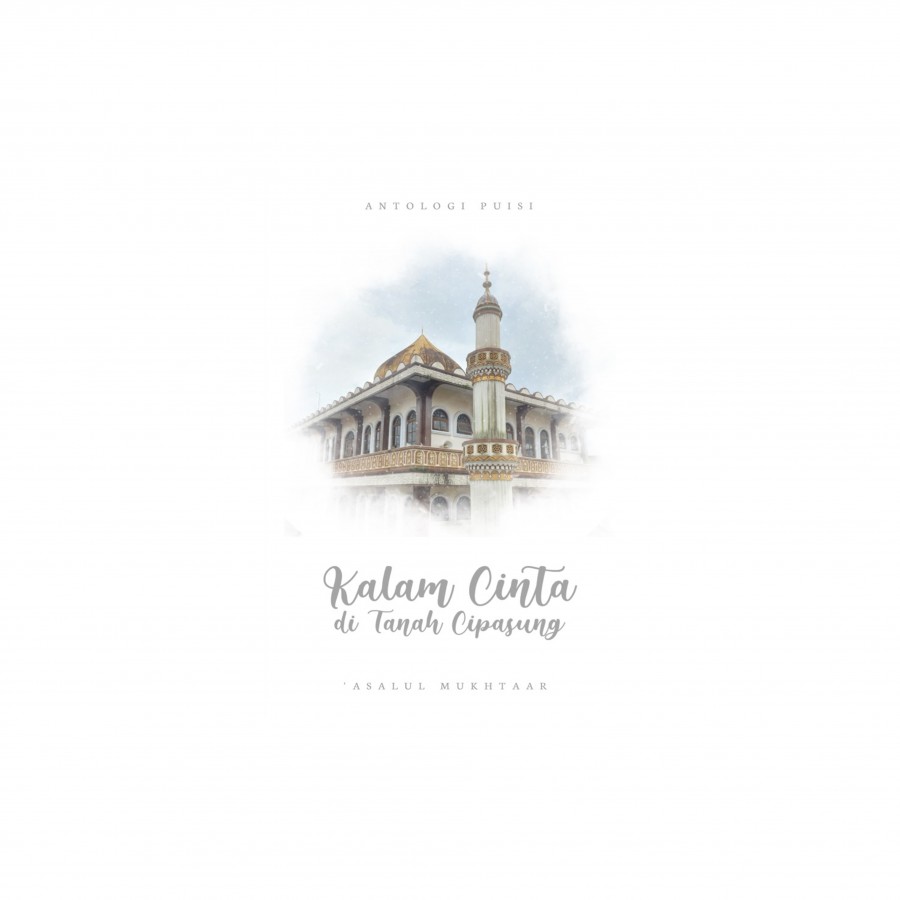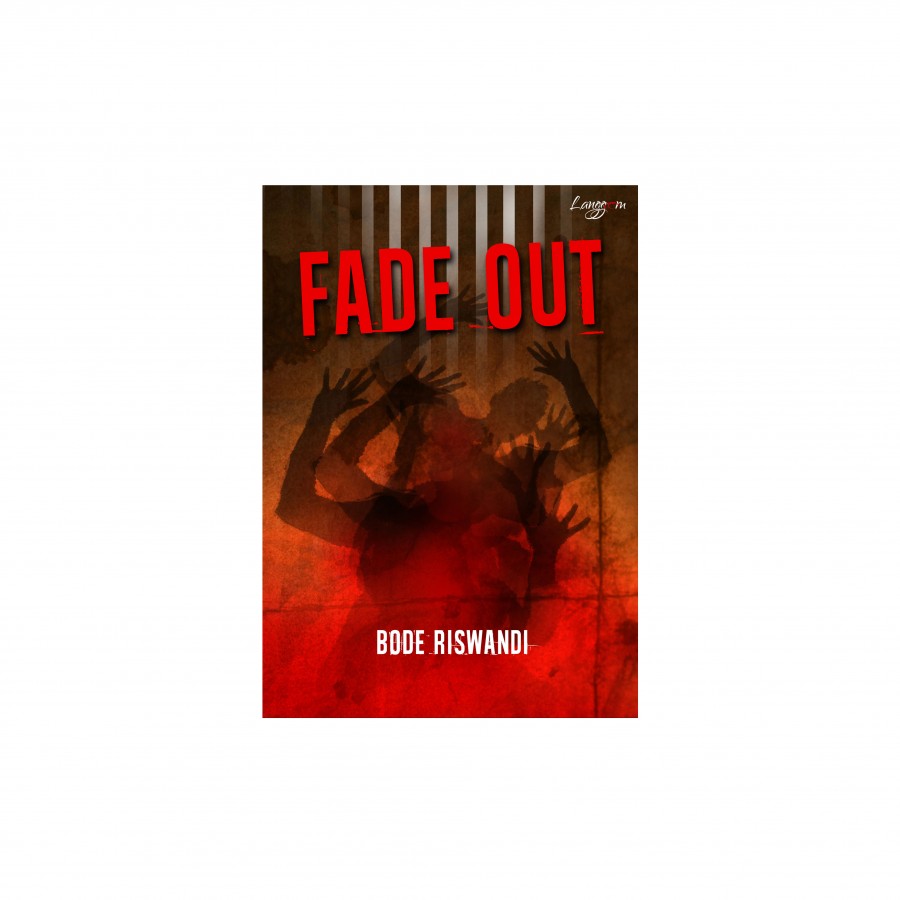Sopir yang sering ugal-ugalan itu masih duduk dengan tenang, sambil bersiul menunggu penumpang yang masuk. Begitu bus melaju pelan, ia memusatkan perhatiannya. Waktu suasana hening, ia mulai bertingkah, menggunakan kekuatan penuh, mobil melaju kencang, membuat para penumpang bergoyang-goyang gemetaran. Setelah suasana kembali tenang, Yurice memberiku sebuah tas kecil. Apakah isinya sama seperti dulu, pikirku. Kubuka perlahan memastikan, isinya sama, seperti beberapa hari yang lalu, uang yang lumayan tabal. Aku tahu tas ini pemberian siapa? Siapa lagi kalau bukan abang iparnya Yurice yang bernama Faruk. Aku pernah berniat membuatnya babak belur, setelah ia memberiku uang itu. Aku kira ia bermaksud menyogokku dengan uang yang ada dalam tas itu, agar aku meninggalkan Yurice. Benar kata Yurice, aku orangnya emosian, ialah yang bisa melunakkan hatiku yang keras.
“Abangku sudah cerita tentang pertemuan kalian. Waktu itu kau marah-marah tidak menerima uang ini, ketika Bang Faruk bermohon kau meninggalkan aku. Uang itu tidak bermaksud menyogokmu, tapi bentuk permohonan, kau terima atau tidak, dia sudah berniat tetap mengasih uang itu untukmu. Dia kasihan melihatku, yang terus dimarahi ayah, karena ia tahu masih menjalin hubungan denganmu. Kau yang merasa disogok, tidak ingin cintamu yang berharga ditukar dengan uang seberapa pun jumlahnya. Kau tidak ingin jejakku dihapus dari hatimu. Kau sosok pecinta yang baik, tidak percuma seluruh hatiku berlabuh di hatimu. Kau yang menolak uang itu, membuktikan kau menganggapku berarti dalam hidupmu, dan aku suka itu. Aku begitu menghargai caramu. Karena itu tanpa ada keraguan sedikit pun, aku tanggalkan rasa takutku.” Kemudian bibirnya mendekat, seakan ingin menggigit telingaku. “Bahkan pakaianku pun sudah kutanggalkan untukmu seorang,” katanya dengan suara parau. Sedikit ia bergeser lagi. Kepalanya tertunduk lesu, masih ada yang ingin ia ucapkan.
“Aku melangkah dengan jantung berdegup kencang memilih pergi bersamamu. Aku punya firasat, aku dan kau yang bertanggung jawab, adalah pasangan yang sempurna. Kau yang perasa memperlakukanku seperti yang kuinginkan. Aku tidak meminta apa pun darimu, kecuali meminta cintamu yang tulus itu,” Yurice mengatakan isi hatinya yang meluap-luap, membuatku megap. Aku disanjung oleh kekasih sendiri, dan aku senang. Telingaku melebar, pikiranku yang tadinya melayang-layang kini mulai terarah, fokus mengingat sesuatu.
“Uang ini tidak dikasih cuma-cuma. Aku pinjam kok, suatu saat nanti kau dan aku wajib melunasinya meskipun dicicil, begitu pesan dari pemilik.” Gadis cantik itu pintar menggodaku. Memang aku sangat membutuhkan uang itu. Apalagi saat-saat genting seperti ini. Tapi aku tidak mau dikasih cuma-cuma. Aku merasa masih kuat, tidak mau dikasihani. Jika aku tidak berhasil di suatu tempat, masih banyak tempat lain untuk berlayar, yang bisa menampungku untuk bekerja keras, sampai aku sukses. Aku terima uang pinjaman dengan senang hati.
“Terima kasih Bang Faruk. Maaf atas kesalahanku,” lirihku di dalam hati, memandang ke pinggir jalan, ranting pepohonan meliuk-liuk dipermainkan angin. Aku merasa menyesal. Aku benar-benar tidak bisa mengontrol emosi pada saat pertemuan kami itu. Jika sampai terjadi pertarungan antara aku dan Faruk, aku belum tentu menang melawannya yang berbadan gendut.
“Ipung,” seseorang membuatku terkejut, ia duduk tak jauh dariku dengan seorang perempuan berjilbab. Ia memegang pundakku, dan menepuk-nepuknya dalam bus itu, lalu ia meletakan tas kecil.
“Kau Ipungkan?” Aku yang bingung belum menjawab, ia menggoyang-goyang tubuhku, yakin dengan dugaannya, dan seakan ia ingin mengajakku mengobrol panjang. Aku tatap wajahnya lekat-lekat. Aku berpkir sebentar, lupa-lupa ingat, di mana ya aku kenal lelaki ini. Aku pusatkan perhatian, menggunakan pemikiran penuh, mengingat-ingat masa lalu. Jangan-jangan dia salah orang, ah tidak mungkin, dia sendiri langsung fasih menyebut namaku.
“Aku Genta, temanmu waktu di pesantren. Dari tadi aku perhatikan kamu, tapi kamu tidak menegurku,” lelaki itu menyebut namanya sebelum aku tanya.
Memoriku berputar pada masa lalu, ketika masih mondok di pesantren. Sekarang aku baru ingat, setelah menatap wajahnya lekat-lekat, dan kuperhatikan baik-baik. Benar dia Genta, murid nakal waktu kami duduk di bangku kelas tiga dulu. Pernah dua minggu dia tak masuk kelas. Wajar kalau aku tak mengenalnya tadi, banyak perubahan pada dirinya. Penampilannya begitu rapi. Dulu badannya kurus kerempeng, sekarang berisi. Pipinya yang cekung waktu di pesantren, sekarang terlihat sudah menonjol. Perutnya yang dulu kempes, sekarang sudah berlebihan maju ke depan. Wajahnya yang dulu ditempeli jerawat keras seperti batu, sekarang bersih dan licin, terlihat menawan. Yang membuatku benar-benar tidak mengenalinya, kepalanya yang dulu sering botak karena dapat hukuman, kini rambutnya panjang dan gondrong.
“Kau tidak berubah, masih seperti dulu,” tuturnya mendahuluiku.
“Dari mana kau tahu, mungkin kamu yang tidak berubah, masih nakal seperti dulu,” aku membalasnya, sambil mengoceh, dan kami pun tertawa bersama ketika bus terus melaju.
“Maksudku, wajahmu Ipung yang tidak berubah itu, kalau kelakuanmu, mana aku tahu, apa kau sudah menikah?” Aku geleng kepala menjawab pertanyaannya.
“Kamu sudah menikah?” Giliranku yang bertanya.
“Sudah, tapi Tuhan belum memberi keturunan,” jawabnya memandang perempuan yang mungkin sudah tertidur.
“Memangnya kau menikah sudah berapa lama?”
“Enam bulan masih.”
“Gila, dengan menikah enam bulan, kau berharap dapat keturunan, apa kata orang-orang nanti.”
“Aku tidak pernah mendengarkan apa kata orang, aku hanya mengikuti kata hatiku,” ia dan aku sama-sama tertawa, aku pun tahu ia cuma bercanda. Dan aku tak ingin menanyakannya lagi, tahun berapa sebenarnya ia menikah.
“Sekarang kamu tinggal di mana?”
“Di Jogja, sekarang lagi menyelesaikan S3. Aku dapat beasiswa kawan,” dia promosikan dirinya dengan bangga, sambil menyebut nama universitasnya yang terkenal. Di dunia kampus dan perkuliahan, dia jauh lebih beruntung daripada diriku yang bernasib sial. Aku ini seperti kayu lapuk yang tak laku dijual. Aku jadi malu berhadapan dengan calon doktor itu. Mungkin tak lama lagi akan dapat gelar Prof. Aku siap mendoakan temanku itu.
“Perkenalkan ini Yurice. Tak lama lagi kami akan menikah,” aku melarikan persoalan, berbicara tentang jodoh. Aku takut, bercampur malu kalau ditanya tentang pekerjaan, apalagi tentang kuliah. S1 saja aku tidak kelar, aku kuliah terkatung-katung, akhirnya tamat riwayatnya. Dalam pertemuan ini, aku hanya menceritakan semua kejadian buruk yang menimpa antara aku dan Yurice, kekasih hatiku itu.
“Dari awal aku mengenal gadis ini, orang tuanya tidak senang melihatku. Pertama kali aku datang ke rumahnya ibunya langsung mengusirku setelah tahu kami berbeda keyakinan.” Mendengar penjelasanku yang tangkas dan tegas, lama sekali Genta menutup mulut, aku tahu ia merasa kaget, menganggap ada yang tidak beres dengan diriku, tapi ia tak mau berkomentar. Dia hanya mengangguk-anggukkan kepala. Mungkin dia yakin takkan bisa turut membantuku dalam masalahku.
“Aku berharap, dalam waktu cepat ini luluh hati keluarga pasanganmu untuk menerima kamu,” baru ia berkoar lagi, setelah beberapa detik terdiam. Aku menelan ludah merenungi kata-katanya, kemudian memalingkan wajah menatap sesaat ke luar. Aku cemburu pada mereka yang direstui.
Depri Ajopan, S.S. Lulusan Pesantren Musthafawiah Purba-Baru, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Menyelesaikan S-1 Prodi Sastra Indonesia di UNP. Sudah menulis beberapa karya fiksi dan sudah diterbitkan. Cerpennya pernah dimuat di beberapa media cetak dan online seperti, Singgalang, Riau Pos, Jawa Pos Radar Banyuwangi, Koran Merapi, Pontianak Post, Kedaulatan Rakyat, Suara Merdeka, Sinar Indonesia Baru, Jawa Pos Radar Lawu, Lensasastra.id, Langgampustaka.com, tatkala.co, Kurungbuka.com, Labrak.co, LP Maarif NU Jateng, Harian Bhirawa, ayobandung.com, Mbludus.com, g-news.id, Literasi Kalbar.com, Radar Madura.id, marewai.com dll. Penulis anggota Komunitas Suku Seni Riau mengambil bidang sastra. Sekarang mengajar di Pesantren Basma Darul Ilmi Wassaadah Kepenuhan Barat Mulya Rokan Hulu-Riau, sebagai guru Bahasa Indonesia.