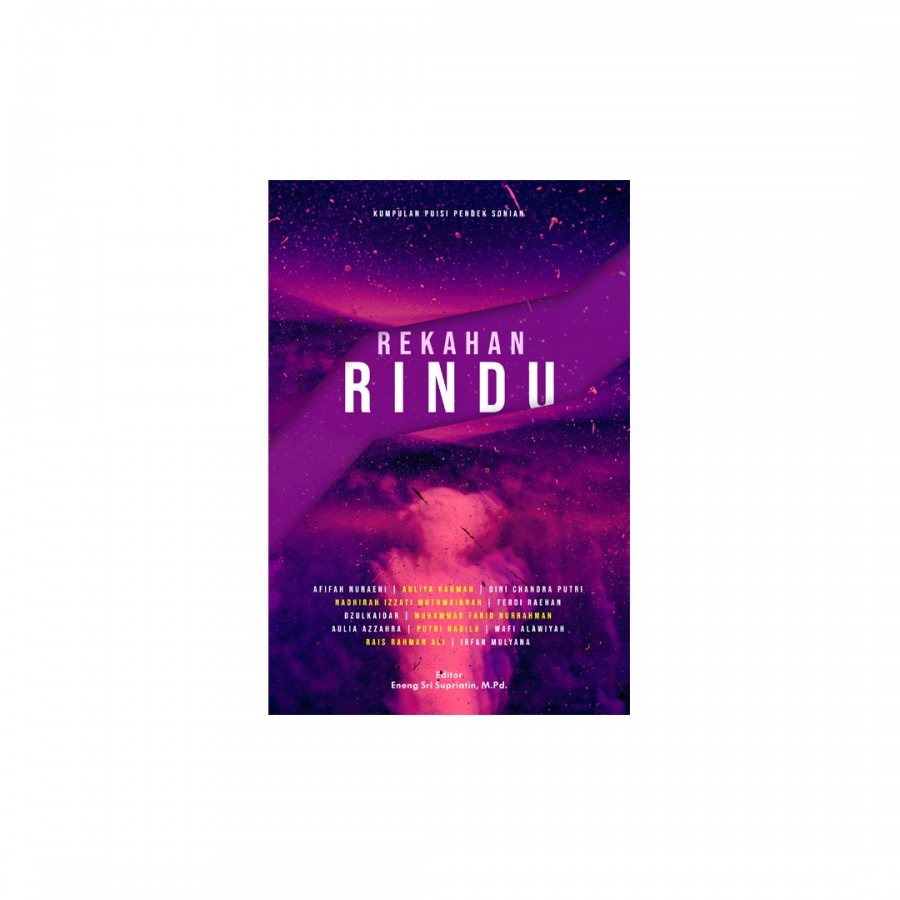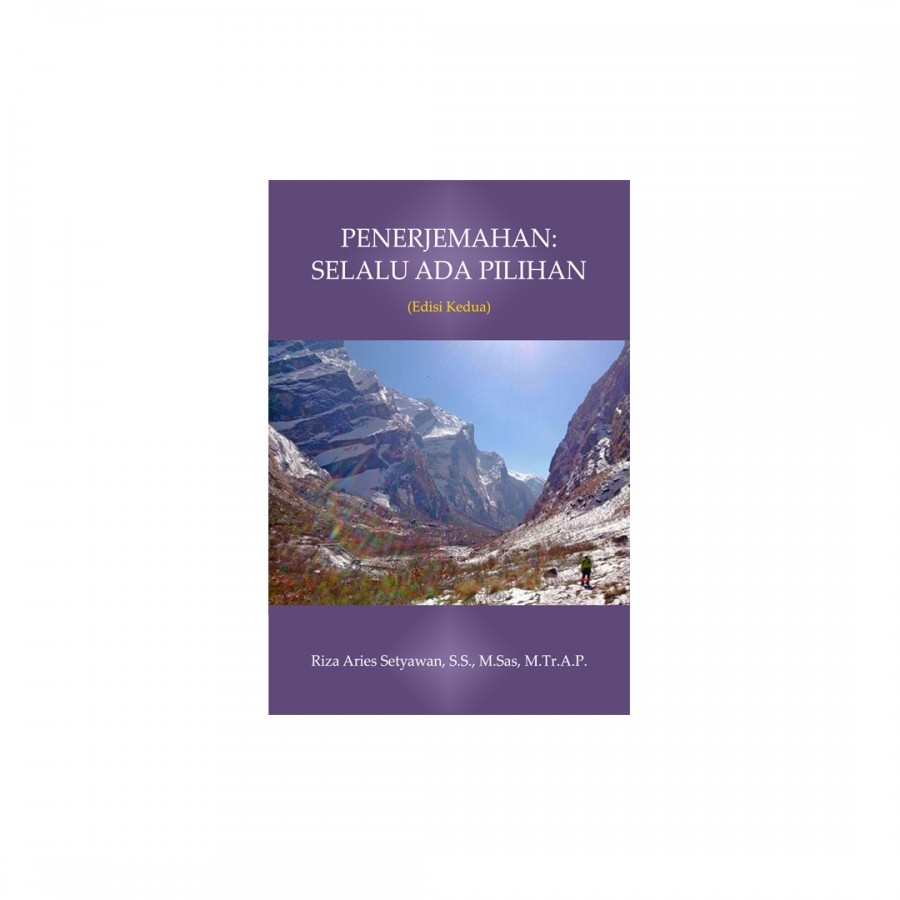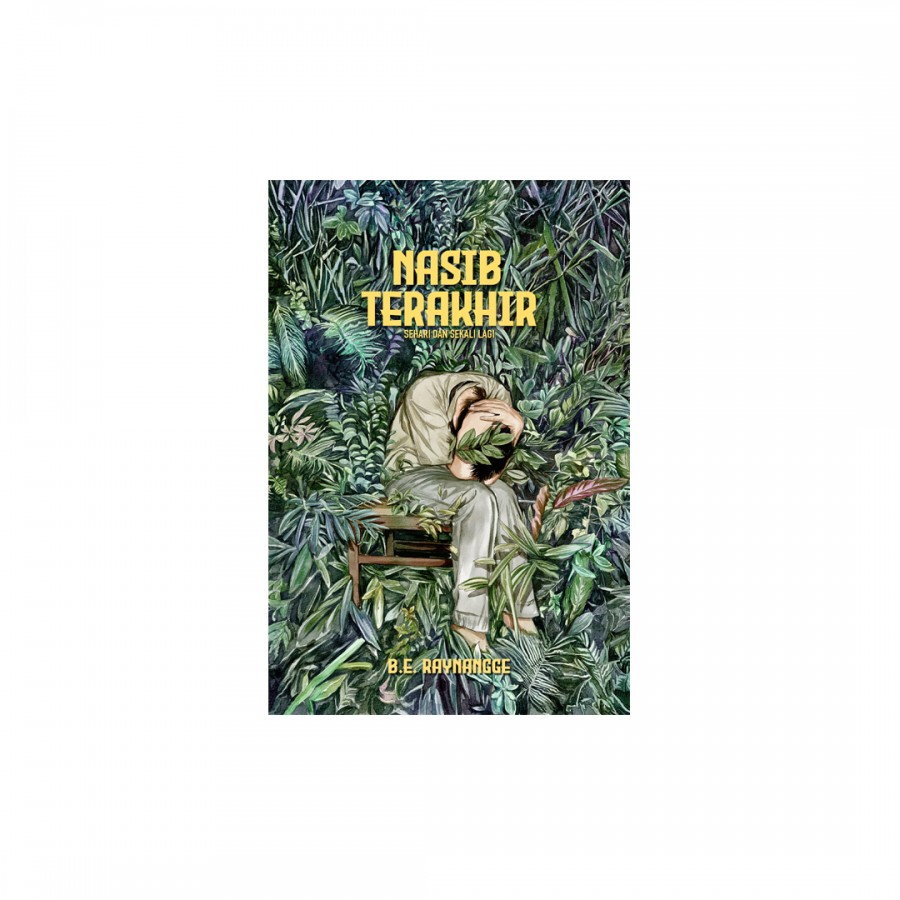Malam ketika Bapak tersungkur tak sadarkan diri di beranda, seorang tabib dengan jubah serba putih itu mestinya mampu menunda kematian bila ambulans tiba beberapa menit sebelumnya. Namun, di antara begitu banyak peristiwa, hanya sisa jarak menuju rumah sakitlah kurasakan waktu kian melambat dan memanjang, tak peduli selengang dan secepat apa pun mobil melaju seiring bising sirene meraung-raung menembus dengung hujan.
Maka inilah yang terjadi: Sang Maut memapasi kami di tengah perjalanan dan sesegera menghabisi nyawa Bapak dengan satu ayunan sabitnya; membuat lelaki itu berkelejat seketika, tak sanggup lagi menyangkal ajal sendiri. Aku tak menangis sebagaimana ia tak ingin ditangisi, meski pada detik penghabisannya itu ada terasa sebuah godam menghantam dada, membekaskan lekuk lubang di mana pilu kedukaan kelak menggenang.
Demikianlah, esoknya kuserahkan Bapak kepada haribaan alam. Di halaman belakang rumah, sebagaimana pintanya. Penguburan itu berlangsung khidmat dan sendu sebab memang seharusnya begitu. Dan mau tak mau, kuingkari juga janji untuk tak menangis saat kubaringkan ia di samping Ibu yang tabah menunggu, sebagaimana Bapak menanti saat-saat untuk kembali bersama setelah meniti segala rindu.
Walau, dengan seorang paman aku sempat berbantah tentang kamar terakhir mereka. Aku paham. Sejak tiga tahun silam, sekeliling hanya tinggal puing sebab para tetangga telah ingkah terusir dipaksa menyerahkan tanah mereka. Itulah yang ia resahkan; bahwa suatu saat aku pun kan terpaksa minggat dan terpaksa pula mengungsikan tubuh orang tuaku ke lain tempat. “Jangan kubur ia di sana, dan sekalianlah pindahkan adikku,” titahnya. Namun aku tak setuju. Dosa apakah yang kelak harus kutanggung bila tak memenuhi mimpinya untuk dimakamkan di tanah sendiri?
Nyaris seperempat abad setelah Ibu mengantarku nyelinap ke bumi melalui sebuah lorong di tubuhnya, Bapak cuma habiskan sisa usia semata untuk mencinta kijing pualam yang memendam Ibu, seakan-akan perempuan itu masih bisa diajak bicara bila ia mengadu rindu, tak peduli bahwa kini istrinya hanyalah onggokan tulang-belulang. Selalu begitu. Ya, dulu pernah kusarankan agar ia lupakan Ibu dan kawin dengan seseorang yang lain. Toh bagaimanapun Ibu bagiku hanyalah hantu asing yang tak benar-benar kukenal wujudnya kecuali dalam pigura dan cerita-cerita. Akan tetapi, seperti mudah diterka, tetap saja Bapak kukuh untuk setia. “Dia tak akan pernah selesai kucinta,” katanya. Maka, seperti ribuan sore yang silam, masih kan kudapati ia duduk bergeming menyeka kijing Ibu sembari sesekali berucap sesuatu atau sesekali menangis sedu.
Memang aku pernah jengah menyaksikan kesetiaan konyol itu. Dan sebelum seorang paman bertitah, telah jauh hari kunyatakan usul untuk mengungsikan tubuh Ibu ke sebuah tempat nun jauh, di bawah lembah atau di punggung gunung, paling tidak biar Bapak tak akan saban waktu menungguinya seolah setan dan siluman diam-diam saling membahu untuk menculik jerangkong Ibu. Ia malah ngamuk marah-marah. “Kelahiranmu renggut perempuan itu dariku. Tak akan kubiarkan lagi siapa pun memisahkan kami.” Aku mengerti. Sejak itu kutanggung juga kesetiaan Bapak. Kutemani ia dalam badai kesepian yang tak henti-henti memilinnya.
***
Kali itu Bapak dan aku duduk di beranda tanpa saling bicara, tanpa juga bertanya mengapa angin tak kedengaran. Sesekali, kulihat ia hanya memejamkan mata cukup lama, entah membayangkan apa. Mungkin ia cuma terkenang kepada Ibu, atau mungkin juga tengah merenungkan kematiannya sendiri. Sebab, setelah milih berhenti sebagai janitor di satu gedung kesenian, ia sering mengaduh nyeri di dada. “Seperti ditikam sabit Sang Maut,” keluhnya, suatu ketika. Meski begitu, selalu saja ia menolak saban kuajak ke rumah sakit dan membual bahwa tak ada dokter lulusan universitas mana pun yang sanggup pulihkan kesakitannya.
Namun, nyatanya yang ia renungkan tak lebih dari sekadar rumah ini. Sebab tiga tahun lalu segerombolan orang datang ke balai warga, mengajak kami berkhayal tentang sebuah apartemen nan megah, yang berarti kami harus ingkah menyerahkan segala kenangan yang dipunya. Memang, dengan tandas, saat itu juga Bapak menolak untuk beranjak, meski hari-hari setelahnya seribu teror menggedor-gedor pintu dan membuat kami mesti tidur berselimut rasa takut. Begitu pun kalau malam kian ranum, selalu saja aku terbangun oleh tangis dan jeritan.
Maka, sesaat setelah membuka mata, berkatalah ia bahwa dirinya merisaukan kediaman kami selepas tiba ajalnya nanti. “Aku tak takut bila esok atau lusa atau kapan pun juga akan mati. Toh kau pun sudah bisa mengurus dirimu sendiri. Yang kuresahkan semata hanyalah bahwa di kemudian waktu seluruh kenangan keluarga kita yang terpatri di sini, di sekeliling dindingnya, akan lenyap seiring kematianku.” Demikianlah ia kemudian memintaku bersumpah untuk menjaga peninggalannya, dan aku berusaha meyakinkan agar ia tak perlu meresah.
“Di sinilah, di samping istriku, kelak aku mesti dikuburkan,” pinta Bapak tak berselang lama. Dengan lugu aku beria saja. Toh ini tanahnya sendiri dan akhirnya pun tak ada hal lain lagi yang ia harapkan ketimbang rebah bersisian dengan Ibu sebagai sepasang jenazah yang mengulang kembali malam pengantin. Hanya dengan cara itulah, ia menebus tahun-tahun yang hilang dalam kisah mereka. Insyaallah. Jadi, kelak bila somnambulis mulai gentayangan di kota-kota yang insomnia, bila di alun-alun itu seribu kunang-kunang beterbangan mengitari tiang gantungan; kan kudengar angin berdesir lirih sekali, itulah Bapak dan Ibuku yang silih membacakan puisi.
Kami terjaga di sana hingga malam tiba dan, seperti yang hari yang sudah-sudah, Bapak berkisah tentang istrinya. Saat itu, gantian akulah yang memejamkan mata selagi ia terus bercerita dan terus bercerita. Aku terlelap dan sekejap bermimpi tentang kelebat bayang seorang perempuan asing yang sekonyong-konyong mengecup keningku sebelum lesap ke ujung gelap dan, entah sebab apa, itu mem-buatku terhenyak seketika. Bapak yang ternyata masih me-ngoceh pun mendadak memandangku dengan mata yang penuh tanya, “Kenapa?” “Mimpi buruk,” sahutku seraya beranjak hendak mengambil arak.
Kulewati ruang tamu di mana Ibu terpasung dalam sebuah pigura, menatapku tanpa kata. O, kaukah itu yang mencium keningku dalam mimpi singkat tadi, Bu? Ia mem-bisu. Selalu. Tapi aku tetap berdiri memandanginya lamalama, mengharap ia kan berucap sesuatu, sekadar nyatakan rindu. Dan ia masih membisu. Tak kutangkap apa-apa dalam pigura itu selain makna kematian. Aku mungkin akan menungguinya di sana hingga berabad-abad kemudian bila tak teringat untuk mengambil botol arak di dapur. Maka, kubiarkan Ibu terpenjara dalam bingkai tua itu.
Namun, sekembalinya ke beranda, kudapati maut tengah mencabik-cabik Bapak. Ia hanya bisa meringkuk di lantai, mengerang kesakitan, dan tak sanggup melawan. Setengah panik, sesegera kupanggilkan ambulans dan lantas berusaha menguatkannya selagi menanti mereka tiba. Tapi waktu seolah melambat. Tak kunjung kudengar bunyi sirene meraung-raung di udara. Langit hanya mendung. Kosong hampa.
Barulah setelah menit-menit terbuang percuma, seorang petugas akhirnya menelepon. Sungguh, saat itu kuharap ia berucap kalau sesosok setan menyesatkannya ke negeri-negeri antah-berantah ketimbang harus nerima kabar bahwa sebuah ekskavator yang melintang depan gapura menghalang jalan mereka. Maka, begitulah akhirnya ambulans tiba di rumah sakit dengan sia, sebab Sang Maut telah lebih dulu mencegat kami di tengah perjalanan.
***
Tanpa mengindahkan saran seorang paman, esoknya Bapak kubaringkan bersisian dengan Ibu sebagaimana permintaannya untuk mengulang kembali malam pengantin mereka. Memang, tetamu mempelai yang cuma terdiri dari beberapa sanak famili dan sisa tetangga tidaklah begitu ramai. Tak ada juga tangis haru atau gelak bahagia. Dalam udara mendung itu, semua hanya sediam dan kadang saja saling pandang tak berkata.
Namun, tak seperti dalam puisi, bukan desir angin yang mengusir pabila kemudian kami membubarkan diri. Bukan pula karena gerimis mulai berderai dan cahaya telah raib membuat langit tak berwarna. Akan tetapi, sebuah ekskavator menderu meruntuhkan tembok halaman rumahku, membuat para tamu ingkah sesegera tanpa sempat bertanya kepada tuhan, “Apakah mungkin kami bisa bahagia?” Maka, dalam satu kepanikan, orang-orang berlarian tunggang-langgang bahkan sebelum Bapak diturunkan dari kerandanya.
Ke balai warga seseorang merangkulku pergi dan untuk beberapa saat, aku hanya termangu selagi menahan diri agar tak gumamkan racauan cengeng. Seseorang yang lain menabahkanku. “Akan kita kuburkan nanti,” ucapnya. Tapi kubilang tak perlu. Sekarang juga harus kubaringkan bapakku di kamar terakhirnya. Nyaris seperempat abad Bapak menunggu untuk kembali tidur dengan Ibu. Aku tak ingin ia menanti lagi dan lagi.
Jadi, di sanalah, di sisi istrinya, hari itu Bapak dikuburkan. Ia telah benar-benar rebah untuk mengulang kembali malam pengantinnya. Ya. Walau sebagai sepasang mayat, sebab tak ada kesempatan lain yang ia miliki kecuali dalam kematian. Penguburan itu berlangsung khidmat dan sendu sebab memang seharusnya begitu. Dan mau tak mau, kuingkari juga janji untuk tak menangis saat kubaringkan ia di samping Ibu yang tinggal tulang kerangka sebab lama menunggu, sebagaimana Bapak menanti saat-saat untuk kembali bersama setelah meniti segala rindu.
Angga Saputra lahir di Bandung, 2000. Semasih kuliah, ia pernah bergiat di Lembaga Pers Mahasiswa “Jumpa” dan kini turut mengasuh Ruang Studi Alternatif, komunitas literasi yang berbasis di Tamansari. Kumpulan cerita ini adalah buku debutnya.
Ia bisa disapa via Instagram @pseudoangga
*Cerpen ini dipilih dari buku kumpulan cerpen berjudul "Rumah yang Neraka" karya Angga Saputra. Dapatkan bukunya (di sini) untuk mendapatkan potongan harga.