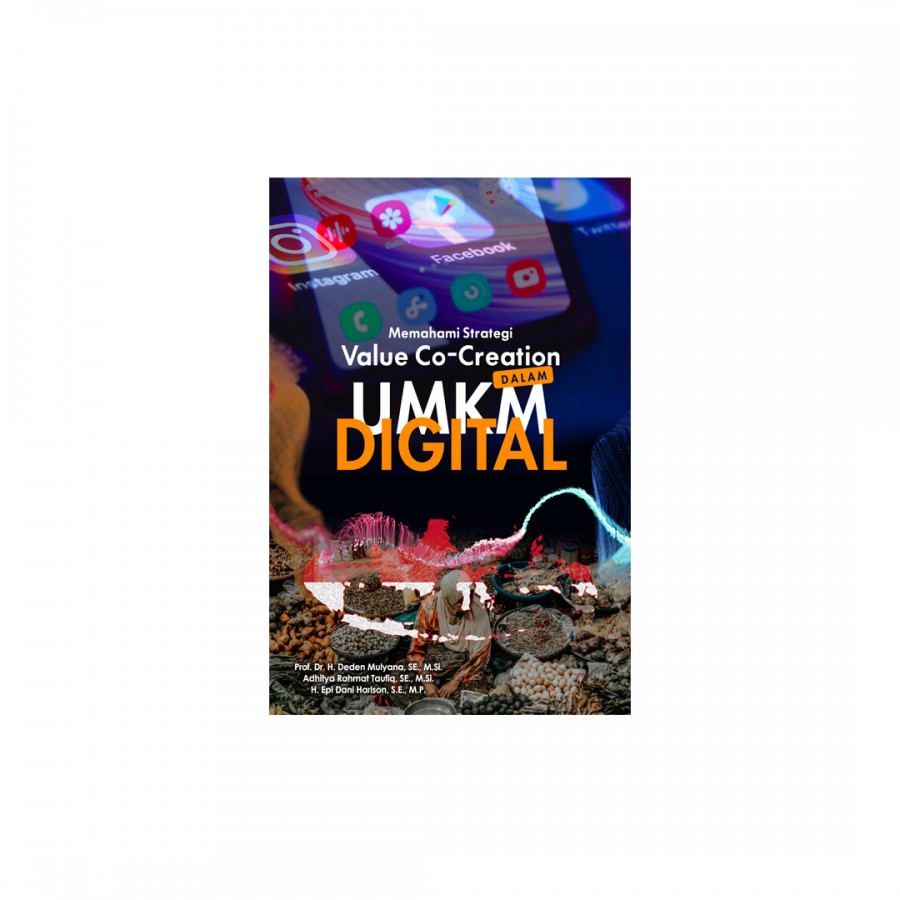-2014.jpg)
Eleana, seorang perempuan yang dulu pernah akrab sekali. Bahkan aku pernah menulis puisi untuknya soal kedekatan kami. Bait terakhir dari puisi itu kira-kira seperti ini:
Kita semakin tak beda dengan semoga dan amin
Kau semoga aku amin; atau sebaliknya
Tetapi yang pasti tidak ada semoga yang sempurna tanpa amin.
Sekarang masing-masing kami bersikeras menahan dera-dera kenyataan. Menghindari perjumpaan empat mata—memang kami tidak akan pernah berjumpa lagi—sambil tetap membiarkan sebagian dari diri berubah pelan-pelan. Menata bagian dari diri yang berantakan tanpa memaksakan apa yang sudah jadi urusan semesta.
***
Aku tidak mungkin salah ingat. Dulu, ketika masih dalam masa kuliah, Eleana paling sering menemani aku ke Gramedia. Sekalipun berjam-jam, ia selalu bersedia menunggu. Jarang menuntut agar segera pulang.
Kami pernah menghabiskan sekitar enam jam lamanya di Gramedia. Aku berkeliling dari satu rak buku ke rak yang lain. Memegang sekaligus membaca beberapa sinopsis. Sementara Eleana berjalan di sebelahku tanpa banyak bicara.
“Ini salah satu buku yang ditulis oleh penulis favoritku.” Aku memulai pembicaraan sambil memegang sebuah buku edisi hard cover.
Spontan Eleana menoleh ke arahku.
“Judulnya apa? Siapa yang menulisnya?”
“Melipat Jarak. Karya Sapardi,” jawabku singkat.
“Kovernya bagus. Aku suka,” kata Eleana sembari mengambil buku tersebut dari tanganku.
“Blurb-nya juga bagus. Tiap kata selalu padat makna. Sapardi memang ahlinya puisi,” balasku.
“Blurb artinya apa?” tanya Eleana sambil pandangannya tak berpaling dari buku yang tengah ia pegang.
“Blurb sederhananya seperti sinopsis. Kalau sinopsis biasanya terdapat pada kover belakang novel dan buku cerita umumnya. Sinopsis biasanya merupakan ringkasan cerita dalam novel. Sementara blurb umumnya ada pada kover belakang buku kumpulan puisi seperti ini. Blurb bukan ringkasan cerita tetapi bisa berupa testimoni. Kadang berupa kutipan yang dikutip dari isi buku. Misalnya pada kover belakang buku kumpulan puisi biasanya terdapat kutipan puisi. Sinopsis dan blurb dibuat dengan tujuan yang persis sama; untuk menarik minat pembaca,” aku menjelaskan
“Paham?” lanjutku setelah Eleana tak memberi respons padahal aku sudah menjelaskan panjang lebar soal blurb dan sinopsis.
“Paham Mas. Dasar kutu buku,” celoteh Eleana.
Aku terpukau ketika melihat Eleana senyum simpul sambil berceloteh. Mendadak aku ikut tersenyum. Kami saling pandang selama sekian detik.
“Berarti blurb ‘Melipat Jarak’ adalah ‘Sajak-sajak Kecil Tentang Cinta’ ini, ya?” tanya Eleana memastikan.
“Nah ... Pintar sekali,” balasku.
“Kau harus membaca ‘Melipat Jarak’, atau minimal membaca blurb-nya.” Aku bermaksud menggodanya.
“Hah? Alasannya??” Eleana tampak kebingungan.
“Agar kau paham kalau ‘mencintaimu harus menjelma aku’. Kalau menjelma yang lain berarti mencintai yang lain; bukan mencintaimu,” kataku dengan suara bisikan yang nyaris tak terdengar.
Eleana menoleh sambil tersenyum.
“Gombal. Lebay,” katanya dengan nada bicara sedikit mengejek.
Lagi-lagi Eleana tersenyum. Ini kali senyumnya semakin lebar. Cantiknya semakin membuat mata betah menatap. Ia lalu meletakkan kembali buku yang di tangannya ke tempat semula.
Kami terus berjalan di antara rak-rak buku. Rak buku-buku sastra adalah yang paling banyak menyita waktu. Aku memang suka sekali dengan karya sastra. Entah itu puisi, cerpen, ataupun novel.
Lamat-lamat aku menatap buku-buku sastra yang tersusun rapi pada rak di hadapanku. Pada bagian bawah rak, terdapat beberapa buku kumpulan puisi yang tak asing bagiku. Misalnya buku ‘Tidak Ada New York Hari Ini’ karya Aan Mansyur, ‘Di Hadapan Rahasia’ karya Adimas Immanuel, ‘Surat Kopi’ dan ‘Buku Latihan Tidur’ karya Joko Pinurbo serta buku-buku yang ditulis oleh alm. Sapardi Djoko Damono.
Aku membayangkan sewaktu-waktu buku yang aku tulis juga turut dijual di Gramedia. Diletakkan di rak sastra. Bersebelahan dengan karya-karya Aan, Adimas, Jokpin dan Sapardi. Aku membayangkan sewaktu-waktu aku datang lagi ke Gramedia bersama Eleana dan teman-teman kami. Lalu dengan bangga aku mengajak mereka mengunjungi rak buku sastra, menunjukkan kepada mereka bahwa buku yang aku tulis sudah tersedia di Gramedia.
“Kurang lima belas menit lagi tepat pukul empat belas nol-nol. Masih belum mau pulang?” kata Eleana sambil melangkah ke arahku.
Mendadak lamunanku menjadi buyar. Aku menatap Eleana. Tampak seperti ada yang lain dengan cantiknya. Tanpa berpikir panjang, aku menggenggam tangannya.
“Kita pulang sekarang!” kataku.
Dalam perjalanan pulang, Eleana tak banyak bicara. Aku mulai mencemaskannya. Jangan-jangan ramahnya mendadak menjadi marah karena aku keasikan melihat-lihat buku tanpa memedulikannya. Jangan-jangan Eleana merasa diabaikan. Jangan-jangan Eleana menjadi kesal karena aku kelamaan menghabiskan waktu di Gramedia.
“Cantik, apa yang terjadi? Baik-baik saja, kan?” tanyaku gugup.
“Kita menghabiskan waktu selama enam jam di Gramed. Melewatkan jam makan siang. Ini sudah pukul empat belas lewat. Aku takut maagku kambuh,” jawab Eleana.
Sumpah. Mendengar itu, aku merasa seperti telah melakukan kejahatan besar terhadap Eleana. Aku merasa seperti telah melukai Eleana. Bagaimana kalau maagnya benar-benar kambuh. Sialan! Aku menaikkan kecepatan kendaraan roda dua yang selalu memudahkan setiap perjalanan kami. Di bahu kiri jalan ada sebuah tempat makan sederhana. Aku memilih berhenti di situ.
Kami hanya berbicara satu dua kata saja di tempat makan itu. Aku canggung sekali. Ketika pesanan kami datang, masing-masing langsung sibuk sendiri. Sesekali aku memandang Eleana diam-diam. Sepertinya ia sudah sangat lapar. Itu diisyaratkan oleh cara makannya. Tanpa membutuhkan banyak waktu, Eleana menghabiskan makanannya. Aku juga demikian. Kami memutuskan untuk segera pulang setelah makan.
Tetapi sebelum itu, aku dan Eleana berjalan ke arah pemilik warung. Masing-masing kami mengeluarkan uang dua puluh lima ribu rupiah untuk membayar makanan. Kau jangan kira makanan yang kami makan tadi dibayar hanya oleh salah satu dari kami saja. Tidak. Tidak demikian. Kami membayarnya sendiri-sendiri. Eleana tidak pernah mau jika aku membayar makanan yang ia makan.
Dalam perjalanan sehabis makan, aku benar-benar tak bisa banyak bicara lagi. Kata-kata seperti sudah wafat. Aku ragu memulai pembicaraan. Setelah tiba di kosnya, aku langsung meminta maaf kepada Eleana.
“Tak apa. Jangan dipikirkan lagi. Kapan aku tidak memaafkanmu? Sudahlah. Sebaiknya kau langsung pulang saja. Hati-hati di jalan. Jangan ngebut. Jangan nakal!” kata Eleana.
Aku hanya bisa mengangguk.
Aku bahagia sekali mendengar Eleana berkata demikian. Apalagi ketika ia mengatakannya sambil tersenyum. Syukurlah. Berarti semua baik-baik saja.
“Makanya jangan terlalu kutu buku. Jadinya lupa jam makan. Dasar!” Eleana lalu membalikkan badan setelah berkata demikian. Masih sempat aku melihat senyumnya. Aku semakin yakin bahwa semua memang baik-baik saja.
***
Terakhir aku bertemu Eleana dua bulan lalu. Sebelum semua media ramai memberitakan peristiwa naas yang menimpa aku dan Eleana. Termasuk media tempat aku bekerja sebagai wartawan. Ketika itu Eleana meminta aku menemuinya di kafe ini. Tepat saat senja hari.
Pagi ini aku datang lagi ke kafe tempat aku menemui Eleana dulu. Kafe masih sepi. Hanya beberapa orang saja yang berkunjung. Biasanya pengunjung kebanyakan datang ketika senja hari. Aku duduk lagi di kursi yang sama. Orang-orang tidak menyadari kehadiranku. Kami sudah beda alam. Aku bisa melihat mereka tetapi mereka sama sekali tidak akan bisa melihat aku.
Sebelum menemuinya di kafe ini pada awal bulan April lalu, aku memang merasa ada yang aneh. Tak seperti biasanya, Eleana meminta aku menemuinya di sebuah kafe. Toh tempat biasa kami bertemu bukan di kafe.
Mengapa Eleana tak meminta aku untuk terlebih dahulu menjemputnya? Mengapa ia mendahului aku ke kafe? Sederet pertanyaan itu mengiringi perjalananku menuju kafe tempat Eleana menunggu.
Tepat hari ini, tanggal sembilan belas Juni, harusnya aku dan Eleana merayakan anniversary. Jika saja Eleana dulu tidak memberi aku kopi dengan kandungan racun Syanida, hari ini kami genap tiga tahun berpacaran. Bahkan aku sudah membulatkan tekad untuk melamarnya tahun ini juga. Tetapi itu tak mungkin terjadi.
Aku masih tak percaya bahwa Eleana memutuskan untuk mengakhiri hubungan kami dengan cara tak biasa dan tanpa alasan-alasan yang pasti. Kalau hari ini kau ingin bertemu dengan Eleana, langsung saja ke tempat tahanan. Eleana ada di sana. Ia sedang menebus kesalahannya. Perlu aku katakan bahwa anak di rahimnya sama sekali bukan anakku; agar kau tak salah sangka ketika bertemu Eleana.
*Aprianus Defal Deriano Bagung, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Penulis buku “Kemeja Kenangan.” (Kontak WhatApp: 082144524563).