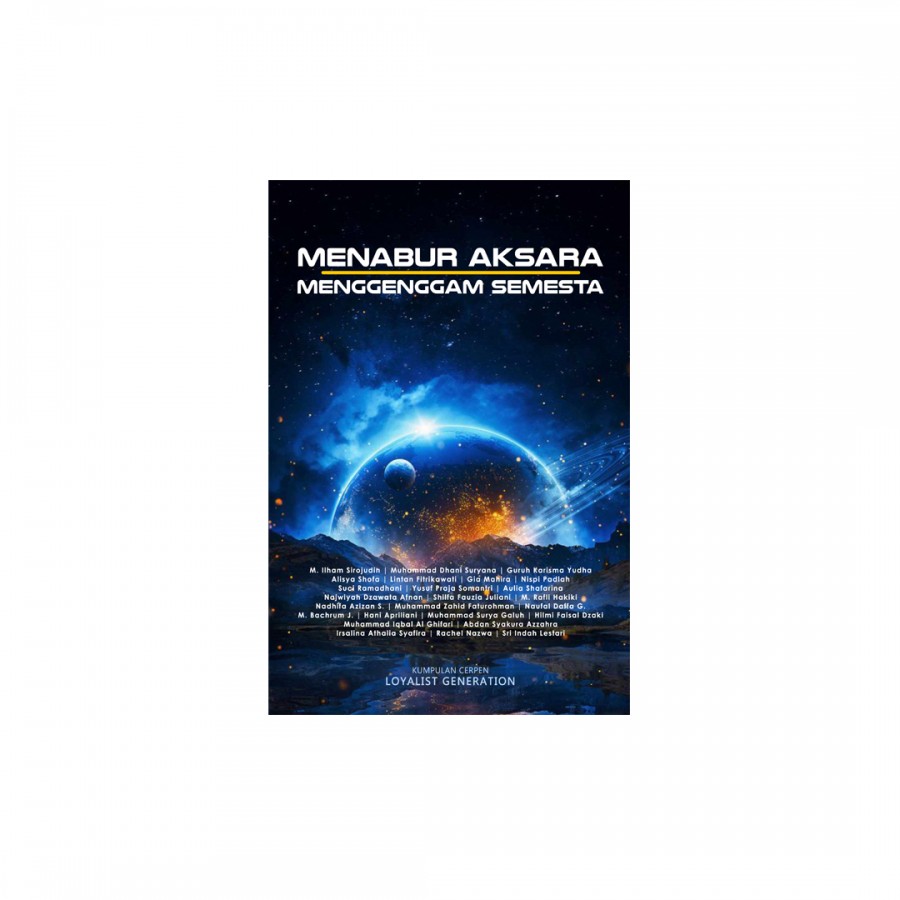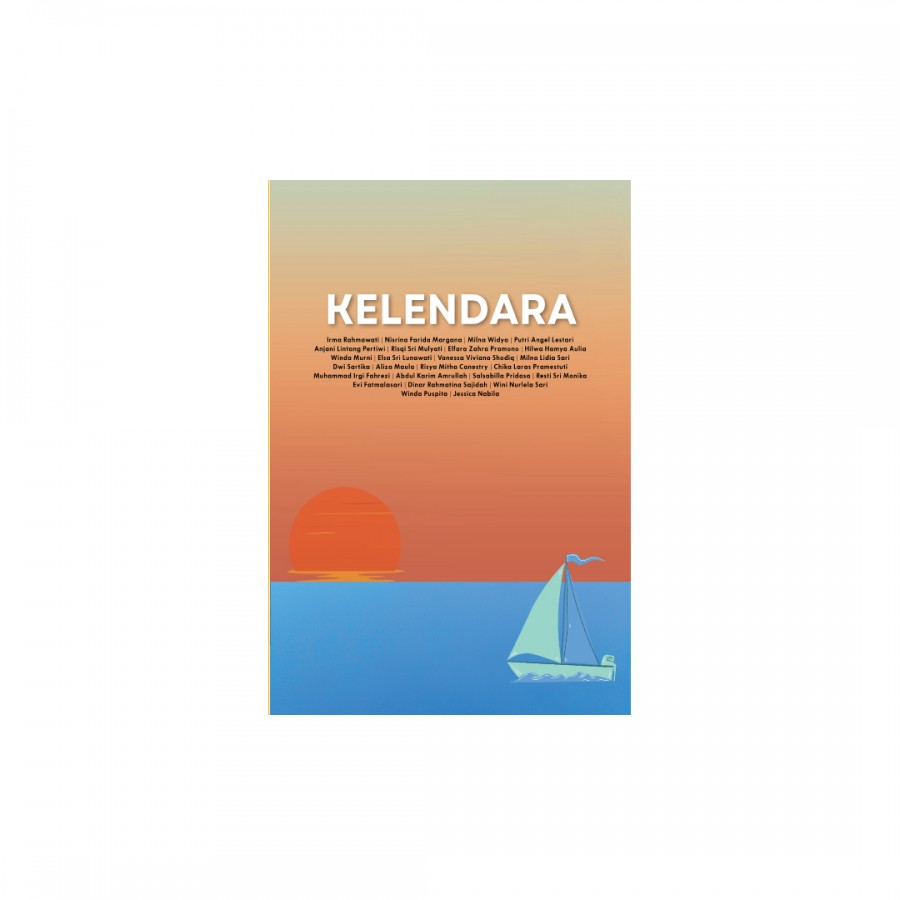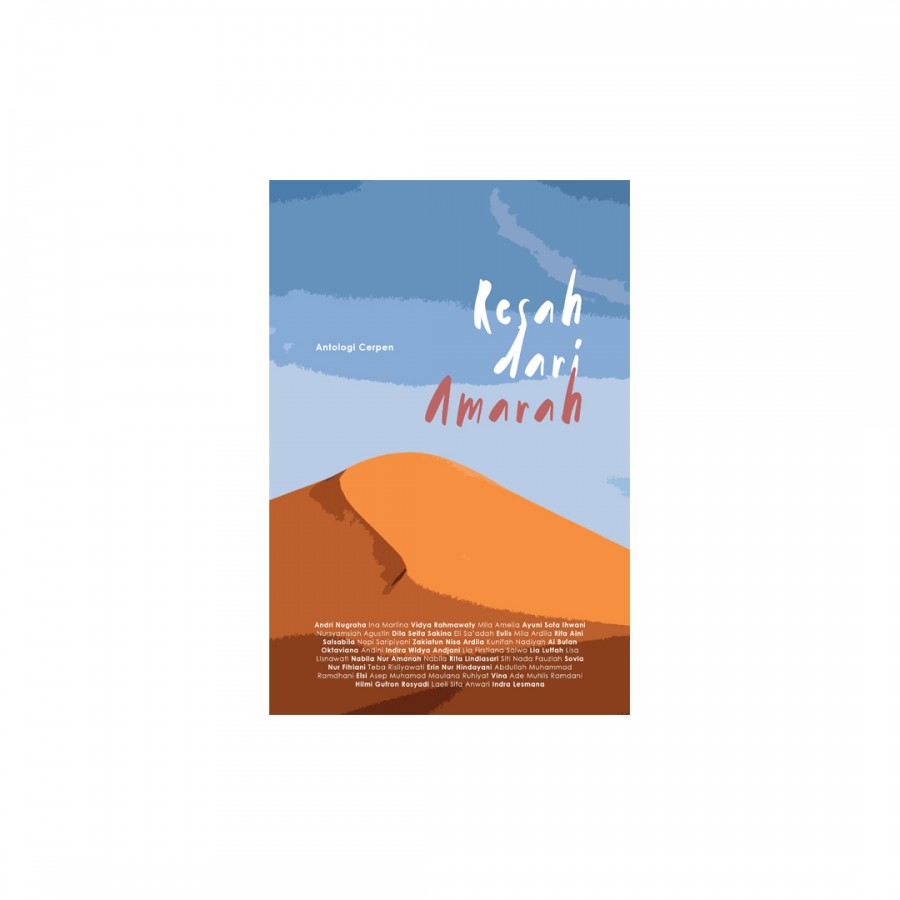“Mulai hari ini, aku harus punya teman,” Hanama berbisik dalam hati, mencoba membulatkan tekadnya.
Sudah hampir dua pekan terlewati sejak pertama kali Hanama masuk sekolah, tapi tujuannya masih sama: menggaet seorang teman. Dipikirnya, ia mesti lekas-lekas memiliki seseorang untuk diajak bersenda gurau, bermain lompat tali, mengerjakan PR bersama, atau berbagi bekal makan siang.
Maka, dari bawah pohon ketapang kencana itu, Hanama mengamati kumpulan siswa yang menggelesot di tepian sebuah undakan, hanya berjarak beberapa depa dari tempatnya melendeh. Dari hasil menguping, Hanama tahu bahwa kawanan bocah itu gemar bertukar cerita horor sejak sepuluh hari terakhir.
Namun demikian, Hanama menemui kesulitan. Hal ini bukan karena ketidakmampuannya dalam berbahasa, melainkan karena ia tak pernah melihat hantu sebagaimana yang ada di dalam cerita teman-temannya itu. Menurut Hanama, wujud dan tabiat hantu yang mereka utarakan sungguh berbeda.
Namun tekad tetaplah tekad. Hanama merancang rencananya sekali lagi. Bermodalkan keberanian seadanya, gadis berpita kuning itu melangkah sambil merunduk seraya mencari-cari kalimat untuk mengawali perbincangan.
“Hai,” sapa Hanama, “namaku Hanama. Apa aku boleh duduk di sini?”
Bocah-bocah berbusana merah-putih itu sontak menengok ke arah Hanama yang berdiri tepat di samping himpunan bunga asoka, lalu mencermati perawakannya dari atas sampai bawah.
“Eh? Kamu mau apa ke sini?” jawab salah satu siswa yang bertubuh tambun.
“Aku punya cerita. Ekhm…. Cerita horor.”
Suasana mendadak hening. Beberapa anak mengerutkan dahi. Sebagian yang lain mengusap dagu. Rasa heran melanda. Mereka masih berupaya mengenali Hanama dan menerka-nerka dari mana gadis pemurung itu datang, walaupun Hanama jelas-jelas mengenakan seragam yang sama persis dengan mereka.
Di tengah semerbak bunga asoka yang beterbangan ke sana kemari, Hanama menyunggingkan senyum sambil menunggu respons, berusaha mengenyahkan rasa canggung yang tak dapat terhindar.
“Memangnya kamu pernah melihat hantu?” tanya seorang anak perempuan yang sedari tadi mengulum permen.
“Tidak. Tapi setidaknya aku bisa mengingatnya samar-samar. Ini biasa diceritakan ibuku.”
“Oke, hantu apa yang hendak kamu ceritakan?” timpal yang lain, “kuntilanak? Genderuwo? Atau Mister Gepeng? Ah, kami tidak menerima cerita tuyul dan babi ngepet!”
Hanama termenung sejenak, separuh mematung. Gadis itu tak serta-merta menanggapi. Ia tahu, pertanyaan itu pada akhirnya akan terlontar juga. Hanama kadang merenung dalam hati, apakah hantu mesti mempunyai nama? Jika ya, bagaimana prosedurnya? Apakah nama itu diberikan berdasarkan dari bentuknya atau tindak tanduknya?
Lagi pula, bukankah nama tak begitu penting?
***
Hanama selalu menantikan cerita hantu milik ibunya, yang secara khusus hanya dituturkan kepadanya. Bagi Hanama, ibunya adalah orang yang paling mahir dalam menggodok cerita horor: bernas, terperinci, sekaligus mengerikan setengah mampus.
Selama hampir lima tahun berturut-turut, di tiap malam Sabtu, Hanama akan berbaring di ranjang setelah Ibunya selesai mandi dan berbenah sepulang dari kantor. Lantas, Ibunya akan menutup tirai dan menyalakan lampu tidur, sedangkan Hanama akan menggenggam erat boneka kura-kuranya.
Di bawah redupan cahaya, Ibunya berkisah bahwa dahulu ada sosok hantu yang menghuni rumah. Bertahun-tahun silam, ketika rumah Hanama baru saja rampung dibangun, hantu itu sempat menetap di kamar ibunya sebelum akhirnya minggat dan berkeliaran di sekitar rumah.
Wujudnya cukup menimbulkan rasa was-was dan membuat bulu kuduk merinding. Hantu itu berpostur jangkung, hampir setinggi lemari kayu yang teronggok di pojok kamar Hanama. Sosok menakutkan itu juga memiliki tangan dan kaki yang dipenuhi bulu, sekilas menyerupai monster Himalaya.
“Bedanya, hantu itu berbau anggur,” ungkap Ibunya hambar, “bagian atas kepalanya agak botak dan matanya merah menyala. Di selingkung rahang dan bibirnya, terdapat kumis serta cambang yang menjalar. Cara hantu itu bergerak di antara dinding rumah pun sangat aneh, yakni dengan menyeret kakinya yang sempoyongan.”
Setiap pagi buta, ujar Ibunya, hantu itu acapkali mendiami sofa beludru berwarna toska yang ada di ruang tengah. Di situ, momok berbadan besar itu tergolek di depan TV.
Yang terjadi sesudahnya, makhluk berparas buruk itu akan mengerang kesakitan seraya menggeret tembok kamar mandi, menumpahkan berbagai peralatan ke dasar ubin, lalu mendekam di sudut. Ibunya memaparkan bahwa kala itu, suara raungan hantu itu bisa berpendaran ke seisi rumah dan kerap menyebabkan Hanama kecil terbangun dari tidurnya.
Ibunya kemudian mengisahkan asal-usul hantu tersebut. Mulanya, hantu itu tak pernah mengusik. Hantu itu akan pergi saat fajar mulai menyingsing dan kembali ketika matahari terbenam.
Lambat laun, hantu itu malah bersemayam di rumah, ogah mencari makan, dan lebih memilih menghabiskan waktunya di petopan kumuh bersama dedemit lainnya kala malam singgah.
“Apakah hantu itu memang tidak butuh makan atau minum seperti kita, Bu?”
“Hantu bertampang jelek itu cuma doyan mengisap rokok, Han,” tegas Ibunya, “maka, agar tidak mengamuk, Ibu sebisa mungkin menyajikan rokok dan secangkir kopi hitam, lalu dia tidak akan berhasrat untuk makan ataupun minum.”
Hanama hanya manggut-manggut tanda mengerti. Selagi menyimak, ia berulang kali menoleh ke mata ibunya, di mana ada sesuatu yang enggan ia selami lebih dalam. Sementara itu, jam telah menunjukkan pukul 9 malam.
“Ibu, apa aku pernah melihat sosoknya?”
“Kamu pernah digendongnya, hanya sesekali. Itu dulu, saat kamu masih berumur satu tahun. Demi Tuhan, itulah hal yang paling meresahkan Ibu. Ah, mungkin kamu sudah lupa.”
“Selain itu, tidak pernah lagi?”
“Tidak,” tandas Ibunya.
Hanama menelan ludah, ngeri mengandaikan adegan yang terukir di kepalanya.
“Rasa-rasanya, hantu itu mirip seperti kita, ya? Seperti manusia?” Hanama masih melanjutkan rasa penasarannya.
Saban kali kalimat itu menyembur dari kerongkongan Hanama, Ibunya buru-buru membungkam mulutnya sendiri dan menghentikan kisahnya tanpa aba-aba untuk sepersekian detik. Namun, hingga kini Hanama belum lagi menangkap maksud dari perilaku ibunya tersebut.
“Bu, apakah hantu itu betul-betul tidak memiliki nama?”
“Tidak,” Ibunya menaikkan nada bicaranya, “dia tidak pantas mempunyai nama, bahkan dengan nama yang ada dalam ingatanmu sekalipun. Baginya, nama adalah sebuah kutukan.”
“Lantas, mengapa aku memanggilnya demikian?”
“Kamu masih terlalu kecil, Han. Masih mudah diperdaya.”
Untuk kesekian kalinya Hanama mengangguk-angguk ringan, membuat wajahnya yang lugu tampak bodoh.
“Apakah hantu itu berbahaya? Apakah dia juga suka menyerang kita?”
“Hantu itu suka berteriak-teriak, menendangi pintu, memecahkan vas peninggalan Nenek, dan adakalanya membanting perabot dapur,” suara Ibunya mulai bergetar, “dia mampu menghancurkan segala yang ada di rumah ini. Seperti iblis. Ya, seperti iblis!”
Tiap kali cerita sampai pada babak ini, entah mengapa, selalu terbayang di benak Hanama tatkala hantu itu mengamuk dan menghancurkan isi rumah. Ia cukup yakin bahwa penampakan itu pernah terjadi di hadapannya, meski hanya mencungul sepintas lalu. Entah di hari apa, di bulan apa. Hanama tak kunjung mendapatkan kepastian.
Kendatipun demikian, dari sini pula memori Hanama akan hantu bengis itu mengabur dan hilang, disapu angin malam yang berhembus melalui celah ventilasi kamar. Sejurus kemudian, Hanama merasakan kecupan hangat di keningnya.
“Tenang saja, Han. Hantu itu sudah Ibu usir, dia tidak akan pernah mengganggu kita lagi,” kamar itu seketika disesaki kesunyian, “namun jika suatu hari kamu melihatnya, larilah! Larilah sekencang yang kamu bisa!”
“Hantu itu, kan, cuma sendiri? Kenapa aku harus takut, Bu?”
“Satu hantu saja sudah cukup membuat seorang Ibu menderita.”
Bersamaan dengan penghabisan cerita, Hanama sekali lagi memperhatikan mata ibunya dengan saksama. Hampa belaka. Dari penglihatannya, hanya tampak gelombang air yang mengalir perlahan dan membasahi pipi Ibunya.
“Ibu menangis?”
***
Hanama masih berpijak di tempatnya seperti sediakala, di sebelah rumpun bunga asoka yang bergoyang halus. Ia memijat-mijat jemarinya, seolah-olah akan ada peristiwa menegangkan di ujung hidungnya. Sesudah itu, dibetulkannya pita kuning di sela-sela rambutnya yang merosot.
Di sisi lain, kerumunan bocah cilik itu hanya termangu dan saling berpandangan satu sama lain. Mereka gagal menyembunyikan rasa mencekam yang terpantul di wajah masing-masing. Cerita horor milik Hanama terdengar sangat maujud dan berbeda dari semua yang pernah mereka jumpai.
“Apa hantu jahat itu masih gentayangan sekali waktu?” sergah seorang siswa berkacamata, menentang mata Hanama dengan tajam, “sebab, biasanya ada arwah yang masih tidak tenang di alam sana.”
“Ia tidak pernah kembali lagi. Ibuku bilang, hantu itu akan ciut ketika tahu ada Kakek dan Nenek yang kini tinggal di belakang rumah,” jelas Hanama, “konon, Kakek memiliki ilmu putih yang sanggup membantu Ibu menghalau hantu.”
Tanpa mereka sadari, lonceng sekolah berdentang lima kali. Jam istirahat telah usai. Tapi semua perhatian anak-anak itu masih terpaku pada Hanama.
“Jadi, Hanama, hantu itu tidak punya nama?”
“Tidak.”
“Hantu itu harus memiliki nama,” tukas yang lain, “ayo, berikan hantu itu sebuah nama!”
“Caranya?”
“Coba ingat-ingat perbuatannya, misalnya, apakah dia suka mencuri sesuatu?”
Hanama menengadah sembari menghela napas. Ia dapat memastikan bahwa satu-satunya hal yang direnggut oleh hantu itu ialah kebahagiaan dari mata ibunya.
Tak lama berselang, ditatapnya burung-burung gereja yang berkerubung di atas gedung. Ibunya pernah berkata, kehadiran burung gereja sama dengan keberuntungan. Dan seiring dengan itu pula, Hanama percaya bahwa sebentar lagi dirinya akan mempunyai teman yang selama ini diidam-idamkannya.
“Baiklah, aku biasa menyebutnya ‘Ayah’.”
Muhammad Faisal Akbar lahir di Jakarta dan bermukim di Depok. Menulis cerpen dan esai di berbagai media daring. Ia dapat dijumpai melalui Instagram @icalbar