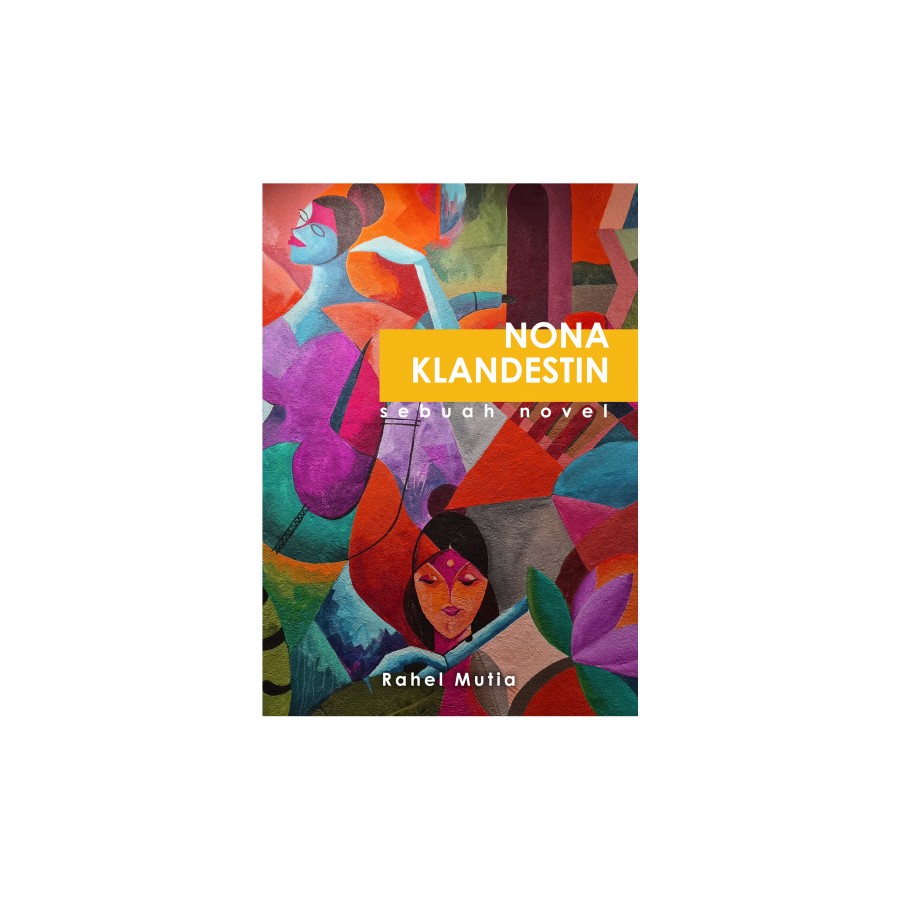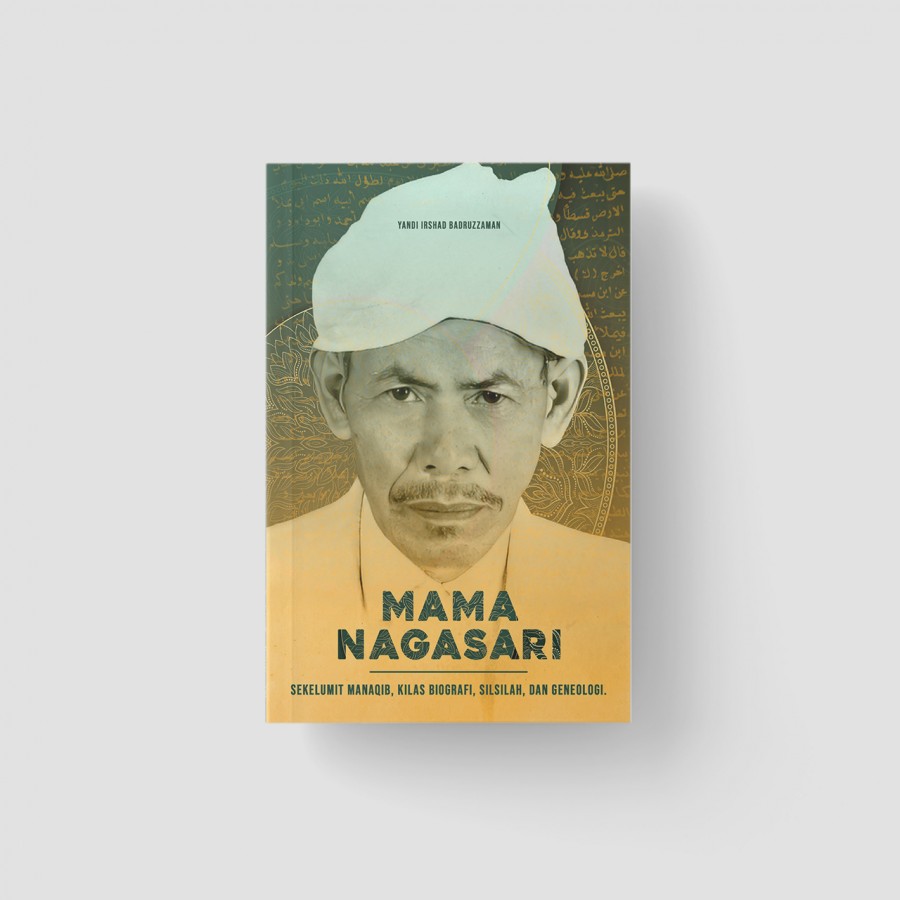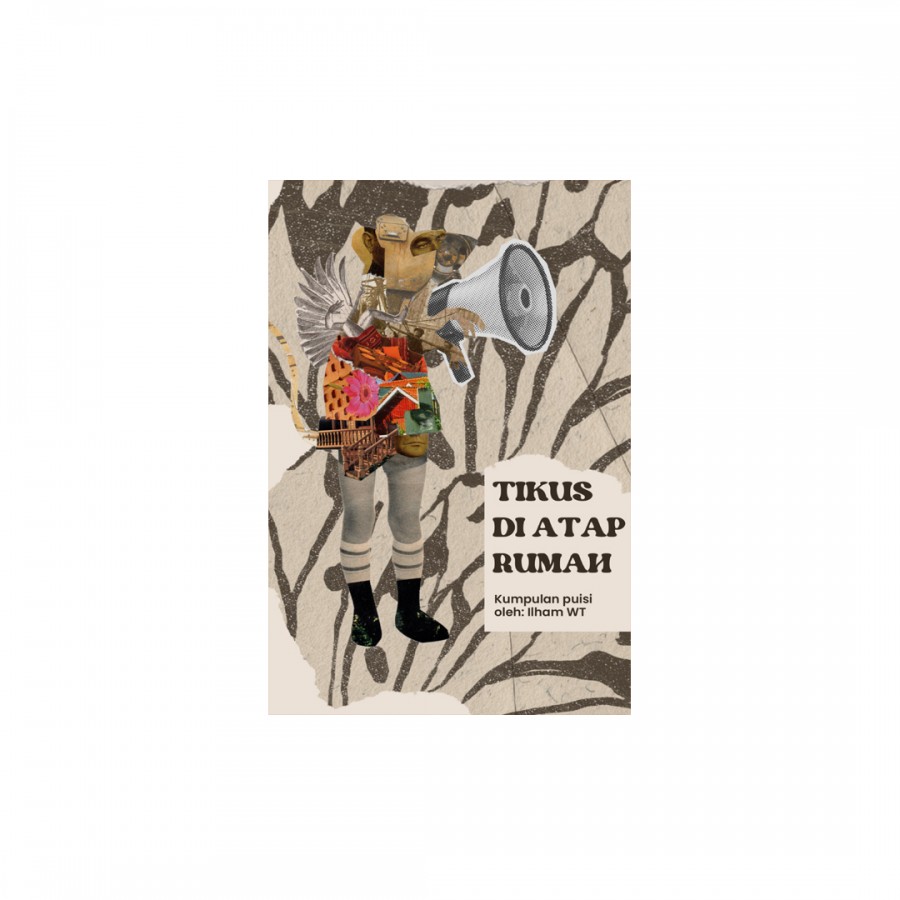Kata-kata syukur masih mengembang dari bibirnya meski di depannya, orang-orang terus meletupkan hewan-hewan najis seperti anjing dan babi. Sebab, yang demikian itu masih lebih baik ketimbang kasak-kusuk yang ia dengar, batinnya. Namun, pada akhirnya ia mengerti juga, bahwa bagaimanapun cara gunjingan itu sampai kepadanya, tetap saja ia merasa terlukai.
Tahu jika sumpah-serapah akan segera menghambur dari mulutnya, maka lekas-lekaslah Kupupu mendesah panjang—menguar segala kesumat dari lubang hidungnya.
Lantas, setelah membayar sebungkus wortel dan kentang, Kupupu pun segera kembali ke rumahnya. Dari sebuah rak perabot, ia kemudian mengambil sebuah talenan dan pisau—mulai mencacah wortel dan kentang tadi menjadi potongan-potongan kecil. Saat itulah, di dalam tempurung kepalanya tiba-tiba meletus beberapa gelembung sabun.
***
Kupupu merupakan seorang kembang desa—gadis yang terlampau cantik dan menggoda. Maka, tak heran apabila banyak lelaki, bahkan yang sudah berusia senja dan beristri, suka berlama-lama memandangi tubuhnya yang ranum itu.
Sekali waktu, ketika Kupupu sedang asyik menikmati tempias hujan yang memercik ke sana kemari dari jendela kamarnya, tiba-tiba saja hatinya menjaring satu perasaan ganjil. Kupupu merasa jika ada sepasang mata yang diam-diam mengawasinya dari kejauhan. Dan benar saja, sesaat kemudian, dari seberang rumahnya tiba-tiba muncul seorang lelaki tua yang berjalan terpincang-pincang merampas perhatiannya. Lantas, dari ruang tamu rumahnya, kemudian terdengar sebuah suara:
“Saya ingin mengawininya, Mak, mohon izin,” katanya.
Mendengar hal tersebut, sebongkah batu pun segera menghajar dada Kupupu. Tentu bukan sekali itu saja kalimat semacam itu merajami lubang telinganya, tapi ia dua puluh tahun lebih tujuh bulan, ia paham dan mengerti, bahwa lelaki tua itu mesti dikecualikan. Orang-orang memanggilnya sebagai Tuan Besar.
Setelah lelaki tua itu pergi, Kupupu segera menyusul Mamaknya ke ruang tamu. Dengan mata yang keruh, kemudian disusurinya wajah Mamaknya dengan suatu perasaan ganjil. Namun, pada saat yang hampir bersamaan, Mamaknya tiba-tiba mengangkat wajah—lurus menatap mata Kupupu, seperti sedang berusaha mencari sebuah jawaban. Tak mau diperlakukan seperti itu, Kupupu pun segera membuang pandangannya melewati sebuah jendela.
Mengetahui gelagat Kupupu itu, Mak Kruget pun kemudian berkata: “Terserah kamu saja, Nak.” katanya dengan penuh pengertian. “Tapi, Mamak sebenarnya tidak setuju kalau kau harus kawin dengan dia.”
Mendengar pengakuan tersebut, Kupupu merasa jika ada angin yang tiba-tiba berembus ke dalam dadanya. “Tapi… tapi bagaimana kalau dia tidak menerimanya, Mak?” balasnya kemudian.
Lantas, dengan sorot matanya yang jernih, Mak Kruget lalu berkata, “Mamak benar-benar menyayangimu, Nak. Sungguh!”
***
“BUKAN cinta namanya kalau tidak gila,” gumam Mak Kruget, bukan kepada siapa pun.
Di ruang tamu yang terlampau sederhana, yang hanya digelar selembar tikar pandan dengan beberapa piring makanan dan gelas minuman di atasnya, Mak Kruget menjamu Tuan Besar.
“Silakan diminum dulu, Tuan,” katanya.
Air muka yang terpancar dari wajah Mak Kruget saat itu adalah isyarat jika ia sudah sangat siap dengan keputusannya, dengan jawabannya, dengan segalanya. Namun, setelah si Tuan Besar menatapinya dengan pandangan angkuh seorang pembesar, Mak Kruget akhirnya goyah juga: ia harus membetulkan posisi duduknya beberapa kali.
“Bagaimana?” tanya si Tuan Besar. Masih dengan sikap yang sama.
“Begini, Tuan,” kata Mak Kruget mula-mula. “Sebenarnya saya setuju-setuju saja jika anak saya menikah dengan Tuan. Apalagi Tuan kan orang punya. Saya percaya jika semua kebutuhan anak saya akan terpenuhi tanpa terkecuali. Tapi, setelah saya pertimbangkan kembali, saya merasa kalau untuk saat ini, Kupupu masih belum cukup umur untuk menikah, Tuan. Tapi, itu bukan ber-arti…”
Belum sempat Mak Kruget menyelesaikan kalimatnya, si Tuan Besar segera menukas: “Jadi, maksud kau, lamaranku ditolak begitu?”
“Bukan begitu maksud saya…”
Lagi-lagi, si Tuan Besar kembali memotong, bahkan setengah menghardik, “Alah, jadi orang miskin saja belagu, sok jual mahal…”
“Bukan cinta namanya kalau tidak gila,” leguh Mak Kruget, setelah dengan kasar si Tuan Besar membanting pintu rumahnya.
***
SETELAH beberapa kali berkruget-kruget seperti seekor ulat, tubuh Mak Kruget akhirnya tergolek lemas dengan mata membelalak dan mulut berbusa. Sedang di dekatnya, Kupupu tak henti-hentinya meratapi nasib yang tak pernah sedikit pun ia bayangkan sebelumnya itu.
“Ampuni aku, Mak. Ampuni…”
Selepas mengantar mayat Mamaknya, hari-hari berikutnya sering kali hanya dihabiskan Kupupu dengan duduk-duduk melamun di atas lincak di belakang rumahnya. Dan matanya seolah tak pernah lelah untuk menyisir setiap lanskap rumahnya itu—yang diam-diam telah merekam segala percakapan dan adegan antara ia dan Mamaknya, yang kemudian, dirampas dengan sangat kasar dari tangannya.
Beberapa minggu setelah kematian Mamaknya, tibalah malam gila yang gantian menyergap Kupupu. Ketika Kupupu sedang khusyuk mengambil air wudu di sumur belakang, beberapa orang lelaki tiba-tiba menyergap dan memelintirkan tangannya ke belakang—selembar kain hi-tam kemudian merampas seluruh kesadarannya.
Dalam samar-samar cahaya lampu, Kupupu perlahan-lahan mulai menginsafi nasibnya: seekor kambing yang telah berada di atas sebuah ceruk kematian dengan semua kaki yang telah dibebat seutas tali. Menyadarinya, maka menggelinjang-gelinjanglah Kupupu di atas ranjangnya.
Mendengar ringkik ranjang, empat orang lelaki pun segera muncul dengan wajah-wajah yang sangat mengerikan. Tak berhenti sampai di sana, dari pintu yang sama, lalu mengeluyurlah seorang lelaki tua yang tak asing lagi bagi ingatan Kupupu, bagi ingatan buruknya.
“Ampun, Tuan, ampun,” rintih Kupupu. Saat itulah, air matanya mulai menjelma kerikil-kerikil tajam yang merajami kedua belah pipinya sendiri.
Menyaksikannya, si Tuan Besar justru tergelak dengan puas. Lalu mendekati telinga Kupupu, “Kenapa kau menangis, pelacur? Menyesal kau menolakku, heh?” katanya.
***
KUPUPU benar-benar jatuh ke dalam jurang gelap tak berujung. Dengan tipu muslihatnya, di depan orang-orang, si Tuan Besar menuding Kupupu telah berbuat serong dengan seorang pemuda. Kata si Tuan Besar lagi, tentu saja karena hal itu muka kampung menjadi coreng-moreng, dan yang lebih mengerikan lagi, bisa mengundang kebencian Tuhan turun dari langit. “Mata kepala saya sendiri saksinya,” silat si Tuan Besar.
Maka, pada suatu sore yang tampak biasa-biasa saja, orang-orang kemudian membakar rumah Kupupu tanpa ampun. Dan sama halnya dengan unggunan api yang melumat habis pekayu rumahnya, kabar serong tentang Kupupu pun dengan cepat tersebar ke setiap telinga orang-orang.
Lantas, saat Kupupu kian silap dalam hidupnya, tiba-tiba saja ia memilih sebuah jalan yang sangat mengerikan: di dekat sebuah jembatan, Kupupu menyewa sepetak kamar yang dijadikan warung bagi tubuhnya sendiri.
Namun, saat Kupupu kian maklum dengan keadaan perutnya, ia mendadak terjaga akan hidupnya—terkenang olehnya sebuah kalimat purba milik Mamaknya: bukan cinta namanya kalau tidak gila.
***
KUPUPU terus mencacah wortel dan kentang menjadi potongan-potongan yang sangat kecil.
“Bukan cinta namanya kalau tidak gila kan, Mak?” leguh Kupupu kemudian, setelah dengan lincah melempar matanya melewati kaki-kaki pepohonan—berhenti pada sebongkah batu piramida yang berdiri di atas setumpuk tanah. Saat itulah, di atas kepala Kupupu, tampak seorang malaikat yang sedang melayang-layang memper-hatikan gelagat sebilah pisau.
Aflaz Maosul Kamilah lahir di Garut, Jawa Barat, 08 September 1998. Mulai menyenangi kegiatan baca-tulis ketika mengikuti program “ilegal” Paket 3 di SMA-nya. Sebuah program yang tanpa sepengetahuan Kemen-dikbud, diam-diam “merombak” mata pelajaran Bahasa Indonesia menjadi sekadar membaca dan menulis. Me-nyelesaikan pendidikan Sastra Indonesia dari Universitas Padjadjaran pada 2021.
*Cerpen tersebut diambil dari buku kumpulan cerpen yang berjudul “Sanghyang Taraje” karya Aflaz Maosul Kamilah. Miliki bukunya hanya di langgampustaka.com