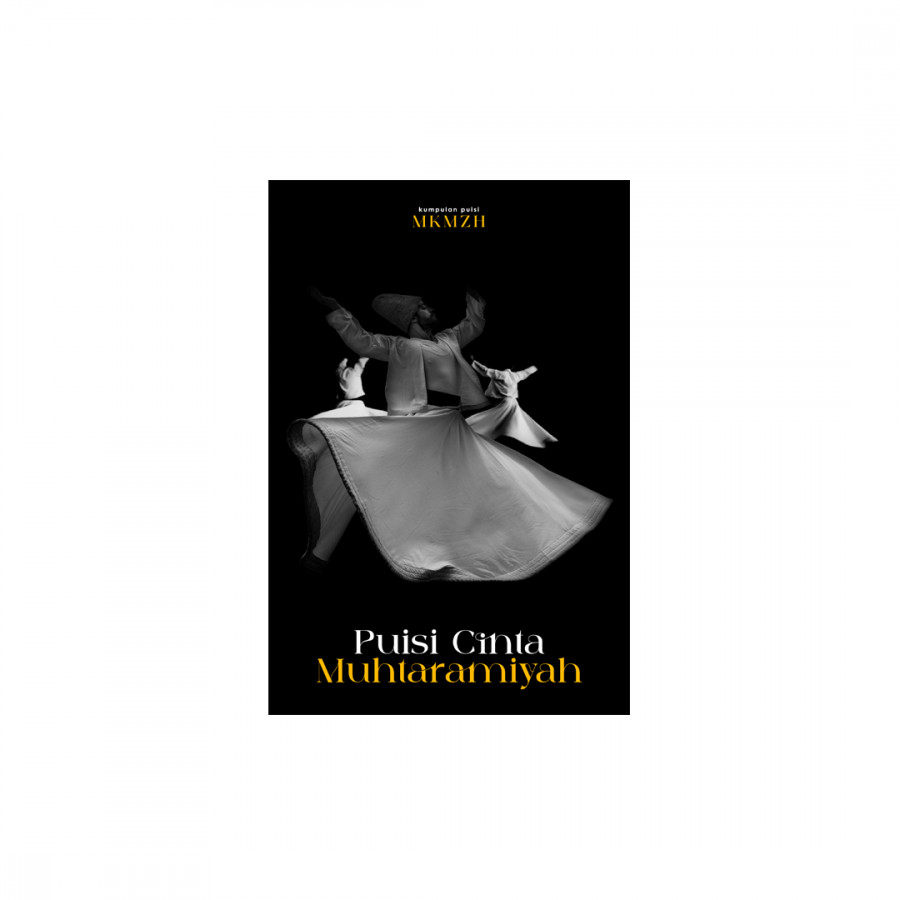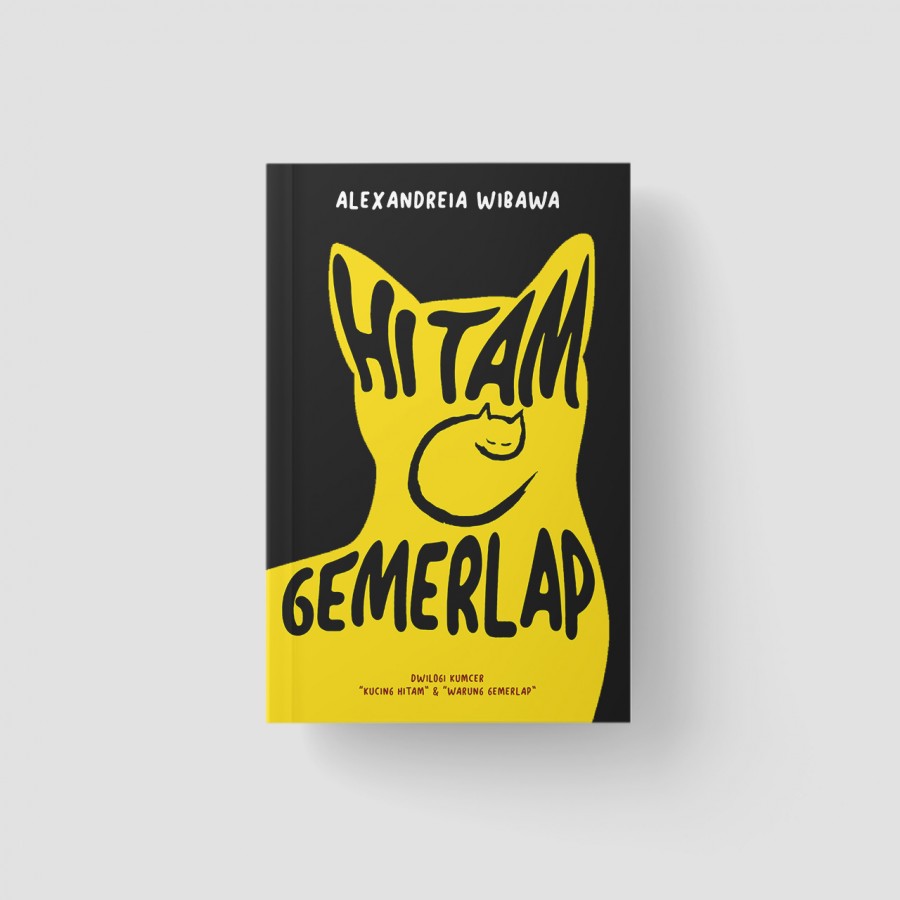Bagi Orang Ambon, merantau dari Tasikmalaya ke Bandung itu ibarat pelesir. Tapi bagi Mang Sanip, di usia dua belasan, sudah mandiri cari makan sendiri di Bandung itu sudah luar biasa. Meski merantaunya tidak mesti melintas lautan.
Medio tahun tujuh puluhan, Mang Sanip muda meninggalkan kampungnya di kaki Gunung Galunggung. Menenteng baju-bajunya dibuntal kain sarung, menumpang opelet menuju Bandung dengan penuh harapan. Tanpa keahlian, tanpa ijazah, tanpa koneksi bahkan membaca dan menulis saja sulit. Kecuali mengaji, itu lain perkara.
Berbagai profesi dijalani Mang Sanip. Dimulai jadi kuli angkut di terminal, tukang catut, kenek opelet, kerja di tauke pemilik toko hasil bumi, narik becak hingga mencoba berjualan. Nah, di antara semua pekerjaan yang pernah dijalani, nampaknya Mang Sanip berjodoh dengan profesi narik becak. Sisanya, terutama berdagang, hanya menemui kegagalan.
Memang kegagalan adalah jatah semua bangsa, semua orang, semua makhluk. Mau sahur tapi baru terjaga pas imsak, itu sebuah kegagalan di tingkat sederhana. Mau nembak gebetan yang cantiknya minta ampun tapi ternyata sudah beranak dua, itu juga kegagalan dalam kadar yang lebih signifikan.
Bagaimana profesi narik becak tidak menguntungkan? Lah, sepeda motor saja yang harganya beberapa ratus ribu tidak semudah sekarang untuk dimiliki, apalagi mobil pribadi. Angkot belum ada. Bemo pun trayeknya terbatas.
Mulanya Mang Sanip beroperasi di sekitar Jalan Kejaksaan, Braga, hingga Cihapit. Selain teduh oleh pohon-pohon besar, jalannya cenderung datar. Penumpangnya sebagian adalah orang tua yang masih fasih cas cis cus Holland Spreken. Mereka naik becak dari Jalan Marconi ke toko roti Het Snoephuis yang masih menjual melk brood, krenten brood, moorkoppen, kaastengel, kletskoppen hingga es krim home made macam moorkus, marasquino dan frambos. Jaraknya pendek tapi ongkosnya bisa tinggi.
Lewat profesi ini Mang Sanip bertemu jodohnya. Sang istri, Bi Teti, asal Gang Apandi. Gang di sebelah bekas Toko Buku Djawa, tepat di seberang toko legendaris Braga Permai atau Maison Bogerijen.
Narik becak uangnya lumayan kala itu. Seharian nyaris tak ada waktu berhenti. Turun satu, naik yang lain. Hingga becak dilarang di beberapa ruas utama kota, termasuk Braga. Mang Sanip pindah mangkal ke Kosambi. Tapi becak masih jaya hingga daerah bebas becak meluas ke Jalan Asia Afrika dan sekitarnya.
Nah, masa sulit pun dimulai. Kalau dulu tukang becak dicari penumpang, sekarang penumpang dicari tukang becak. Tempat ramai macam Terminal Leuwi Panjang jadi tempat pilihan untuk mangkal.
“Mangga, Pak, becana!” teriakan semacam itu lazim menyambut penumpang turun.
“Wios ku abdi kantongna dibantun!” walau tidak yakin sang penumpang akan naik becak atau tidak.
Selain pembatasan wilayah operasi dan tukang becak makin banyak, trayek angkot juga makin luas. Ongkosnya jauh lebih murah. Kaum Mang Sanip makin tersisih. Mang Sanip makin jarang pulang. Becaknya lebih sering jadi tempatnya tidur.
Pernah suatu ketika Bi Teti menyusulnya ke terminal. “Sudahlah, Pak, pulang,” begitu ajakan Bi Teti. “tidak usah diteruskan, uang bisa dicari di tempat lain. Ingat umur!” Tapi Mang Sanip tak bergeming. Narik becak sudah sangat mendarah daging, hingga akhirnya tak pernah pulang sama sekali.
Bi Teti atau anaknya sering ke terminal. Membujuknya pulang berulang kali. Bahkan anaknya menawari motor supaya jadi ojol. Mang Sanip tetap kokoh pada sikapnya.
Penumpang makin susut dilibas zaman, Mang Sanip makin uzur tapi tetap tak pulang-pulang. “Kalau Bapak tetap mau narik becak, bagaimana kalau becaknya pake motor?” suatu kali anaknya yang makin dewasa menawari begitu. “Bapak tidak usah ngegowes, atau bapak bisa narik sayur di Pasar Andir pake bentor,” Tapi Mang Sanip tetap bersikukuh narik becak meski di Terminal Leuwi Panjang sudah tak ada lagi orang naik becak.
Mang Sanip mangkal tak pulang-pulang dekat benteng di mulut gang pinggir terminal. Istrinya tak lagi menemuinya. Juga anaknya. Makan minum hanya dari pemberian tukang ojek atau supir angkot. Mandi di masjid kampung sebelah terminal. Tidurnya tetap di becak. Ojek online, bentor, angkot, dan taksi makin banyak lalu lalang. Hanya tinggal Mang Sanip setia jadi tukang becak seorang.
Suatu ketika lewat tengah malam. “Becak, Pak?” seseorang mengagetkan Mang Sanip. Akhirnya ia dapat penumpang!!!
“Mari, Pak, mau diantar ke mana?” pertanyaan lazim tukang becak kepada penumpang.
“Ke tempat yang saya tahu dan bapak tidak tahu,” suara berat penumpang itu menjawab.
“Jadi, biar saya di belakang dan bapak duduk di depan,” lanjut penumpang itu.
“Lah? Siapa kamu?” Tanya Mang Sanip sambil curiga dan waspada serta bersiap mendorong becak untuk kabur.
“Apakah kamu rampok atau malaikat maut?” lanjut Mang Sanip.
“Aku malaikat maut. Waktumu di dunia sudah habis. Aku menjemputmu pulang!” tegas penumpang itu pula.
Mang Sanip meski sudah tua, masih sigap mendorong becaknya dengan cepat lalu mengayuh becak secepat kilat menjauh. “Aku tidak mau mati sekarang!!! Aku belum dapat penumpang!!!”
Malaikat maut tak mengejar. Dia melongo. Entah terkejut atau bingung menghadapi orang macam Mang Sanip. Berdiri di keremangan lampu malam jalanan. Mematung diam.
Benteng pinggir terminal Leuwi Panjang. Lalu-lalang macam-macam orang dan kendaraan. Seorang tukang becak tertidur di becaknya. Tak ada satu pun orang menganggapnya.
Sehari, seminggu, bahkan berbulan-bulan. Becak dan pemiliknya tetap tak beranjak dari tempatnya. Mang Sanip, tertidur di becaknya siang dan malam. Mati tidak, bangun pun tidak.
Tatang Koswara, lahir di Garut pada tanggal 2 Februari 1973, bertempat tinggal di Bandung. Memperoleh pendidikan dasar di SDN Kiansantang, bersekolah menengah di SMPN 2 Garut dan SMAN 5 Bandung. Menyelesaikan studi Teknologi Kimia Tekstil pada Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil pada tahun 1993 dan memasuki Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Kristen Maranatha tahun 1993 hingga lima semester saja, tidak dituntaskan. Kini bekerja sebagai pengemudi, dan freelance bermain biola di Bandung. Menulis cerpen dan feature sejarah. Buku kumpulan cerpen terbarunya berjudul "Bragaweg Kala Meneer Hollandsche Berkuasa" yang diterbitkan oleh Langgam Pustaka.
*Cerpen ini dipilih dari buku kumpulan cerpen berjudul "Bragaweg Kala Meneer Hollandsche Berkuasa" karya Tatang Koswara. Dapatkan bukunya (di sini) untuk mendapatkan potongan harga.