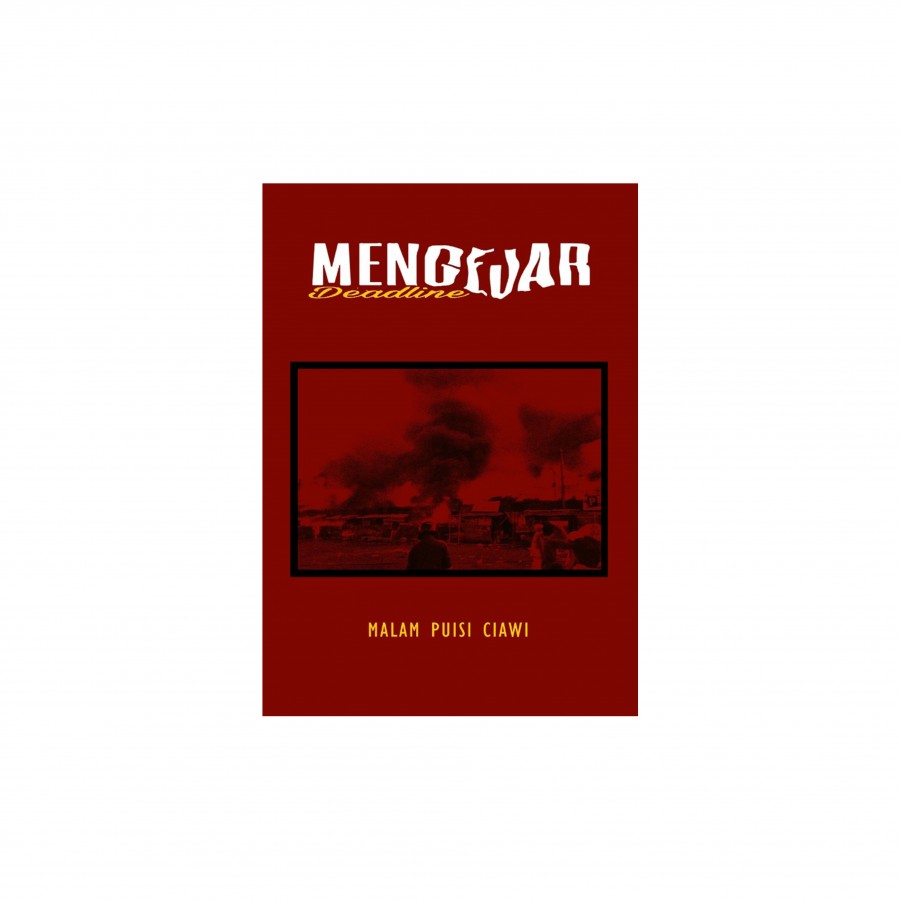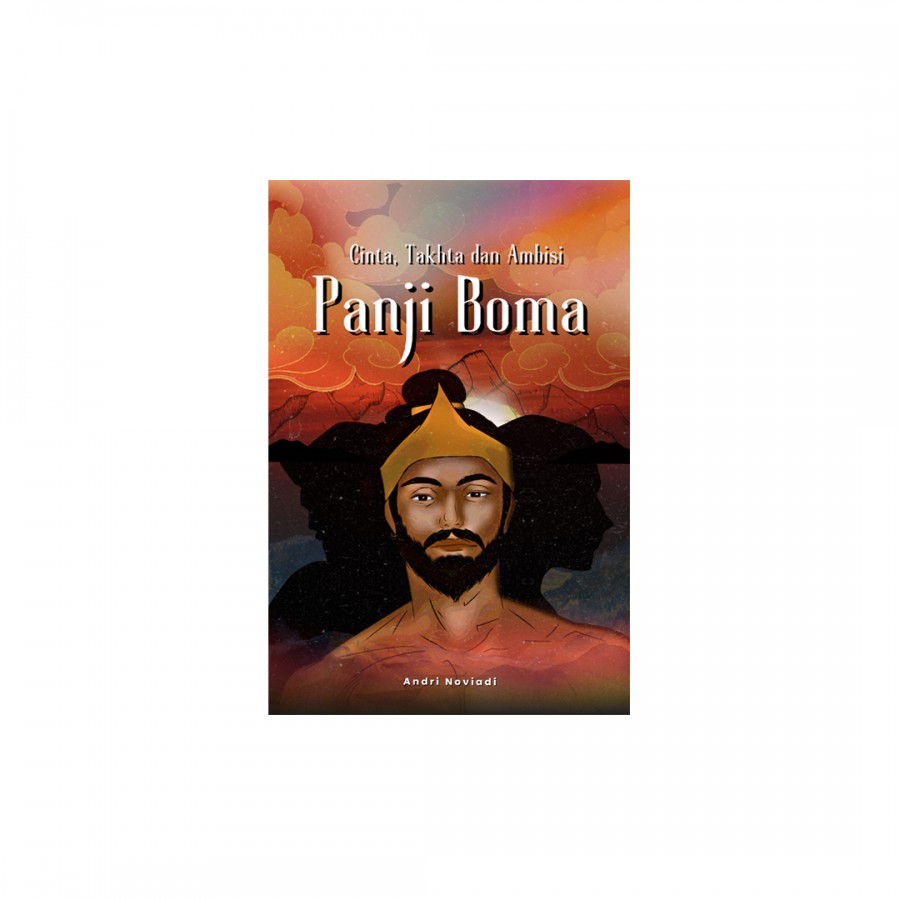Mata Bulan Melihat Apa?
Oleh Aprianus Defal Deriano Bagung
Sekarang bahagia sekali hatimu. Kau melihat anakmu sudah tumbuh besar. Terakhir kau mengecupnya ketika ia masih sangat belia. Ketika itu, anakmu masih belum apa-apa. Hanya tahu menangis sebagai cara bicara. Kadang-kadang tersenyum sementara matanya tetap terkatup. Lalu kau mengecup keningnya. Kau elus pipinya yang masih merah dengan sangat hati-hati. Kasih mengalir dari tanganmu menuju malaikat kecil yang kehadirannya membuat kau harus berpikir seribu kali untuk melanjutkan pekerjaanmu sebagai aktivis dan seniman yang kritis.
Sebenarnya sejak istrimu mengandung kau mulai was-was. Aktivis dan seniman yang kritis bisa dibilang sebagai profesi yang haram di era itu. Yang paling khawatir adalah istrimu. Apalagi mendengar kabar bahwa dari hari ke hari semakin banyak jumlah orang hilang. Meninggalkan istri, anak, keluarga, kekasih, dan banyak orang lagi.
“Kapan kau akan berhenti? Aku semakin takut kalau saja sewaktu-waktu suaramu tak kudengar lagi; kabarmu tak kutahu lagi” keluh istrimu suatu malam di bawah temaram bulan yang cahayanya menyusup ke dalam kamar melalui jendela yang gordennya sengaja tak ditutup.
“Mengapa kau berkata seperti itu? Sejak kapan kau mulai tidak mempercayaiku, sayang?” katamu sambil tersenyum ke arah bulan.
“Semakin banyak orang hilang dari hari ke hari. Kondisi sekarang sangat labil. Tidak stabil. Berhenti bertingkah seperti ini atau kau akan dianggap sebagai bagian dari sayap kiri nanti” istrimu bersikeras meminta agar engkau berhenti.
Sejenak lengang. Tidak ada suara. Sepi hanya pecah oleh hembusan nafas sepasang manusia. Kau menoleh ke arah istrimu yang sedari tadi menyandarkan kepala di pundak kananmu. Kau menatapnya dalam-dalam. Membaca resah yang diisyaratkan matanya; memahami ketakutan yang disuarakannya.
“Dasar sarjana hukum. Kata-katamu cantik. Cantik sekali” katamu dengan nada rayu.
Mendengar itu, istrimu menarik nafas dalam-dalam lalu mengembusnya pelan, seperti mengisyaratkan pasrah yang dalam. Selanjutnya ia mengalihkan pandangannya ke jendela, ke bulan yang samar-samar itu. Malam semakin larut. Satu per satu kata-kata mulai beristirahat. Akhirnya tidak ada lagi pembicaraan. Hening bertakhta penuh. Kau melihat istrimu pulas lebih awal.
Hari-hari menjelang persalinannya, istrimu lebih banyak meringis. Bercerita kalau sebentar lagi ia akan mempertaruhkan hidupnya demi kehidupan manusia baru. Istrimu yang adalah alumnus perguruan tinggi negeri, fakultas ilmu sosial dan politik, program studi Hukum itu sepertinya sudah siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi di hari persalinannya nanti.
Berkali-kali kau berdecak kagum sembari menggeleng-gelengkan kepala melihat istrimu yang begitu gigih dalam menyelesaikan segala masalah yang ia hadapi. Kau merasa menjadi aktivis sekaligus seniman paling beruntung karena berhasil menikahi perempuan yang tegar kekal; panjang sabar; sayangnya lapang.
***
Malam ini, sebagaimana rutinitasmu bersama beberapa aktivis dan seniman lainnya ketika akhir pekan, kau berangkat dalam diam menuju markas diskusi para aktivis dan seniman. Tentu saja kau berangkat setelah sebelumnya mendapat nasehat yang luar biasa banyaknya dari istrimu. Tampaknya kau adalah lelaki yang sangat menghargai dan menyayangi istrimu. Sebelum melakukan apapun, kau pasti selalu meminta izin dan memohon restu dari sang istri.
Tiba di markas, kau melihat Wiji sedari tadi duduk sambil berkutat dengan buku yang dibacanya di bawah remang cahaya lampu. Kau lihat Wiji tampak serius membaca buku yang tengah dipegangnya. Sama sekali Wiji tidak menyadari kehadiranmu. Hal itu membuatmu berjalan ke arahnya.
“Hei, seniman Tongos” katamu sambil terus berjalan mendekat. Wiji yang sedari tadi khusyuk membaca spontan langsung melihat ke arahmu. Ia tersenyum dan menutup buku yang tengah ia baca.
“Sejak kapan kau di sini, Yadin?” ungkap Wiji membalas sapaanmu dengan tanya.
“Sejak kau kabur karena takut dengan Tim Mawar beberapa hari lalu. Hahahaha…” kau membalas Wiji sambil tertawa.
“Ahhhhh, dasar Yadin Muhidin. Aktivis tukang sindir yang sialan! Hahahahah…”
“Apa yang perlu kita bahas malam ini, seniman Tongos?” kau bertanya pada Wiji dengan nada suara yang sengaja dikecilkan karena takut akan keberadaan mata-mata pemerintah.
“Yang pasti kita membahas hal penting dan menyangkut orang banyak”
“Ada begitu banyak hal penting di negara ini. Hal penting mana yang kita bicarakan malam ini?”
“Apa yang lebih penting dari mencari cara agar benar-benar bebas merdeka? Tidak dipimpin oleh pemimpin otoriter; pemimpin korup yang menumbuhsuburkan praktik KKN” kata Wiji menjawab pertanyaanmu penuh semangat.
Spontan kau menoleh ke arah kanan. Kau melihat seorang pemuda tengah duduk sendiri sambil memperhatikan pembicaraanmu dengan Wiji. Lantas kau langsung memanggilnya dan menyuruhnya.
“Hambali, instruksikan teman-teman di belakang dan yang ada di luar markas untuk segera masuk. Kita akan segera memulai diskusi malam ini” katamu dengan nada memerintah.
Tanpa sempat mengucapkan sepatah kata pun, pemuda bernama Hendra Hambali itu langsung berjalan ke arah pintu masuk markas. Ia sigap memanggil beberapa aktivis di luar markas untuk segera masuk. Setelahnya ia berjalan ke arah belakang markas. Menyampaikan bahwa diskusi akan segera dimulai. Mendadak, ruangan berukuran sedang itu langsung dipenuhi oleh beberapa pria. Hambali adalah yang paling terakhir mengambil tempat dalam ruangan sebab harus memastikan semua aktivis lain sudah masuk ke dalam markas.
Wiji duduk tak jauh dari pojok sebelah kanan ruangan. Di dekat cahaya lampu. Tepat di sebelahnya, kau duduk sambil memegang pena dan buku kecil bak catatan harian. Sesekali kau mengarahkan penamu pada kertas di hadapanmu. Wiji memulai diskusi dengan terlebih dahulu membacakan beberapa agenda diskusi.
Diskusi berlangsung alot. Argumentasi tumpah ruah dari banyak kepala yang hadir. Sesekali kau berdiri dan menyampaikan argumen yang kau rasa perlu. Tak jarang juga kau kelihatan serius mengarahkan penamu, menulis entah apa, dan membolak-balikkan kertas dalam buku yang ada di hadapanmu.
Setelah sekitar dua jam lebih, diskusi sepertinya akan selesai. Akan berakhir beberapa menit lagi. Masing-masing orang sibuk dengan catatan kecil dan urusan-urusan lainnya di tempat mereka duduk. Ada yang merapikan sweater yang dikenakan. Ada yang sibuk memasukkan catatan kecil ke dalam tas mini yang digantung di pundak. Beberapa lainnya tengah berbincang kecil-kecilan, entah membicarakan apa.
“Ingat! Harus tetap waspada. Mata pemerintah ada di mana-mana dan melihat apa pun yang dilakukan oleh siapa pun. Tim Mawar semakin brutal dalam menjalankan aksinya. Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Al Katiri, dan Ismail sampai hari ini belum diketahui keberadaannya sejak 1997, tahun lalu. Kemungkinan besar mereka berhasil diculik dan dihilangkan oleh Tim Mawar. Berhati-hatilah!” pesan Wiji sebelum akhirnya diskusi benar-benar selesai.
Satu per satu mereka meninggalkan markas sederhana itu. Kau masih duduk di tempatmu sementara Wiji kelihatan sibuk membereskan catatan dan hendak beranjak dari tempat duduknya.
“Aku mencemaskan keselamatanmu, seniman Tongos” kau memulai percakapan.
“Bukan waktunya untuk membicarakan hal itu. Selagi kita berhati-hati, kita aman; kita selamat. Kita harus berhasil menjadi seperti batu karang yang dalam keadaan apapun selalu bersedia memecahkan badai yang datang” Wiji berbicara sambil berjalan meninggalkanmu di tempat dudukmu.
***
Tahun 1998 adalah tahun yang cukup parah dalam kepemimpinan orde baru. Aksi-aksi masyarakat mulai dilakukan terang-terangan. Krisis ekonomi yang melanda negara membuat masyarakat mulai tidak percaya lagi dengan segala program yang dicanangkan bapak pembangunan. Di sana-sini ada aksi demonstrasi menuntut banyak hal. Tokoh-tokoh kunci yang menginisiasi aksi demonstrasi satu per satu ditangkap. Disekap entah di mana dan akhirnya tidak pulang sampai hari ini.
Sejak diskusi terakhir yang diadakan pada Maret 1998, kau jadi lebih sering mengadakan pertemuan diam-diam dengan Wiji Thukul. Biasanya menjelang matahari hadir di timur, kau dan Wiji menyusup menembus gelap malam. Mengadakan perbincangan empat mata di lorong-lorong kota yang dirasa aman dari operasi Tim Mawar.
Kau jadi sering meninggalkan rumah. Meninggalkan istri dan anakmu tanpa terlebih dahulu berpamitan. Kadang, ketika hari masih belia, kau pulang ke rumah. Istrimu menyambut dengan pelukan erat yang mengisyaratkan kekhawatiran akan keselamatanmu. Selanjutnya kau, istri dan anakmu duduk melingkar di meja makan. Sarapan pagi sambil bererita banyak hal. Kau dan istrimu bersikap seolah semua baik-baik saja. Ketika itu anakmu sudak berusia sekitar tiga tahun. Ia tumbuh menjadi perempuan kecil yang pandai berbicara.
“Ayah, tadi malam mata bulan melihat ayah” anakmu memulai percakapan di ruang makan.
“Ohh ya?? Siapa yang mengatakan itu kepadamu, cantik?” kau berbicara sambil mengelus-elus rambut si perempuan kecil itu.
“Ibu bilang begitu, ayah” balasnya
Kau tersenyum ke arah istrimu tanpa mengucapkan apa-apa. Istrimu membalas senyumanmu dan berkata bahwa Nisa, anak semata wayangmu itu, akhir-akhir ini suka bercerita tentang bulan yang dilihatnya melalui jendela kamar. Setiap sebelum tidur, ia akan bertanya “mata bulan melihat apa malam ini, bu?” Lalu istrimu menjawab seperti sedang berdongeng. Ia mendadak menjelma pendongeng yang seolah banyak tahu soal bulan. Anakmu hanya akan terlelap setelah tahu malam itu mata bulan melihat apa.
April 1998 kabar Wiji sudah tak kau ketahui lagi. Surat-surat yang kau kirim melalui orang yang merahasiakan keberadaan Wiji sudah tak jelas lagi nasibnya. Ada sekitar tiga surat yang sudah kau serahkan kepada jembatan rahasia yang selalu menghubungkanmu dengan Wiji. Persisnya, surat-surat itu belum ada yang dibalas satu pun sementara kau sudah siapkan lima surat lain yang kau rencanakan untuk dikirim kepada Wiji. Bukan Wiji saja, si Tukang antar surat itu juga tidak tampak lagi batang hidungnya. Tidak diketahui lagi nasibnya. Pikiranmu semakin tak tenang.
Hingga awal Mei 1998, masih belum juga ada surat balasan dari Wiji. Kau bingung harus berbuat apa. Kau bingung harus mengirim ke mana surat-surat yang kau tulis yang jumlahnya sudah sekitar belasan surat. Kau tak tahu kalau Wiji tengah melarikan diri dan berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya.
“Ayah, malam ini mata bulan melihat apa?” tanya putrimu suatu malam, ketika kau menemaninya tidur.
Malam itu, 12 Mei 1998, untuk pertama kalinya kau ditanyakan seperti itu oleh anakmu sebab malam-malam sebelumnya kau jarang di rumah. Sekalipun kau pulang, anakmu pasti sudah pulas terlebih dahulu. Istrimu tersenyum. Berharap kau menceritakan suatu dongeng yang tidak saja untuk si buah hati, tetapi juga untuk dirinya.
“Sayang, malam ini mata bulan melihat dua perempuan cantik. Perempuan-perempuan itu adalah nafas ayah. Bulan terlalu polos untuk tidak menerobos jendela kamar demi melihat dua perempuan cantik itu. Kadang-kadang bulan malu sendiri ketika tahu ada yang lebih cantik darinya…” entah apa kata terakhir yang kau ceritakan malam itu. Tetapi yang pasti, kau berhasil membuat istri dan anakmu tertidur pulas. Bahkan kau berhasil meninabobokan dirimu sendiri setelah mendongeng panjang lebar soal mata bulan.
Dua hari setelahnya, kau meninggalkan rumah. Berpamitan kepada istrimu tetapi tidak kepada anakmu. Sejak itu, sejak kerusuhan pada 14 Mei 1998, kau tak lagi pulang ke rumah. Istrimu sangat mengkhawatirkan keselamatanmu. Ketika Mei sudah tiba di hari ke delapan belas dan kau belum juga pulang, istrimu semakin khawatir dan semakin sering menangis sendiri.
Sehari sebelum tumbangnya kekuasaan orde baru, istrimu kembali ke Jakarta setelah sebelumnya berangakat ke Surabaya untuk menitipkan Nisa pada Kakek dan Nenek. Tepat pada 21 Mei 1998, salah satu dari sekian banyak orang yang menduduki atap Gedung MPR adalah istrimu. Ia berkoar-koar menyuarakan keadilan menuntut agar suaminya dipulangkan sementara ia sendiri juga tak tahu di mana dan apa yang terjadi dengan suaminya.
Sementara di Surabaya, Nisa kesulitan untuk tidur. Dongeng yang dikisahkan nenek bukan dongeng prihal mata bulan. Dari sudut kamar, kau menyaksikan putrimu berusaha tidur. Di kepalanya masih menyala tanya soal mata bulan melihat apa malam ini. Kau berjalan mendekat. Merebahkan badan di sebelah Nisa.
“Malam ini mata bulan melihat ibu, sayang. Ibu sedang berjuang di tanah abang. Malam ini mata bulan melihat cantikmu. Bulan lagi-lagi malu, sayang. Kau jauh lebih cantik darinya” katamu sambil tersenyum ke arah putrimu. Tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaanmu. Nisa dan Nenek masih membicarakan hal lain. Kau sulit menerima kenyataan bahwa kau sudah di alam lain. Entah di Surga atau di Neraka, kami juga tidak tahu.
Jakarta di tahun 1998 menjelma kota yang angker. Jakarta adalah saksi bisu hilangnya banyak orang-orang baik yang hari ini seolah sengaja dilupakan negara. Nasibmu, Wiji Thukul dan banyak orang lainnya belum diketahui jelas hingga hari ini. Tidak ada yang tahu apakah kamu masih bernafas atau justru hanya sisa tulang saja.
*Penulis akrab disapa Apri Bagung. Gemar membaca dan menulis puisi, cerpen, dan essai. Buku pertamanya berjudul Kemeja Kenangan (kumpulan Puisi). Sekarang tengah merampungkan naskah antologi cerpen dan naskah novel di sela-sela kesibukkan kuliah. Instagram @defalderiano_ )