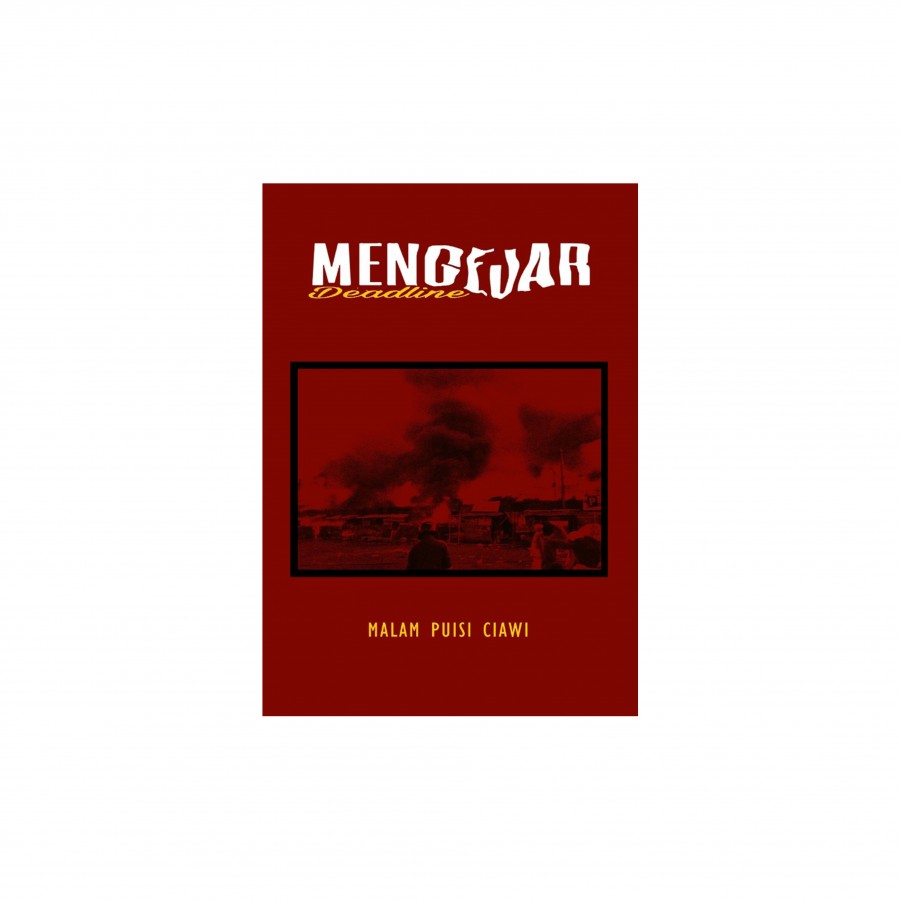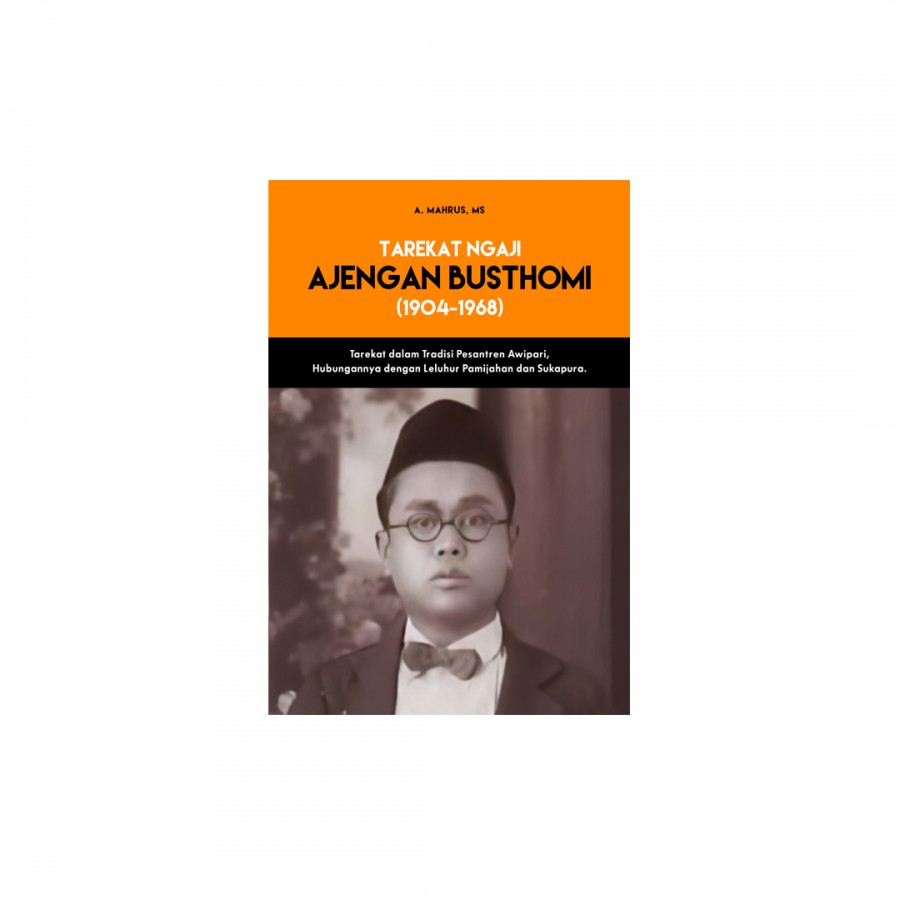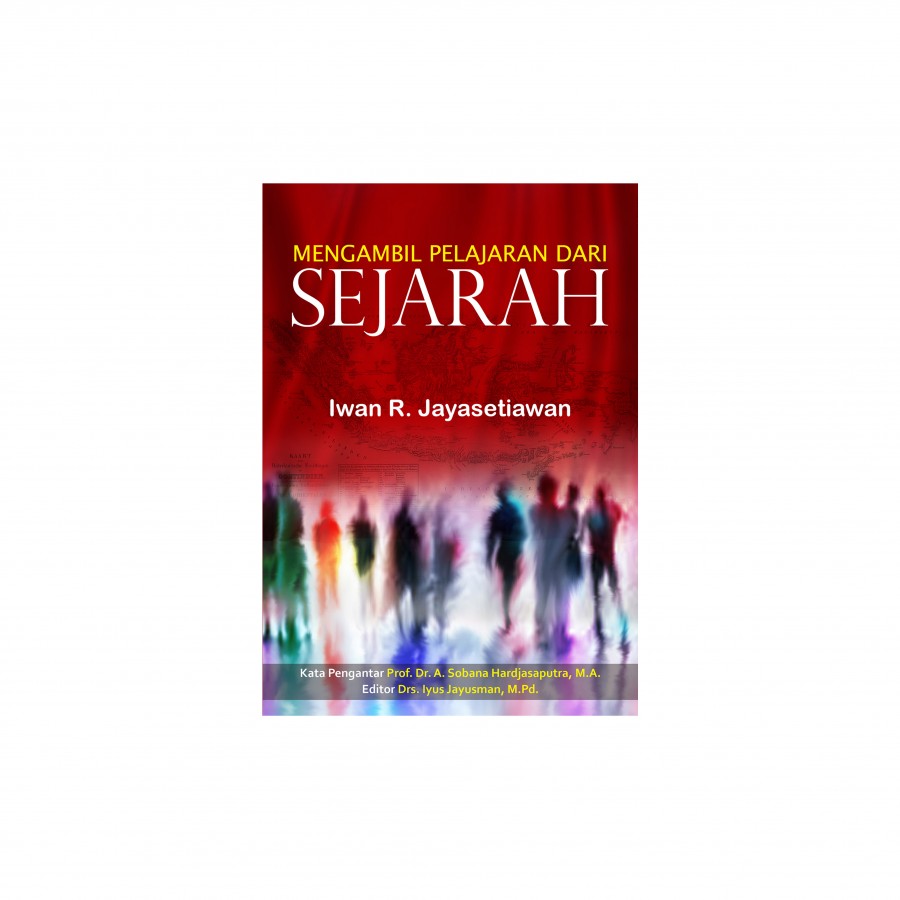“Seorang wanita berusia 21 tahun ditemukan tewas di Klinik X tempatnya bekerja. Tidak ada tanda-tanda pembunuhan ataupun bunuh diri. Pihak Rumah Sakit belum memberikan keterangan mengenai penyebab kematiannya hingga kini.”
*
Aku mengunci diri di kamar sambil terisak. Nenek menamparku dan memaki kalau aku adalah pembawa sial. Aku sayang sama kakek, tidak mungkin aku penyebab kematian kakek.
“Dhani, ayo ikut Kakek memancing ikan!” kalimat itu selalu membawa kebahagiaan buatku. Aku yang saat itu berumur 9 tahun senang sekali jika kakek mengajakku memancing. Kakek akan membawaku dengan mobil Jeep Katana miliknya, menuju ke kolam pemancingan. Aku membayangkan bisa bermain di sekitar situ, menjala udang kecil untuk digoreng dengan adonan tepung terigu menjadi peyek. Tugasku memasang cacing pada mata kali dan melepaskan ikan yang ditangkap kakek untuk kemudian memasukkannya ke dalam keranjang anyaman.
Semua itu tinggal kenangan indah buatku sekaligus menorehkan kepedihan. Dua hari yang lalu kakek meninggal. Tanpa sebab, tanpa didera sakit, tidak kecelakaan atau apa pun yang menyebabkan kematian. Kakek hanya... meninggal begitu saja. Kata dokter karena serangan jantung. Padahal kakek adalah manusia tersehat di keluargaku. Entahlah, pada akhirnya serangan jantung adalah alasan yang paling masuk akal. Dokter brengsek! Saat kuliah dia pasti mahasiswa terbodoh. Setiap ujian pasti dia nyontek. Ijazahnya pasti beli. Aku memaki dengan air mata yang tak henti meleleh di pipi. Tapi dalam lubuk hatiku merasakan kematian kakek tidak ada hubungannya dengan dokter yang bodoh. Aku hanya perlu seseorang untuk disalahkan.
Aku tahu penyebabnya, karena seminggu yang lalu aku melihatnya. Seorang wanita berbaju biru di atas atap gedung sekolah yang kalap melempar-lemparkan laptop, tas, dan handphone-nya ke bawah, lalu ia menangis sesegukkan. Aku tahu hanya aku yang bisa melihat wanita itu, karena ini bukan hal pertama. Jadi aku tidak pernah melaporkannya kepada guru atau memberitahukan teman-temanku.
“Gara-gara kamu!” nenek berkata tajam sambil menyusut air matanya.
“Seharusnya kamu ikut mati dengan kedua orang tuamu. Bahkan mereka juga mati karena kamu! Anak pembawa sial! Seharusnya sejak lahir, kubuta-kan matamu itu!” nenek menjerit-jerit histeris. Sampai kemudian ia menamparku. Nenek dilerai oleh beberapa tamu yang datang melayat. Aku berlari ke kamar. Pipiku merah. Hatiku berdarah.
*
Entah apa istilahnya. Orang mati, arwah penasaran atau makhluk astral, umurku enam tahun ketika pertama bertemu dengan mereka. Tepatnya melihat mereka.
Aku sedang memasukkan sepeda ke garasi, sepulang bermain boneka dari rumah Tantri, sahabatku. Dia seperti sedang menatapku di pojok garasi. Seorang anak laki-laki, usianya sedikit lebih tua dariku. Anak yang berpakaian aneh, seperti pulang dari sunatan. Ia mengenakan celana pangsi dan kain yang dililit. Anak itu juga mengenakan ikat kepala seperti mau pentas pencak silat.
Merasa heran, aku bertanya padanya “Ngapain kamu ada di garasiku?” Dia diam saja. “Kamu anak daerah sini? Rumah kamu di mana?”
Dia sama sekali tidak menjawab. Entah karena tidak melihatku atau tidak mengerti bahasaku, atau mungkin dia buta. Yang jelas dia tidak bereaksi terhadap perkataanku.
“Pulang sana. Sudah sore. Nanti mamamu marah, seperti mamaku kalau aku pulang kesorean.” Lalu aku bergegas masuk ke rumah melalui pintu yang menghubungkan garasi dengan dapur. Saat aku menoleh ke pojok ruang garasi, anak itu tidak ada.
Aku menceritakan kejadian itu kepada Mama, dan ia hanya berkata kalau itu teman khayalanku. Selang enam bulan sejak kejadian itu, orang tuaku meninggal karena kecelakaan di jalur tanjakan menuju ke luar kota. Mobil mereka terhimpit truk yang mundur tak terkendali, terseret masuk ke jurang.
Setelah lulus SMP aku baru mengerti maksud dari teman khayal. Namun aku semakin yakin kalau teman khayal dan anak yang aku temui di sudut garasi waktu itu adalah hal yang berbeda.
*
Setelah kematian kakek, nenek membawaku ke rumah seseorang. Aku diberikan begitu saja seperti memberikan bungkusan barang. Kalimat terakhir dari nenek padaku adalah, “Aku menyesal tidak segera membawamu ke sini, sejak awal. Sejak adik bayimu meninggal. Mungkin dengan menjauhkanmu dari keluarga kita, semua orang akan selamat!”
Nenek pergi. Aku menatap wanita tua pemilik rumah itu yang tersenyum padaku. “Dhani, ayo masuk. Akan aku tunjukkan kamarmu. Mulai sekarang kau akan tinggal bersamaku. Panggil aku Nenek Uti.”
Dalam kebingungan, aku yang berusia 12 tahun merasakan mataku panas dan air mata menggenang di pelupuknya. Ratusan pertanyaan ingin kuutarakan entah kepada siapa. Mungkin pada wanita yang minta dipanggil Nenek Uti. Tapi itu nanti. Aku punya banyak waktu, rasanya selama umur hidupku.
*
Sejak lulus SMK 3 tahun yang lalu, aku diterima kerja di klinik mata milik Dokter Ramdan Sp.M. sebagai karyawan di bagian administrasi. Namun pekerjaanku lebih sering mengurus komputer dan program sesuai bidang pendidikanku di SMK. Selain aku, ada Tita di bagian pendaftaran, Ismi asisten dokter, Bu Dewi seniorku di bagian administrasi, dan Mella yang membantu Pak Azis yang adalah apoteker, yang bekerja di klinik ini. Hampir semua pegawai wanita di sini mengidolakan Dokter Ramdan, bahkan Bu Dewi. Dokter Ramdan seorang yang perhatian tidak hanya kepada pasien tapi kepada kami, ditambah pula tampangnya yang bagaikan ‘vitamin mata’ itu, aku mengakui. Sebagian besar pasien bahkan sudah sembuh penyakitnya tanpa diperiksa dan minum obat hanya dengan bertemu Pak Dokter Ganteng. Beberapa di antara para karyawan di sini bahkan terang-terangan bersaing mengambil hati Dokter berusia 34 tahun dan masih lajang itu.
Dokter Ramdan menggunakan rumah warisan keluarganya yang bergaya arsitektur zaman kolonial Belanda ini sebagai tempat praktik sekaligus apotek. Rumah yang lumayan besar dan antik, nuansa seram kadang muncul jika aku menatap sekeliling. Teringat penampakan sosok-sosok yang sejak kecil kutemui di sudut-sudut tak terduga di suatu tempat. Namun sudah lama aku tidak lagi melihat mereka. Beberapa kali sejak aku tinggal bersama Nenek Uti, aku menanyakan hal itu. Penglihatanku, kenapa selalu diiringi meninggalnya orang-orang, dan kapan bencana ini berakhir. Namun Nenek Uti selalu punya cara untuk mengalihkan topik pembahasan. Seperti sengaja tidak ingin aku tahu kebenarannya. Aku hanya bisa mengira-ngira jawaban sendiri tentang semua ini.
Terakhir kali aku melihat penampakan adalah sebulan sebelum nenekku meninggal, ya, nenek yang jahat itu. Ketika itu aku kelas 2 SMK. Cukup lama jeda sejak aku melihat wanita berbaju biru di atap gedung sekolah yang kemudian menyebabkan kakekku meninggal. Aku melihat seorang pria muda, mungkin sebayaku, berjalan melintas di kamarku dan menembus tembok keluar kamar. Jantungku berdetak kencang, siapa yang akan meninggal? Saat itu kupikir setiap kali melihat sebuah penampakan, seorang yang kusayangi akan meninggal. Aku benar-benar takut Nenek Uti-lah yang akan pergi. Aku tidak mau kembali tinggal dengan nenek kandungku yang tampaknya tidak menyayangi aku. Namun tampaknya orang yang meninggal sejak saat itu adalah mereka yang tidak kusukai. Entah kenapa aku senang karena neneklah yang meninggal.
“Dhani!” Tita berdiri di samping mejaku, mengusik lamunanku, “Sudah berapa kali aku bilang, ada yang salah dengan program komputer di meja resepsionis. Belum juga kamu perbaiki?” Tita membanting mug di mejaku dengan kesal.
Aku menatap gadis itu. Mahluk beringas yang tidak beda jauh dengan Mella. Selalu saja mengganggu hidup tenangku. Mella bahkan pernah dengan sengaja menumpahkan minuman jeruk ke atas pakaianku. Mereka menganggap aku juga sebagai saingan mereka dalam persaingan meraih hati Dokter Ramdan hanya karena aku pernah diajak makan malam oleh "Dokter Idola" itu. Kelakuan mereka sungguh lebay, mungkin meniru tokoh antagonis di sinetron yang menjadi tontonan racun mereka.
“Pokoknya malam ini kamu harus memperbaiki komputer depan.” Tita melengos setelah melemparkan lirikan kejinya.
*
Pukul setengah 10 malam. Aku menatap jam bundar besar di ruang depan. Aku menyandarkan punggung dan menghela napas. Tinggal sedikit lagi. Aku mengutak-atik komputer di meja resepsionis. Sudah loading. Setelah selesai, aku bisa pulang.
Aku beranjak untuk mengambil minum ke ruang belakang. Klinik ini sungguh bertambah seram jika sudah tidak ada siapa-siapa. Langit-langit yang tinggi, beberapa pilar, jendela-jendela serta pintu yang besar dan sebuah tangga menuju lantai dua yang selalu kuhindari karena mirip tangga di film horor. Memang masih ada Pak Teddy, satpam yang berjaga di pos di halaman, tapi di dalam rumah besar ini, aku sendirian. Malam ini perjalanan bolak-balik dari ruang depan ke ruang belakang terasa sangat jauh, melewati beberapa ruangan dan pintu melalui lorong dan sebuah taman kecil di tengah rumah.
Dokter Ramdan sedang keluar kota sejak kemarin menghadiri seminar. Entah kenapa, tiba-tiba aku tersenyum saat membayangkan Dokter Ramdan. Pria bertubuh tegap tinggi, berkacamata, selalu tampil rapi, berwajah agak oriental dengan senyum yang khas. Sebenarnya aku malu mengakui ini, tapi aku juga menyukainya, hanya saja aku tidak bisa melakukan hal sebagaimana Tita dan Mella yang terang-terangan menunjukkan rasa suka mereka di hadapan Dokter Ramdan karena aku terlalu introvert.
PRANG! Aku menjatuhkan mug air minum yang kubawa dari ruang belakang. Tubuhku gemetaran, kedua telapak tanganku terasa dingin dan aku yakin wajahku sepucat kertas. Saat kembali mengambil air, di ujung tangga menuju ke ruang periksa, aku melihat sesosok pria asing berpakaian tentara, lengkap dengan topi kompeni dan senjata yang terselempang di punggungnya. Ia berdiri tegap seolah sedang berjaga di depan pintu besar yang terletak di bawah tangga. Seorang tentara Belanda!
Aku ingin berlari tapi kakiku terasa lumpuh. Sosok itu bergeming. Air mata mengalir dari ujung mataku. Tidak mungkin, setelah sekian lama, kenapa aku melihat mereka lagi. Siapa yang akan meninggal. Aku tidak mau seseorang yang aku sayangi. Sekelebat wajah Dokter Ramdan melintas di kepalaku. Tidak! Jangan Dokter Ramdan! Orang yang kubenci yang harusnya meninggal. Ingatan akan nenekku melintas di kepalaku. Wajah-wajah mereka yang selalu menjahatiku berputar-putar. Kemudian wajah kedua orang tuaku, kakek dan nenek. Nenek Uti. Semua berkelebat.
“AAAAAAAARGHHHHH !!” aku menjerit sekuatnya, menjadi histeris dan menjerit-jerit seperti orang gila. Aku merasakan tubuhku terkulai lalu semuanya menjadi gelap.
*
“Terima kasih sudah bersedia datang ke sini, Dok.” Kata Nenek Uti, “Jika bukan karena membaca diary Dhani, aku juga segan mengganggu waktumu yang sibuk. Dhani sangat sering menulis tentang Dokter dalam bukunya.”
“Tidak apa-apa, Nek. Sungguh. Saya merasa punya tanggung jawab terhadap karyawan saya. Sekiranya ada yang bisa saya bantu...”
“Dhani datang ke rumah ini saat ia berusia 12 tahun.” Nenek Uti memotong kalimat Dokter Ramdan, “Di usianya yang masih sangat muda ia sudah kehilangan hampir seluruh anggota keluarganya. Dimulai dari adik bayinya yang berusia satu tahun. Lalu kedua orang tua, kakek dan neneknya...”
“Kenapa bisa terjadi hal yang mengerikan itu? Kecelakaan? Sakit?” Dokter Ramdan tampak amat bersimpati.
“Kutukan masa lalu.”
“M..maksudnya?”
“Dhani memiliki mata kila-kila. Pada setiap generasi di keluarganya ada satu keturunan yang memiliki mata itu. Aku mengetahui hal ini dari cerita suamiku yang adalah sepupu kakeknya Dhani. Nenek moyang keluarga Wangsareja ratusan tahun silam entah bagaimana aku tidak paham, pernah melakukan ritual yang membuat seseorang bisa berhubungan dengan dunia paralel.”
Dokter Ramdan bersandar dengan wajah tegang dan setengah tidak percaya dengan kisah itu. Sepanjang yang diketahuinya, itupun dari wikipedia, dunia pararel dipercayai sebagai sebuah dunia yang berjalan sejajar dengan dunia realita di mana kita berada. Di samping kehidupan yang kita kenal dan jalani saat ini, ada satu atau lebih kehidupan lain di suatu tempat dan berjalan secara bersamaan dengan dunia kita.
“Sejak saat itu keturunan Wangsareja seolah mendapat kutukan.” Lanjut Nenek Uti, “Dalam setiap generasi ada satu keluarga yang mewarisi mata kila-kila. Ia bisa melihat sosok dari dunia paralel. Benar, yang dilihat oleh Dhani selama ini bukan hantu atau penampakan. Sosok-sosok itu adalah mereka yang berada di dunia pada suatu tempat yang lain, yang dapat terlihat oleh Dhani menembus ruang dan waktu. Dhani pernah bercerita bahwa pertama kali ia melihat sosok-sosok itu adalah ketika berusia enam tahun di garasi rumahnya. Sebenarnya kemampuan itu muncul saat berusia empat tahun, namun Dhani tidak mengingat penglihatan pertamanya. Dan setelah itu adik bayinya meninggal tanpa sebab.”
“Maaf, Nek. Mengapa harus ada yang meninggal setiap ada penglihatan? Apakah itu semacam....” Dokter Ramdan ragu mengatakannya.
“Tumbal?” Nenek Uti seperti bisa membaca pikiran. Dokter Ramdan mengangguk.
“Bukan.” Nenek Uti menggeleng, “Ini bukan pesugihan. Aku belum sempat menceritakan semua ini pada Dhani. Aku tidak sanggup mengatakan hal yang sebenarnya padanya. Dia akan terus menyalahkan diri sebagai anak sial. Aku tidak tega. Jadi, Dhani tidak pernah mengetahui hal ini hingga akhir. Ini kutukan seperti yang kukatakan di awal. Kematian satu keluarga yang memiliki anak dengan mata kila-kila itu sendiri adalah kutukannya. Jika ingin dikaitkan dengan logika, mungkin untuk keseimbangan alam semesta, entahlah. Yang pasti sejak tahu cerita itu aku jujur, aku takut untuk punya anak. Dan ternyata anak mata kila-kila itu lahir dari keluarga sepupu suamiku.”
“Jadi...maksudnya....jika keluarga memiliki mata kila-kila...” Dokter Ramdan terbata.
“Seluruh keluarga itu akan habis. Semuanya meninggal tak tersisa, yang terakhir adalah si pemilik mata kila-kila.”
*
Pemakaman sudah sepi dari orang-orang yang mengantar. Sebuah papan nisan tertancap di kuburan yang baru bertuliskan :
|
WARDHANI PUTRI WANGSAREJA Lahir: 29 Februari 1998 Wafat: 12 Maret 2019
|
Alexandreia Wibawa, penulis novel ”Supata Sangkuriang” yang lahir di Kota Tasikmalaya pada hari Jumat, 12 Agustus. Suka melukis dan menggambar, karyanya dipajang di akun Instagram @kuya_ijo.