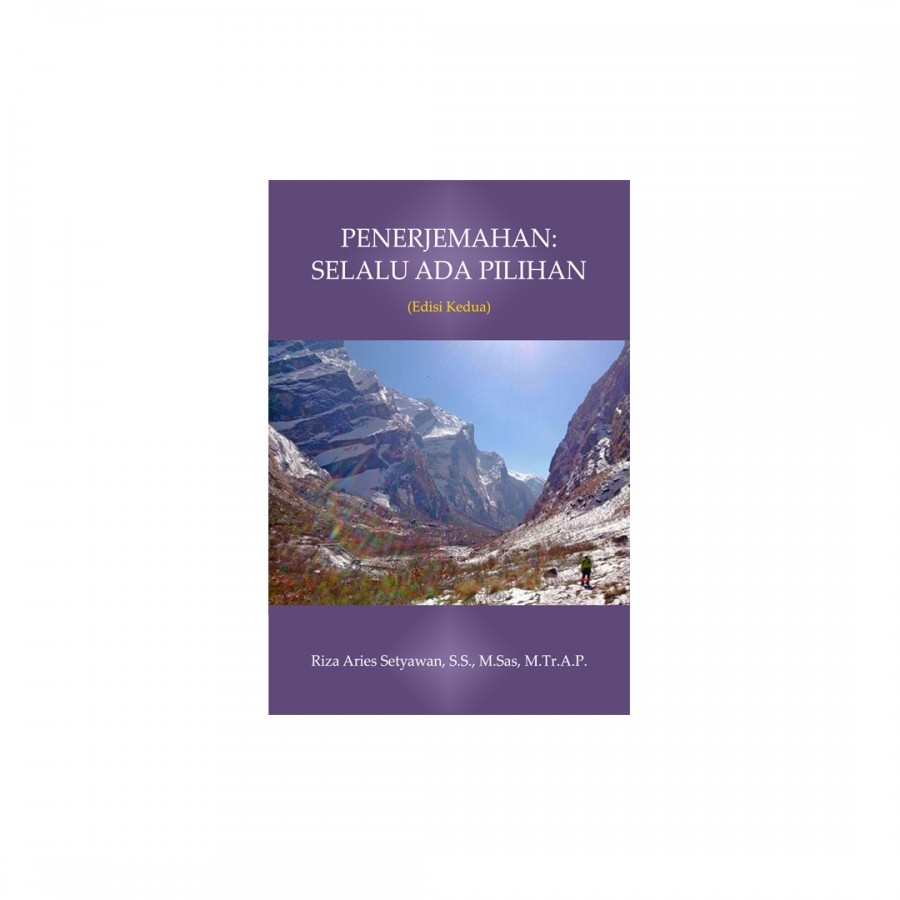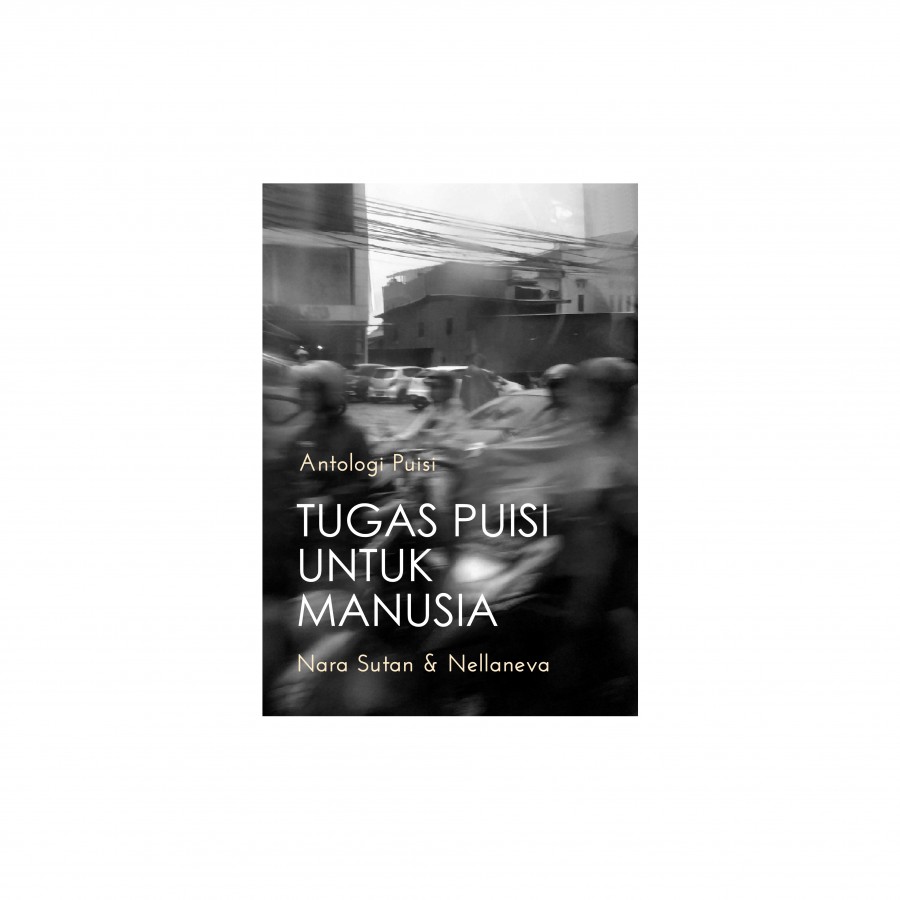Bagaimana mungkin seseorang menjadi pelaku sekaligus korban dalam hidupnya? Bahkan menariknya, pertanyaan yang paling sering ditemukan, bagaimana bisa seseorang itu menyibukkan diri selain menjadi korban, pelaku, ia serakah menjadi hakim? Tak habis sampai di situ, ditambahnya pekerjaannya dengan membuat penjara bagi dirinya. Kaukira habis pekerjaannya. Belum. Entah ada angin apa, dengan ikhlas ia mengurung dirinya dan membuang kunci sel sejauh mungkin.
Entah sia-sia atau tidak, aku menceritakan keikhlasanku melepas dirinya dan pergi. Tidak, bahkan malam ini aku tak pernah merasa sia-sia. Aku siap berdeklarasi, bahwa aku tak sia-sia. Aku jadi pahlawan. Aku siap berdeklarasi, memilikiku adalah keberuntungan. Tetapi mungkin hanya aku yang menyadari. Tuanku? Tidak.
Biar kuceritakan tentang alasanku lari. Tiga hari yang lalu. Tuanku, masuk ke ruang bawah tanah, tempat ia menyimpanku bersama kanvas. Nafasnya terengah-engah, seperti habis lari kencang karena dikejar anjing. Tapi alasan itu sepertinya tidak pas, ditangannya ada ember putih dengan tagline anti bocor. Diletakkannya di dekat kanvas, oh air biasa. Dia duduk memandangi kanvas. Matanya menyala, seperti banteng melihat kain merah.
Tiba-tiba dia bicara seakan melihat dirinya di kanvas padahal itu kanvas baru, “Lihat Mus, lihat! Siapa engkau? Dia tertawa Mus, dia memang tertawa. Tetapi bukan untukmu Mus. Siapa engkau berharap lebih? Apa yang engkau harapkan dari hanya menunjukkan lukisan Mus. Di matanya engkau hanya pengangguran Mus. Sadarlah Mus sadar.”
Musafir, pelukis ulung yang mengurung dirinya di ruang bawah tanah. Selesai mengumpat dirinya sendiri dengan mengecap dirinya pengangguran, tak habis ternyata marahnya. Ia lanjut berkata, “Lihatlah dengan jelas Mus. Uang adalah keutamaan. Persetan dengan semua lukisan di sini. Uang adalah keutamaan Mus. Bahkan jiwamu tak lebih hanya sekedar pelengkap di ragamu, Mus. Sadar. Kau miskin Mus. Semua yang ada di ruang ini adalah bukti kau miskin. Bukti kau pengangguran.”
Gila Musafir ini. Mana mungkin kita semua adalah bukti kemiskinan baginya. Sialan, dia tak sadar kini yang diumpatnya bukan lagi dirinya. Melainkan aku, kanvas, ruang ini, bahkan imajinasinya yang ia tuang melalui campur aduk warna. Apa yang salah dari kami? Wahai Musafir pelukis yang menciptakan dinding penuh dengan kanvas yang sudah kau tuangi warna, apa salah kami? Bukankah engkau yang menggunakan kami? Bukankah kami setia ada di sisimu? Bukankah kami adalah yang tidak pernah mengumpat tentang dirimu?
“Lihatlah kalian. Akan kumusnahkan kemiskinanku. Akan kuhancurkan bukti kemiskinanku. Sialan!” Kata Mus. Semakin gila dia dipenuhi amarah, diangkatnya ember yang ber-tagline anti bocor yang berisi air. Dibasahi kami dengan arah yang kacau. Basah. Sudah. Basah. Tiga kali ia gerakan dengan kacau. Kemudian Mus pergi ke pojok ruang, di sana ada lukisan bunga matahari yang besar, disiramnya. Sebelahnya lukisan mobil sport, disiramnya. Depan lukisan mobil sport ada lukisan seorang lelaki yang sedang merokok, disiramnya. Di sebelahnya lukisan petani menanam padi, disiramnya. Airnya habis. Ember dibanting.
Matanya semakin menyala. Semakin terasa ketakutan ini bagi aku. Aku takut menjadi korban amarah dari Mus yang sedang tak terkendali ini. Aku takut aku hancur. Aku takut, aku tak bisa lagi berteman dengan dia. Tidak dia mendekat ke arah kami lagi, ke arah aku dan kanvas. Ditendangnya kanvas baru itu. Rusak sudah.
Tidak dia mulai melihat ke arahku, jangan. Keranjang ini jangan diangkat Mus. Ayolah kita teman, kita bersahabat Mus, cukup. Cukup Mus. Sialan, jangan diangkat kubilang. Tidak ini terlalu tinggi. Aku bisa merasakan kini aku tepat di atas kepala Musafir. Baik diangkat saja. Jangan dibanting. Tidak, cukup Mus. PRAK! Aku dan keluargaku di keranjang berpisah semua. Kami berpencar tak berencana. Cukup Mus. Biarkan kami menjadi yang terakhir korbanmu.
Lukisan yang kautumpuk di atas lemari itu jangan kauhancurkan juga Mus, Jangan!
Mus naik, ke atas kursi. Diraihnya lima lukisan yang ditumpuk itu, satu persatu dia injak. Tak jelas bisa kulihat, lukisan apa itu. Yang pasti, tumpukan pertama sudah hancur. Dia banting dan injak sambil berteriak. Lukisan kedua, dia lihat, dia banting, dia injak, dan hancur. Lukisan ketiga, dia lihat, dia banting, dia injak, dan hancur. Lukisan keempat, dia lihat, dia banting, dia injak, dan hancur. Mus teriak. Nafasnya terengah-engah. Dia berhenti sejenak.
Lelahkan Mus? Cukup Mus. Sisakan satu saja. Istirahatkan dirimu. Jangan lagi ada korban. Istirahatlah Mus. Aku tahu tenagamu sudah terkuras. Sudahlah Mus. Marahmu tak akan menyelesaikan segalanya. Istirahatlah dan jangan menjadi hakim pada kejadian yang tak menyenangkan hatimu.
Tubuh yang sudah kelelahan itu, Tiba-tiba tegak lagi. Mata yang sudah memancarkan lelah kemudian menyala lagi. Tangannya gemetar, memegang lukisan kelima. Diangkatnya tinggi-tinggi kemudian Mus teriak, “Aaaaaa.” Klek! Mus diam. Teriakannya mendadak berhenti. Ada yang jatuh dari lukisan itu. Aku tak bisa melihatnya dengan jelas. Mus mencari sesuatu yang jatuh itu.
Ketemu. Kertas. Kertas apa? Mus membukanya. Diam sejenak. Matanya terpaku pada selembar kertas. Mata yang menyala itu mulai redup apinya. Muka yang ia tegangkan otot-otot wajahnya, mulai melunak. Luwes. Ia diam. Kemudian, ia melihat seluruh ruangan. Dari sudut, menuju sudut. Dari atas, ke bawah. Dari bawah, ke sudut. Terus, mungkin beberapa kali.
Mus menatap kami, dengan lukisan kelima di tangan kirinya dan selembar kertas di tangan kanannya. Mus melihat kita. Mus melihat kehancuran yang ia buat. Kenapa Mus? Apa isi kertas itu Mus? Mus menangis.
Tertunduk lemas, kemudian roboh dengan lututnya. Menangis. Mus menangis. Untuk ke sekian kalinya, aku menjadi saksi mata. Untuk ke sekian kalinya, kita semua menjadi saksi mata atas air mata Musafir.
Nasibku masih lebih baik, dibanding saudara-saudaraku di ruangan ini yang telah Musafir hancurkan. Aku masih utuh. Aku masih utuh. Tapi aku terkurung di kegelapan ini.
“Bu, maafkan aku. Aku tidak membenci lukisanku Bu. Aku tidak membenci. Bu, maafkan aku. Ruangan ini hancur Bu. Bu, beginikah rasanya patah hati. Apa mungkin, engkau begini saat ayah pergi tanpa alasan, Bu. Beginikah rasanya ditinggalkan orang yang telah memberikan harapan kebahagiaan?” kata Musafir.
Ibu? Penguasa ruangan ini sebelum Musafir. Apa lukisan itu adalah lukisan seorang wanita yang sedang menyulam? Jika benar, itu adalah lukisan hasil tangan ibunda Musafir. Seorang wanita yang suka menyulam, kemudian tiba-tiba melukis karena patah hati. Dulu, ibunda Musafir menjadikan kami sebagai saksi mata, air mata sedih, air mata haru, air mata kebahagiaan, air mata kemarahan, dan segala air mata.
Surat? Apa benar itu adalah surat. Biar kuingat kembali. Pernah suatu malam, pintu ruangan ini dibuka. Ibunda Musafir masuk dengan air mata. Tubuhnya gemetar. Duduk dibangku tempat ia menyulam. Kemudian melihat sudut demi sudut ruangan ini. Sampai akhirnya, ia menatap satu lukisan. Lukisan sebuah pemandangan indah. Di sana, tertera sebuah penanda. “Hujan di Suatu Malam, di Bulan Agustus.” Itu adalah lukisan yang dibuat oleh ayah Musafir.
Mungkin kau merasa tak jelas. Ruangan apa ini. Ini ruangan yang menjadi saksi bisu, banyak kisah dari keluarga ini. Dari mulai ayah Musafir yang menjadikan ini tempat melukis, tempat menyulam ibunda Musafir, sampai akhirnya Musafir kembali menjadikan tempat ini sebagai tempat mengekspresikan perasaannya dengan cat, kanvas, dan kuas.
Malam itu, saat menatap lukisan ibunda Musafir mengambil secarik kertas dan pena. Ia tuliskan bagaimana sedihnya malam itu. Ia tuliskan apa yang membuatnya sedih, menahan rindu pada suaminya yang kemudian hanya pecah lewat air mata. Aku tak tahu persis kata-kata apa saja yang ia tulis, yang aku ingat hanya poin-poin itu saja. Setelah ia menulis, dilipatnya surat itu dan ditempelkan pada lukisan “Hujan di Suatu Malam, di Bulan Agustus.”
Mus, masih lemas. Amarahnya mereda. Kurasa surat yang isinya tentang kisah di suatu malam yang terjadi pada bundanya dulu menyadarkannya. Kurasa, surat itu mengantarkan suatu pesan. Ketika sedih yang hadir dalam hidup, tak bisa kau terima dengan bijak maka kesedihan terus menjadi kesedihan. Sama dengan rindu, ketika rindu yang hadir itu hendak kau lawan, maka rindu akan semakin melawan. Biarkan rindu tetap tumbuh dengan semestinya dan nikmatilah, karena rindu hadir bukan karena kau kesepian tapi karena kau setia pada perasaanmu. Biarkan sedih tetap ada dengan semestinya, sesungguhnya tak ada hal yang hadir tanpa alasan.
Ruangan ini sudah berantakan. Lukisan sudah banyak yang hancur. Saudara-saudaraku banyak yang patah. Tapi aku dapat meyakinkan diriku sendiri, Mus akan merapikan kembali. Karena aku tahu, Mus adalah pelukis sejati. Dia sebenarnya menyadari, bahwa melukis tidak membuatnya menjadi miskin. Dengan melukislah, ia mampu mengekspresikan perasaannya. Aku yakin, karena aku mengenalmu Mus. Bangkitlah. Rapikan kembali.
Tapi Mus, aku berharap engkau tak dapat menemukanku di sini. Bukan karena aku tak mau menemanimu untuk mengekspresikan perasaanmu, aku hanya perlu istirahat Mus. Aku lelah melihat banyak air mata. Biarlah aku tetap di sini Mus. Kemudian, kalian yang mengetahui keberadaanku sekarang, jangan beritahu posisiki pada Musafir. Diamlah. Biarkan aku berhenti menjadi saksi mata ada air mata lagi. Biarkan aku istirahat di sini.
Mus, kuharap kau tak memiliki banyak pekerjaan untuk menghancurkan dirimu. Jangan bekerja menjadi hakim, untuk menghakimi diri sendiri. Jangan bekerja menjadi jaksa untuk menuntut hukuman pada dirimu sendiri. Jangan bekerja sebagai tersangka untuk menyakiti diri sendiri. Jangan bekerja menjadi sipir penjara, apalagi membuat penjara untuk dirimu. Cukuplah satu Mus, cukuplah menjadi pelukis yang berbahagia dan bijak. Cukuplah jadi pelukis, seperti biasanya. Kembalilah, jadi Musafir sang pelukis yang bijak.
Lampung, Agustus 2021
Anisya N. Fauzi, seorang mahasiswi yang lahir di Ciptawaras, 22 Januari 2002. Aktif di media sosial Instagram @saya_anisya dan bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Desa Sukapura, Kec. Sumber Jaya, Kab. Lampung Barat, Prov. Lampung.