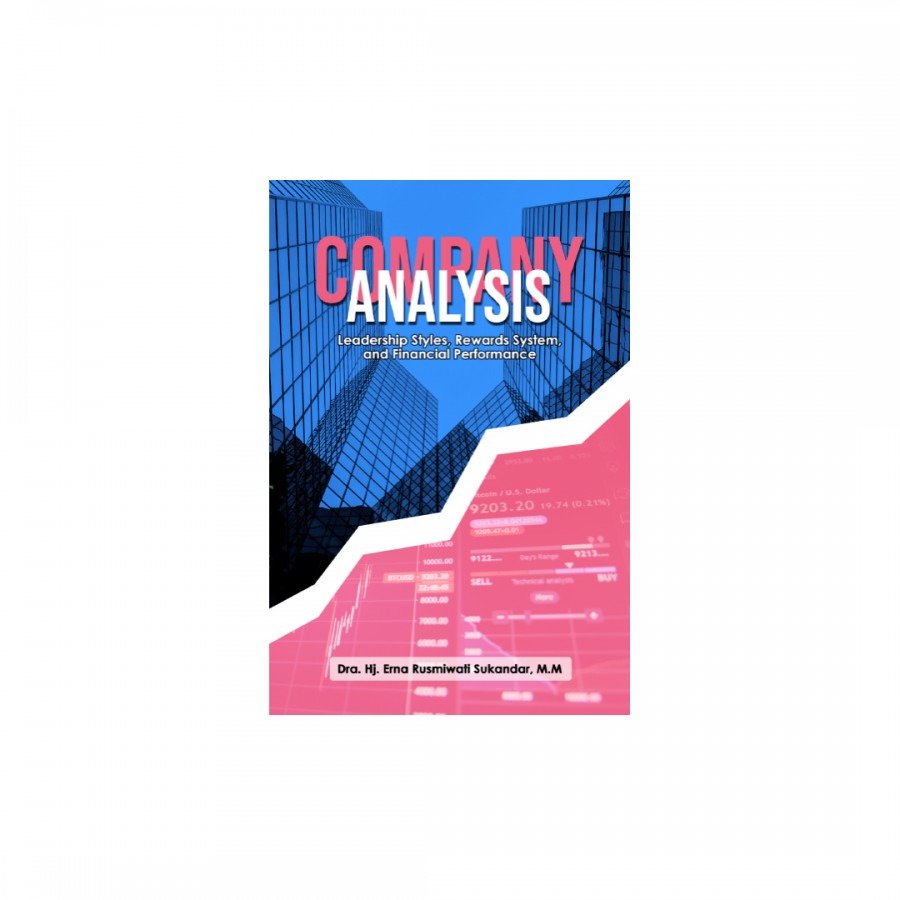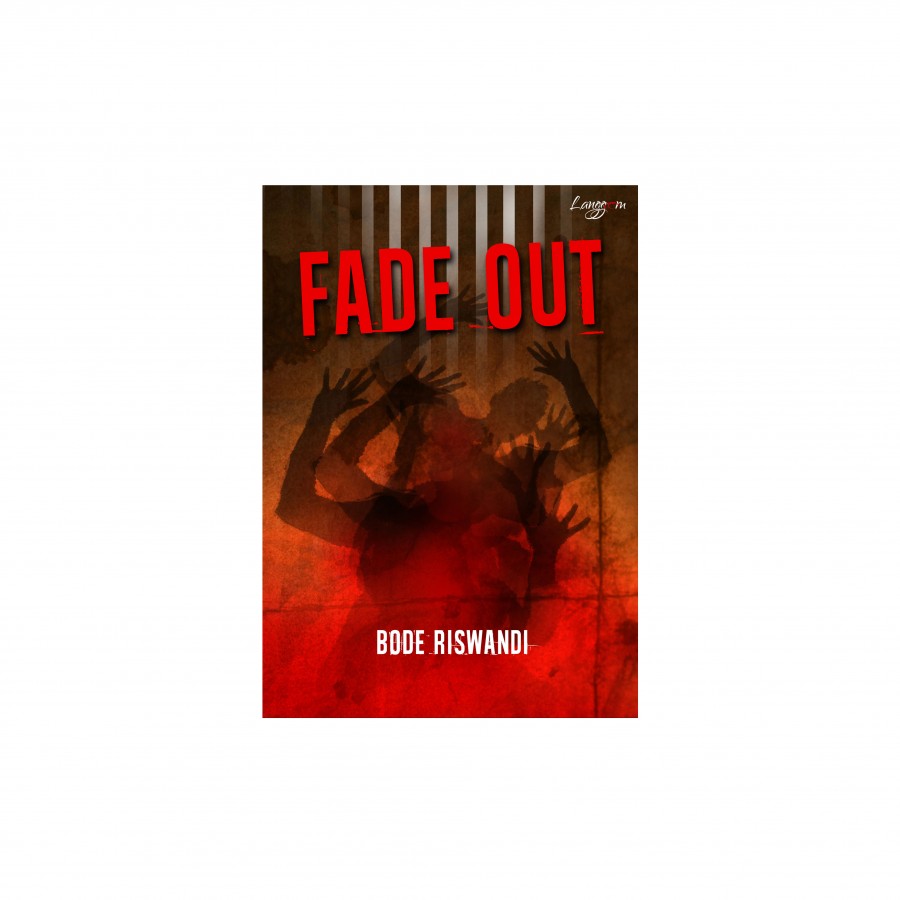“Kapan kita makan?” Tanyamu malam ini.
Kali ini sungguh berbeda. Biasanya, kita selalu banyak tertawa. Sesekali berbicara tentang beberapa puisi yang berseliweran di media digital. Sesekali juga, kau bertanya tentang makna puisi yang sebenarnya aku tak tahu juga. Namun, demi obrolan malam yang berkelanjutan, aku akan menjawab seadanya dan sebisanya. Tak jarang aku akan banyak ngawur.
“Apakah nasi sudah matang?” Lanjutmu.
Bunyi token malam ini tidak seperti biasanya. Biasanya, bunyi token sebagaimana mestinya. Namun, malam ini agaknya berbeda, seolah lebih noise dan memberi nada olok-olok kepada diriku. Sebisa mungkin aku abai, tapi bunyi token benar-benar tak bisa kuabaikan. Bunyinya terlalu meresahkan untuk aku yang telah pasrah.
“Bagaimana? Apakah air sudah hangat dan bisa untuk membuat dua cangkir kopi?” Kamu menegaskan.
Aku tahu bahwa gas LPG 3 kilogram khusus rakyat miskin sudah habis sedari tadi pagi. Sial benar! Sebenarnya niatan hendak berutang gas sudah sedari tadi siang, tapi kedai yang biasa tempat aku berutang tak kunjung buka. Biasanya, kedai tersebut akan menjadi tempat paling enak untuk berutang. Selalu dibolehkan walau setiap kali berutang akan mendapat ucapan pedas dan banyak tatapan mengenaskan dari pembeli lain atau barang kali para pengutang lain.
Aku tidak menjawab pertanyaanmu. Malam begitu asing. Setidaknya bagiku. Memang sudah sering kau dan aku lewati malam tanpa makan. Namun, tidak seperti ini, setidaknya ada minuman hangat untuk membasahi kerongkongan dan menekan asam lambung naik ke hulu hati. Tentu hal itu didampingi sedikit cemilan. Hanya sedikit untuk mengenakan alur obrolan.
“Bagaimana jika kita bermain sambung kata!” Aku mencoba mengalihkan laparmu.
Kau tidak menjawab. Aku tahu bahwa laparmu telah sampai pada titik tak patut diabaikan sebagaimana mengabaikan bunyi token listrik. Beberapa kali aku mendengar perutmu berbunyi. Kemungkinan terbesar perutmu berbunyi karena lapar. Naif sekali aku rasanya jika bertanya, apakah kau ingin ke kamar kecil?
“Debat capres kemarin kita kelewatan. Bagaimana jika menonton siaran ulangnya di YT?” Sekali lagi aku mencoba mengalihkan laparmu dan menekan bunyi keroncong perutmu.
Kau hanya menarik sedikit bibir sebelah kirimu. Lalu, menghela nafas. Aku paham bahwa kau sudah bosan. Bosan dengan kualitas video 144 yang selalu aku terapkan di YT. Hal itu bukan bentuk dari pelitnya diriku. Namun, itu semacam penghematan agar paket data 2gb pertiga hari tak habis dalam sehari.
Selain itu, aku juga mafhum bahwa kau mulai muak dengan visi dan misi. Tak bisa percaya dengan program-program apabila capres kelak terpilih. Subsidi pangan, subsidi pupuk, pembangunan merata, sekolah gratis, jaminam masyarakat miskin, dan lain sebainya itu sudah melekat di benakmu sebagai janji semata. Tentu, begitu juga denganku. Namun, mencoba kembali berharap, ya, tetap saja pada akhirnya hidup kita hanya akan seperti ini.
Bunyi token yang selalu mengesalkan. Beras subsidi yang rasanya tak layak untuk dimakan. Gas 3 kilogram yang sulit didapatkan. Belum lagi bahan bakar minyak yang sering kali naik. Untuk bahan bakar minyak mungkin tak apa karena kau dan aku tak punya kendaraan pribadi. Ehh, namun tetap saja, menaiki angkot ongkos juga naik. Pada akhirnya, mentok mengenakan tungkai kaki menempuh jalan kian-kemari. Ketika kau letih, “bangsat, terlalu jauh untuk ditempuh hanya dengan menggunakan kaki. Bajingan besar!” Sumpah serapahmu akan lekas keluar.
“Membosankan! Lebih baik menonton video pendek di reel IG! Jelas mendapat pengetahuan jika tidak minimal sebagai hiburan!” Tukasmu dengan nada harus dilaksanakan.
Aku tak segera memenuhi permintaanmu itu. Hal ini butuh pertimbangan yang matang dan tidak boleh gegabah atau asal-asalan. Sisa paket dataku tak lebih dari 700mb. Selain itu, menonton video pendek di reel IG tidak bisa diatur kualitas video. Hal tersebut akan memakan banyak paket data lebih cepat dari pada menonton debat capres di YT dengan kualitas 144. Setidaknya semacam itulah hipotesisku.
Namun, demi mengalihkan rasa lapar dan menekan bunyi keroncong perut, aku segera membuka IG. Kita menonton video pendek di reel IG cukup lama. Sesekali serius memperhatikan video, tetapi lebih banyak tertawa dengan postingan yang aneh-aneh. Setidaknya kita mendapatkan tawa dari pada hanya mendapat janji saja.
Tidak butuh waktu lama. Notifikasi dari operator mengirimkan pesan cinta untuk segera mengisi pulsa agar dapat membeli paket data. Ponsel pintar layar retak dan LCD tompel hitam di sudut kiri atas seolah kehilangan fungsi. Kau menatapku cemberut. Aku mematikan layar ponsel dan memasukkan ke saku kiri. Setelah itu, aku tersenyum lebar.
“Besok beli paket!” Ujarku mencoba tenang seolah di saku kananku terdapat Bung Karno dan Bung Hatta yang tersenyum akan dilepaskan dari saku busukku. Padahal hanya menyisakan sisa-sisa tembakau yang aku beli ketengan.
Aku ingin mengajakmu berbicara tentang hal-hal yang fungsinya mengalihkan rasa laparmu. Namun, aku takut pembicaraan akan membawamu pada rasa lapar yang sangat. Aku memilah-milah seolah tengah menjawab soal abc;
A. Berbicara tentang puisi Nizar Qabbani dan melakukan pembedahan secara singkat saja.
B. Bercerita tentang betapa hebatnya AI yang bisa membuat ilustrasi hanya dari beberapa kalimat.
C. Membicarakan cerita pendek yang terakhir kamu tulis dan terbit di salah satu media daring serta menyatakan pendapatku tentang struktur cerita yang kaku. Tidak kurang dengan pembahasan honor yang sangat lama diberikan.
D. Mencoba mengajakmu bermain catur walau aku tahu bahwa kau akan kalah karena setiap langkahmu tidak memiliki variasi tipu muslihat.
E. Atau mengajakmu menatap bulan dan tidak lagi memedulikan bunyi token, gas, dan nasi yang tak akan matang karena beras telas habis.
Aku sangat bingung hendak mengajakmu membicarakan apa. Padahal banyak motivator dadakan di IG berkata, dalam hubungan rumah tangga sangat penting pembicaraan atau yang disebut sebagai komunikasi antara suami-istri. Bangsat sekali pernyataan tersebut, banyak bicara hanya akan membuat perut semakin lapar. Mungkin yang dimaksud motivator dadakan tersebut ketika perut telah kenyang, token listrik tak pernah berbunyi, gas 3 Kg tidak pernah habis, dan paket data internet tidak lagi sekarat. Mungkin itu yang dimaksud dengan komunikasi antara suami-istri harus lancar agar terciptanya harmonisasi.
“Apakah kau masih ingat dengan puisi Chairil Anwar dengan judul Derai-derai Cemara?”
Tentu aku masih ingat dengan puisi itu. Puisi yang aku bacakan di depan kelas saat kelas 10 SMA untuk nilai praktik mata pelajaran Bahasa Indonesia. Aku ingin segera menjawab pertanyaanmu. Namun, aku memilih mengernyitkan kening agar tercipta garis-garis yang tak lagi halus. Sebenarnya hal itu aku lakukan agar terlihat seolah mengingat-ingat. Namun, tidak seperti itu, aku hanya ingin menunda menjawab dan berpikir ada apa tetiba kau menanyakan puisi yang entah berapa tahun lalu aku bacakan dengan suara lantang di depan kelas.
“Ternyata kau sudah lupa dengan itu puisi!” Tuduhmu sambil menghela napas panjang.
“Tentu aku masih ingat. Buku puisi Tuan Chairil masih ada di rak buku. Sesekali aku masih membuka buku itu dan membacanya.”
“Itu bagus. ‘Terasa hari akan jadi malam’.” Kau ucapkan larik kedua bait pertama puisi itu.
“Apakah kata ‘terasa’ pada larik itu bermakna paling, dalam keadaan yang sifatnya sengaja, atau dalam keadaan yang sifatnya tidak sengaja?”
Aku terdiam sejenak. Memang setelah tamat kuliah ada beberapa hal yang selalu kita pertahankan, yaitu membaca, menulis, dan memberikan ruang dialektika untuk karya. Aku tak ingin terburu-buru menjawab pertanyaanmu. Sudah sering kali, setiap pertanyaan yang berkaitan dengan karya sastra akan memiliki ujung pertautan dengan kehidupan nyata. Setidaknya kaitan yang akan selalu kau buat dengan cerminan hidup ini.
“Lalu, ‘hidup hanya menunda kekalahan’.” Sambungmu dengan tegas.
“Kita menyerah?” Tanyaku yang sebenarnya kata ‘menyerah’ aku pinjam dari diksi puisi Tuan Chairil.
“Semestinya, kita mendeklarasikan kepasrahan. Pasrah pada keyakinan, pasrah pada kenyataan, dan pasrah pada impian yang terpendam.”
Aku benar-benar tak bisa menimpal pernyataanmu. Aku tahu bahwa yang kau sampaikan itu benar. Namun, bukankah manusia bisa dikatakan manusia seutuhnya ketika tidak berhenti berharap, berjuang, dan banyak ha-ha-hi-hi?
“Oh iya, dan juga pasrah pada kematian!” Kau menekankan kalimat itu dengan pandang yang memastikan.
Aku tatap dua bola matamu yang masih kuat menantang kehidupan. Tidak sedikit pun kau tampak menyerah dari tatapanmu itu. Apakah kita saling termangu? Tidak, tampaknya hanya aku yang termangu. Berpikir terlalu jauh bahwa kau akan mengakhiri hidup dengan menyayat pergelangan tangan semacam drama tragedi. Namun, drama tragedi apa yang menyayat pergelangan tangan hanya karena lapar, token listrik berbunyi, gas 3 Kg habis, dan kuota sekarat? Aku meyakini tidak ada drama tragedi semacam itu. Paling-paling yang membumi di negeri pertiwi adalah cinta-kasih tak sampai!
“Aku ingin..,”
Belum selesai aku berbicara, ponsel pintar layar retak dengan tompel di LCD berbunyi-berdering dengan nyaring menandakan pesan dari salah satu aplikasi sosial media masuk. Untung saja paket data yang aku beli masih memberikan bonus gratis akses aplikasi Whatsapp.
Segera aku membuka kunci layar ponsel. Nomor baru mengirimkan pesan. Kau terpengaruh untuk melirik isi pesan tersebut. Kau tersenyum membaca pesan itu. Aku lebih tersenyum melihat kau tersenyum. Pesan itu ditujukan kepadamu yang berisikan bahwa cerita pendekmu yang kau kirim empat bulan lalu akan diterbitkan di koran digital akhir pekan ini.
“Apakah kita akan makan?” Tanyaku dengan senyum segar padamu.
Diego Alpadani merupakan pedagang bawang dari pasar ke pasar. Saat ini, Ia berdomisili di Kabupaten Agam, Sumatra Barat.