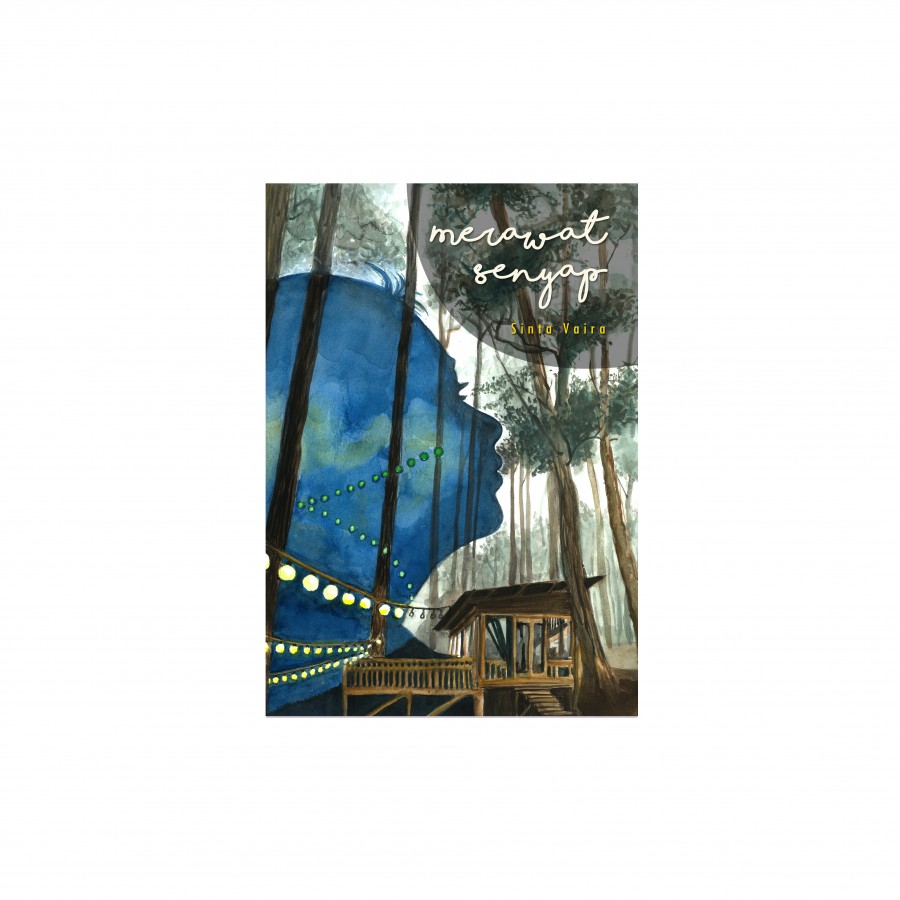Pada suatu malam, Jibril bersiap untuk tidur yang nyenyak. Ia sudah mengalami cukup banyak kelelahan dua hari terakhir. Awalnya, ia naik bis antar kota ke Kediri. Lantas dari terminal, ia mencarter ojek dan meminta ojek itu mengantarnya ke Menang. Namun tukang ojek itu, seorang pemuda yang tampaknya belum berusia dua puluh tahun, tolol luar biasa.
“Saya tidak tahu Menang,” kata tukang ojek itu.
Jibril tidak percaya ada orang Kediri yang tidak tahu Menang, apalagi jika orang itu adalah tukang ojek. Namun memang begitulah kenyataannya. Pada akhirnya, Jibril memutuskan mencari tukang ojek lain, dan si pemuda, yang merasa telah bersusah payah menawarkan jasanya barusan, menggerutu dan meminta sepuluh ribu rupiah sebagai ganti rugi.
“Tapi kau tidak rugi apa-apa,” kata Jibril keberatan. Dan ia bersikeras untuk tidak memberikan serupiah pun kepada pemuda parasit itu.
Beberapa saat setelah itu, dengan hati yang dongkol, Jibril menemukan seorang tukang ojek setengah baya dengan motor Astrea Grand yang tampak butut. Namun tukang ojek itu mengatakan ia tahu di mana Menang, dan bersumpah bahwa ia sudah terbiasa mengantar peziarah ke sana.
Jibril menatap motor tukang ojek itu dengan sedikit bimbang. Dan tukang ojek itu menepuk-nepuk sepatbor yang retak dan berkata, “Motor ini bahkan bisa membawa Sampean ke ujung dunia.”
Barulah setelah Jibril menaiki motor itu, ia menyadari bahwa dirinya juga tolol. “Seharusnya aku pesan ojek Online,” gerutunya. “Dan siapa tahu harganya lebih murah dari ini.”
Tukang ojek meminta seratus ribu untuk satu kali jalan. Dan ia bersedia menjemput Jibril sesuai jam yang mereka sepakati dengan tambahan seratus ribu lagi jika urusannya di tempat suci itu sudah selesai. Jibril menolak dan yakin bahwa sudah cukup dirinya mengalami penindasan hari itu.
Tukang ojek menurunkannya tepat di halaman Pamuksan Sri Aji Jayabaya dan ketika Jibril menyerahkan selembar seratus ribu, lelaki setengah baya itu mendoakan agar Jibril mendapat apa yang ia ingini. Doa itu sedikit melunakkan hati Jibril dan ia tersenyum sambil mengucapkan terima kasih.
“Ngomong-ngomong,” kata tukang ojek sebelum menarik gas. “Apa yang Sampean ingini?”
Jibril mengatakan bahwa itu urusan pribadi. Dan tukang ojek juga tidak terlihat terlalu penasaran.
Malam itu, Jibril bergabung bersama sekitar enam belas orang, bersimpuh khusuk di sebuah panggung menghadap bola beton besar yang berlubang di tengah-tengahnya dengan mata terpejam dan memanjatkan doa-doa.
Semalaman Jibril berada di sana. Pagi-pagi betul, ia turun dan bermaksud segera memesan ojek daring. Sayangnya, ponselnya kehabisan daya dan ia memutuskan bertanya ke orang lewat tentang pangkalan ojek terdekat. Hari belum terlalu siang ketika ia sudah kembali berada di Terminal Kediri, menggerutu karena mesti membayar seratus lima puluh ribu rupiah kepada tukang ojek yang mengantarnya, dan menyesali kenapa ia tidak membikin kesepakatan saja dengan tukang ojek pengendara motor Astrea Grand butut yang mengantarnya kemarin.
Di atas bis, dalam perjalanan kembali ke Surabaya, Jibril merasa sangat mengantuk. Namun ia terlalu gembira sehingga tidak bisa tidur.
Pada suatu malam, Murni terbaring di atas tempat tidurnya dalam keadaan sadar. Matanya mengerjap-ngerjap. Ia kesal dan marah. Sehabis Magrib, Jibril meneleponnya dan mengatakan semua sudah beres.
“Seumur hidupku,” kata Jibril di ujung sambungan, “aku tak pernah berdoa sekhusuk itu.”
Sebelum itu, Jibril mengucapkan banyak permintaan maaf karena baru menghubunginya. Lelaki itu mengatakan ponselnya mati dan baru bisa mengisi daya setelah sampai di rumah. Murni mengomelinya dan mengatakan untuk keperluan itulah, maksudnya mengisi daya ponsel darurat, orang-orang menciptakan Powerbank. Jibril sepenuhnya mengabaikan omelan itu dan menyampaikan kabar gembira bahwa sebentar lagi mereka akan menikah.
Seorang kenalan telah memberitahu mereka bahwa Raja Jayabaya bisa mengabulkan segala keinginan. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan datang dan berjalan jongkok ke petilasan sang raja di Menang dan berdoa supaya segera mendapat pekerjaan pengganti. Dan demikianlah mereka mendapatkan pekerjaan pengganti. Orang-orang sakit menahun mengirim anggota keluarganya untuk berdoa memohon kesembuhan di sana, dan demikianlah mereka terbangun pada suatu pagi dalam kondisi sehat walafiat, seolah-olah tak pernah sakit sebelumnya. Bahkan, kata kenalannya, beberapa hari sebelum membacakan proklamasi kemerdekaan, Soekarno menyempatkan diri untuk berdoa di sana.
“Kalian pikir kenapa Soekarno dan bukannya Syahrir atau Hatta yang membacakan teks proklamasi?” kata kenalan mereka.
Pada waktu itu, Murni membayangkan alangkah sibuknya Raja Jayabaya dalam kuburnya. Dan kenalannya menyahut bahwa itulah risiko menjadi seorang raja. “Kau tidak akan bisa beristirahat bahkan ketika kau sudah mati jika kau menjadi seorang raja, apalagi jika kau raja yang merupakan titisan Batara Wisnu seperti Raja Jayabaya.”
Jibril menyambut antusias kabar itu dan berencana sesegera mungkin berziarah ke Pamuksan Sri Aji Jayabaya dan berdoa agar ia bisa menikahi Murni segera. Namun Murni sedikit ragu.
“Ia,” kata Murni, “maksudku Raja Jayabaya itu, sibuk dengan urusan-urusan besar. Apakah ia sempat mengurusi urusan pernikahan macam urusan kita?”
Jibril tidak peduli. Ia tetap pergi keesokan harinya. Dan kemudian, selepas Magrib tadi, Jibril menceritakan apa saja yang ia kerjakan di Pamuksan Sri Aji Jayabaya.
“Pada awalnya,” kata Jibril di ujung sambungan, “aku menceritakan duduk persoalan kita. Aku bahkan menghabiskan tiga jam pertamaku untuk melakukannya. Aku katakan bagaimana kita bertemu pertama kali di sebuah pengajian tepat sebulan setelah kematian Ida. Dan bagaimana pada waktu itu masing-masing dari kita tahu bahwa kita sama-sama jatuh cinta. Lantas aku katakan pula bagaimana kita janjian ketemu di kedai kopi, jalan-jalan di mall, dan seterusnya hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Lantas Robi. Tentu saja aku menceritakan tentang Robi, sama banyak dengan aku menceritakan tentangmu. Aku katakan Robi yang bersikap dingin sejak awal ia kukenalkan kepadamu, Robi yang selalu menolak setiap kita ajak jalan-jalan, yang mengatakan masakanmu keasinan atau terlalu pedas, yang bahkan tidak menyentuh jam tangan yang kauhadiahkan dalam kotak kecil dengan bungkus kertas berwarna biru yang cantik pada hari ulang tahun keempat belasnya seminggu lalu, dan Robi yang jadi uring-uringan dan mengatakan bahwa kubur ibunya belum kering benar, dan alangkah celakanya jika aku menikah pada waktu itu. Tentu saja itu tidak benar, maksudku perihal kubur ibunya itu. Aku sampaikan kepada Sri Aji Jayabaya bahwa aku telah mengecek kubur Ida dan benar-benar yakin bahwa tanah kubur itu sudah mengering. Bahkan kembang-kembang sekarannya juga sudah jadi tanah. Sudah lebih dari enam bulan sejak Ida dikubur di sana. Aku berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Sri Aji Jayabaya melunakkan pikiran Robi dan akhirnya bocah itu mau menerimamu sebagai ibunya yang baru. Dan aku yakin betul Sri Aji Jayabaya akan melakukannya. Kau tahu kenapa?”
Jibril diam sejenak, menunggu reaksi Murni. Namun Murni diam saja.
“Sebab aku telah membacakan untuk sang raja Alfatihah, surat Yasin, dan Ayat Kursi. Masing-masing tujuh puluh kali. Lidahku sampai kelu,” kata Jibril bangga, berharap Murni akan berseru saking gembiranya.
“Apa kau mendengarkanku?” seru Jibril di ujung sambungan karena ia tidak mendengar Murni mengatakan apa pun. “Halo… haloo… kau di sana?”
“Kau gila!” pekik Murni setelah beberapa saat. “Kau tidak mendengar apa yang dikatakan temanmu jika Sri Aji Jayabaya adalah titisan Dewa Wisnu? Kenapa kau justru membacakannya Alfatihah dan segala macam itu!”
Jibril terkejut mendengar itu. Namun dengan segera, meski sedikit terbata, ia menjawab juga, “Kulihat, semua peziarah melakukan hal yang sama.”
Murni meraung. “Ini tidak akan berhasil, ini tidak akan berhasil!”
Lantas ia menutup telepon.
Pada suatu malam, ketika semua orang tertidur, Ida bangkit dari kuburnya yang lembab. Ia menyelinap ke dalam kamar Robi. Mengelus rambut bocah berpipi tembem dan berdagu belah itu, kemudian mengecup ubun-ubun si bocah.
Si bocah terbangun dan menguap. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Namun ketika Ida berjalan keluar kamar, Robi membuntutinya. Ida menembus tembok dan masuk ke kamar Jibril, lantas menampar pipi lelaki yang baru saja jatuh tertidur itu.
Tiga kali.
Ketika Jibril tergelagap bangun dan mengira dirinya mengalami mimpi buruk, Robi mengetuk pintu kamar.
“Ibu datang,” kata Robi, “dan ia tidak suka jika Ayah akan menikah lagi.”
Dadang Ari Murtono lahir di Mojokerto, Jawa Timur. Selain menulis cerpen juga menulis novel dan puisi. Sudah menerbitkan banyak karya, dan buku-bukunya juuga mendapatkan banyak penghargaan.
*Cerpen ini diambli dari buku kumpulan cerpen berjudul “Peta Orang Mati” karya Dadang Ari Murtono. Banyak cerpen lainnya yang sangat menarik untuk dibaca di buku kumpulan cerpen “Peta Orang Mati”. Dapatkan bukunya (di sini) untuk mendapatkan potongan harga.