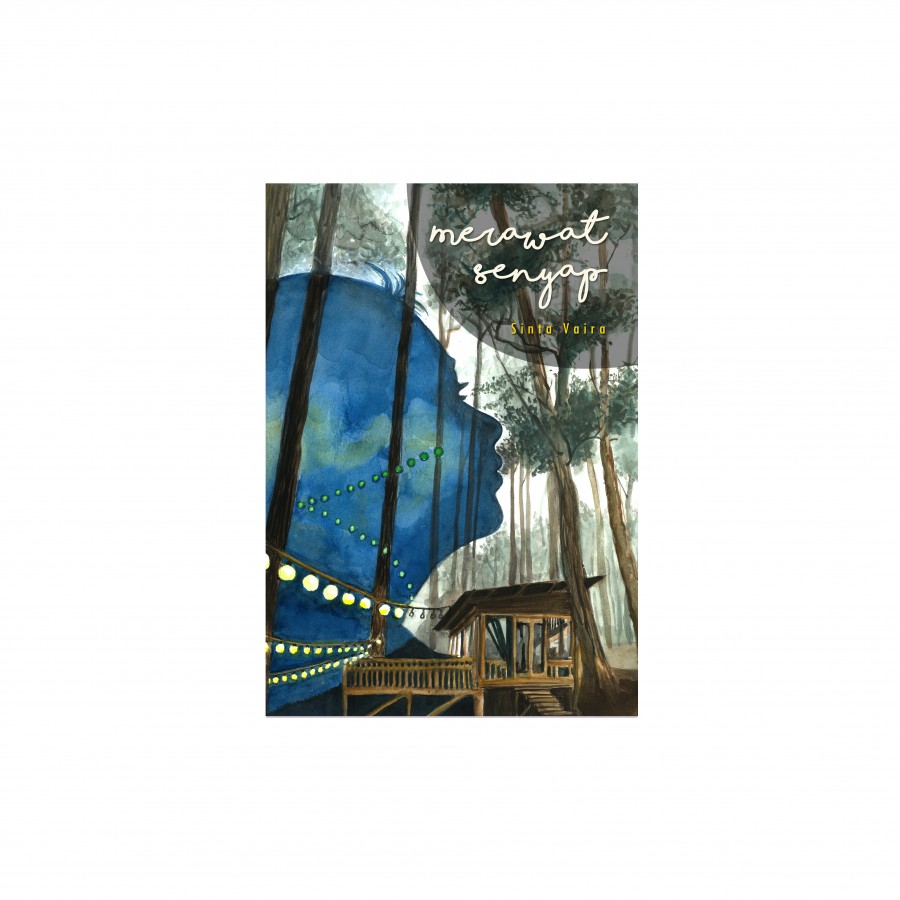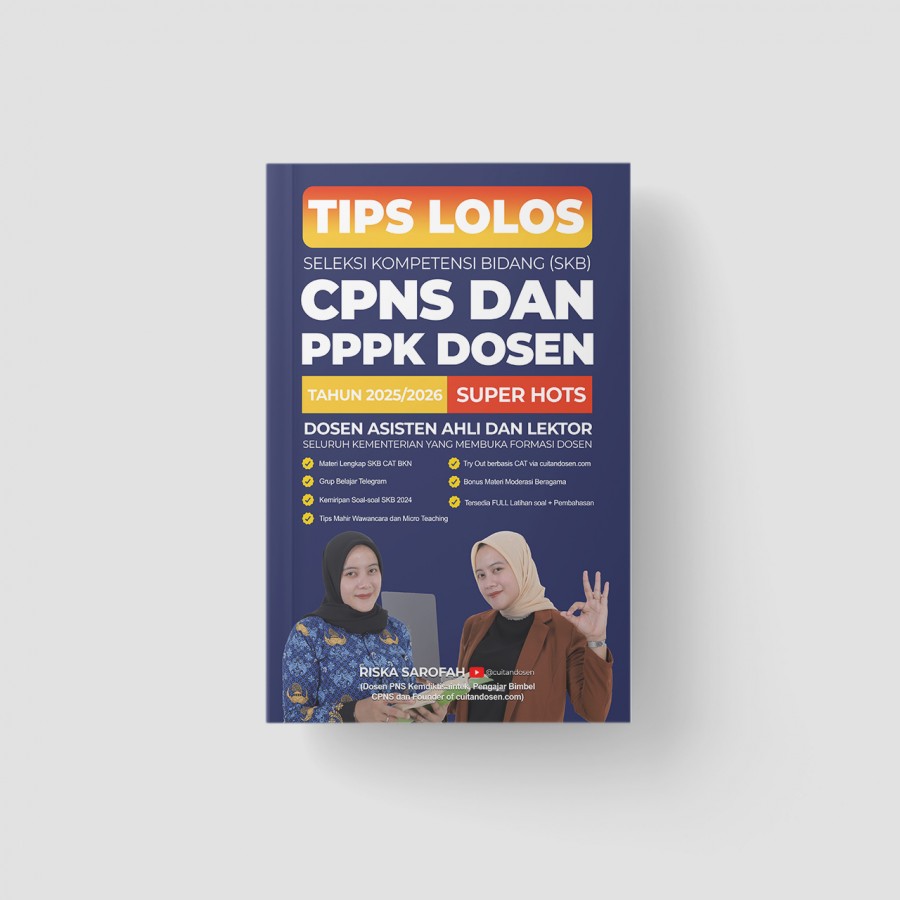Peluru kaliber 30,06 mm itu melesat dari moncong Mouser; tepat mengenai bagian belakang telinga, dan celeng itu pun menguik-nguik, menggelepar-gelepar, lalu tak bergerak lagi.
Marbun gegas menuju buruannya. Tamim, si tukang lampu blor, terseok-seok di belakang. Aki truk pada tas rangsel itu menggelantung di punggung seperti buah nangka yang menjuntai pada batang. Tak sampai dua menit mereka tiba di semak-semak yang telah tersibak-sibak. Seketika Marbun menampakkan wajah bingung. Celeng itu tidak ada. Hanya tersisa ceceran darah.
Tamim merapat ke Marbun. Wajahnya pucat pasi. Bulu kuduknya berdiri. Apalagi ketika tiba-tiba udara di sekitarnya dipenuhi bau bangkai.
“Siluman Dewi Celeng,” desisnya.
“Siapa?” tanya Marbun.
“Dewi Celeng,” kata Tamim, “pelindung para celeng.”
Marbun pernah mendengar nama itu, tapi cenderung tak percaya. Di hutan mana pun yang pernah dia terabas, tahayul seperti itu selalu ada. Namun, dia pilih tak berkata apa-apa. Tak ingin berdebat dengan warga asli Cikidang itu. Mereka lalu meneruskan perburuan, tapi sampai pagi menjelang tak ada celeng lagi yang mereka jumpai.
***
Marbun baru saja turun dari mobil dinas ketika Didit, anaknya yang baru kelas IV SD menghampiri.
“Pa, tadi Didit ketemu celeng. Seperti foto di ruang tamu itu, lho.”
“Ketemu di mana?” tanya Marbun sambil merangkul pundak buah hatinya itu dan berpikir sudah saatnya Didit diberi adik agar tak terlalu banyak berfantasi.
“Di gerbang sekolah.”
“Boneka?” tanya Marbun lagi, mengelus rambut sang anak.
“Bukan.”
“Cosplay?”
“Bukan!” seru bocah sepuluh tahun itu, merengut. “Celeng beneran!”
Marbun menatap Didit dan mukanya tampak terkesiap.
“Celengnya sedang apa?” tanyanya
“Tidak ngapa-ngapain. Hanya mengawasi Didit.”
“Terus?”
“Celengnya dua. Yang hitam banget ketemu waktu Didit baru datang di sekolah. Celeng satunya, yang tidak hitam banget, waktu Didit pulang.”
“Celengnya ngomong apa?” tanya Marbun lagi. Dalam hatinya mulai timbul tanda tanya.
“Tidak ngomong apa-apa.”
“Yang ngeliat kedua celeng itu siapa aja?”
“Didik tidak tahu. Tadi tidak nanya ke teman-teman.”
***
Marbun sudah hampir lupa cerita Didit tentang celeng di gerbang sekolahnya itu ketika dua hari kemudian istrinya mengatakan hal yang sama.
“Celeng beneran?” tanya Marbun. Keningnya berkerut.
“He eh. Masak Mama bohong,” jawab istrinya.
“Mama salah liat kali?”
“Suer! Mama lihat dari jendela kaca ruang tamu. Celeng itu berdiri di trotoar, mengawasi rumah kita. Saat Mama keluar, celeng itu kabur. Lewatnya di dekat bak sampah. Hilang di belokan menuju rumah Pak Tanu. Jangan-jangan babi ngepet, ya Pa?”
Marbun tak menjawab. Tiba-tiba ingatannya melayang pada cerita Tamim tentang Dewi Celeng. Juga celeng yang pernah ditembaknya, tapi bangkainya tak ada itu. Meskipun demikian, Marbun pilih menyimpan cerita itu untuk dirinya sendiri. Tak ingin membuat Maya, teman kuliah di fakultas hukum yang kini jadi istrinya itu menjadi resah.
Dia tak terlalu yakin celeng-celeng yang dilihat anak-istrinya itu ada hubungan dengan hobinya. Mungkin hanya halusinasi mereka. Apalagi ada hubungan dengan kasus korupsi pupuk yang sedang dia tangani.
***
Sabtu pun datang. Marbun kembali berburu ke Cikidang. Kali ini mengajak Marno, sopir kantor yang sering mengantarnya ke mana-mana. Marbun tak percaya hantu, siluman, atau sebangsanya. Celeng ya celeng! Perihal celeng yang seminggu lalu dia tembak, tapi bangkainya hilang, kemungkinan besar hanya kena serempet kupingnya.
Seperti sebelumnya Marbun berniat menyewa jasa Tamim sebagai penunjuk jalan, penggendong aki, sekaligus tukang sorot lampu blor. Selain tahu seluk-beluk Hutan Cikidang, Tamim juga pembenci celeng. Mereka tiba di Cikidang menjelang Isya. Marbun berhenti di warung kopi di ujung desa. Tamim sering nongkrong di situ. Namun, Tamim tidak ada.
“Kapan?” tanya Marbun, kaget.
“Hari Minggu, Om,” jawab remaja berjaket merah itu.
“Minggu?” Marbun tersentak. Dahinya berkerut sedalam selokan. Berarti tak sampai sehari setelah pemuda itu berburu dengannya. “Kenapa? Sakit apa?” tanyanya lagi.
“Nggak jelas, Om. Tahu-tahu badannya panas. Mengigau, menyebut-nyebut Dewi Celeng. Sorenya mati.”
Marbun tetap meneruskan berburu, dan tak terlalu menghiraukan proses mati yang aneh itu. Orang bisa mati kapan saja dan di mana saja dan dalam berbagai cara. Igauan orang yang sekarat bisa macam-macam. Kebetulan saja Tamim menyebut-nyebut nama Dewi Celeng, bukan Dewi lainnya.
Rencana Marbun, mereka tidak usah jalan kaki menerobos semak atau menyusuri jalan setapak seperti biasanya. Cukup dari atap mobil. Marno yang menyopiri sementara dia yang mengoperasikan lampu sorot sekaligus bertindak sebagai sniper. Kalau harus menggendong aki seberat lima belas kilo sambil membawa lampu blor sejauh lima kilo meter, bisa-bisa Marno yang kurus kering itu menyusul Tamim, tamasya ke akhirat. Begitu pikir Marbun.
Mobil Jeep yang sudah dimodifikasi itu kembali melaju, menyusuri jalanan yang sedikit mendaki. Pepohonan pinus bertambah rapat. Sampai di sebuah pertigaan, Marbun menyuruh Marno membelokkan mobil ke arah kiri, keluar dari jalan beraspal. Mereka bertemu jalan tanah yang becek akibat hujan dua jam sebelumnya. Kabut cukup tebal menyelimuti udara, tapi lampu halogen masih bisa menembusnya.
Tiba di kawasan hutan yang dipenuhi ilalang, Marbun menyuruh Marno menghentikan mobil. Nalurinya, di tempat itu banyak celeng. Saat Marbun bersiap pindah ke atap mobil, seekor celeng tiba-tiba keluar dari balik semak-semak, lalu menghadang di tengah jalan. Hanya berjarak lima meter dari mobil. Besar sekali. Sebesar anak kerbau.
“Pak, Pak! Celeng! Celeng!” teriak Marno panik.
“Sudah tahu. Jangan berisik!”
Marbun mengambil senapan. Merayap lewat jendela, naik ke atap mobil. Terlalu berisiko menembak celeng sedekat itu dari atas tanah. Kalau tembakannya meleset, bisa-bisa dia mampus diseruduknya.
Di bawah sorotan lampu kabut, celeng itu bergeming. Moncong hitamnya berlendir. Mata merahnya menyorot tajam. Tangan Marbun gemetar saat memasukkan peluru. Selama menjadi pemburu, belum pernah dia menjumpai situasi seperti itu. Bertemu celeng yang tidak takut kepada pemburunya.
Marbun mengambil napas, menempelkan popor senjata ke pipi kanan. Setelah sejenak mengatur napas, ditariknya pelatuk. Klik! Senapan macet. Tiba-tiba mesin mobil mati. Disusul lampunya. Seketika gelap gulita. Marbun gemetar. Apalagi ketika bau bangkai yang entah dari mana datangnya itu tiba-tiba menyerbu udara lalu menyeruduk lubang hidungnya.
***
Ketika SUV yang dikendarai Marbun berbelok ke Perumahan Griya Tawang, belum juga melewati portal yang tanpa penjaga, seekor celeng seukuran anak kerbau melintasi jalan. Marbun kaget dan segera mengerem. Saat itulah sepeda motor yang dikendarai dua orang itu memepet mobilnya. Terdengar letusan dua kali. Marbun terkapar. Lima detik kemudian motor tanpa plat nomor itu menghilang. Begitu juga celeng yang segede anak kerbau itu.
Dewanto Amin Sadono, guru dan penulis, beralamat di Kajen, Kabupaten Pekalongan. Cerpen-cerpennya dimuat di beberapa media dan menjadi juara utama lomba. Novel Ikan-Ikan dan Kunang-Kunang di Kedung Mayit dinobatkan menjadi juara I pada Perpusnas Writingthon Festival, Oktober 2022
*Cerpen ini diambli dari buku kumpulan cerpen berjudul “Kisah Ganjil Tangan Buntung” karya Dewanto Amin Sadono. Banyak cerpen lainnya yang sangat menarik untuk dibaca di buku kumpulan cerpen “Kisah Ganjil Tangan Buntung”. Dapatkan bukunya (di sini) untuk mendapatkan potongan harga.