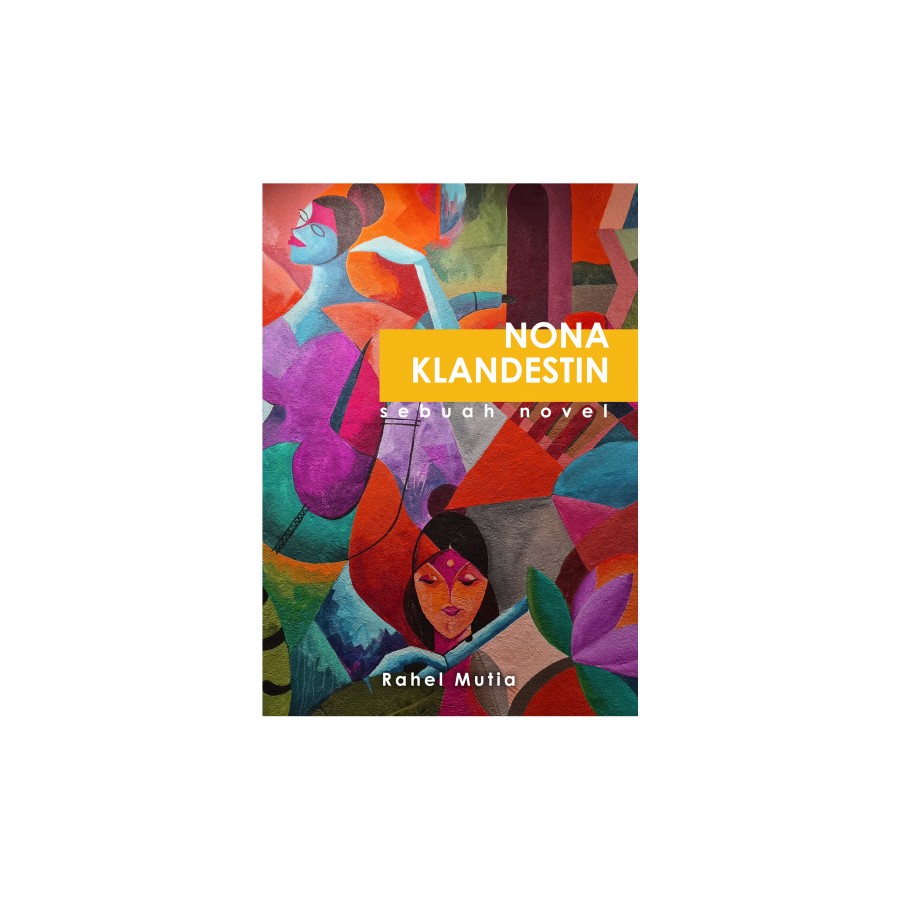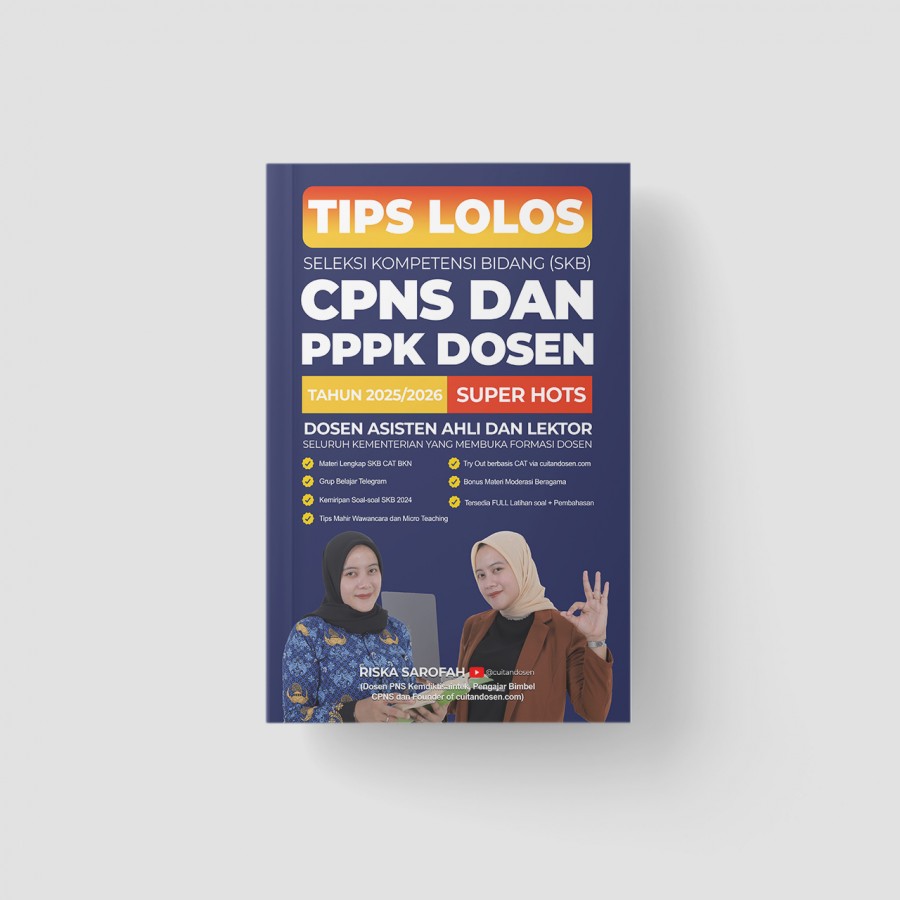Beduk Magrib belum bertalu. Lukisan lembayung terhampar di atas kanvas langit saat kaki kananku melangkah keluar dari pancuran selepas membasuh wajah, tangan, dan kaki. Tiba di pekarangan rumah, delapan pasang mata dengan senjata terhunus menghadang. Mereka melompat dari balik gundukan beluntas yang berdiri rapat memagari pekarangan rumah.
Wajah penuh berewok berdiri paling depan. Tangan kanannya mencengkeram gagang gada. Aku lekas mengenali wajahnya. Namanya Atmawinata. Dia bajingan paling populer di Desa Jambu. Baginya jeruji besi laksana hotel, sekedar tempat meluruskan punggung selepas lelah bergulat dengan kejahatan.
Sungguh di luar nalar. Mengapa angin tiba-tiba menerbangkan tubuh bajingan itu ke depan hidungku? Di dalam ribuan rak yang tersimpan dalam kepalaku tidak ada buku cerita tentang pertikaian aku dan dirinya. Pikiranku berkaru melayang-layang ke dunia antah berantah.
“Juragan Guru! Sekarang harus ikut dengan kami!”
Tamu tak diundang di pekarangan rumahku tiba-tiba menghardik.
“Sebentar. Ada apa ini? Mengapa aku harus ikut dengan kalian?”
“Jangan banyak tanya Juragan! Tinggal ikut saja. Apa susahnya?”
Lebe yang berdiri di belakang Atmawinata maju tiga langkah mendekati sambil mengacungkan golok di tangan kanannya beberapa inci dekat urat leherku.
“Begini Juragan!”
Atmawinata mendorong tubuh Lebe ke samping kirinya.
“Ini ada surat penting dari kuwu yang harus disampaikan ke kecamatan malam ini. Kata Juragan Kuwu, surat ini harus diantarkan Juragan Guru sendiri.”
Nada bicara Atmawinata terdengar lebih lembut di telingaku.
“Mengapa harus aku? Bukankah ada petugas pengantar surat di desa?”
“Ini perintah Juragan Kuwu!”
“Yang bener saja. Aku tidak percaya. Untuk membuktikan! Mari kita ke rumah Juragan Kuwu sekarang!”
Tidak masuk akal Juragan Kuwu memberi perintah untuk menyampaikan surat ke kecamatan yang jaraknya kurang lebih tujuh setengah kilo dari desa dan harus sudah diterima malam ini juga. Alasan yang sangat mengada-ada. Bukankah masih ada hari esok? Lagi pula seandainya ini perintah Juragan Kuwu. Beliau bisa menemuiku sendiri. Lihatlah ke selatan! Rumah Juragan Kuwu terlihat jelas dari sini.
Aku mematung tidak bergerak. Atmawinata dan Lebe tidak lelah memaksa. Mereka menyeret tubuhku ke dalam rumah. Sedangkan anak buahnya berjaga-jaga di luar. Beduk Magrib bertalu. Tirai malam pelan-pelan mengusir lembayung yang tadi merajai langit. Ujung golok Lebe menempel pada kulit leherku. Api yang mengalun di dalam lampu teplok yang baru dinyalakan menyaksikan dari balik kaca.
“Sekarang tinggal pilih! Mau hidup atau mati?”
“Bunuh saja aku sekarang!”
“Jangaaa…n!”
Tiba-tiba terdengar jeritan istriku yang tergesa-gesa keluar dari balik pintu kamar. Isak tangisnya mengiringi sambil menyaksikan ujung golok menempel dekat urat leherku.
“Jika Juragan Guru membantah! Bukan saja kepala Juragan yang segera berpisah dari tubuhnya. Nasib istri Juragan juga bakal sama.”
Mendengar Atmawinata menyebut-nyebut nama istriku. Hatiku meleleh. Aku hanya menyesalkan. Mengapa Juragan Kuwu yang tempat tinggalnya tidak terlalu jauh dari rumahku diam saja? Apa dia tidak melihat dan mendengar kejadian yang menimpaku? Seandainya mengetahui? Mengapa tidak segera menolong? Atau? Jangan-jangan Juragan Kuwu sama mendapat ancaman dari Atmawinata?
Suara binatang malam mengiringi langkah kami menembus kegelapan malam. Kami berdelapan masing-masing memegang senjata berupa golok, pedang, dan gada. Aku sendiri diberi sebilah pedang sambil diawasi salah seorang dari mereka. Setelah melewati jalan desa lalu menyusuri jalan setapak yang di kanan kirinya kebun, sawah, dan hutan kecil pinggiran desa.
Atmawinata sebagai hoofdrol menyuruh kami meluruskan kaki setelah menyeberangi sungai lewat jembatan bambu. Api yang menari-nari di atas obor, semua dipadamkan. Di pinggiran desa, tampak sebuah rumah panggung yang berdiri sendiri. Jaraknya terpisah dari rumah-rumah lainnya.
“Itu rumah yang akan kita rampok malam ini. Yang punya rumah namanya Ki Naryan. Aku mengetahui di rumah itu banyak uangnya.”
Biji mataku nyaris terpental ke udara mendengar kalimat yang dilontarkan Atmawinata. Di dalam isi kepalaku bergolak pertanyaan. Jika hendak merampok. Mengapa Atmawinata mengajak aku?
Sepintas mataku melongok rumah yang hendak dirampok. Pagar dari ruas bambu mengelilingi rumah. Beberapa pohon kecil tumbuh di sekitarnya. Sebuah lampu teplok kecil yang menyala tergantung di dekat pintu rumah.
“Sekarang kita bagi empat kelompok. Aku dan Lebe bakal masuk ke dalam rumah. Awas! Jangan sampai ada yang kabur! Jika melihat ada yang hendak menolong. Jangan ragu tebas saja!”
Kemudian Atmawinata memandang wajahku.
“Awas Juragan Guru! Harus menuruti perintahku! Jika tidak. Umur Juragan tidak akan lama lagi.”
Mulutku terkunci mendengar ancaman Atmawinata.
Atmawinata mengendap-endap mendekati rumah. Kami mengekor di belakangnya. Aku disuruh menjaga bagian timur rumah sambil diawasi seorang anak buah Atmawinata. Dalam hitungan detik, kaki Atmawinata dan Lebe menjejak di atas tangga rumah. Brak … Sebuah tendangan dari kaki kanan Lebe menerjang pintu rumah. Aku segera mengambil langkah seribu menuju hutan kecil pembatas desa. Orang yang berjaga denganku dengan cepat mengimbangi langkah kakiku.
“Mau lari kemana Juragan? Saya tebas lehermu!”
Sebelum kaki kanan menyentuh tapal batas hutan kecil dengan desa, orang yang mengejarku berhasil menyusul dan mendorong tubuhku hingga terjengkang di atas tanah. Kerah bajuku ditarik ke tempat yang lebih terang. Tak lama kawan-kawannya yang ikut mengejar tiba. Aku langsung dikurung dengan ujung golok menempel pada kulit tenggorokan.
Di dalam rumah. Atmawinata dan Lebe yang sebagian wajahnya ditutup kain hitam menyeret yang punya rumah ke ruang tengah.
“Di mana kunci dan uangnya kamu simpan?”
Ki Naryan pemilik rumah bungkam.
“Cepat! Disimpan di mana uangnya?”
Mulut yang punya rumah memilih bungkam. Atmawinata tersulut amarahnya.
“Mau dipukul dengan gada heh?”
Buk… Buk… Kepala gada menghantam wajah yang punya rumah dua kali. Pukulan ketiga tepat menghantam lubang hidungnya. Ki Naryan tidak sadarkan diri. Kepala dan hidungnya mengucurkan darah segar. Sedangkan istrinya, tulang kering kakinya dipukul kepala gada oleh Lebe hingga terjerembap di lantai.
Atmawinata setengah berlari menuju dapur. Tujuannya ke pinggir tungku yang terbuat dari tanah liat. Ada kebiasaan jika orang kampung suka menyimpan uang di pinggir tungku. Di dapur, dia berpapasan dengan perempuan tua yang bersembunyi karena sangat ketakutan ketika mendengar keributan di tengah rumah. Melihat wajah berewok Atmawinata masuk dapur seketika perempuan tua itu berteriak sekeras-kerasnya.
“Tolong …! Tolong …! Ada rampok!”
Atmawinata terperanjat bukan main. Gada ditangannya segera menghantam dahi perempuan tua di depannya hingga tersungkur ke tanah tidak jauh dari tungku.
Teriakan perempuan tua itu membangunkan tetangga-tetangga Ki Naryan dan segera mencari sumber suara. Atmawinata dan Lebe tergopoh-gopoh meninggalkan rumah Ki Naryan sambil menggondol uang sebesar f 3 (tiga florin/gulden). Mereka lari secepat kilat menuju perbatasan desa dengan hutan kecil sebelum tetangga Ki Naryan tiba.
Sambil mengatur napas supaya teratur, Atmawinata memandang wajahku dengan bengis.
“Apa yang terjadi dengan Juragan Guru?”
“Tadi Juragan Guru mencoba kabur pada saat Akang mendobrak pintu rumah. Terpaksa saya kejar.”
“Mengapa tidak dibunuh saja sekalian?”
“Ampun Kang. Saya tidak berani. Jika saya bunuh. Istrinya akan segera mengetahui siapa pelakunya. Nanti perbuatan kita akan mudah terbongkar.”
“Betul katamu. Sekarang kita pulang saja melalui hutan! Awas Juragan! Jangan sampai perampokan ini menyebar ke mana-mana! Jika sampai menyebar! Juragan dan keluarga tidak akan lama hidup di muka bumi ini!”
Aku menarik napas lega. Untuk sementara nyawa dan keluargaku selamat. Nyatanya, mereka memendam rasa takut andaikata rahasianya terbongkar.
Di sekitar tempat tinggalku, kakiku tidak bisa melangkah bebas sejak peristiwa perampokan malam itu. Ke mana kaki melangkah, mata-mata Atmawinata selalu mengawasi. Di rumah, di sekolah, di setiap sudut desa mata mereka membuntuti punggungku. Aku mendengar berita jika ketiga korban perampokan sudah dirawat di rumah sakit. Polisi bergerak cepat mencari pelakunya.
Kabar mengejutkan datang dari Juragan Kuwu tetanggaku. Mulutnya enteng mengatakan jika sehari sebelum peristiwa perampokan terjadi dia melihat sepuluh orang yang wajahnya tidak dikenal beriring melewati jalan desa. Juragan Kuwu meyakini jika merekalah pelakunya. Mengapa Juragan Kuwu berbohong?
Untunglah kondisi seperti ini tidak berlarut-larut. Setelah Ki Naryan bangun dari pingsannya, empat orang veldpolitie dan politie agent bergerak cepat menggeledah rumah Atmawinata dan Lebe Desa Jambu. Menurut kabar yang beredar, Ki Naryan mengetahui persis suara orang yang mengancamnya pada malam terjadi perampokan. Dari penggeledahan rumah Atmawinata dan Lebe, polisi menemukan uang sebesar f 3, golok, dan gada yang digunakan pada saat merampok. Setelah meyakini barang bukti itu benar, kedua orang itu diseret ke onderdistrict Dayeuhluhur karena kejadian perkara termasuk ke wilayah tersebut.
Esok harinya pada saat aku mengajar di sekolah tiba-tiba polisi mendatangiku.
“Juragan Guru harus ikut ke Dayeuhluhur.”
“Ke Dayeuhluhur? Apa salah saya? Apa ada hubungan dengan perampokan yang dilakukan Atmawinata?”
“Nanti saja dijelaskan di sana. Sekarang Juragan Guru ikut saja dulu ke Dayeuhluhur.”
Aku sangat yakin, ini pasti ada sangkut pautnya dengan perampokan yang dilakukan Atmawinata dan Lebe.
Tidak salah dugaanku. Aku dituduh bekerja sama dengan Atmawinata dan Lebe merampok rumah Ki Naryan. Sekarang aku paham. Si bajingan Atmawinata menimpakan sebagian kesalahannya kepadaku. Pantas saja dia menyeret kakiku agar mengikuti langkahnya malam itu.
“Menurut pengakuan Atmawinata, dia merampok karena disuruh Juragan Guru. Dan hasilnya akan dibagi dua dengan dirinya.”
Begitu penuturan Asisten Wedana yang menginterogasi aku.
“Maaf Juragan! Bukan seperti itu kejadiannya. Saya akan menceritakan kejadian yang sesungguhnya asal diberikan jaminan. Seandainya kasus ini selesai, saya mohon segera dipindahkan mengajar dari Desa Jambu. Saya takut kaki tangan Atmawinata akan menghabisi nyawa saya seandainya masih tinggal di Desa Jambu.”
“Silakan Juragan Guru menceritakan kejadian yang sebenarnya. Masalah pindah mengajar. Itu bisa diusahakan nanti.”
Mendengar jaminan dari Asisten Wedana, aku segera menceritakan kejadian dari pertama hingga selesai. Tanpa satu pun yang terlewat. Asisten Wedana yang duduk di depanku manggut-manggut sambil sesekali mengusap dagunya. Besok harinya, aparatur desa yang menjadi anak buah Atmawinata diciduk lalu dijebloskan ke dalam jeruji besi. Sedangkan Kuwu Desa Jambu diberhentikan sementara sampai menunggu keputusan dari Landraad Cilacap.
Tidak lama, aku dipindahtugaskan mengajar di Desa Panulisan. Belum seminggu mengajar, aku menerima selembar besluit pemberhentianku dari kegiatan belajar mengajar untuk sementara waktu hingga kasus perampokan ini selesai.
“Sekarang yang berdosa sudah dijebloskan ke penjara. Yang tidak berdosa sudah dibebaskan. Begitulah pengalamanku,” kataku kepada jurnalis Sinar Pasoendan yang sengaja datang ke rumah.
“Pengalaman Kang Guru luar biasa. Jika tidak keberatan saya akan jadikan hoofdartikel di koran kami.”
“Silakan terserah saja! Mudah-mudahan jadi cermin bagi yang membacanya,” jawabku tanpa ragu-ragu.
Setelah menandaskan kopi yang tinggal seperempat gelas lagi, jurnalis muda itu mohon pamit dan segera meninggalkan rumahku.
***
*Rekaan dari berita di Koran Sinar Pasoendan terbit Kamis 27 Desember 1934, 20 Puasa 1353.
Hoofdrol : tokoh utama / pemimpin
Veldpolitie : polisi lapangan
Politie agent : agen polisi
Onderdistrict : pemerintahan setingkat kewedanaan
Landraad : pengadilan
Besluit : surat ketetapan
Sinar Pasoendan : koran harian berbahasa sunda di jaman hindia belanda
Hoofdartikel : artikel pokok/utama
Eli Rusli, alumnus UPI Bandung. Menulis cerpen dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda, dimuat di beberapa surat kabar dan media online. Buku terbarunya "Cerita Pendek yang Tidak Pernah Selesai" (Kumpulan Cerpen), Penerbit Langgam Pustaka (Juni 2024).