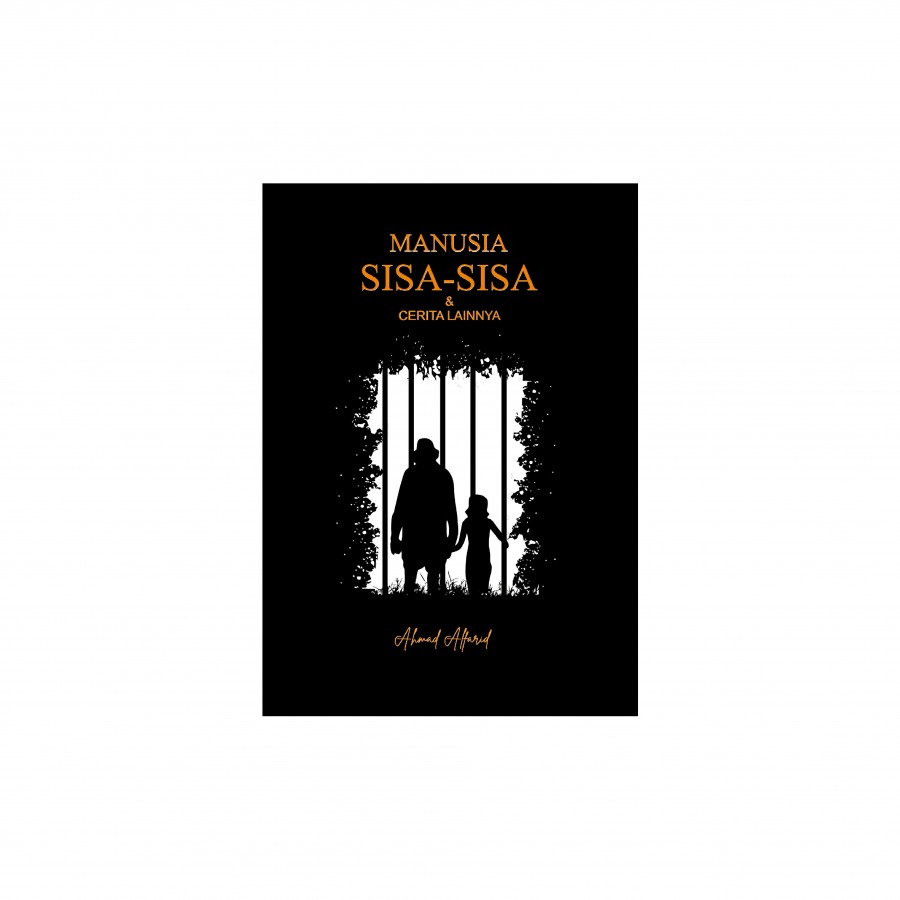Ia melawan dengan tenaga seadanya. Menendang-nendang udara dingin yang memulun di sana. Di atas meja, matanya dicongkel sendok panas. Teriakan dibungkam sunyi. Decit meja terdengar gusar. Punggung yang berkeringat. Bulan penuh di ujung mata. Lalu tiada.
Mengingat itu semua. Bulan penuh pucat. Punggung awan menjadi siluet. Beberapa mata lelaki dewasa yang ganas, memburu ketakutannya. Itu semua ia ingat betul. Nama-nama, lekuk wajah, suara-suara serak pemabuk selalu memusing di dalam kepalanya. Mereka yang memaksanya masuk ke dunia tanpa cahaya. Tanpa keadilan. Tanpa rasa mengenal wajah-wajah baru, yang tiba hanya suara.
Hidup di dunia yang fana dari cinta. Menjadikannya lelaki yang dipaksa tua. Sejak usia enam tahun, ia dijual ibunya—seorang lacur dengan rezeki tak mujur. Lantai sekolah tak pernah ia tumpu. Jalanan menjadi rumah terluas bagi kakinya mencari segala kebahagiaan. Melantunkan suara receh di lawang angkot, etalase warung nasi, sampai kursi-kursi panjang di halte bus. Ia mencari isi perutnya di sana. Beberapa kawannya sama tak mujur di didik nasib. Gurat kehidupan sudah diatur sedemikian rupa agar mereka tetap sengsara.
Ia tak mengenal Tuhan, yang ia kuasakan hanyalah uang. Dengan uang segalanya bisa ia dapat dan lakukan. Tanpa uang tak ada nasi remes, tak ada teh tawar, tak ada lem fox kesukaannya.
Godet—seorang preman yang selalu meminta setoran padanya—mengajarinya begitu. Bahwa hidup bukan milik mereka. Hidup hanya milik orang-orang di balik kemeja dan jam kerja yang jelas penghasilannya. Hidup milik mereka yang punya kepala dengan isi dari sekolah-sekolah. Tak ada hidup bagi orang-orang yang tidur pulas di jalanan, dengan nyamuk dan dingin yang menggigit.
Ia ingat, betapa ia menjadi anak paling di sayang Godet. Setorannya tak pernah kurang, bahkan ia bisa tambah nasi rames dua kali jika ia ingin. Saban malam, ia disuguhkan kardus tebal untuk merebahkan punggung, tak sama dengan anak lain yang tidur di koran atau paling banter kardus indomie.
Namun di balik kesenangannya diperlakukan baik oleh Godet. Ada saja yang tak berterima dalam dirinya. Setiap malam Godet tiba dengan bau anggur murahan di mulutnya. Saat angin menyisir debu di atas lantai plester, dengan lubang-lubang mirip genangan bekas hujan di jalan. Daun-daun kecil—yang hidup pada retakkan tembok penuh coretan—bergoyang. Kawan-kawannya yang lelap dalam mimpi yang tak seperih hidupnya. Godet akan menariknya ke belakang gedung tua, lalu membuka celananya dan memasukkan sebatang kejantanan ke liang dubur yang sudah tak terasa perih. Waktu seakan berputar lambat. Seperti langkah seorang tua saat menyeberang jalan.
Dalam hati kecilnya, ia tak senang dengan perlakuan Godet. Sering ia melawan, namun lebam biru sudah pasti tumbuh mana suka di tubuhnya yang lapang dengan belukar dan pohon-pohon yang mati. Tak pernah ia melakukannya lagi. Dengan Godet memukulnya, ia sudah membayangkan kematian begitu dekat dengan dirinya. Sedekat udara dengan cakrawala.
Suatu waktu, ia pulang dengan segumpal receh di sakunya. Ia akan sembunyikan sebagian dari Godet. Agar ia bisa membeli lem yang sangat ia senangi. Kepalanya akan melayang ke langit, menyusuri seluruh isinya. Seseorang bekerja di dalam kepalanya, mengoyak pelan sampai ia lupa segala kerumitan yang hidup melilit kesengsaraannya.
Godet sudah menunggunya dengan kaki ditumpukan ke meja. Punggungnya bersandar pada kepala kursi sekolah dasar yang kawannya curi dari sekolah yang sepi. Konco-konco Godet duduk di mana suka, seperti jamur di akar pohon besar yang muncul di tanah. Mata mereka penuh padanya. Buas dan mengerikan. Seperti segerombol serigala yang menemukan seekor tikus. Entah, hatinya menolak untuk melangkah ke sana. Kawan-kawannya belum pulang. Dengan langkah pelan, ia hampir Godet. Sebungkus receh ia keluarkan dari saku celana. Menyimpannya pelan di punggung meja, dekat sepatu Godet yang mengkilat. Segera ia berbalik dan memulai langkah untuk kelar dari segerombol serigala itu.
“Sisanya kau sembunyikan di mana?”
Ia berhenti dalam beberapa langkah. Hatinya seakan tertusuk oleh kata-kata yang keluar dari mulut Godet. Ia takkan bisa mengelak dari Godet. Tanpa berpikir panjang, ia akan berlari menuju lawang yang hanya beberapa langkah dari tempat ia terpaku. Namun tak semua niat berjalan sesuai kehendak. Seorang konco menghalanginya. Lalu ia diterkam oleh segerombol serigala dengan liur yang menetes pada tanah penuh debu.
Ia digusur ke ruang yang sudah disiapkan Godet untuk menghakimi semua anak yang menghianatinya. Ia dilempar ke tanah, lalu hantaman sepatu Godet tepat di rahangnya. Napasnya sesak. Pandangannya memutar di langit-langit. Langit-langit yang sudah tak utuh. Awan bisa masuk ke mata dari sana, juga langit gelap.
***
Matanya terbuka. Bulan penuh di langit. Pucat. Menyinari sebagian punggung awan yang berderap di usung angin. Mata merah tiba di mukanya. Mata dengan segala dosa. Ia melawan dengan tenaga seadanya. Sendok dengan nyala bara, mencungkil matanya. Teriakan seakan sunyi di kuping orang-orang yang menahan tubuhnya. Segumpal darah menyungai di pipinya yang lebam.
Mufidz At-thoriq Syarifudin lahir di Bandung, 26 Juni 1994. Dari kecil menetap di Tasikmalaya bersama keluarganya. Menulis cerpen, puisi, cermin, essai/laporan budaya, dan naskah drama. Beberapa karyanya pernah dimuat Pikiran Rakyat, Kabar Priangan, Banjarmasin Post, Radar Tasikmalaya, Buruan.co, Radar Banyuwangi, Bentangpustaka.com, Detakpekanbaru.com, Majelissastra.com, sastramu.com, Pos Merto Prabu, BuanaKata.com, raamfest.com, ngaosart.tk, Buletin Estetika Diksatrasia, dan lain-lain.
Cerpen “Lukisan Lusni” menjadi juara 1 Lomba Menulis Cerpen Se-Jawa Barat Gebyar Bulan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Siliwangi 2016, cerpen “Gelisah” menjadi Juara 2 FSA II Lomba Menulis Cerpen Se-Priangan Timur UPI Kampus Tasikmalaya 2014, “Di Tubuh Cermin, Marnus Bermain” menjadi Cermin pilihan Penerbit Bentang Pustaka. Antologi cerpen “Batu yang Dililit Ari” menjadi nominator Siwa Nataraja Award II Bali (2016) dan antologi cerpen “Kampung Sebelah” masuk 8 besar Siwa Nataraja Award II Bali (2016).
Cerpen dan puisinya juga tergabung dalam beberapa antologi bersama. Buku kumpulan cerpen tunggalnya “Bapak Kucing” (2015), “Batu yang Dililit Ari” (2016), dan yang terbaru “Gelanggang Kuda” (2018). Selain menulis, aktif juga di Teater 28, Beranda 57, Langgam Pustaka dan sekarang menjadi Ketua Rumpun Sastra Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya. Dapat dihubungi via ponsel 082127424881, facebook/surel: mufidzatthoriq@gmail.com, instagram: @mufidzatthoriqs.