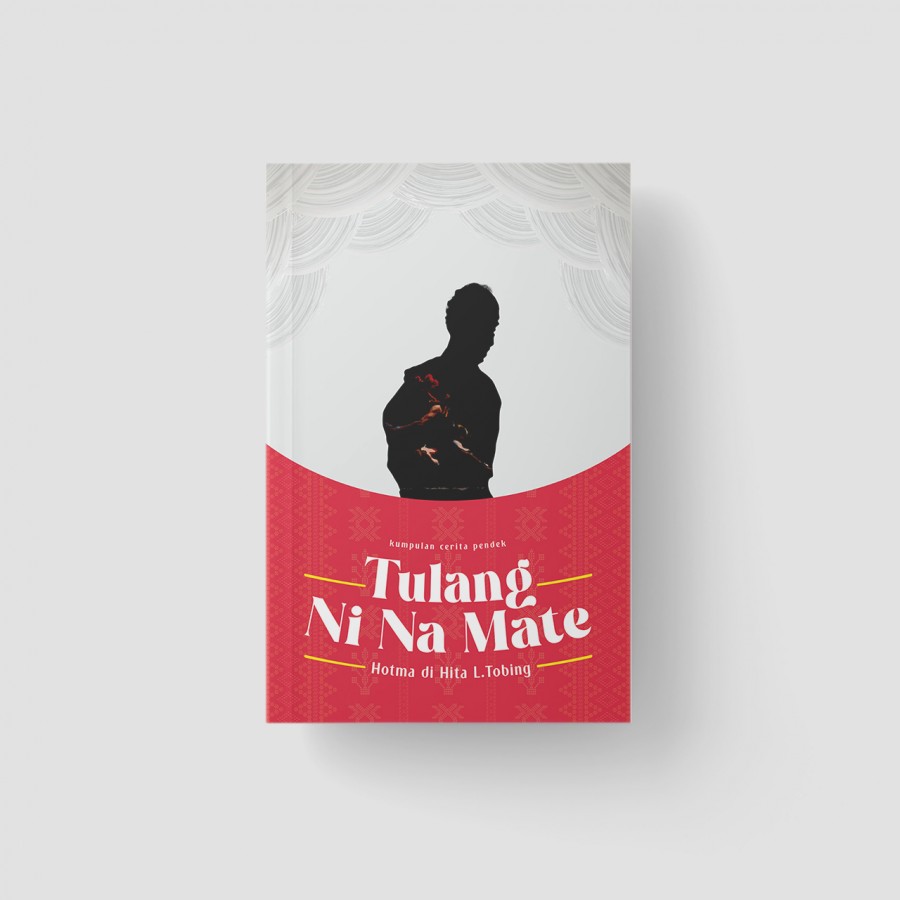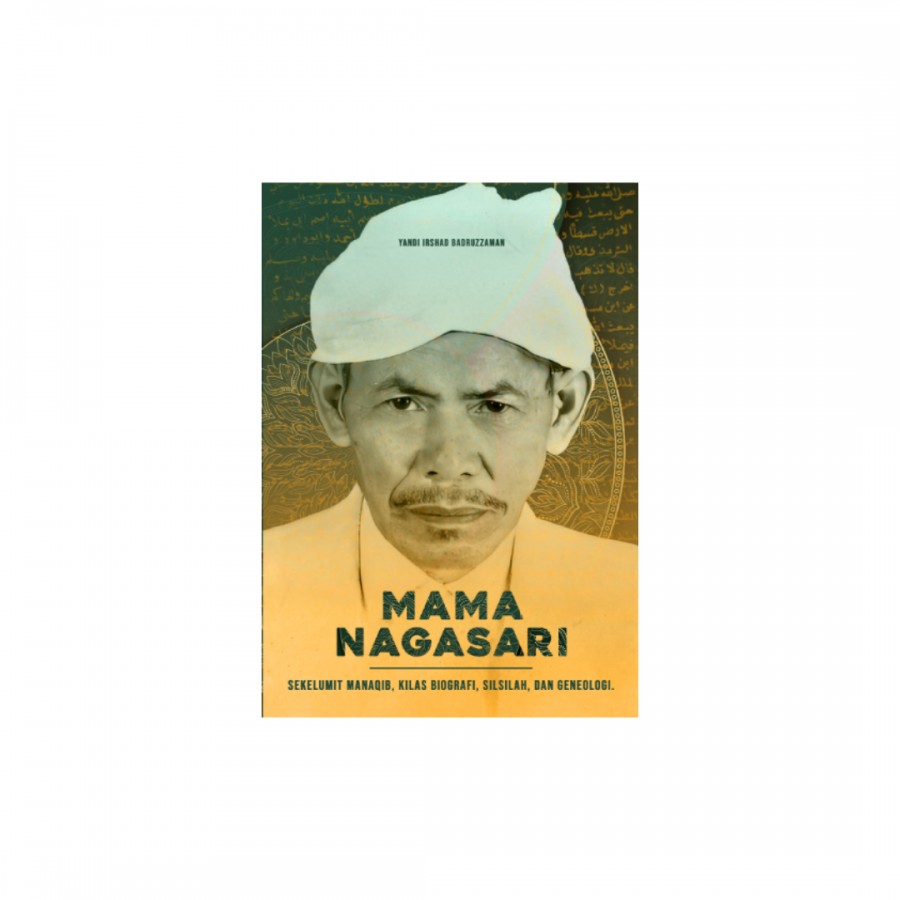Begitu palu sidang itu kuentakkan, lidahku tiba-tiba lepas begitu saja tanpa sebab, menggelepar di atas meja lalu jatuh di antara ratusan sepatu dan sendal jepit di antara kaki-kaki kursi ruang sidang, tanpa darah yang menetes, tanpa disertai rasa perih.
Kejadian itu begitu tiba-tiba, hanya aku sendiri yang melihatnya. Kejadian aneh itu membuatku tak habis pikir. Keningku mengerut. Bagaimana mungkin daging lunak itu bisa-bisanya meloncat dari dalam mulutku, lalu menghilang begitu saja?
Tanpa menoleh kiri-kanan, aku segera merangkak di antara kaki-kaki kursi, apalagi kalau bukan untuk mencari lidah yang melompat itu. Tapi entahlah, daging kenyal itu hilang begitu saja di antara ratusan kaki-kaki meja-kursi dan kaki-kaki manusia di ruangan tersebut.
Setengah putus asa aku lalu meminta bantuan setiap orang yang ada di ruang sidang—Penjaga, hakim, juru ketik, wartawan sampai mang Mudin si tukang parkir. Tapi selain tertawa, mereka malah menganggap aku gila.
Secepat kilat kemudian aku melompat ke dalam mobil, memeriksa inci demi inci kursi dan bagasi, siapa tahu lidah sialan itu bersembunyi dalam Volvo mewahku.
Setelah semua kompleks kantor pengadilan tempatku bekerja itu aku ubek-ubek, dari WC sampai taman belakang, dan tidak ketemu, aku lalu memutuskan mencarinya di sepanjang trotoar Jenderal Sudirman, kemudian menuju Sejahtera dan Studio 21, dengan harapan lidah sialan itu ngumpet di sana. Tapi biar bagaimanapun juga, aku sudah mencarinya dari terminal yang ramai sampai ke sekitar kompleks pekuburan yang sepi sekali pun, lidah merah jambu itu tak jualah ketemu.
Aku tak tahu lagi harus mencarinya ke mana. Aku pikir lidah sialan itu mungkin sudah dicincang penjual daging dan kemudian dijadikan bakso. Mungkin juga seekor anjing telah menelannya menjadi daging cincang. Tapi entahlah, itu baru kemungkinan.
Atas saran istri, aku lalu mengunjungi seorang psikiater ternama di bilangan jalan Perintis Kemerdekaan. Namun sayang sekali dia tidak bisa membantuku menemukan potongan lidahku yang hilang itu. Laki-laki berkacamata tebal itu malah melontarkan ratusan pertanyaan yang sedemikian aneh padaku.
“Apakah saudara selama ini sering berbohong? Apakah saudara hidup dari uang hasil korupsi? Apakah saudara membeli mobil dari uang amplop? Maksud saya, apakah dari semua pertanyaan tersebut saudara sering atau pernah melakukannya selama satu tahun terakhir saudara menjabat sebagai hakim, sehingga kejadian ini menimpa saudara? Kesimpulannya adalah ini semua terjadi akibat perbuatan saudara sendiri. Saya tidak bisa membantu saudara lebih banyak. Saya hanya bisa mengatakan carilah lidah saudara sampai ketemu.”
Karena putus asa, aku kemudian menghubungi beberapa teman dari kalangan wartawan media cetak dan elektronik untuk memuat berita kehilangan, apalagi kalau bukan tentang lidahku yang hilang itu. Sebagai imbalannya aku menawarkan 300 juta bagi yang menemukannya dalam keadaan utuh. Dan iklan tersebut terbukti manjur. Banyak kemudian yang menelepon.
“Bagaimana, apa saudara sudah menemukan lidah saudara? Kalau belum, bagaimana kalau saudara transplantasi lidah saja? Cuma 500 juta saja kok.”
Atas semua telepon itu kemudian kepalaku rasanya malah mau pecah. Hanya uang yang mereka inginkan. Tidak ada seorang pun dari mereka yang ingin membantuku tanpa imbalan uang.
“Kau tidak akan bunuh diri bukan?” sisi lain dari diriku bertanya memelas.
“Bakal!” bagian yang satunya mengumpat.
Setelah menutup pintu kamar, aku lalu merenung lama-lama. Masih teringat kata-kata psikiater brengsek itu beberapa hari lalu: "Ini adalah akibat perbuatan saudara sendiri! Bagaimana mungkin benda kenyal yang bernama lidah itu bisa meninggalkan saudara begitu saja?"
***
Berhari-hari setelah kehilangan lidah, aku memang lebih banyak berdiam diri di kamar. Aku bingung harus melakukan apa. Bagaimana caranya aku bisa berhubungan dengan para klien dan menyapa setiap orang di kantor dengan mulut tanpa lidah? Bagaimana aku bisa melakukan semua itu? Apakah mereka dapat mencerna apa yang kukatakan saat bicara?
Ya, berbulan-bulan aku hanya tidur dan meratapi nasib. Setiap hari yang kulakukan hanya mengumpati anjing berbulu hitamku yang selalu menyalak seolah-olah menertawakanku karena tak bisa menyalak sepertinya. Bagaimana mungkin, bahkan satu-satunya lidah kepunyaanku itu telah hilang, dan anjing itu malah mengejekku dengan menjulurkan lidahnya.
“Keluar kau, anjing bodoh!”
Dengan sekali bentak anjing itu pun kusuruh pergi. Aku bahkan mengatakan kepadanya agar jangan pulang sebelum menemukan potongan lidahku.
Oh Tuhan! Bagaimana mungkin aku hidup tanpa lidah? Bagaimana Jika saja lidah itu ditemukan para penjahat dan memakainya untuk menipu, bagaimana? Oleh seorang politikus culas, misalnya? Oh…
Sebelum tidur, setiap malam, aku selalu memanjatkan doa, berharap keadaan lidahku itu baik-baik tanpa luka sedikit pun, atau paling tidak ia sekarang berada di tempat aman, atau tidak ditemukan orang yang tidak bertanggung jawab.
***
“Hm… sungguh lidah yang bersih. Bahkan dalam keadaan kotor begini pun, lidah ini tetap saja memesona. Ah, lidah siapa ini?” Mbok Minah memungut lidah itu pelan-pelan.
Didekatkannya potongan lidah itu ke ujung daun telinganya, berharap ada selarik suara yang akan ia dengar. Sepi. Tak ada erangan minta tolong atau suara apa pun. Siapakah yang tega memotong lidah semacam ini? Bayangan di kepalanya berkelebat ke ribuan manusia pada zaman dahulu yang dipotong lidahnya secara semena-mena, ke negeri 1001 malam, ke tengah belantara hutan pedalaman, cerita tentang bangsa bar-bar yang membuat sup dari lidah-lidah saudara mereka sendiri yang mereka bunuh.
“Lihatlah…” Ia menunjukkan lidah itu pada suaminya, Tarjo, “lidah yang indah bukan?”
Tarjo terbelalak.
“Memang. Tapi di mana kamu dapatkan?”
“Di jalan”
“Di jalan?”
“Ya, di jalan, tempat di mana anak-anak kita si Tarmin, Tejo dan Limah mengais rezeki sebagai pengemis. Saya akan menyimpannya, Bang. Atau bagaimana kalau abang memakai lidah ini?”
“Maksudmu?”
“Mengganti lidah abang dengan lidah ini. Mbok kira, lidah ini pasti bukan kepunyaan orang sembarangan, bang. Ini pasti milik orang pintar. Dari kota barangkali, Bang. Mbok dan anak-anak tentu akan senang punya suami dan bapak yang pintar ngomong kayak guru ngajinya si Tarmin. Ayolah, Bang!”
Tarjo tersipu. Terus terang ia memang paling suka gaya bicara Kyai Hamid, guru ngajinya si Tarmin anak bungsunya itu. Benar-benar karismatik, seperti ustaz Aa Gym dalam kuliah subuh di TV.
“Ayolah, Bang. Cobalah lidah ini!”
Tarjo tertawa ngakak.
“Ngapain tertawa, Bang?”
“Apa kau tahu siapa pemilik lidah itu, Mbok? Bagaimana kalau lidah itu ternyata milik seorang demonstran yang kayak di TV itu, Mbok? Atau milik seorang penjahat, misalnya, Mbok? Orang yang suka menyebarkan desas-desus? Nah, bagaimana kalau lidah itu ternyata milik seorang yang suka mengkritik, Mbok? Atau bagaimana kalau seandainya lidah itu milik pejabat yang suka menipu rakyat? Bagaimana kalau lidah itu kepunyaan genderuwo?”
Mbok Minah tersenyum nakal.
“Bagaimana kalau kita simpan saja lidah ini, Bang?”
“Terserah kau sajalah.” balas Tarjo.
Dan seperti yang dikatakan pada suaminya, Mbok Minah lalu menyimpan lidah itu di atas langit-langit rumahnya agar tidak dikira daging sapi oleh Tarmin anaknya, yang mungkin lalu ia goreng dengan sambal terasi sebagai lauk makan sebelum ngaji. Siapa tahu, angannya.
Tapi betapa terkejutnya ia ketika didapatkannya lidah itu sudah terselip begitu saja ditali kutangnya. Mbok Minah tentu jijik bukan main. Ia lalu membuang lidah itu sejauh-jauhnya. Tapi aneh, sebentar kemudian ia mendapatinya sudah ada di saku roknya, kadang di bawah bantal di atas seprei, bahkan lidah itu menyelusup di kolong tempat tidurnya, masuk dalam mimpinya setiap malam.
Sembari menyandarkan kepalanya dibantal, Mbok Minah melihat lidah itu melayang-layang di rel kereta api, tepat di sekitar pemukiman kumuhnya, lalu membesar dan menjilati semua rumah-rumah kardus di sekeliling rumahnya itu menjadi recehan uang yang sangat banyak!
Berikutnya juga lidah itu kemudian menjilati semua gedung dan pusat perbelanjaan di sekitarnya. Intinya seluruh kota dijilatinya lahap. Mbok Minah heran melihat semua yang dijilati lidah itu menjadi recehan uang yang banyak.
Buru-buru Mbok Minah berlari masuk ke ruangan tengah untuk memberi tahu suaminya.
“Bang. Abang, Tarjo, sekarang Mbok tahu lidah siapa itu,” ia berteriak gembira. “Lidah itu ternyata kepunyaan hakim yang di TV kemarin hari.”
Sunyi-sepi sekeliling.
Tapi selain sepi yang ia dapati, Bang Tarjo, suaminya, seakan sembunyi.
“Lidah sialan!” umpat mbok Minah.
Sejurus kemudian dengan sepotong tisu, lidah itu ia genggam dan dilemparnya jauh-jauh. Jauh-jauh, berharap akan ada seekor anjing kelaparan yang menerkamnya dengan lahap.
***
Betul saja, sebelum dilindas sendal jepit orang yang lalu-lalang, seekor anjing berbulu hitam menemukan potongan lidah yang terbungkus kain tisu itu, menjepitnya di antara gigi geriginya yang tajam, lalu bergegas menuju ke sebuah Villa.
Sayang, sebelum pemilik Villa itu melihat apa yang dibawa si anjing, tiga butir peluru telah ia muntahkan, tepat mengenai batok kepala anjing berbulu hitam tersebut. Si penembak berdiri, lalu mengumpat dengan suara yang tak begitu jelas terdengar.
“Saya kan sudah bilang, jangan kembali sebelum menemukan lidah sialan itu. Dasar anjing bodoh!”
Wahyu Sastra, lahir pada tanggal 4 April tahun 1982 di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Indonesia. Jatuh cinta pada karya fiksi sejak kuliah di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Makassar. (tahun 2000). Ia menyukai seni lukis, sketsa, gambar, karikatur. Di dunia literasi, pada Oktober 2023, Wahyu menggagas terbentuknya Rumah Aksara NTB, sebuah komunitas muda yang bergerak untuk meningkatkan minat baca dan menulis fiksi di Nusa Tenggara Barat. Hingga hari ini Wahyu sudah menulis beberapa buku. Ia menyukai semua jenis tulisan fiksi : essay, puisi, cerpen dan novel. Awal menulis ia menyukai gaya surealis untuk cerpen dan mantra di puisi. IG : wahyusastra.penulis