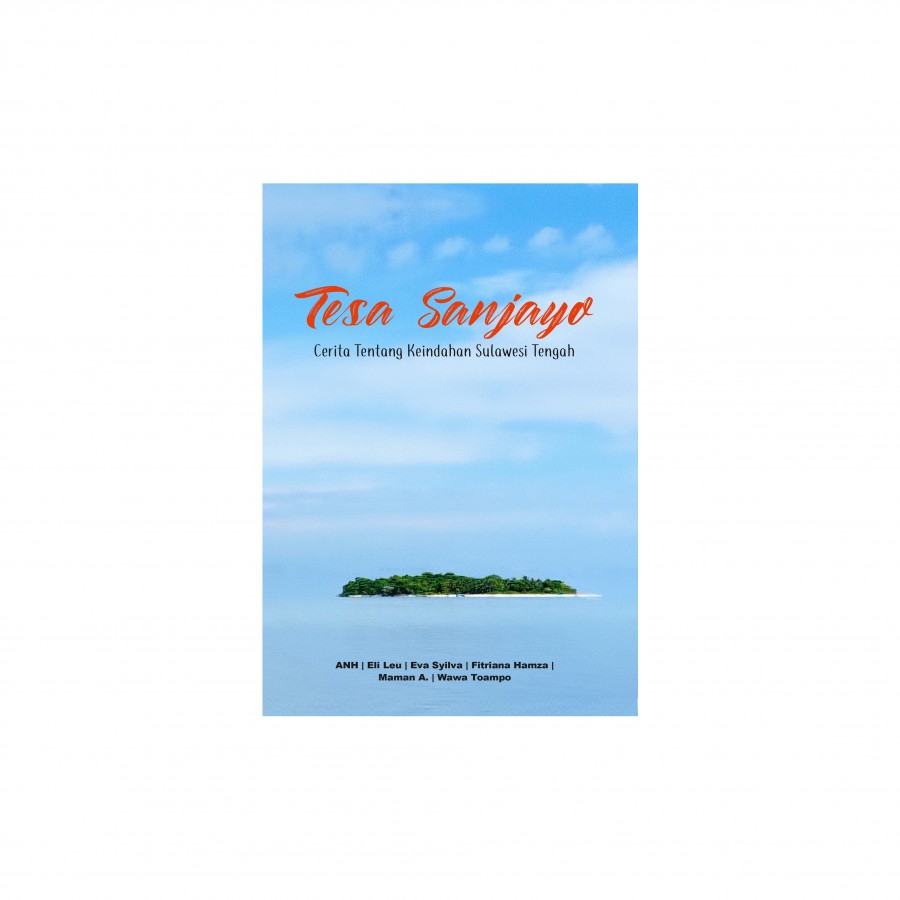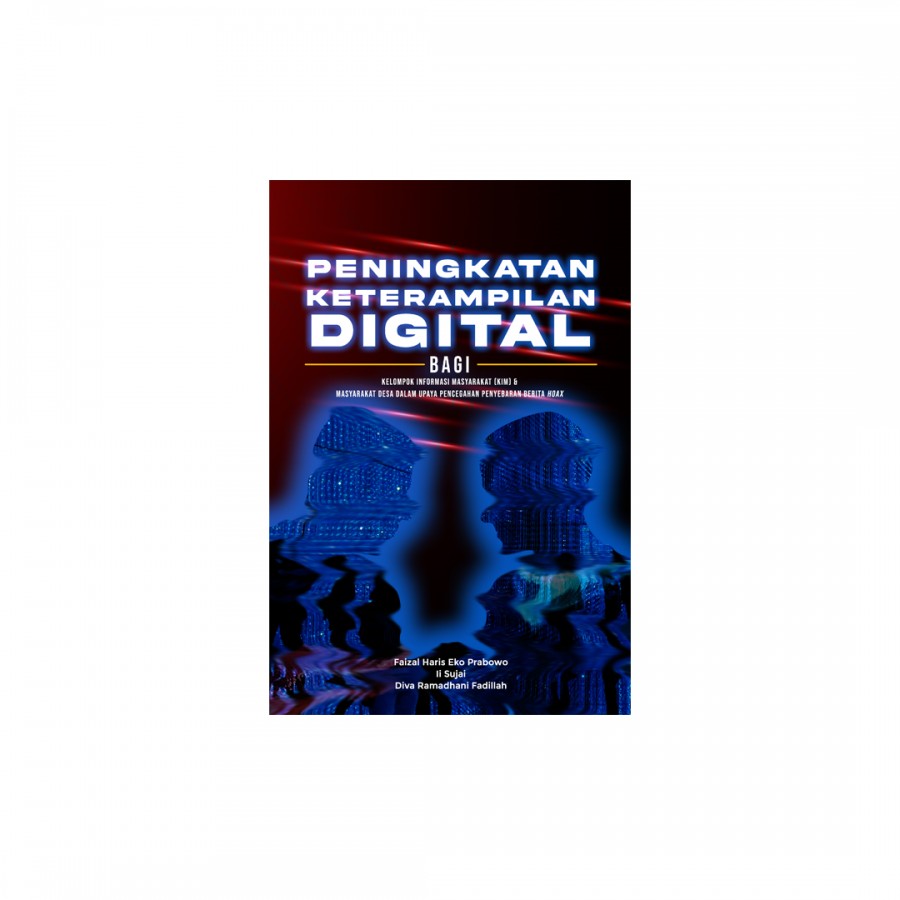BAGI seorang pemalas yang dipaksa untuk menyapu halaman, gugur daun itu sebuah kejengkelan. Sedangkan pengamat alam membacanya sebagai pertanda kemarau. Boleh saja para penyair merasakan daun-daun yang Berjatuhan itu semacam puisi. Tidak akan menjadi dosa besar juga jika kita tak memiliki anggapan sedikit pun tentang itu. Tentang hal-hal yang sudah terlewatkan tanpa makna.
Tetapi tidak berlaku bagi sebagian orang yang percaya, hal kecil serupa kepak kupu-kupu dapat menyebabkan perubahan pada lapisan atmosfer. Benar, kita sering kali melewatkan hal kecil itu begitu saja. Membiarkannya berlalu terbawa waktu, hingga pada akhirnya sesuatu yang besar telah menimpa kita. Sesuatu yang berasal dari tumpukan takdir.
Seperti halnya yang tegah dialami Fana. Kini ia berada di sebuah rumah dengan pelataran yang luas. Duduk berdua bersama tuan rumah di beranda. Berbincang sambil menikmati suguhan kopi. Di pekarangan itu terdapat pohon-pohon. Suasana hati Fana kini sudah tenang. Padahal semalam jiwanya dalam kondisi rapuh. Ia hendak mengakhiri hidup. Satu langkah kaki tubuhnya mungkin sudah terburai. Untungnya, si Tuan rumah ini dapat mencegahnya melompat dari atas gedung.
“Kehidupan itu...” Tuan rumah berkata kepada Fana. Ia menahan ucapannya, menyeruput segelas kopi hangat dan menghisap keretek.
“Kehidupan itu?” tanya Fana penasaran.
Fana memperhatikan wajah orang itu dalam-dalam. Matanya sangat tajam. Ia tak berani menatapnya langsung. Dialihkanlah pandangannya itu pada dahi, terdapat keriput dan tanda hitam di sana. Kata orang, hanya seorang ahli beribadah saja yang memiliki tanda seperti itu.
“Tunggu, apakah Saudara mendengarkan azan berkumandang?” tanya tuan rumah mengalihkan pembicaraan.
“Saya tidak terlalu yakin, Tuan. Tetapi, sepertinya sebentar lagi memasuki waktu Ashar.”
“Ah...” orang itu menghela nafas sambil menyingsingkan lengan baju kirinya. Memperhatikan jam emas di pergelangan. Jarum pendek hampir menyentuh angka tiga, sedangkan yang panjang di angka enam. Di bawah jam itu terdapat gambar yang terlihat samar, tapi sudah pasti itu adalah sebuah tato.
“Masih lama, kok. Silakan Saudara cicipi kopinya, nanti keburu dingin! Bukankah kenikmatan kopi itu ketika sedang panas. Jangan sampai Saudara melewatkannya!”
“Terima kasih, Tuan.” Fana menjawab sambil mengambil cangkir miliknya. Ada keraguan yang terbersit di hatinya karena melihat tato itu. Air mukanya berubah. Seakan tak percaya dengan apa yang ia lihat.
Tanpa sengaja, ia menumpahkan kopinya. Sontak, hal itu membuatnya menjadi kikuk. Tak pernah sedikit pun ia berpikir seorang yang dianggapnya alim itu memiliki tato. Orang yang baru dikenalnya itu, yang memasukkan kedamaian di hatinya yang keruh itu, adalah seorang yang bertato.
“Ah, maaf Tuan. Saya tadi tak sengaja.” Ucap Fana sambil membersihkan tumpahan kopi di meja.
“Tak perlu risau. Pasti Saudara kaget melihat tato ini, kan? Toh, tato ini pun merupakan bagian dari tubuh saya. Ia melekat di sini. Pada pergelangan mengitari nadi. Wajar saja bila saudara memandang saya menjadi lain. Terlebih saya mengenakan peci berwarna putih.”
“Tidak, saya tidak bermaksud begitu.”
“Tak bisa dipungkiri, manusia memang demikian. Saya pun terkadang keliru dalam menilai seseorang.”
Suasana diliputi kecanggungan. Fana menjadi malu terhadap dirinya. Ia termenung memandangi secangkir kopi yang tinggal setengah. Hitam pada cangkir itu memantulkan wajahnya. Ia melihat dirinya. Angin berembus kencang, membawa serta debu dan daun-daun mati. Daun-daun itu kemudian berjatuhan di pekarangan.
“Ah, kehidupan itu...” kata Si Tuan rumah mencoba memecahkan kecanggungan, ia menghayati angin yang mendera wajahnya.
Namun, maksud baik itu tak bisa dicerna Fana. Ia mengartikannya menjadi sesuatu yang lain. Kejengkelan. Ia merasa dipermainkan.
“Tuan, bolehkah saya bertanya, mengapa Tuan sela-lu tak selesai melanjutkan kata-kata ketika Tuan menyebutkan kehidupan? Memang benar, bahwa semalam Tuan telah menyelamatkan hidup saya. Tetapi pada percakapan kita sore ini, ketika Tuan bicara mengenai kehidupan, Tuan selalu begitu. Apakah Tuan hendak mengejek saya? Jika akhirnya begini, lebih baik Tuan membiarkan saya mati saja! Maaf bila saya lancang.” Kata Fana memberanikan diri.
“Ah, maafkan jika sikap saya ini menyinggung. Jujur, saya tidak ada maksud demikian. Kesejatian hidup itu sangat sulit untuk diungkapkan. Sulit diartikan. Saya hanya takut Saudara memiliki makna tersendiri tentang kehidupan. Ah, sekali lagi maafkan jika perbuatan saya itu menyinggung perasaan Saudara.
Terlebih angin tadi mendesir begitu syahdu. Saya hanya tak ingin melewatkannya, tidak lebih. Angin itu. Angin musim kemarau yang kering. Angin yang mengembuskan kehidupan sekaligus kematian.
Kematian bagi daun-daun yang renta. Namun, daun-daun itu akan lapuk dan menjadi pupuk. Menjadi kehidupan. Dan, kehidupan pun akan berlangsung jika si pohon memiliki serbuk sari, atau biji-biji yang beterbangan seperti pohon mahoni. Ah, angin itu begitu syahdu, benarkan Saudara?”
Mendengar jawaban dari tuan rumah, Fana termenung. Kata-kata yang lembut tapi menusuk. Tepat ke dasar jantungnya. Ia tak bisa berkata-kata. Ia malu terhadap kelancangannya. Hanya karena sebuah tato dan ucapan yang tak selesai ia menilai buruk seseorang. Fana kini berpikir: Apakah hatinya sudah lebih pekat dari kopi?
“Saudara,” Kata tuan rumah sambil menepuk bahu Fana. “Tidaklah wajar daun gugur oleh angin di malam hari, kecuali ada badai yang menerpa. Terlebih daun itu masih muda, belum saatnya ia terjatuh. Malam adalah tenang. Semua beristirahat, termasuk bumi. Kecuali pada malam itu bumi sedang sakit. Bukankah Saudara serupa daun yang hendak jatuh di malam hari? Jika boleh tahu, apa gerangan yang membuat Saudara ingin berbuat demikian?”
Fana masih kikuk. Ia tak menjawab. Orang itu memberikan simpul senyum. Senyum paling sejuk. Pada senyuman itu tergambar ketulusan. Hati Fana kembali tergerak. Mungkin oleh senyum inilah orang itu meluluhkan hatinya. Melunturkan keinginannya untuk mengakhiri hi-dup tadi malam. Fana memintanya untuk mengulangi pertanyaan tadi. Di hatinya sudah mulai timbul kepercayaan.
“Jika saya boleh tahu, apa gerangan yang membuat Saudara ingin berbuat demikian?” Tuan rumah bertanya singkat.
“Apa artinya saya hidup pun saya tak tahu. Ada atau-pun tidaknya saya di dunia ini mungkin tak begitu berpengaruh. Sejak kecil, saya selalu diabaikan oleh orang tua, dicaci-maki, bahkan tak jarang mendapatkan siksaan. Saya sempat berpikir untuk mengakhiri hidup sejak dulu.
Saat ini, permasalahan hidup semakin rumit. Hutang yang melilit, ditagih oleh rentenir, kena PHK. Keinginan untuk mengakhiri hidup pun kembali muncul, tekad itu semakin bulat saat kuliah istriku mendua. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ia bercinta dengan lelaki lain.” Fana bercerita panjang lebar. Tanpa terasa, air matanya mengalir, membasahi pipi.
“Sungguh berat apa yang Saudara alami.” Ucap tuan rumah prihatin. Ia merangkul Fana erat, kemudian mengusap-usap pundaknya. Sampai tangis itu reda. Setelahnya, ia lanjut berkata, “tetapi, begitulah hidup, Saudara. Paradoks. Bukankah kita bernapas itu untuk hidup? Namun, Dengan napas itu pulalah kita mendekati kematian. Oksidasi membawa kita mati secara perlahan. Kita telah mengemban beban sejak kita dilahirkan. Gen dan sel dalam tubuh kita telah terbiasa menanggung beban yang bebal itu. Penyakit-penyakit jiwa. Itulah yang memberat-kan hidup. Ah, maaf jika saya terkesan menceramahi.
Tetapi Saudara telah keliru, saya harus meluruskan. Itulah kewajiban saya. Itulah takdir saya. Takdir Saudara juga. Seandainya saya tak berada di balkon kantor malam kemarin, tentunya cerita yang tercipta akan berbeda. Mungkin, kita tak akan menikmati kopi beserta angin kemarau yang kering ini di beranda. Bukan begitu, Sau-dara?
Ah, sederhananya Saudara selalu melewatkan hal-hal kecil dalam hidup. Itulah yang menyebabkan prasangka berlebihan. Saudara pasti tidak menyadari pernah berbuat kebaikan. Seperti halnya membuang paku dari jalan. Mungkin awalnya Saudara tak sadar, bahkan merasa jengkel karena tertusuk. Tetapi, tanpa Saudara sadari, Saudara telah menyelamatkan beratus-ratus kendaraan yang melintas, misalnya.
Tentunya, sabar terhadap cobaan pun merupakan kebaikan. Namun, bukankah Saudara tidak tahan? Sau-dara tergoda untuk mengakhiri hidup. Saudara kurang memperhatikan hal-hal kecil. Jika Saudara hendak melihat, saya tak keberatan untuk memperlihatkan.”
Orang itu membuka jam emasnya. Meletakkannya dekat asbak di atas meja. Gambar itu pun kini terlihat jelas. Tato Naga. “Ini, gambar ini saya buat untuk menutupi sayatan pada nadi. Dahulu saya pun sempat berada di posisi Saudara. Saya merasakan apa yang Saudara rasakan kemarin. Saya mengerti.” Tandas orang itu seraya mematikan puntung rokoknya.
Fana tercengang. Benar, di tangan orang itu terdapat luka yang tertutup oleh naga. Luka yang merobek nadi. “Orang ini serupa gunung es. Tak bisa ditebak.” Pikir Fana.
“Sekali lagi saya katakan. Kita dipertemukan oleh takdir. Suatu saat, jika takdir berkata, Saudara pasti akan dipertemukan dengan orang yang memiliki permasalahan hidup yang sama. Saat itulah, Saudara akan berperan seperti saya. Karena saya pun dulu begitu, ada seseorang yang menyelamatkan hidup saya.”
Fana mencermati setiap kata-katanya. Ia tak membantah. Pikirannya melayang jauh. Pada sebuah paku. Ya, ia pernah menyingkirkan sebuah paku ke tepi jalan. Ingatan tentang kebaikan-kebaikan kecil lainnya pun turut bermunculan. Ada juga kebaikan-kebaikan besar yang per-nah ia lakukan terbersit di pikirannya. Ah, namun kebaikan-kebaikan besar itu hanya membuatnya pamrih.
Bahkan kini pikiran Fana dapat melacak sebab-sebab kecil mengapa semua beban ini menimpanya. Jauh. Jauh sebelum ia mendapati istrinya selingkuh, ekonomi keluarganya hancur dan di PHK. Ia mengingat masa-masa kecilnya dulu. Ia ingat karena hal sepele ia selalu dimarahi oleh ayah, selalu diabaikan oleh ibu.
Fana kini mengingat masa kerjanya. Saat ia giat untuk mengambil lembur. Ternyata, ia telah membuka petaka bagi rumah tangganya. Istrinya tak pernah mendapat belaian. “Ia kesepian, wajar saja bila selingkuh” Pikirnya. Apa yang dikejar Fana dulu semasa kerja sekarang baginya adalah sebuah komedi: Untuk keluarganya ia rela lembur, tetapi karenanya keluarga hancur.
Sampai akhirnya, ia merasa lelah dengan pekerjaannya. Ia menjadi tak bersemangat, sehingga pada suatu waktu Fana melempar masam mukanya pada atasan. Sialnya, atasan itu adalah orang yang pendendam. Suatu Fana membuat kesalahan. Ia dipanggil ke ruangan untuk diminta pertanggung jawaban. Akhirnya, ia di PHK.
Rentetan peristiwa itu, yang menjadi alasannya bunuh diri, kini begitu menggelitik hatinya. Dari hal sepele seperti melemparkan muka masam ia tertimpa beban ini. Kemudian, Fana menertawai itu. Menertawai takdir. Komedi dan Tragedi kehidupan. Tuan rumah itu benar pikir Fana.
Angin berembus sekali lagi. Membawa serta daun-daun yang terus berjatuhan. Daun-daun yang sudah tua. Juga debu-debu. Tuan rumah kembali menghayati angin yang menepis wajahnya. Fana melakukan hal yang sama.
“Ah, kehidupan itu serupa daun-daun.” kata Fana sambil menyeruput kopi yang hampir dingin. Ia tersenyum kepada orang itu. Simpul senyum yang sama teduh. Kemudian ia berkata lagi, “Kehidupan itu serupa daun-daun, Tuan. Ah, mohon maaf saya menuntaskan kata-kata yang sempat Tuan tunda.”
Galang Gelar, lahir di Bandung 6 Desember 1997. Menetap di Ciamis sejak SD. Bukan seorang pribadi yang baik dalam bersekolah formal. Menulis cerpen dan sudah menerbitkan sebuah buku kumcer berjudul "Darahmu Tetap Saja Berwarna Merah"
*Cerpen ini diambil dari buku kumcer berjudul "Darahmu Tetap Saja Berwarna Merah" karya Galang Gelar. Banyak cerita menarik lainnya di buku tersebut. Dapatkan bukunya (di sini) untuk mendapatkan potongan harga.