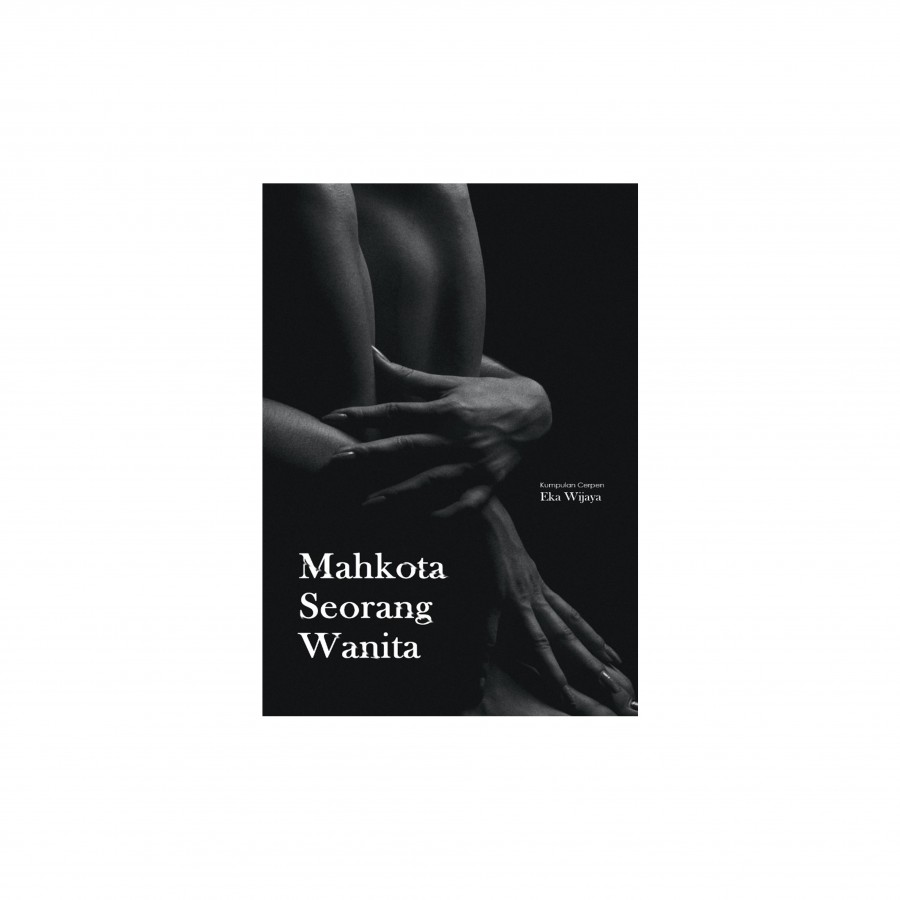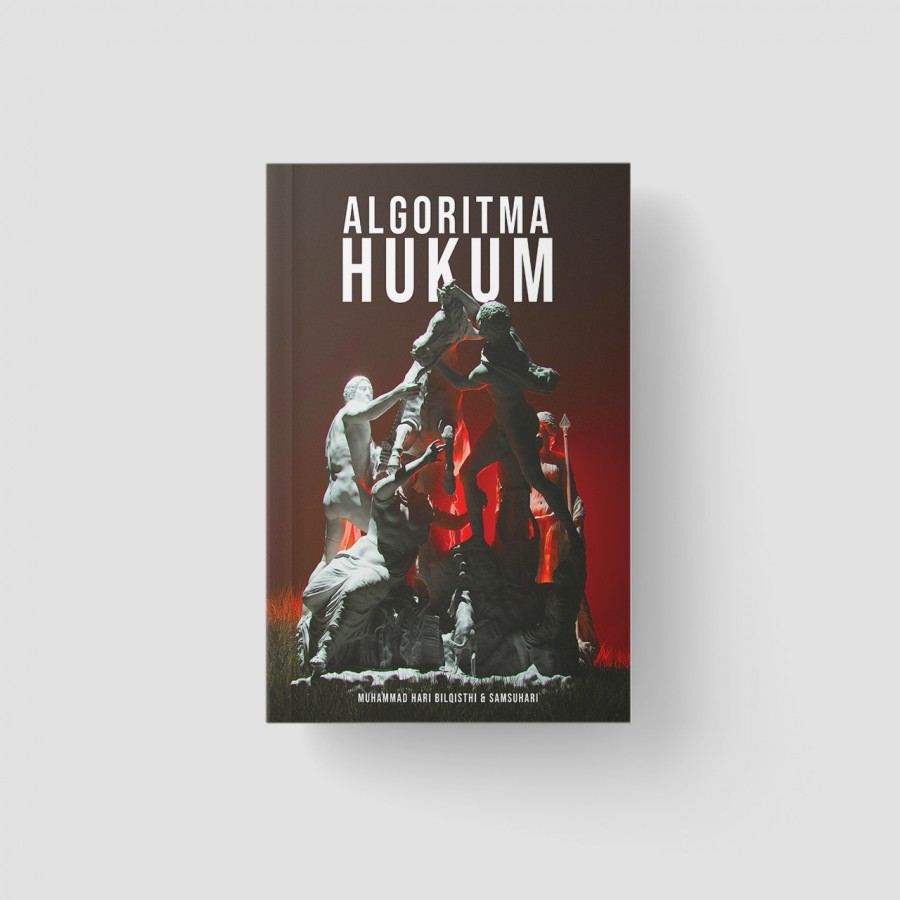Ratna mengepalkan tangan, menahan gejolak amarah yang membara di dadanya. “Sudah berapa kali aku bilang, tanah itu takkan pernah jatuh kepada kalian! Niat buruk itu takkan pernah aku biarkan tercapai! Tek Lis, mendiang ibuku dan keturunannya yang berhak memilikinya! Kenapa Datuak masih saja keras kepala perihal ini? Berapa kali lagi akan kau seret aku ke pengadilan? Tidakkah Datuak lihat? Aku. Selalu aku yang menang di pengadilan! Setinggi apa pun jabatan Datuak dalam kaum ini, yang namanya hakku, tetaplah punyaku. Takkan pernah menjadi milikmu dan tua bangka itu!”
Datuak Rajo, tetua kampung yang disegani, mengerutkan kening. “Atas dasar apa kau berbicara begitu, hah? Aku tetua kampung ini. Aku yang tahu bagaimana seluk-beluk kaumku! Enak saja kau bilang begitu, memandang rendah orang yang jadi kepercayaan kaum! Aku Datuak kau! Aku ketua Kerapatan Adat Nagari di tanah yang kini kau pijak. Bustam, mamak kau itu masih bernapas dan berjalan di dunia ini. Tidakkah kau malu merebut hak dari Mamak kau?”
“Duhai Datuak yang paling tinggi, Tetua yang paling aku segani dalam kaum. Tanah ini, takkan pernah jatuh semuanya kepada Mamakku itu. Datuak kira aku tak tahu apa? Orang-orang kota itu ingin memperbaiki irigasi nagari ini. Dan pipa airnya akan mengambil banyak tempat di tanah kami. Pemerintah akan memberi uang ganti-rugi untuk itu. Datuak bersekongkol dengan mamakku yang tua itu demi uang, kan? Tanah bagiannya sedikit sekali yang terpakai, kan? Hanya sedikit uang yang akan didapatinya. Karena rasa tamaknya itu, diajaknya Datuak dan petinggi adat lain berada di pihaknya. Kalian sudah merencanakan hal ini dari jauh-jauh hari. Takkan kuizinkan kau mengambil hak kami sedikit pun!” Ratna meledak, emosinya tak terbendung.
Bustam, Mamak Ratna, berteriak. “Upiak! Omong kosong apa yang kau bicarakan. Di mana otakmu? Berani-beraninya kau menuduh Datuak dan mamakmu yang tidak-tidak! Tidakkah kau diajari adab? Sopankah kau berteriak begitu pada Datuak kau? Aku sudah muak sekali sebetulnya. Kau kamanakan tak tahu adab! Selama ini kau tak pernah aku bentak. Tapi melihat adab kau sekarang, tak lagi bisa kutahan rasanya! Tanah itu memang sudah dibagi tiga. Ada jatahku, jatah etek kau, dan jatah bundo kau di sana. Tapi aku belum mati! etekmu juga belum mati! Tanah itu masih menjadi hakku!” Urat-urat di kepala Bustam seperti ingin keluar.
“Dasar tak tahu sopan santun! Keluarlah kau dari rumahku ini!” Kesabaran Datuak Rajo sudah habis, ia mengusir Ratna dari rumahnya.
“Baiklah, aku pergi dulu. Bagaimanapun aku akan memperjuangkan hak ibuku dan Tek Lis!”
Derap Langkah Ratna terdengar di tengah rumah yang besar itu. Akhir-akhir ini, Mamak dan keponakan itu bersitegang mengenai tanah warisan mereka. Sudah berapa kali kasus ini dibawa ke pengadilan, tetap saja Bustam kalah. Tanah itu dinyatakan milik Ita dan Lis, adiknya. Ita adalah ibu dari Ratna, sudah lama meninggal. Dan Lis, adiknya itu seperti tidak peduli dengan persoalan mereka, Lis tak peduli soal uang ganti-rugi. Karena itulah, ia berani menggugat keponakannya, Ratna perihal tanah warisan. Dengan menyogok Datuak dan petinggi adat nan tamak itu, mudah baginya membuat Datuak Rajo berada di pihaknya.
Perselisihan ini bermula dari rencana perbaikan irigasi di Nagari Koto Gadang. Pemerintah akan memberikan uang ganti rugi yang fantastis kepada pemilik tanah yang terkena proyek. Bustam, tanah saudaranya paling banyak terdampak. Ia berniat memanfaatkan situasi ini untuk memperkaya diri. Tanah mereka tak memiliki batas resmi, hanya pohon durian sebagai penandanya. Tanah sebelah Utara milik Bustam, sebelah timur milik Lis dan sebelah barat milik mendiang Ita, adiknya. Proyek itu hanya mengenai sedikit tanahnya di perbatasan milik Ita dan Lis. Pikiran licik menguasainya. Di perbatasan tanah ketiganya hanya ditandai dengan pagar kayu. Ia menggeser pagar kayu itu diam-diam agar ia menerima uang ganti-rugi lebih banyak. Kesempatan emas! Ia akan jadi kaya raya.
Ratna mengerutkan kening, heran melihat pagar kayu yang menjadi batas tanah milik Bundo, Mamak, dan Eteknya tampak bergeser. Awalnya, ia tak terlalu curiga. Namun, saat hendak mengunjungi rumah Mamaknya untuk mengantarkan rendang, langkahnya terhenti. Suara percakapan di dalam rumah terdengar jelas, meskipun ia tak bermaksud menguping. Kata-kata seperti “tanah”, “uang kompensasi”, “pemerintah”, “irigasi”, dan “jatah per orang” berputar-putar di kepalanya.
Seketika, Ratna memahami situasi. Kekecewaan menggerogoti hatinya. Mengapa Mamak yang ia hormati tega melakukan hal itu? Mamaknya hanya menginginkan uang untuk dirinya sendiri. Eteknya, Lis, takkan pernah peduli. Ratna tak bisa membiarkan hal itu terjadi. Ia berbalik arah, pulang ke rumah, tanpa jadi menemui Mamaknya.
Sejak hari itu, Ratna membenci Mamaknya. Ia memilih untuk tidak menceritakan hal ini kepada Eteknya, tak ingin membebani wanita tua itu.
“Dasar tua bangka, sudah bau tanah masih saja sibuk perkara uang. Takkan kubiarkan, lihat saja nanti. Tek Lis tidak akan peduli mengenai hal ini, Tek Lis selalu mengutamakan saudara-saudaranya. Ia takkan ribut perkara uang. Atau mungkin saja Tek Lis akan memberi semua bagiannya kepadaku? Astaga, bukankah tanah Tek Lis yang paling banyak terkena dampak? Uangnya juga akan lebih banyak dari milik Bundo. Alamak, kaya mendadak aku ini!” Ratna tersenyum senang.
“Cih, tua bangka itu pasti akan merencanakan kemenangan baginya, pantas ia membawa Datuak dan gerombolannya. Dia kira aku tidak tahu akal busuknya. Jika ia membawa perkara ini ke pengadilan, aku akan membawa nama Bundo dan Tek Lis agar menang. Tentu saja ini akan berhasil. Tanah yang terkena itu hanyalah tanah Tek Lis dan Bundo. Proyek itu hanya lewat sedikit di tanah tua bangka itu. Dengan drama air mata, aku akan memiliki simpatisan dari masyarakat sekitar. Hahaha, mudah saja perkara ini.” Ratna tertawa puas di dapur rumahnya sendirian. Bayangan uang banyak datang kepadanya.
Kejadian itu terjadi waktu lalu, Bustam membawa kasus ini ke pengadilan. Hasilnya, setelah dilakukan pengukuran sesuai sertifikat tanah, terbukti bahwa Bustam telah menggeser batas tanahnya ke arah milik Lis dan Ita. Uang kompensasi yang besar itu pun akan jatuh ke tangan Lis dan Ratna, ahli waris Ita. Ratna, bersama Lis, selalu memenangkan persidangan. Mereka tampil sebagai korban dalam kasus ini.
Kabar perselisihan ini menyebar luas, menarik perhatian masyarakat Nagari Koto Gadang, bahkan hingga ke luar daerah. Banyak yang iba melihat Ratna memperjuangkan hak Bundo dan Eteknya yang sudah tua. Mereka mengutuk perbuatan Bustam dan Datuak Rajo. Namun, tidak sedikit pula yang membela Datuak. Masyarakat terpecah menjadi dua kubu. Sebagian masih percaya kepada Datuak Rajo, meyakini bahwa ia tak mungkin melakukan hal itu dan pasti tahu yang terbaik untuk kaumnya. Sementara itu, kubu lainnya mendukung Ratna, gadis yang dianggap ditindas oleh Datuak dan Mamak kandungnya.
Perselisihan itu telah berlangsung selama dua tahun. Hari ini, pihak pemerintah memberikan informasi kepada Zul, Wali Nagari Koto Gadang, bahwa uang ganti rugi akan dicairkan secara bertahap dan proyek akan segera dimulai. Kabar ini sampai ke telinga Bustam. Ia langsung mengajak Datuak Rajo menuju kediaman Zul.
Di sana, Datuak Rajo mendesak Zul untuk menyerahkan jatah uang ganti-rugi tanah Lis dan Ita kepada Bustam.
“Biarlah uang itu diurus oleh keluarga mereka,” desak Datuak.
Zul, yang merasa terdesak, mencoba menjelaskan dengan sabar. “Datuak, bukan aku bermaksud menolak permintaan Datuak, tapi dalam pengambilan uang ganti rugi ini haruslah disertai bukti sertifikat tanah dan tanda tangan pemilik. Jika ingin diwakilkan, Uda Bustam harus membuat surat pernyataan kuasa atas Ita dan Lis. Tanda tangan Ita bisa diwakilkan oleh ahli warisnya, Ratna. Barulah aku bisa menyerahkan uang ganti rugi ini kepada Uda Bustam,” terang Zul.
“Baiklah kalau begitu. Kau tunggulah Zul. Akan diurus suratnya oleh Bustam. Kalau begitu aku pamit dulu. Dan aku peringatkan kau, jangan sampai uang itu kau berikan kepada Ratna!” Datuak Rajo meninggalkan rumah Zul dengan nada mengancam. Zul hanya mengangguk pasrah.
Di perjalanan pulang, Datuak Rajo tak lupa mengingatkan Bustam. “Jika uang itu nantinya sudah kau dapatkan, jangan lupa kau bagi aku dan yang lain, Bustam. Kau ingatlah perjuangan aku selama ini. Aku rela namaku dicap buruk oleh kaumku hanya untuk memenangkan sengketa kau ini. Jangan kau lupa bagianku!” ucapnya.
“Aman Datuak, jangan Datuak ragukan itu. Jika uang itu sudah sampai di tanganku, akan kubawa Datuak ke Tanah Suci! Ikutan yang Datuak inginkan?” jawab Bustam.
“Hahaha, tahu saja kau Bustam. Tapi bisalah kau ajak aku ke Bali bersama Istriku. Ia merengek ingin pergi ke Bali di usia senjanya.” Datuak Rajo kembali menyebutkan permintaannya.
“Oi, apa pun itu Datuak. Asal Datuak berhasil membuat uang itu jatuh sepenuhnya kepadaku,” ujar Bustam. Hingga sampailah mereka di rumah masing-masing.
Sayangnya, takdir berkata lain. Keesokan paginya, Bustam ditemukan meninggal dunia. Ia terjatuh di kamar mandi, kepalanya terbentur keras ke lantai. Pemakaman segera dilangsungkan. Desas-desus berhembus di antara warga.
Di sisi lain, Datuak Rajo dilanda kekhawatiran. “Ais! Mati pula si Bustam. Bagaimana ini, sudah jauh langkahku sampai ke sini, tak mungkin aku biarkan menjadi percuma. Uang kompensasi itu akan cair esok lusa. Lis dan Ratna yang akan menerimanya. Tidak akan kubiarkan. Bagaimana pun aku harus tetap memiliki uang itu!” gumam Datuak Rajo di rumahnya.
Ratna, yang mendengar kabar kematian mamaknya, menunjukkan ekspresi gembira. “Astaga, akhirnya aku tak usah susah-susah ke pengadilan lagi. Akhirnya drama episode aku menjual air mata cukup hari ini. Uangnya akan jatuh kepadaku! Tua bangka itu tak punya keturunan, istrinya juga sudah lama meninggal. Hahaha, datanglah kepadaku uang!” ucap Ratna.
Tiba-tiba, Lis datang dan memukul pelan pundak Ratna. “Upiak, kenapa kau tersenyum-senyum? Belum selesai kau berkemas? Ayo kita kembali ke rumah Mamakmu, pasti sudah banyak tamu. Tadi aku meminta tolong si Wil menyambut tamu yang ingin mengantarkan beras. Kasihan, pasti ia sudah sangat kewalahan. Cepat, Upiak, kita ke sana,” pinta Lis kepada keponakan satu-satunya.
“I-iya, Tek. Aku sudah selesai. Mari kita pergi,” jawab Ratna gugup.
Mereka berdua segera menuju rumah duka, menyambut tamu yang berdatangan. Hingga malam hari, Ratna dan Lis sibuk menyiapkan pengajian kecil untuk mendiang Bustam. Mereka memutuskan untuk bermalam di rumah Bustam.
Tiga hari berlalu sejak kematian Bustam. Kekhawatiran mulai menggerogoti Datuak Rajo. Warga sudah mulai menerima uang kompensasi.
“Bagaimana ini, Ratna dan Lis takkan mengambil uangnya untuk beberapa hari ini, kan? Mereka terlalu sibuk mengurus pengajian untuk Bustam. Apa aku harus mendatangi si Zul? Meminta uang itu agar aku saja yang membaginya. Aku bilang saja, sebelum kematiannya Bustam berpesan begitu kepadaku,” gumam Datuak Rajo, menggigit-gigit kuku jempolnya. “Ya, begitu saja. Aku akan menemui Zul.” Tanpa menunggu lama, Datuak Rajo bergegas menuju rumah Zul.
“Wah, Datuak, ada perlu apa kemari, mari masuk dahulu,” Zul mempersilakan Datuak Rajo masuk.
“Tak usah, di sini saja. Aku cuma ingin bilang, uang kompensasi itu, si Bustam berwasiat kepadaku. Ia ingin agar uang itu diberikan kepadaku terlebih dahulu. Nanti aku yang akan membagi kepada Lis dan Ratna.”
“Oi, Datuak. Apakah mendiang Uda Bustam berwasiat begitu? Sepertinya ini akan menjadi masalah yang panjang. Mari masuk sebentar Datuak, ada...”
Belum selesai Zul berucap, Ratna memotong ucapannya. “Oi, Datuak! Cerita apalagi yang akan kau karang, hah? Mamakku bahkan sudah mati. Takkan kubiarkan kau mengambil jatah kami. Kau tak memiliki hak atas uang ganti-rugi kami ini!”
Ratna dan Lis, yang baru saja tiba, menunjukkan kemarahan mereka. Datuak Rajo terkejut melihat mereka.
“Pandai sekali kau mengarang, Datuak. Oi, tampak akan percaya saja aku mendengarnya. Dari awal sudah jelas. Jatah Mamakku itu hanya sedikit. Selebihnya akan jatuh kepadaku semuanya. Eh, kepada Tek Lis juga maksudnya,” ucap Ratna, suaranya sedikit gugup.
Lis hanya diam, seakan percakapan orang-orang di depannya ini tak penting. “Ah, sudahlah terima saja kenyataannya, duhai Datuak yang paling disegani kaum. Kau takkan mendapatkan apa pun. Sedikit pun.” Ratna menekan intonasinya.
“Sudahlah, buang-buang waktuku saja. Tek, ayo pulang. Pak Zul, kami pamit pulang saja. Muak sekali aku melihat Datuak gila uang itu!” Ratna berlalu begitu saja, tanpa menghiraukan Zul yang mencoba menenangkannya.
“Oi Ratna, tidak baik berbicara begitu,” tegur Zul.
Tangan Datuak Rajo mengepal kuat. “Kau ajari sopan santun keponakan kau itu, Lis. Tak ada etikanya berbicara kepadaku. Ingin sekali kucabik mulutnya,” marah Datuak.
“Diamlah, Datuak. Muak juga aku lama-lama meladeni masalah ini. Kau tidak ada bedanya dengan hewan rakus yang mengincar hak milik kami! Jijik sekali aku dibuatnya,” Lis meninggalkan rumah Zul.
Sepasang sorot dendam terpancar dari mata Datuak Rajo. “Akan kubunuh kalian!” bisiknya dalam hati.
Dendam membara di hati Datuak Rajo. Semalaman ia tak bisa tidur, benci menggerogoti jiwanya. Bayangan Ratna dan Lis, yang telah mempermalukannya di depan Zul, terus menghantuinya.
“Kalian tunggu saja. Ini akan menjadi hari terakhir kalian!” gumamnya, mata melotot ke arah pisau yang paling tajam di rumahnya. Emosi sesaat menguasainya. Ia sudah bertekad untuk menghabisi mereka.
Datuak Rajo melangkah cepat menuju rumah Ratna. Ia memasuki rumah itu dengan langkah penuh amarah. Matanya mencari sosok Ratna. Pisaunya tersembunyi di balik punggungnya. Ketika sampai di kamar Ratna, ia melihat Ratna tertidur pulas. Tanpa ampun, ia menusuk Ratna beberapa kali dengan pisau yang telah ia siapkan. Ratna seketika terbujur kaku, tak bernyawa.
“Mati kau! Sekarang tinggal Lis, dan aku bisa memiliki uang itu sepenuhnya!” Datuak Rajo tertawa puas, suaranya bergema di ruangan itu. Bajunya berlumuran darah Ratna, namun ia tak peduli.
“Sial, tidak terpikirkan olehku ke mana akan kubuang mayat perempuan sialan ini,” gumamnya, wajahnya dipenuhi kebingungan.
“Aku kuburkan saja di halaman rumahnya, takkan ada yang sadar selama beberapa hari. Akan kulakukan hal yang sama kepada Lis. Dan sebelum orang-orang sadar, aku akan mendesak Zul memberikan uang itu kepadaku, lalu aku akan kabur bersama istriku sejauh-jauhnya. Ya, ya begitu saja,” monolognya.
Saat ia hendak menggendong mayat Ratna, tiba-tiba sebuah benda tajam menusuk jantungnya. Darah mengalir deras, menodai tanah. Pandangannya menjadi gelap. Ia kehabisan darah, tubuhnya ambruk. “Mati kau!” teriak seseorang. Pisau itu masih tergenggam erat di tangannya. “Mati juga kalian semua! Tak ada bedanya kalian dengan binatang yang berebut bangkai. Datuak yang rakus, Mamak yang tamak, dan kamanakan tak tahu diri. Dikiranya selama ini aku tak peduli masalah ini. Dikiranya aku tak tahu otak licik mereka. Sekarang nikmati siksa kalian. Tak kalian dapati uang-uang sialan itu!”
Suara itu berasal dari Lis. Pisau berlumuran darah masih tergenggam erat di tangannya. “Baiklah, setidaknya aku sudah membuat keributan ini berhenti. Aku berharap tidak akan ada Datuak Rajo, Bustam, dan Ratna yang lain di kampung ini,” ucap Lis, mengarahkan pisau ke jantungnya. Pandangannya pun menjadi gelap. Sudah. Semua telah berakhir.
Ghina Rufa'uda, Mahasiswi aktif Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas @ghinarufaudagazali