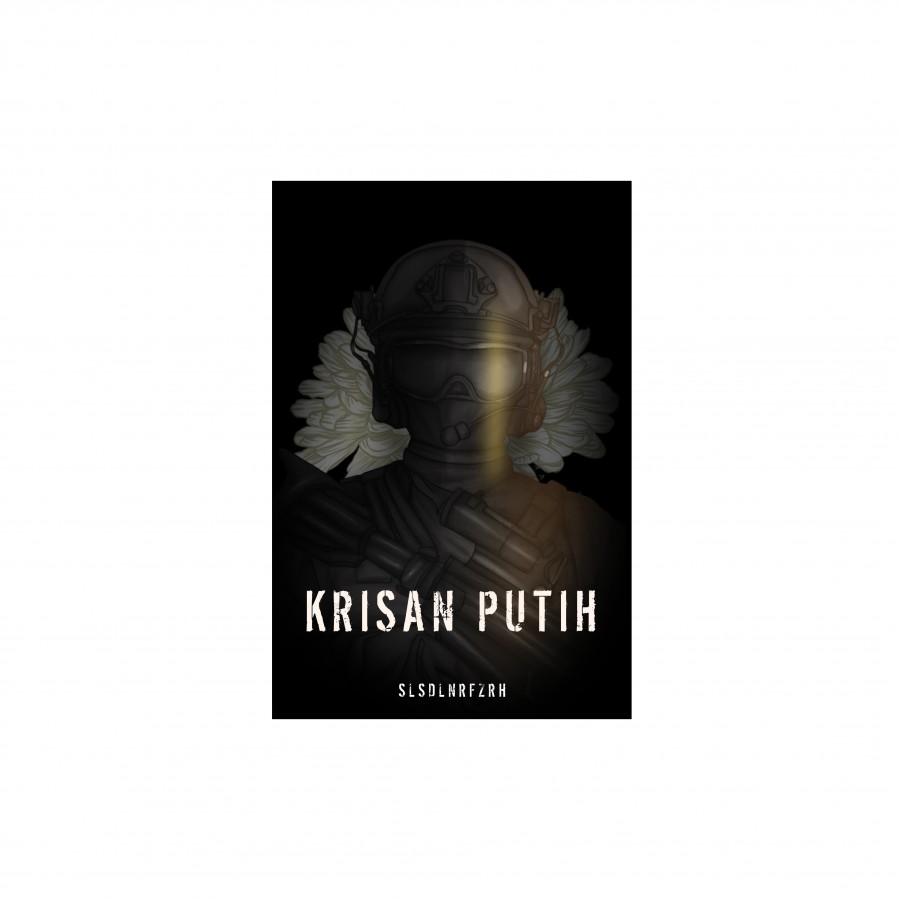Ibu pernah bilang bahwasanya sehari sebelum Niskala lahir, beliau memimpikan naga terbang mampir ke rumah untuk numpang makan nasi. Mohon jangan dicari apa arti mimpi tersebut, sebab saking tidak masuk akalnya, Niskala sendiri malu mendengarnya. Tapi yang pasti Ibu senantiasa mengulang-ulang hikayatnya itu seperti kaset rusak pada saat acara keluarga.
Bapak dulu pernah bilang, dahulu saat jaman penjajahan bahu kirinya sempat ditembak Belanda. Tidak seperti Ibu yang hanya menjelaskan hikayat kebanggaannya tanpa bukti konkret. Bapak justru sebaliknya, Bapak menunjukkan bukti tersebut lewat bekas luka yang cukup besar di bahu kirinya.
Semua orang di rumah sepertinya memang suka mengarang. Terlebih Ibu, kalau sudah mendongeng Ibu bisa menceritakan apa saja. Dari sayur kangkung yang membuat otak kuat, sampai kebanyakan jajan yang bisa membuat otak bodoh. Kalau Niskala menolak untuk tidur maka Ibu akan menepuk-nepuk punggung Niskala seraya menyanyikan berbagai macam lagu. Dari lagu anak-anak sampai lagu nasionalisme. Kalau sudah kehabisan lagu, tak jarang yang dinyanyikan ibu adalah lagu Indonesia Raya atau Nyiur Hijau.
“Mas, sambung lagi dong ceritanya!”
Sepertinya kemampuan mengarang cerita Ibu dan Bapak terwariskan kepada Niskala. Niskala mendongak ke depan, mendapati empat bocah di hadapannya. Pikirannya yang tadi gentayangan ke masa lalu, kini berada di tempatnya lagi.
“Walah sampe mana, toh tadi?”
"Itu Mas, dari tukang kayu sampe jadi raja Jawa."
"Ohhh iyaa. Jadi, tukang kayu ini loh teman-teman, menebang pohon beringin untuk membikin kursi buat anaknya, lalu untuk mengasih anaknya makan apa yang dilakukannya coba?"
"Makan duit rakyat yo, Mas?"
"Tet tot" Niskala menyilangkan jari.
"Ngutang dulu ndak sih?"
"Ngutang yang wakeh yo Mas?"
"Tapi dengan menghutang hidup lebih menantang."
Jawaban-jawaban itu membuat Niskala terkikik. "Yak, teman-teman. Jadi, untuk mengasih anaknya makan bapaknya ini menyembelih banteng."
"Sayang keluarga dong, Mas. Pohon beringin ditebang, banteng disembelih."
"Ya begitulah yang kita lihat teman-teman." Niskala melirik jam tangannya. "Gaess, aku muleh ndisek yo?"
Niskala mengeluarkan isi tasnya, ada sebungkus rengginang dan kembang goyang di sana. Dua bungkus jajanan itu langsung dikerubungi oleh empat bocah ingusan tersebut.
"Arep neng ndi, Mas?" Lamki bertanya, saat melihat Niskala berbenah mengemasi barang-barangnya.
"Biasa, menyelamatkan dunia."
Jawaban Niskala dihadiahi senyum kecut. Semua orang di rumah Belajar Merdeka juga tahu rutinitas Niskala seusai mengajar anak-anak.
*
Sehabis Asar, lelaki jangkung itu mulai berjalan menyusuri pinggir kota. Niskala memang suka berjalan, kadang berlari kalau bosan. Hari ini rute yang dipilihnya adalah pinggir kota, dekat tepi laut. Niskala sadar betul kota ini menyimpan banyak sibuk, jalan raya adalah potret bahwa segala urusan dijalankan secara berdesak-desakan.
Namun, agaknya orang-orang hendak beristirahat lebih cepat hari ini, sebab jalan raya di pinggir kota itu terasa lebih lenggang. Niskala memperhatikan sekeliling, kini tatapannya mengarah pada bangku panjang yang khusus disediakan untuk pejalan kaki atau mungkin sekadar buat duduk-duduk saja.
Niskala duduk di sana. Menghela napas sebentar. Matanya berkeliling ke jalan raya di depannya. Berbagai kendaraan hilir mudik melintas. Salah satu yang mengambil perhatiannya adalah sepeda tua yang tengah dikendarai oleh Bapak-bapak. Tanpa aba-aba, sepeda itu berhenti di pinggir trotoar yang searah dengan tempat Niskala duduk.
Sepeda itu dibawa naik ke atas trotoar oleh sang empu, tanpa diduga mengarah ke tempatnya duduk. Sebelum ikut duduk di sana, Bapak itu tersenyum kepada Niskala lalu menyenderkan sepedanya di pinggir bangku.
"Sepedanya bagus, Pak," puji Niskala.
Untuk kedua kalinya bapak itu tersenyum. Alisnya sudah putih, kerut keningnya berisi waktu. Lantas, tak berapa lama Bapak itu memandang ke arah sepedanya. "Ini rumah saya. Saya tinggal di sepeda ini." Tatapan lelaki tua itu menyiratkan sedikit rasa bangga.
Jawaban dari si Bapak menerbitkan perhatian lebih. Niskala menyimpan daftar tanya dalam kepalanya. Dari sekian yang ingin ia tanya, yang justru duluan meluncur dari mulutnya adalah "Anak-anak bapak ke mana?"
Niskala sadar, bahwa sebenarnya ia sama sekali tidak berkepentingan untuk tahu. Namun, yang terjadi adalah di luar dugaan.
Setelah menatap Niskala lama. Seolah-olah memang tiada jawaban, Bapak itu menyeletuk, "saya tinggal sendiri, Mas. Gak ada keluarga, udah 60 tahun saya gak nikah. Saya punya sih 6 sodara tapi mereka punya hidup masing-masing, udah ada kesibukan sendiri."
Sejenak Niskala mencerna penjelasan itu. Kemudian keluar kalimat ajak dari mulutnya. "Pak, mampir ke rumah saya. Di dekat kolong jembatan Trio Amanah. Di sana ada rumah belajar merdeka. Kalo bapak mau, di sana ada tempat pulang yang nyaman, Pak. InsyaAllah."
"Ohh itu Mas yang nduwe toh? Dulu saya pernah dapet nasi kotak dari sana."
Niskala menggeleng "Mboten, Pak. Saya cuma ngajar dikit-dikit. Yang punya Pak Darma."
"Ohh jadi sampean iki guru?"
Lagi-lagi Niskala menggeleng. "Mboten Pak, saya masih mahasiswa."
Kini si bapak mengangguk-angguk, lalu melanjutkan, "Mas ini beruntung loh. Bisa kuliah, bisa ngajar. Lah orang lain belum tentu punya kesempatan."
Kini gantian Niskala yang mengangguk-angguk takzim. Beberapa saat setelah lama berdiam, terdengar suara si Bapak membuka suara.
"Dulu saya kerja di BUMN Mas, 13 tahun. Tapi karena saya sering tidur di depan kantor, saya dipecat terus diusir sama kantor sendiri. Sekarang saya kerja jadi tukang bangunan. Tapi itu kalau ada kerjaannya aja. Sekarang sih jarang dapet kerjaan. Tapi ya selagi saya masih bisa gerak, saya gak apa-apa. Saya masih bisa jalan-jalan sama sepeda saya. Masih bisa keliling-keliling. Saya masih bisa bertahan hidup di jalanan." Tanpa dimintai jawaban, si Bapak bersuka hati menceritakan hidupnya.
"Alhamdulillah, Pak. Hidup kadang memang menuntut kita mencapai ini itu. Tapi kita lupa sama kebebasan dan kelegaan batin kita sendiri." Niskala kemudian beranjak dari duduknya.
"Pak, aku pamit ndisek yo, Pak. Ojo lali loh pak, mampir ke Rumah Belajar Merdeka."
Sebagai balasan, bapak itu mengacungkan jempol ke arah Niskala. Seusai berpamitan barulah Niskala melanjutkan perjalanannya. Percakapan itu membawa kecamuk dalam kepalanya. Semilir angin menampar ujung rambut, Niskala lagi-lagi menghela napas perlahan. Sampai di ujung trotoar, langkahnya terhenti, ia mendapati seorang bocah yang tampak familiar.
Itu Bedul, berdiri di pagar trotoar—trotoar itu memang punya pagar yang membatasi antara jalan dan lautan. Bedul berdiri di sana sambil termenung ke arah laut.
Bedul tak menyadari kehadiran Niskala sama sekali, sampai tiba-tiba telinganya mendadak terjepit oleh sesuatu yang tak kasat mata.
"Aduhh duh duh ..."
"Seko ndi toh, Dul? Semingguan absen di rumah belajar?" datang-datang Niskala langsung ngomel.
Bedul masih meringis. "Ehh Aduh... duh ... Mas Ikal! Ojo jewer jewer ngopo?"
Niskala melepaskan jewerannya. Bedul, anak muridnya yang menghilang semingguan ini akhirnya ketemu. Ia bernapas lega. Menatap ke arah Bedul dengan segudang tanya.
"Kamu ngapain di sini toh, Dul?" tanya Niskala sedikit galak.
"Aku nungguin Bapak loh, Mas."
"Bapakmu neng ndi?"
"Di laut, Mas. Kok bapak ra muleh muleh yo?"
Niskala menatap ke arah laut. Bedul ikut menatap laut. Dua orang itu kini sama-sama menatap laut.
Tiba-tiba Bedul nyeletuk, "Mas, bapak tuh dulu suka cerita, kalo lagi di laut, Bapak nggak takut sama ombak. Kalo lagi hujan, Bapak malah pergi kerja. Bapak kok yo pinter banget, Mas. Bisa tau ikan ada di mana. Bapak juga baik banget. Kata Bapak, "Nanti kalau Bedul ulang tahun, Bapak mau beliin Bedul kue."
“Kepingin kue toh kamu, Dul?"
Bedul mengangguk. "Bedul pingin banget kue. Karena tiap Bedul ulang tahun, kita selalu gak ada rezeki buat beli kue. Bapak bilang, Bedul harus belajar yang rajin di Rumah Belajar Merdeka. Kan Kapan lagi Bedul bisa belajar gratis? Ya siapa tau, kalau Bedul rajin belajarnya, Bedul bisa jadi pilot. Terus, bisa beli kue sendiri. Terus, bisa gantian buat jadi baik ke bapak."
"Ayok ikut aku tuku kue.”
Seolah ada binar di mata Bedul. Niskala mengangguk dan mengisyaratkan bahwa ia serius. Tanpa banyak tanya lagi Bedul segera menggamit tangan Niskala. Takut tawaran itu akan menguap secara tiba-tiba.
“Beneran, Mas?”
Niskala diam saja, ia membawa langkah mereka menuju sebuah toko kecil. Mereka berdua berjalan menyusuri trotoar yang menghadap laut. Beruntungnya toko itu tidak berjarak terlalu jauh, etalase di depannya menunjukkan aneka ragam kue. Bedul mengamati etalase yang di pajang itu satu-satu, matanya melirik penuh oleh rasa ingin tahu.
“Mas, kepingin yang itu,” ujar Bedul sambil menunjuk kue Tart kecil yang dihiasi krim putih dan cokelat di atasnya.
“Mas, nanti kita makan di rumah belajar aja, ya, Mas? Sama yang lain juga.”
“Kan ini kuemu, Dul?”
“Kan aku orangnya baik dan tidak pelit, Mas.” Bedul nyengir memperlihatkan beberapa giginya yang berlubang.
Niskala Cuma melengos mendengar jawaban kepedean Bedul.
"Mas Ikal, nanti kalau Bapak pulang, Bedul cerita ya, kalo Mas Ikal udah beliin Bedul kue," kata Bedul tak berselang menit.
Niskala mengacak-acak rambut tebal Bedul, menahan sedikit rasa sedih yang tiba-tiba menyelusup dadanya. "Ceritain, Dul. Bilangin ke Bapakmu kalau Bedul wes jadi anak yang rajin dan pintar. Jangan lupa, ya?"
Sore itu, matahari mulai tenggelam di ufuk barat, meninggalkan langit yang berwarna jingga keemasan. Niskala terus berjalan, membiarkan pikirannya melayang-layang, memikirkan pertemuan-pertemuan kecil yang ia alami hari ini. Bedul berjalan riang di sampingnya, menenteng kresek berisi kotak kue Tart dengan sekali melompat-lompat.
Sampai di simpang jalan, Niskala berhenti sejenak, menatap langit yang mulai gelap. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Bedul sudah berjalan beberapa langkah di depannya, anak itu senang sekali di belikan kue. Sore itu, uang bulanan terakhirnya habis, tapi dalam benaknya, ia bertekad untuk terus melakukan apa yang bisa ia lakukan, sekecil apa pun itu, untuk membuat dunia di sekitarnya menjadi rumah yang lebih baik.
Salwa Ratri Wahyuni, lahir di sebuah kota kecil di Riau, pada pertengahan tahun 2005, merupakan mahasiswa aktif Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universutas Andalas.