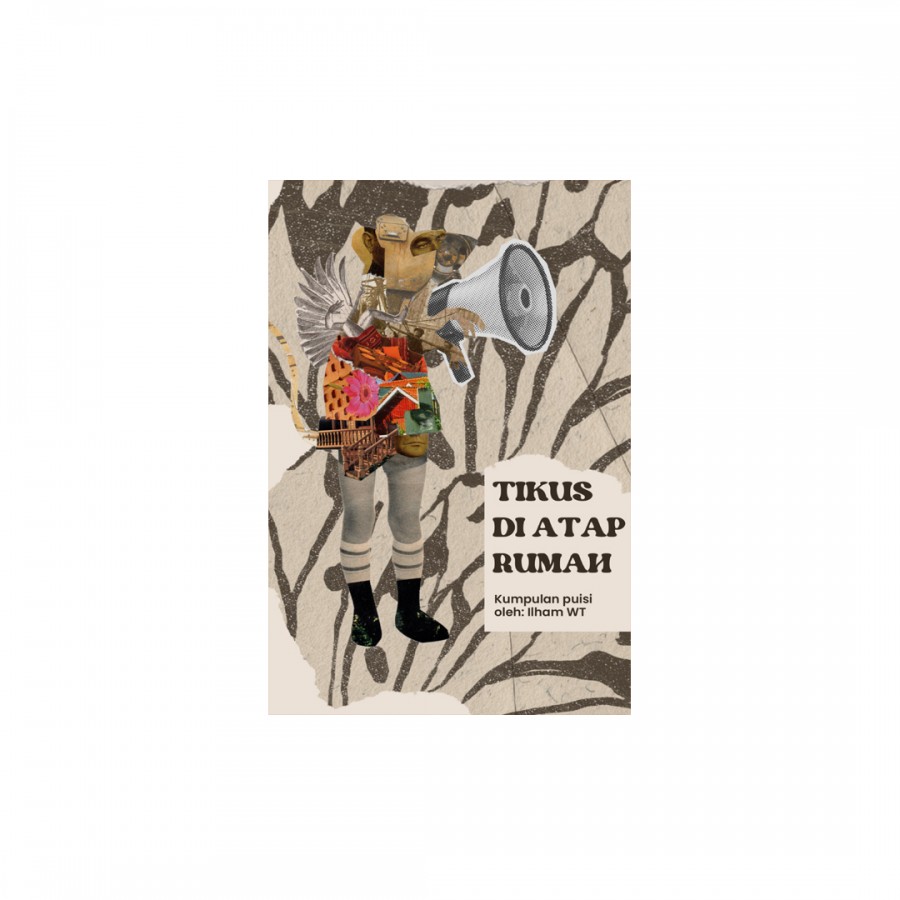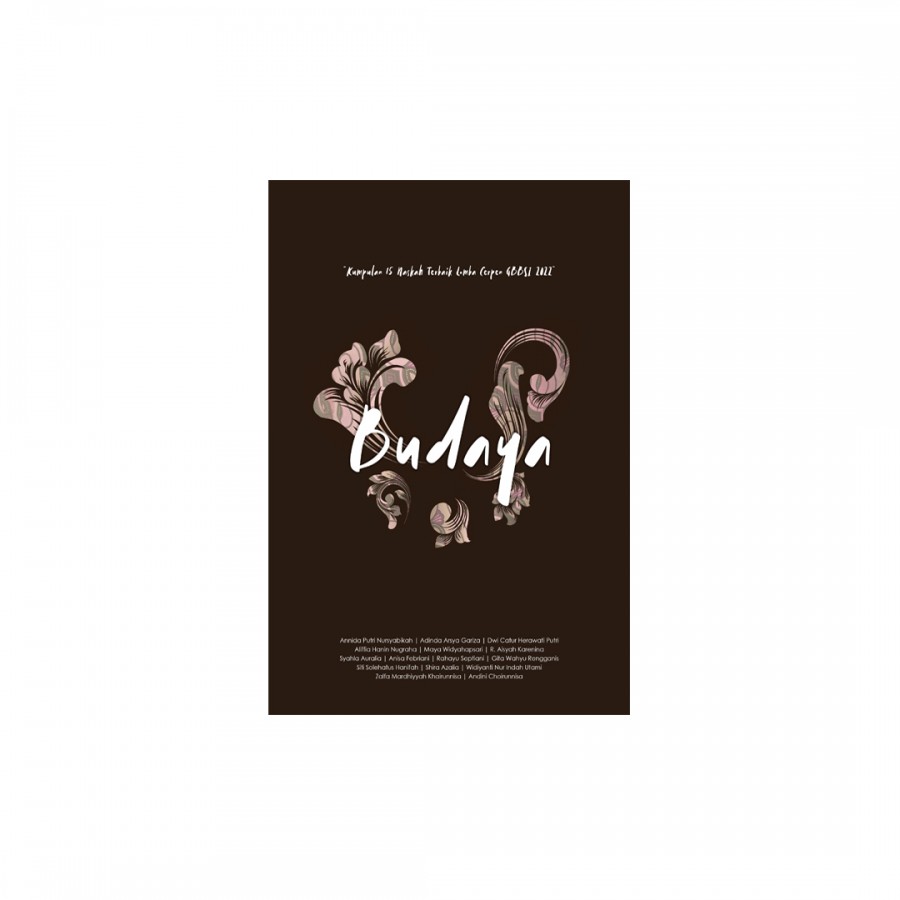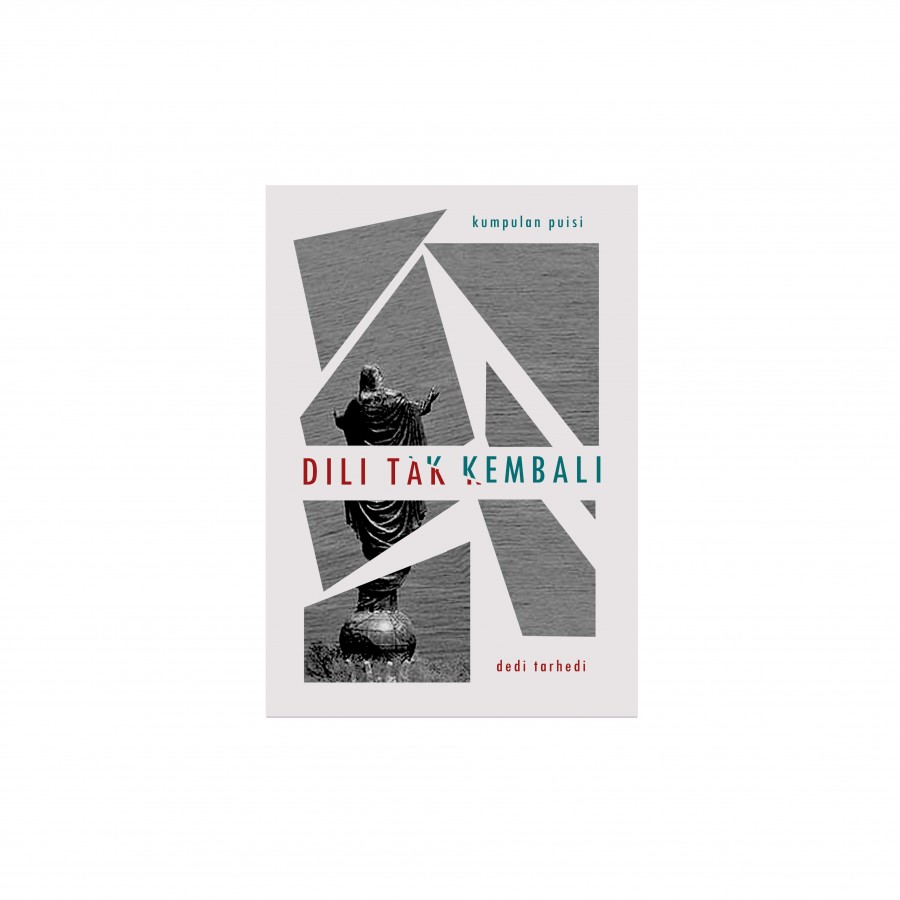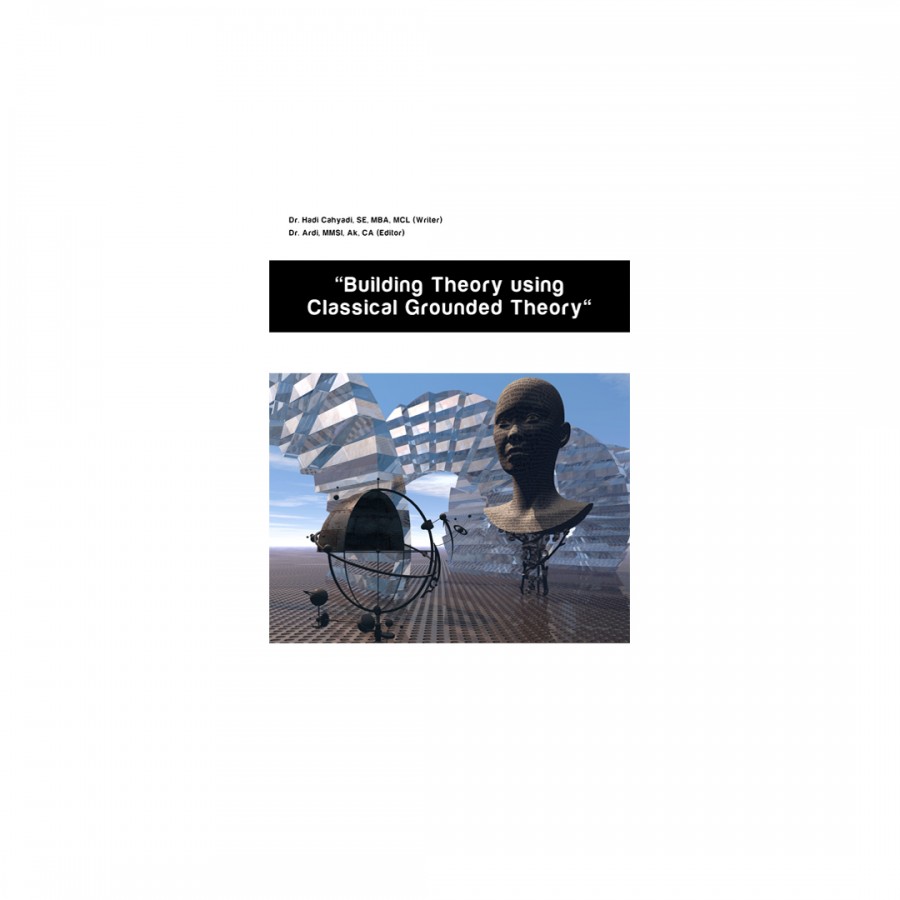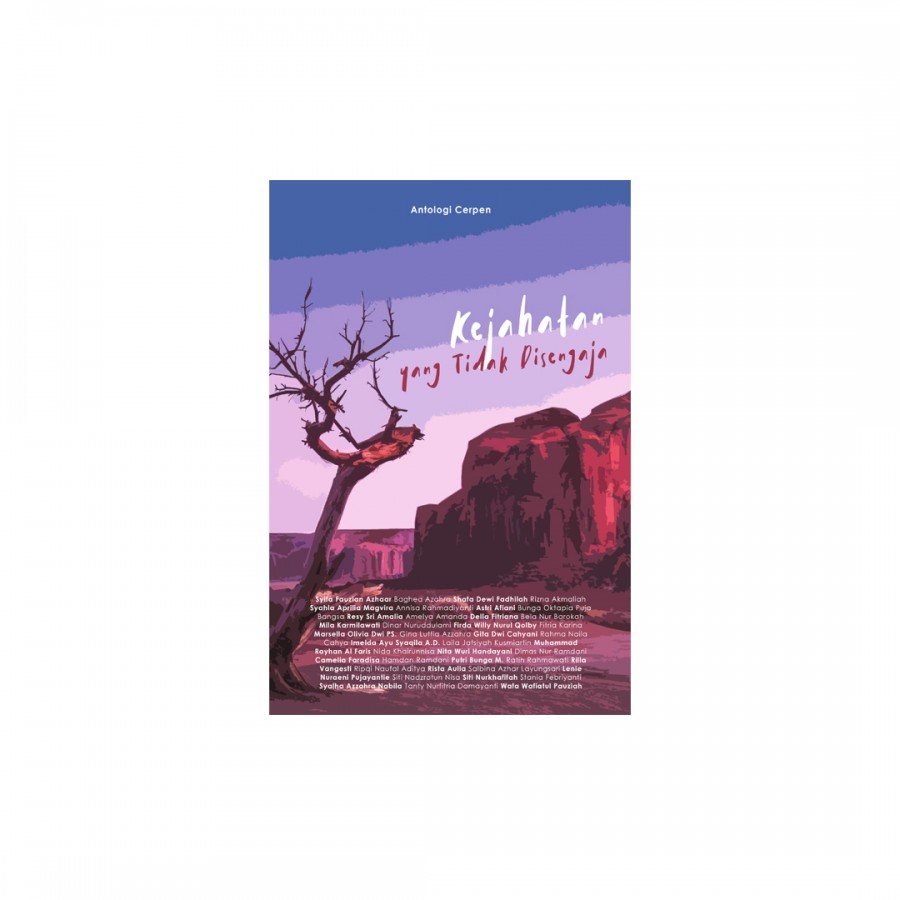“FETISH orang T*******g memang tidak pernah berubah: disiksa sama polisi dan pemerintah,” tulis Dullah di aku facebooknya, yang segera menjadi perbincangan di mana-nama, termasuk di kolom komentar status itu sendiri. Dan di sana, sama seperti di sebuah gubuk yang dikepung oleh sawah dan rawa-rawa—tempat Dullah dan Amir sering menghabiskan siang dan malam, nada yang terbaca adalah keseruan belaka. “Bener-bener disodomi setiap saat. Ckckck,” kata salah seorang. Sementara lebih kurang lima kilometer dari tempat Dullah mengunggah statusnya itu, di kantor Tanah Adat Tegalurug yang tiang-tiangnya tidak lagi terbuat dari batang pohon mahoni tapi campuran beton itu, yang atapnya sudah diganti dengan genteng dari Majalengka itu, yang terasa justru sebaliknya: status Dullah itu adalah bentuk kebencian yang nyata terhadap adat.
Sebenarnya semua adem-adem saja pada awalnya—seadem gubuk Dullah itu saat malam. Semua orang tahu jika siapa pun berhak buat berbicara. Lagipula siapa yang tahu T*******g itu di mana? Benar-benar ada atau cuma karangan belaka? Tapi kemudian, setelah Kepala Adat Tegalurug berkata jika berbicara ada batasnya, barulah keriuhan itu mulai menampakan wujudnya. Para petugas yang juga punya Facebook kemudian membalas dengan macam-macam cemoohan dan ancaman: bahwa orang yang punya kebencian terhadap Tanah Adat adalah orang sinting, dan karena itu, tidak perlu didengarkan; dan selain itu, dia juga harus siap dengan segala kemungkinan buruk.
“Ternyata banyak curut yang caper sama si Memedi sawah itu. Ckckck,” tulis Dullah di status selanjutnya. Tapi, beda dengan sebelumnya, tidak ada satu pun komentar yang terlampir di status terbarunya itu. Orang-orang tampaknya mulai sadar dengan situasi yang mulai memanas itu. Bahkan belakangan, setelah beredarnya kabar tentang patroli siber yang dilakukan oleh Biro Adat, komentar-komentar di status Dullah sebelumnya pun kemudian lenyap sama sekali.
“Kudengar banyak yang marah dengan statusmu kemarin,” ucap Amir sambil membenarkan posisi kursinya. Suara rangkaian bambu yang digerakkan oleh sebuah pancuran terdengar dalam rentang yang konstan dari belakang mereka.
Dullah tidak menjawab. Matanya masih asik mengikuti gerak layar androidnya.
“Kau memang enggak khawatir sama hidupmu?”
“Kenapa aku harus takut sama tuduhan yang tidak pernah aku ucapkan?” balas Dullah. Raut wajahnya menunjukkan jika dia memang tidak takut pada apa pun. “Aku bahkan tidak pernah menyebut nama Tegalurug di status-statusku.”
“Ya, kau memang benar soal itu,” balas Amir. “Tapi benar menurutmu belum tentu benar menurut orang lain.”
“Bangsat, kau lihat status orang sinting ini!” Dullah tergelak, membelokan percakapan di antara mereka. “Wih ngerinya,” ejek Dullah sambil menunjukan layar androidnya pada Amir.
Setelah membaca status yang dimaksud Dullah itu, Amir kembali bertanya, “Jadi kau bener-bener enggak takut sama mereka?”
“Jadi begini ya, Amir lepet,” kata Dullah memulai. “Kau tahu, sudah sepuluh tahun si memedi itu membuat kita sengsara; membuat semua orang melarat. Kemiskinan dan penderitaan tumbuh di mana-mana. Lihat sendiri bagaimana nasib orang-orang Tegalurug sekarang. Berapa banyak yang enggak bisa sekolah? Berapa banyak yang enggak bisa makan? Jadi kurang disiksa apalagi kita ini?” katanya dengan tidak sabar. “Tapi, pas pemilihan kemarin, dengan cuma sedikit bansos dan bujuk rayu, mereka justru beramai-ramai memilih anak si memedi yang masih bau kencur itu. Kalau fetisnya bukan disiksa sama si Memedi, apa coba namanya?” jelas Dullah. “Tapi bagaimanapun juga, dasarnya, si Memedi itu memang suka ngurus kebodohan dan kemiskinan. Dan karena itu, pantat dia dan cecurut-cecurutnyalah yang harus dibubut dengan besi panas. Mulut-mulutnya dicucur dengan logam mendidih.”
Amir tidak menanggapi ocehan Dullah yang berbusa-busa itu.
Dan setelah suara rangkaian bambu serta hewan-hewan sawah dan rawa-rawa menguasai halaman gubuk itu untuk beberapa saat, Dullah kembali melonjak, “Lihat foto polisi yang ngebikin status tadi ini,” katanya ngakak. “Apakah dia ingin menakut-nakuti semua orang dengan muka buruknya itu?”
Tapi, Amir tampak tidak berminat dengan ocehan Dullah itu. Matanya pergi menyeberangi sawah dan rawa-rawa; menuju hutan dengan siluet pohon-pohon yang menyeramkan itu; siluet Hutan Adat Tegalurug.
“Kenapa kau, heh?” kejar Dullah. “Dari dulu kau memang pengecut,” ejeknya.
“Kepalamu pengecut!” sergah Amir, terdengar sangat keberatan. “Aku hanya ingin jalan yang lebih baik dan aman.”
“Ya itu namanya pengecut, Amir lapet. Baru dapet ancaman di Facebook saja nyalimu sudah ciut.”
“Terserah kau sajalah,” balas Amir sambil beranjak dari kursinya. “Aku enggak tanggung jawab kalau ada apa-apa denganmu.”
“Heh dengar Amir lapet, tidak akan ada yang berani sama keturunan Bah Nun yang sakti mandraguna ini,” olok Dullah. Dan seperti olok-oloknya pada Amir, Bah Nun bukanlah siapa-siapa. Dia hanya seorang laki-laki uzur yang punya seribu dongeng di kepalanya; yang ceritanya selalu berkembang dan tidak pernah ada ujungnya. “Biar aku saja yang ngurus si Memedi sama cecurut-cecurutnya itu. Kau bikinkan saja aku kopi,” ejeknya lagi.
Selang beberapa saat, Amir muncul kembali dengan dua gelas arabika. “Kau masih percaya dengan kemagisan hutan itu?” kata Amir setelah menyesap kopinya.
“Bahwa kejahatan akan dibalas dengan kematian tragis? Ya tentu, aku percaya itu. Aku percaya kalau si Memedi dan cecurut-cecurutnya itu akan berakhir dengan mengenaskan. Kerusakan dibalas dengan kerusakan.”
“Bagaimana jika tidak?”
“Tidak mungkin. Dia akan mati dengan rusuk-rusuk yang patah,” jawab Dullah yakin. “Kau dengar itu? Suatu saat angin itu akan menjelma rimbas yang menggulung si memedi hingga mampus. Seperti sabda yang tercatat di kitab-kitab para leluhur.”
Sesaat kemudian, angin yang datang dari hutan itu kemudian benar-benar berhembus semakin kencang—membawa banyak daun dan ranting mati di tubuhnya—membuat Dullah dan Amir meninggalkan halaman lebih awal.
Dan di dalam gubuk berukuran 4 x 5 meter itu, Dullah dan Amir masih meneruskan obrolannya.
“Pemilihan sudah usai dan orang-orang sudah melupakan semua keributan kemarin,” Amir memulai kembali.
“Kau tahu kalau Kepala Adat dipilih langsung oleh masyarakat dan semua orang yang sudah dewasa berhak untuk mengajukan diri. Dan kau tahu juga, kalau dewasa itu ada ukurannya. Yaitu mereka yang sudah berusia lima belas dan hafal seluk-beluk tentang desa. Tidak boleh tidak. Dan lagi-lagi kau juga tahu, kalau dalam kepercayaan kita, anak yang belum dewasa itu manusia kosong; suci dan tidak berdosa. Kita percaya kalau sebelum lima belas, yang hadir pada si anak adalah orang tuanya. Jika dia berbuat baik, maka orang tuanyalah yang baik. Begitu juga sebaliknya: saat dia berbuat keburukan, maka orang tuanyalah yang harus bertanggung jawab. Anak adalah cermin yang memantulkan bayangan orang tuanya. Jadi kalau si belimbing wuluh yang belum cukup umur itu maju dalam pemilihan, maka pada hakikatnya, yang maju adalah orang tuanya; bapaknya sendiri. Dan semua orang tahu, si memedi itu sudah menjabat dua kali. Dan itu batas yang dibolehkan oleh adat.”
“Tapi para sesepuh sudah menerimanya.”
“Dan karena itulah mereka juga akan celaka.”
Untuk beberapa saat, hening terdengar memenuhi ruangan 4 x 5 meter itu.
“Semua orang tahu jika nama Tegalurug adalah sebuah peringatan. Jika sudah tak sesuai, maka cepat atau lambat, tanah ini akan hancur juga. Dijungkirbalikkan dan diganti dengan tanah lain yang lebih suci. Begitu juga dengan orang-orangnya.”
***
Di ujung sebuah jembatan, dua orang polisi yang tempo hari menculik tokoh kita mulai memotong pipet-pipet yang mengikat tangannya. “Kami ditugaskan untuk melepaskanmu malam ini,” kata polisi yang lebih buncit sambil menahan tawa. “Tapi sayangnya kau hanya punya sedikit pilihan. Pergi ke ujung jembatan itu atau langsung kami habisi di sini,” lanjutnya sambil menuding arah seberang dengan pistolnya—tepat di depan hidung tokoh kita. Dan rasa takut yang tidak pernah tokoh kita rasakan sebelumnya pun mulai menggeranyangi sekujur tubuhnya.
“Kau punya sepuluh detik untuk pergi. Dan setelah itu, kami akan memburumu seperti seekor babi,” balas polisi yang satunya lagi dengan tidak sabar.
Gelak tawa mereka terdengar mendengung di tebing-tebing sungai.
Dan di dalam hati, tokoh kita tak henti-hentinya menyumpahi dua polisi yang dia yakini memang ditugaskan untuk melenyapkannya itu. Dan itulah cara mereka untuk bersenang-senang di ujung kematiannya.
Pada saat-saat genting itulah, tokoh kita berusaha mengingat kembali jembatan itu. Saat masih kecil, dia dan teman-temannya sering bermain di sana untuk melemparkan diri ke sungai. Saat normal, tinggi jembatan itu hanya tujuh meter—tergantung volume air yang melintas di bawahnya. Dia juga ingat, saat mendarat di air, dia akan merasakan sensasi segar yang memabukkan—dia akan hanyut beberapa meter ke hilir sebelum merapat dan berjalan kembali ke atas jembatan—untuk berdiri dan menjatuhkan diri kembali ke sungai. Tapi sayangnya, sekarang dia merasa sangat ragu untuk melakukannya. Dia tahu jika hujan sudah lama tidak turun, dan karena itu, pasti hanya ada sedikit air di sana. Dan malangnya lagi, karena malam sedang turun sementara bulan tidak tampak di mana pun, dia tidak tahu persis di sebelah mana dan pada langkah ke berapa air itu mengalir.
“Lihat, aku ternyata punya tiga peluru untuk membunuhmu,” kata si polisi buncit sambil mendongakkan senjatanya kepada tokoh kita. “Fetish-mu juga disiksa sama polisi dan pemerintah kan?” godanya.
Tokoh kita terus berpikir: dengan kondisi kakinya yang sudah hancur dibogem benda-benda tumpul, mustahil baginya untuk sampai di seberang. Dan kalaupun bisa, mustahil dua setan itu akan melepaskannya begitu saja—tidak ada jaminan jika telunjuk mereka akan tetap diam dan berada di tempatnya. Karena itu, keputusannya pun akhirnya bulat; bahwa pada hitungan ketujuh, dia akan melompat ke sungai. Sekali lagi, dia cukup akrab dengan jembatan dan sungai yang mengalir di bawahnya itu. Tapi kemudian, bayangan sinis mendadak muncul kembali di kepalanya: jika dia tidak bisa mendarat di air, maka riwayatnya pasti akan tamat. Tapi bagaimanapun juga, pada akhirnya dia tetap kembali pada pilihan awal: karena berlari pasti mati, maka melompat adalah satu-satunya cara agar nyawanya bisa selamat, meski untuk sementara.
“Enyahlah kau tikus bangsat,” sentak si polisi buncit, persis setelah semua pipet yang mengikat tangan tokoh kita terpotong tuntas.
Dan saat itulah, tokoh kita pun mulai berlari dengan tidak sempurna. Dan tepat pada hitungan ketujuh, tokoh kita pun melompat—melayang—dan kemudian jatuh.
Suara gedebuk terdengar jelas dari bawah jembatan.
****
Entah dari mana kabar itu bermula: kematian Amir bukan terjadi karena siksaan yang dia terima, tapi karena paru-paru yang hancur karena tersabet rusuk-rusuknya sendiri. Dan ihwal kenapa Amir bisa melompat dari atas jembatan, tidak pernah jadi persoalan sama sekali.
Dan setelah kabar kematian Amir itu terdengar, sebuah nomor anonim kemudian mengirim pesan singkat kepada Dullah: “Fetis orang Tegalurug memang tidak pernah berubah: disiksa sama polisi da pemerintah. Ckckck.”
Aflaz Maosul Kamilah lahir di Garut, Jawa Barat pada 08 September 1998. Buku kumpulan cerpen pertamanya, Sanghyang Taraje, terbit pada 2021. Dapat dihubungi melalui instagram @aflazmaosul.