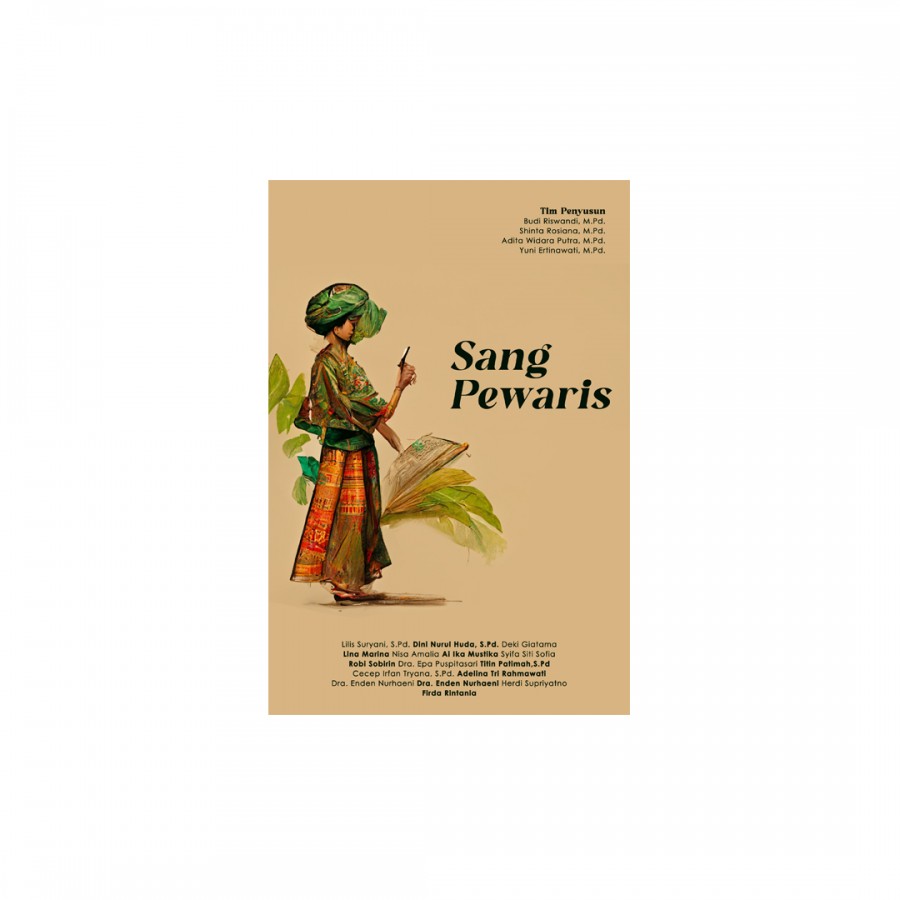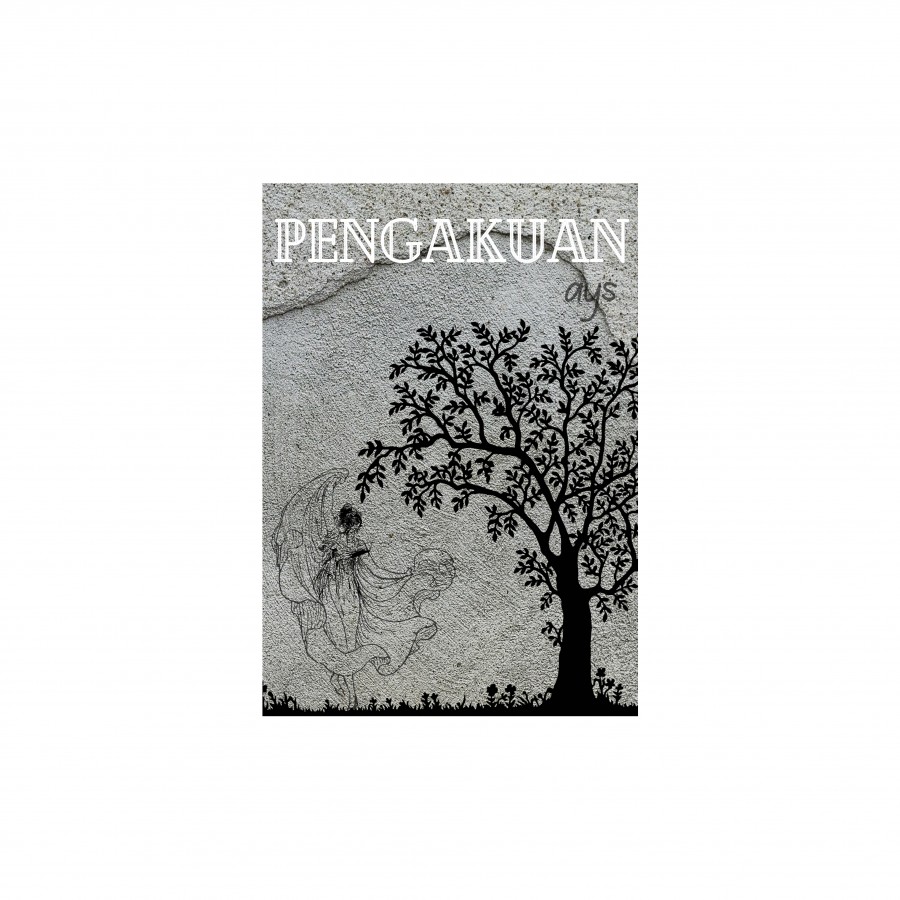Setiap kali orang Tegalsawah bertemu, mereka akan saling bertanya, dengan kecemasan dan kengerian di mata dan suara mereka:
“Seberapa lama ini akan berlangsung?”
Belum pernah mereka menyaksikan kemarau sepanjang itu1—membuat sawah hancur dan terbengkalai selama itu—mengubahnya menjadi padang gulma dan rumput teki sehijau itu, yang justru tubuh subur saat kemarau sedang memanggangnya—menjadi tegal bagi domba dan sapi merumput bebas.
“Jika terus begini, semua orang akan makan teki seperti domba dan sapi pada akhirnya.”
Tentang domba dan sapi yang sedang merumput itu, jika kalian iseng mendekatinya seperti seekor ular dan memasang telinga seperti seekor anjing, beginilah suaranya: krauk krauk krauk! Tapi, jika kalian tidak bisa membayangkan bagaimana suara gigi domba atau sapi yang sedang membabat rumput teki itu, ambillah sawi atau kol yang ada di dapur lalu potonglah dengan pisau tajam dalam sekali entak, begitulah suaranya. Meski merdu, tapi mendengarkannya bukanlah cara terbaik untuk mengaso. Seperti semua tempat di dunia, sawah bukanlah tempat semestinya untuk menggembalakan domba dan sapi. Sawah adalah tempat di mana padi ditanam dan dari sanalah beras dihasilkan. Dan di sini, tempat seharusnya bagi domba dan sapi merumput adalah di utara Tegalsawah—sebuah tempat di mana sungai tidak pernah ada dan selokan tidak pernah diciptakan, yang dalam kekeringannya itu, tetap mampu menumbuhkan rumput dan semak. Tapi, karena sekarang matahari menyala setiap saat seperti lampu yang kehilangan stop kontak—mengubah tegal menjadi sekering gurun dan menyulap sawah menjadi sekering tegal—belut dan lele lenyap seperti kelinci di topi seorang pesulap, para penggembala pun harus kehilangan cara terbaiknya dalam mengaso—menukarnya dengan suara domba dan sapi memamah rumput teki yang tidak seberapa itu.
Dan saat Asep Sapi sedang mengaso dengan cara buruk dan tidak semestinya itulah, Mamat Doma datang dengan lagak seekor domba yang tengah diburu seekor serigala.
“Hoi, Sapi. Aziz Cicak kembali berulah,” katanya.
Mendengar nama itu keluar dari mulut Mamat Doma, Asep Sapi segera beringsut dari tidurnya yang beralas rumput teki dan berselimut bayangan pohon kelapa itu—membuat domba dan sapi yang sedang dia cermati lekat-lekat itu tercekat dan segera kabur.
“Hoi, Doma. Apa yang dia buat sekarang?” katanya saat Mamat Doma masih berjarak sepetak sawah.
“Sebuah gebrakan!”
Setelah Asep Sapi membersihkan kedua lengannya dari serpihan rumput dan butiran tanah, mereka segera beranjak menuju saung yang berdiri di batas antara tegal dan sawah. Suara mereka membuat segerombol burung pipit angkat kaki dari atap saung menuju sebuah pohon pisitan yang telah disulap cuaca menjadi seonggok kayu bakar—persis dua puluh langkah di timur saung.
Dan di saung yang tiang-tiangnya terbuat dari batang pinang, yang atapnya terbuat dari anyaman ilalang, dan papan-papannya terbuat dari palupuh itulah mereka mulai menggosipkan kegilaan Aziz Cicak.
Tapi pertama-tama, perlu kalian tahu jika orang Batujajar memang gemar menjuluki orang dengan nama hewan—baik yang orang itu pelihara atau justru, menggambarkan sifatnya. Asep Sapi karena punya empat sapi dan Mamat Doma karena memelihara lima belas domba. Selain itu, ada juga nama Asep Soang, Jejen Lele, Jajang Kancil, dan lain-lain. Hanya keluarga pesantren—keluarga paling berpengaruh di Batujajar yang luput dari kebiasaan itu. “Hewan adalah makhluk hina dan manusia adalah makhluk suci,” kata mereka. Tapi, di Tegalsawah—bagian kecil di utara Batujajar—tempat orang-orang paling miskin tinggal, tempat di mana hewan adalah teman karib dan sumber hidup, orang-orang diam-diam menjuluki anak bungsu Kiai Sahdi sebagai Aziz Cicak.
Julukan itu sendiri lahir saat pemilihan kades setahun lalu. Di mata orang-orang, Abdul Aziz adalah bintang sinetron yang berperan sebagai seorang nabi, atau setidaknya, orang saleh. Namun, citra itu hangus seketika saat Abdul Aziz bertemu dengan Dadang Sidat dalam sebuah acara debat—di atas panggung, sarung batik Abdul Aziz tiba-tiba menjadi sebuah cucian. Dan keesokan harinya tersiar kabar jika dia mencipratkan apinya pada juru kampanyenya, Khalid bin Walid.
“Tidak! Gus Aziz tidak pernah menyiksaku,” kata Khalid bin Walid kepada semua orang. “Aku jatuh dari motor.”
Karena cerita muskil itulah, orang-orang Tegalsawah kemudian menjuluki Khalid bin Walid sebagai Jamal bin Jamal dan Abdul Aziz sebagai Aziz Komodo. Tapi karena komodo masih terlalu bagus, orang-orang kemudian menukarnya dengan seekor cecak.
Dari kontes-kontes sebelumnya, pertarungan Aziz Cicak dan Dadang Sidat itu memang yang paling sengit dan bahaya. Saat itu, permusuhan menyebar ke seluruh Batujajar seperti api membakar padang ilalang. Lalu, saat Aziz Cicak akhirnya terpilih sebagai Kades Batujajar, dia pun segera menampakkan dendamnya pada Dadang Sidat, pada orang-orang Tegalsawah. Dia bahkan menukar bantuan jalan ke Tegalsawah dengan sebuah gapura selamat datang di atas sebuah sungai. Karena kengawurannya itu, Asep Sapi dan Mamat Doma kemudian menjuluki Aziz Cicak sebagai Pemimpin Tertinggi Revolusi Aziz Cicak.
“Jadi hal tolol apa yang si sinting itu lakukan?” desak Asep Sapi.
“Aziz Cicak mengundang semua orang ke Balai Desa.”
Asep Sapi nyaris muntab dengan ucapan Mamat Doma itu. “Hampir tiap bulan kita pergi ke sana,” katanya. “Jadi berhentilah bermain-main!”
“Sabarlah, aku belum selesai bercerita.”
“Anjing! Kau memang tidak punya bakat buat mendongeng. Tadi nadamu sudah terputus, tolol!”
“Aziz Cicak mengundang semua orang ke Balai Desa, termasuk musuh bebuyutannya ….”
“Anjing!” Asep Sapi setengah melompat. “Dia pasti kesambet dedemit atau genderuwo.”
“Tidak salah lagi,” Mamat Doma membalas. “Jajang Kancil yang menceritakannya padaku.”
Pada suatu hari, Aziz Cicak memanggil Jajang Kancil dan mengawali percakapan itu dengan sebuah pertanyaan, “Bagaimana agar Batujajar bisa cepat maju?”
Untuk menjawabnya, Jajang Kancil pun segera membuka HP-nya dan memasukkan kata kunci “ciri-ciri negara maju dewasa ini”. Jajang Kancil memang sedang tergila-gila dengan frase “dewasa ini”—dia memperolehnya dari dosennya saat sedang ceramah tentang globalisasi. Selain itu, dia juga sengaja memilih kata negara dibanding desa agar jawabannya lebih mengena, katanya.
Sedetik kemudian, layar androidnya menampilkan puluhan artikel dan Jajang Kancil mengetuk yang pertama. Dia terus menggulung layar HP-nya sambil mendikte setiap poin yang muncul—mulai dari ekonomi, pendidikan, dan kemudian: kesehatan dan sanitasi.
Jajang Kancil paham dengan kesehatan, tapi apa sanitasi?
Belum sempat dia menguliknya, Aziz Cicak segera memotong, “Sanitasi? Benda apa itu?”
Jajang Kancil merasa tertimpuk oleh pertanyaan Aziz Cicak yang mendadak itu—dia tidak ingin mencemplungkan seonggok kotoran pada mangkuk namanya. Karenanya, Jajang Kancil segera memasukkan kata kunci baru: sanitasi menurut KBBI. “Usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat,” dengungnya.
“Jadi apa bedanya dengan kesehatan?”
“Sanitasi lebih mengarah pada upayanya,” jawab Jajang Kancil. “Selain itu, objek dari sanitasi juga lebih khusus, yaitu masyarakat.” Jajang Kancil tersenyum, dia merasa puas dengan kemampuannya menarik kesimpulan.
Aziz Cicak mengangguk-anggukan kepala dan beberapa kali menggumamkannya—dia tampak takjub dengan kata itu. “Coba cari tahu tentang konsep itu,” perintahnya.
Dan Jajang Kancil pun mulai menguliknya—dia tahu jika salah satu poin penting dalam sanitasi adalah toilet, dan toilet duduk adalah simbol modernitas dan sanitasi terbaik.
Setelah Jajang Kancil mengatakan penemuannya itu, Aziz Cicak pun segera menugaskan Jajang Kancil untuk membelinya ke Kota Kabupaten.
“Jadi tujuan Aziz Cicak mengundang semua orang ke Balai Desa adalah untuk memamerkannya?” potong Asep Sapi, lalu tertawa ngakak. “Kapan sirkus itu akan berlangsung?”
“Besok sore,” jawab Mamat Doma. “Dan yang tahu cerita ini baru kita berdua,” katanya lagi. “Aku benar-benar tidak sabar untuk menontonnya.”
“Ya, aku juga,” balas Asep Sapi. “Tapi bajingan memang! Dibanding memperbaiki irigasi dan membuat embung, bajingan itu lebih peduli pada gapura dan toilet.”
“Tegalsawah adalah tempat Dadang Sidat lahir dan tinggal,” jawab Mamat Doma. Seekor anjing terdengar menyalak dari arah hutan. “Semua orang tahu itu.”
***
Orang-orang tumpah ke Balai Desa untuk menyaksikan “peristiwa bersejarah” itu—seperti penggalan surat dan pamflet yang Aziz Cicak sebarkan. Namun, karena Balai Desa tidak sepadan dengan orang-orang yang terus datang seperti sebuah bah, Aziz Cicak kemudian memindahkan pentas itu ke Lapang Batujajar yang berjarak sebuah jalan raya dan sepetak kebun singkong. Dan saking ramainya, pentas itu bahkan bisa menandingi sebuah pasar malam dan perayaan kemerdekaan—mengundang pedagang manisan, aksesoris, dan ikan untuk datang.
“Jika hal tolol begini terjadi setiap hari, tukang-tukang itu akan memiliki pabriknya sendiri,” kata Mamat Doma, memandang pedagang-pedagang yang lebih sibuk daripada yang mereka bisa.
“Jika tidak ada kupon, mustahil mereka sebergairah ini,” balas Asep Sapi sambil menyisir hamparan orang-orang.
“Untuk hal begini, Aziz Cicak dan keluarganya memang jenius.”
Makin sore, orang-orang tampak makin tumpah hingga ke sisi lapang dan baru tertahan oleh barisan pohon hanjuang yang memisahkan lapang dan kebun kapulaga. Mereka seperti melupakan matahari yang saat itu sudah sepanas api unggun. Dan setengah jam lagi, pohon-pohon hanjuang itu pasti akan jebol juga.
“Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi Batujajar,” Aziz Cicak memulai pidatonya. Sepiker yang disetel buruk membuat suaranya terdengar berulang-ulang. “Hari di mana kita memulai sebuah era baru,” lanjutnya sambil memutari benda yang terkurung kain hitam itu—mirip mereka yang sedang melakukan haji atau kawanan semut yang sedang menyembah ratunya.
“Tidak salah lagi, itu pasti komputer tercanggih keluaran terbaru,” kata salah seorang. “Dari bentuknya sudah kelihatan jika itu komputer.”
“Tidak, itu pasti motor listrik yang sedang ramai di televisi,” sanggah yang lain.
“Kalian berani taruhan berapa? Itu pasti tas yang bisa membawa kita terbang ke mana pun. Aku pernah menyaksikannya di sebuah gim petualangan.”
“Dan sekali lagi Batujajar akan berutang pada Gus Aziz,” kata seorang pemuda berkopiah hitam.
“Kau dengar itu?” bisik Asep Sapi pada Mamat Domba. “Benar-benar lucu dan menggemaskan.” Lalu mereka pun mulai tertawa-tawa.
“Hoi, monyet! Berhentilah memasang muka tegang begitu,” bisik Asep Sapi pada seorang bocah laki-laki yang sedang menjilati es krim. “Itu hanya sebuah rongsokan, tidak lebih.”
Dan anak itu pun pergi dengan mimik melecehkan.
“Dan hadirin yang saya kasihi,” kata Aziz Cicak. Dia tampak melempar senyum pada Dadang Sidat yang duduk di kursi plastik yang didesain melingkar bersama orang-orang dengan setelan kemeja putih dan jas hitam. “Inilah benda yang menandai era baru itu,” sambung Aziz Cicak sambil menyibak kain hitam itu.
Dan beginilah pemandangan setelah Aziz Cicak menunjukkan benda yang menurutnya revolusioner itu: sebagian memasang wajah syok seperti baru melihat seekor hantu, sebagian lain saling mencubit seolah sedang merasa gemas pada pacar gelap, dan sebagian sisanya menjelma patung-patung kayu; sementara Asep Sapi dan Mamat Doma tampak mengunci mulutnya masing-masing seperti baru mendengar cerita paling lucu di dunia.
“Aziz Cicak memberikan apa yang layak dari sebuah sirkus,” bisik Asep Sapi, masih menyamarkan tawanya.
“Dan atas dasar pemerataan, toilet ini akan langsung dipasang di Tegalsawah, malam ini juga,” kata Aziz Cicak dengan bangga. Dan sorak-sorai pun mendadak pecah, seperti sekelompok suporter menyaksikan sebuah gol kemenangan.
“Anjing!” leguh Asep Sapi tiba-tiba.
Di belakang Aziz Cicak, Wajah Dadang Sidat berubah jadi semerah jantung pisang.
“Dan sebagai simulasi, saya akan mengundang anak Dadang Sidat untuk datang ke tengah-tengah kita,” Aziz Cicak meneruskan pertunjukannya.
“Anjing, anjing!” leguh Asep Sapi lagi.
Di belakang Aziz Cicak, lima orang hansip tampak mengerubungi Dadang Sidat yang terus menggelinjang seperti maling yang berusaha kabur dari amukan warga.
Lalu, dengan bantuan Jamal bin Jamal, anak yang mengidap penyakit yang membuat wajahnya mirip dengan semua penderitanya itu, yang menurut Dadang Sidat dan Asep Sapi sudah hilang selama tiga hari itu, kemudian mendekati Aziz Cicak. Lalu tanpa ragu, Dadang Belut pun mulai melepaskan celananya dan mulai duduk di atas toilet. Dan karena dia tampak tidak nyaman dengan posisinya, Dadang Belut lalu mulai jongkok di atas toilet itu. Dan kemudian, sorak sorai dan cemoohan orang-orang pun segera pecah—menyerupai pesta kembang api pada malam tahun baru.
Dengan seluruh tenaganya, Mamat Doma berusaha menahan dan mengunci Asep Sapi.
“Anjing, anjing, anjing!” dengus Asep Sapi lagi. Wajahnya tampak sebuas serigala.***
Catatan:
1 Diolah dari penggalan pembukaan novel Gabriela, Cengkih, dan Kayu Manis karya Jorge Amado.
Aflaz Maosul Kamilah lahir di Garut, Jawa Barat pada 08 September 1998. Buku kumpulan cerpen pertamanya, Sanghyang Taraje, terbit pada 2021. Dapat dihubungi melalui instagram @aflazmaosul.