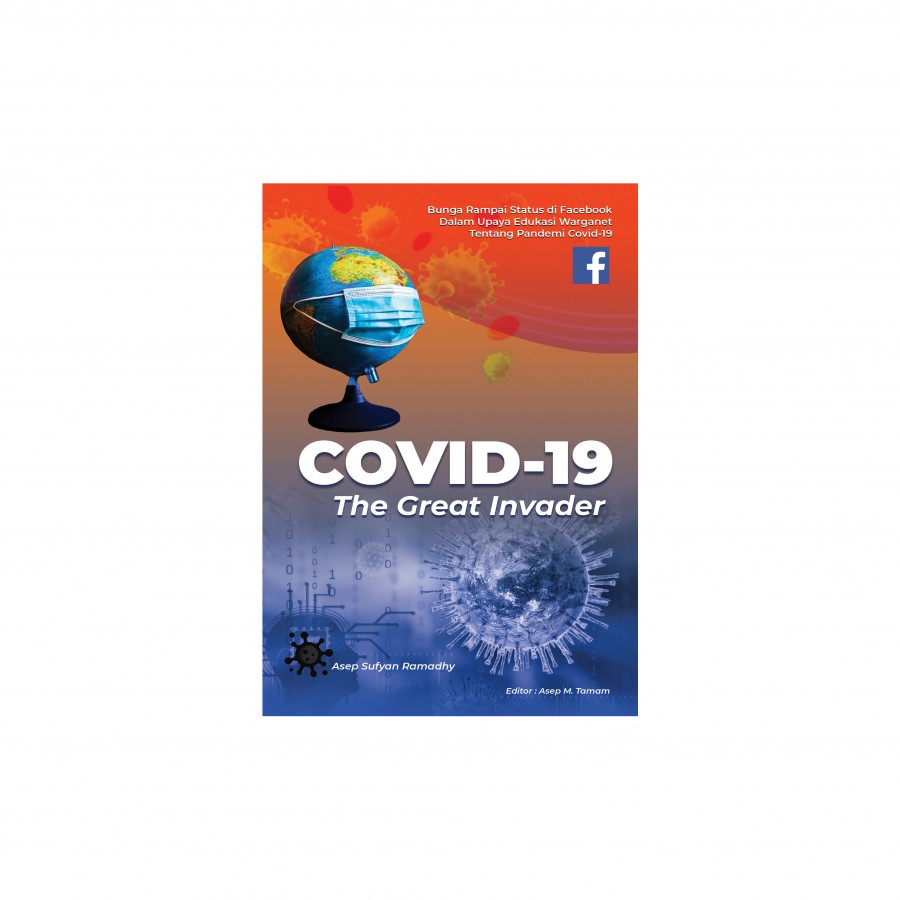Manusia tidak pernah berhenti mempertanyakan tentang dirinya sendiri; identitasnya, makna hidupnya, tujuan hidupnya, dan lain-lain. Namun dalam rentang sejarah yang panjang ini, manusia telah menghimpun banyak sekali alternatif jawaban, yang masing-masing tidak dapat memuaskan seluruh manusia yang dihinggapi kegelisahan eksistensial.
Tentu kita tidak bisa tidak harus berziarah kembali pada pemikiran Jean-Paul Sartre mengenai eksistensialisme. Sartre berkata, dalam sikap ateistiknya yang dingin, bahwa eksistensi mendahului esensi. Hal ini berarti ia menyangkal suatu “desain permulaan” dari nasib manusia dalam proses, sehingga seolah-olah tidak memberikan ruang kebebasan untuk manusia itu. Tentu hal ini dapat dimengerti, bahwa betapa mengerikannya suatu kesadaran bahwa segala nasib hidup kita telah ditentukan oleh “Sesuatu” di atas sana, bahkan sebelum kita dilahirkan sebagai manusia.
Namun pernyataan ini merupakan pernyataan yang relatif sembrono. Kita bisa mengingat kembali wedaran Sartre mengenai être-en-soi, ada-dalam-dirinya, atau kenyataan yang berada di balik yang tampak. Sesuatu yang dalam bahasa Kant adalah Das Ding an Sich. Intinya, sesuatu yang esensinya tidak dapat dikenali dan tidak bertautan dengan kesadaran kita. Namun hal ini, seperti dikritik oleh Van der Weij, bahwa “Sartre terpergok melakukan inkonsekuensi besar sekali,” karena Sartre sendiri justru “mengetahui” hal ini, yang berarti ada pertautan antara kesadarannya dengan sesuatu yang konon independen, tidak bisa dijangkau oleh kesadaran. Sartre, dalam kritiknya Van der Weij, “akan lebih konsekuen bila ia lebih segan lagi menyatakan sesuatu tentang en-soi itu.” Intinya, Sartre terlalu banyak berbicara mengetahui sesuatu yang ia sendiri, secara tidak langsung, yakini “tidak dapat dibicarakan” karena tidak dapat dimengerti.
Akhirnya saya secara pribadi menangkap dikotomi yang terlalu Manikhean pada prinsip fundamental Sartre, yakni bahwa manusia bebas itu berarti Tuhan tidak ada, dan kalau Tuhan ada, berarti manusia tidak bebas. Ketidakbebasan di sini, akibat keberadaan Tuhan, menjadi masalah serius bagi eksistensialisme— khususnya eksistensialisme dalam perspektif Sartre.
Namun saya menelusuri pandangan Heidegger juga, bahwa rasionalitas memang tidak memiliki otoritas absolut. Adagiumnya, atau adagium fenomenologi yang kali pertama digaungkan Husserl, adalah “Zurück zu den Sachen selbst!”, kembalilah pada benda itu sendiri! Adagium ini memberikan tendensi bahwa untuk memahami esensi, maka kembalikan pada Ada yang menampakkan dirinya sendiri, dan bukan pada apa yang kita interpretasikan.
Masalah utama mengenai adanya Tuhan atau sebaliknya bagi saya bukanlah masalah yang relevan. Entah datang dari mana pemikiran bahwa Tuhan hadir dengan segala macam rencana-penciptaan-Nya itu. Saya kira Tuhan juga mampu eksis tanpa harus mencampuri urusan manusia dalam dunia imanen, yakni dunia yang dihidupi oleh individu sadar yang menyusun gagasan eksistensialisme itu.
Spinoza bagi saya lebih dapat diterima, bahwa Tuhan atau alam, natura naturans, adalah yang melahirkan segala eksistensi, kemudian Tuhan atau Alam itu mewedarkan diri dalam substance yang hinggap dalam tiap entitas, yang tidak dapat dimengerti. Barangkali manusia begitu takut dengan sesuatu yang tidak bisa mereka mengerti. Namun dalam keterbatasan semacam itu, lahir pengakuan yang kemungkinan dapat membereskan segala macam poros kegelisahan, atau bahkan keputusasaan. Bila eksistensi kita mendahului esensi, itu layak diterima sebagai semacam panduan hidup luwes, sehingga kita tidak menghadapi ilusi tentang kesia-siaan. Namun menolak sepenuhnya eksistensi “di luar pemahaman manusia” sepenuhnya, yang manurut saya melampaui konsepsi ruang waktu—juga bentuk—tidak akan berpengaruh banyak.
Sartre sendiri dalam bukunya L’existentialisme est un humanisme (1945) menyatakan bahwa “Bila Tuhan ada atau tidak, hal itu tidak akan banyak berpengaruh.” Dalam hal ini saya sepakat dengannya. Namun kenapa di awal-awal, ia seolah-olah memandang ini sebagai sesuatu yang problematik—dan tidak dengan tenang menerima kemungkinan akan eksistensi-Nya.
Dari perdebatan semacam ini, saya menangkap dua realitas. Pertama adalah realitas yang tertangkap oleh sepasang mata eksistensialisme ala Sartre, yakni bahwa kita bebas, dan dengan begitu Tuhan tidak ada. Namun saya memikirkan—dan menerima—suatu kemungkinan, bahwa Tuhan ada (dan mewedarkan diri dalam Alam; tidak dalam wujud antromorfik yang sibuk mengurusi nasib manusia) dan menjadikan kebebasan kita sebagai semacam ilusi.
Ada yang mampu dipahami oleh rasionalitas kita, dan tentu ada bagian yang tidak. “Kebenaran” mengenai sesuatu di luar diri kita, suatu, barangkali, desain sistemis atas nasib manusia, bisa jadi ada, tetapi sepenuhnya tidak dapat dimengerti—apalagi dibuktikan. Saya tidak hendak melibatkan uraian Sam Harris dalam wacana ini. Namun, kebebasan eksistensialis juga menjadi mungkin, karena manusia tidak dapat mengerti realitas di luar dirinya, dan menjadi mampu “merasa bebas menentukan nasibnya” seiringan dengan “pilihan-pilihan Alam”.
Akhirnya, sebagai penekanan, saya hendak menolak pertanyaan “mana yang lebih dulu; eksistensi atau esensi?”, karena bagi saya realitas di luar sana tidak bisa dimengerti dengan konsep, misalnya, waktu dan kemewaktuan dunia yang kita pahami. Sesuatu yang saya yakini adalah, takdir bergerak beriringan dengan pilihan-pilihan kita—tanpa ada interval waktu, karena waktu di “luar sana” tidak eksis, dan waktu “di sini” adalah artifisial.
Candrika Adhiyasa, menulis puisi, novel, cerita pendek, esai. Meminati filsafat (khususnya eksistensialisme dan fenomenologi) dan cultural studies. Pernah belajar ilmu lingkungan di Universitas Gadjah Mada. Instagram @candrimen. No. Kontak: 0821-2006-6009 (WA).