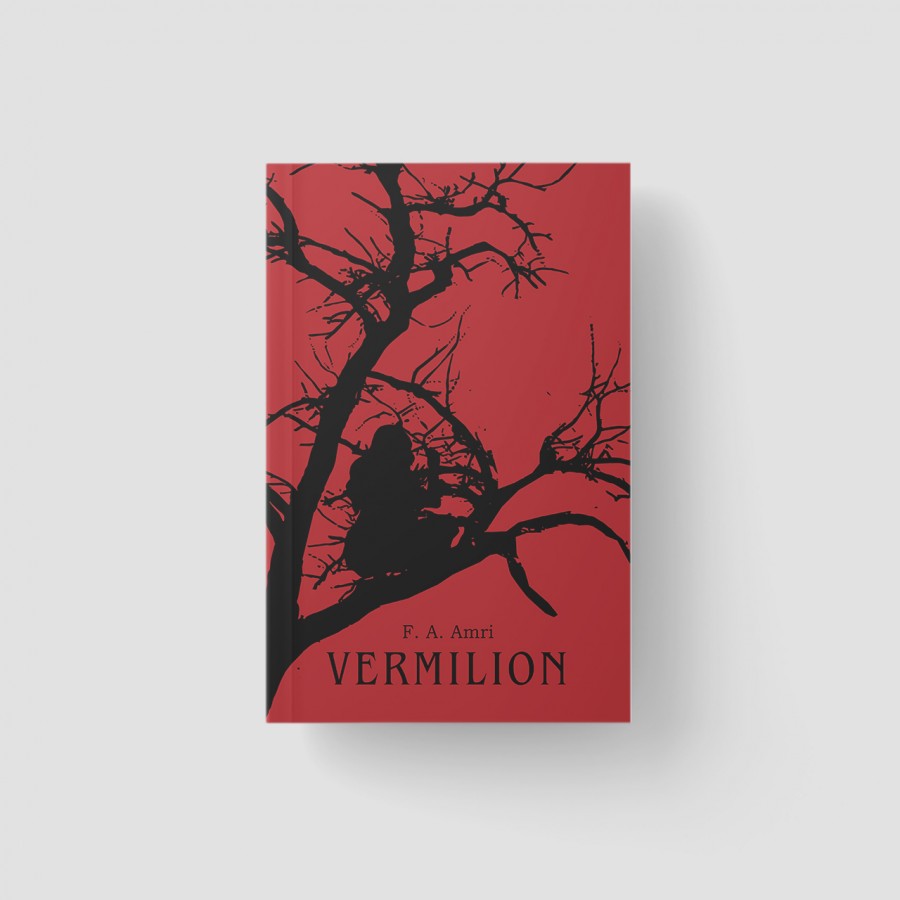“Musik punya kekuatan untuk membangkitkan ingatan dengan amat jelas sampai terkadang membuat sesak dada.”
- Haruki Murakami, Lelaki-Lelaki Tanpa Perempuan (2022:83)
Nama Alma Maheltra baru saya dengar pertama kali—ketika Agus Salim Maolana memperkenalkannya kepada publik saat acara ulang tahun Langgam Pustaka yang ke-8. Sejauh yang saya ingat, sudah lama saya tidak mendengarkan bunyi “denyit” violin (biola) secara rill. Ada kesan “asing” dalam tubuh saya ketika menerima bunyi semacam itu—saat Alma menggesek busur biolanya dalam lagu pertama—yang saya tidak ketahui judulnya, di momen ini muncul sayatan ‘ngilu’ dalam dada saya. Pencandraan bunyi tentu akan sangat subjektif—yang memiliki banyak faktor, salah satunya ‘momentum’. Namun, perlu ditekankan bahwa saya dalam hal ini hanya berbicara momentum bunyi, instrumen dan sensasi.
Dialog yang disampaikan Alma, jelas bukan melalui lirik, melainkan hanya bunyi. Dalam gesekkan nada tertentu—saya menangkap frekuensi “jeritan” yang menghadirkan nuansa “perih” yang menyelimuti bagian dada saya—dan di sana saya berupaya menghayati, meski dengan perasaan “tersayat-sayat” bersamaan dengan itu muncul semacam memori-memori kelam naik ke permukaan—yang sebelumnya jarang disadari. Barangkali benar bahwa setiap bunyi selalu ada duka yang bersemayam. Bunyi bagaimanapun menjadi elemen paling mendasar sebuah komposisi musik. Meski tanpa kehadiran lirik, musik menjadi bebas dari jeratan interpretasi. Dan ketika lirik absen, semua bunyi tampak jernih tanpa ada kontaminasi interpretasi. Maka, makna bunyi bisa berbeda-beda—bahkan menjadi tak terbatas.
Musik yang dibawakan Alma—yang kita kerap sebut sebagai “Instrumental” adalah bunyi murni dari benda itu sendiri. Meskipun ada beberapa nada musik yang familiar, tetapi Alma melalui violinnya menghadirkan warna yang berbeda dari musik aslinya. Ada proses modifikasi pada intensitas bunyi tertentu.
Misalnya, dalam lagu lain yang berbeda—Alma terlihat menyatukan dirinya dengan ritme nada yang intens, ia membiarkan bunyi membebaskan diri dari jeruji bahasa, menyihir pendengarnya masuk ke dalam kepingan-kepingan tersembunyi. Dalam suasana itu, ada semacam paradoks antara persona yang 'menolak' mengingat kembali memori yang sengaja ditutupi rapat-rapat agar tidak muncul, disisi lain ada bagian persona yang "menghayati" kepedihan dengan bisu—yang nyaris memilukan, terkesan seolah ditusuk-tusuk ratusan jarum di sekujur tubuh. Di titik ini bunyi tampak memainkan emosi manusia bahkan mencampur-adukkan hingga kalut; meluap, memunculkan keharuan. "Betapa bunyi dapat meneriakkan keharuan-keharuan yang sebelumnya tidak dapat dibahasakan."
Di sini musik menjadi hierarki paling tinggi dibandingkan seni yang lain, karena ia lepas dari representasi di dunia ini. Bahkan, filsuf “muram” asal Jerman, Schopenhauer—mengistimewakan musik sebagai seni yang paling tinggi—di tempat tertinggi yang tak terjangkau karena musik bukanlah representasi sesuatu yang ada di dunia ini. Di dalam musik tidak akan dijumpai salinan atau tiruan dari suatu eksistensi di dunia. Artinya, musik adalah ekspresi murni dari sifat terdalam dari realitas kita yang memungkinkan membawa kita keluar dari dunia representasi yang ilutif.
Musik yang kita rasakan itu dengan sifat alami yang paling dasar—itulah sebabnya efek dari musik begitu kuat dan merembes daripada seni lainnya, karena musik tidak berbicara tentang bayangan, tetapi tentang benda-pada-dirinya-sendiri. Perlu ditekankan bahwa musik yang dimaksud Schopenhauer adalah musik instrumental. Namun, dalam hal ini saya menemukan benang kontradiksi—antara Murakami dan Schopenhauer. Bila filsuf muram mengatakan bahwa “Musik bisa membebaskan kita dari penderitaan di dunia ini—berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan Murakami dalam satu cerpennya, sejauh yang saya ingat—kira-kira begini, “Musik punya kekuatan untuk membangkitkan ingatan dengan amat jelas sampai terkadang membuat sesak dada.”
Melalui uraian Murakami di atas, saya dan mungkin sebagian pendengar setidaknya sepakat dalam momentum ini—saat mendengarkan Alma, kita diseret jauh pada lanskap yang paling intim. Ketika bunyi denyit itu memantul pada dinding-dinding, kita larut dalam kepedihan yang sunyi. Saya merasakan sebuah situasi di mana saya menemukan kepingan memori memilukan yang tersembunyi di pojok ruangan—Di sana saya membayangkan hendak membuka lemari yang terkunci rapat-rapat, dan ketika saya mencoba menyentuh dan membuka sorongan lemari itu pelan-pelan, ada semacam bekas goresan-goresan—lebih tepatnya bekas sayatan-sayatan halus benda tajam yang membekas di bagian luar dinding lemari. Semakin ditelusuri semakin tampak dan jelas setiap bagian lemari itu—berbeda pula ketebalan sayatan-sayatannya; tebal dan halus—dan kemudian setelah memaksakan membuka setiap sorongan lemari, sensasi perih di bagian dada semakin terasa. Di sanalah seolah-olah saya mendapatkan perasaan yang kompleks—dan mendengar resonansi jeritan yang berbeda di setiap bagian lemari; dari yang paling nyaring sampai yang paling halus—bersamaan dengan itu timbullah perasaan perih sesuai frekuensi jeritan yang ditimbulkan.
Perasaan kompleks ini kemudian disambung dengan kepingan-kepingan memori yang mengandung sensasi “ngilu”. Momentum ini di waktu yang bersamaan—saya rasakan melalui bunyi-bunyi gesekkan yang ditimbulkan dari sentuhan busur dengan senar biola Alma. Perasaan ngilu itu muncul intens ketika Alma membawakan lagu penutupnya, di sana saya menemukan warna yang jauh berbeda dengan lagu aslinya. Ada kompleksitas suasana, dari nuansa lagu aslinya yang riang menjadi melankolis. Perspektif dualis ini semacam memberi kita kesan bahwa dalam “keriangan” akan selalu ada jeritan yang bersemayam. Tentu anggapan itu terdengar “pesimistis”.
Suasana melankolis itu, bila mengutip Heidegger, adalah Befindlichkeit—yang artinya berada, merasa, atau terdapat. Mungkin kata ini dapat diterjemahkan dengan satu kata, ‘ketersituasian’. Dari sini saya beranggapan bahwa ‘merasa’ berkelindan dengan ‘berada’, dan ‘berada’ erat kaitannya dengan ‘terdapat’. Di mana kita mendengar bunyi itu, di situlah suasana hati kita disituasikan, maka di sana jugalah cara mengada kita ditala sesuai dengan situasi. Gambaran saya, “di mana kita mendengar bunyi” adalah sesuatu yang konstruksi dan penuh rekaan atau arti lain yang lebih sederhananya—larut dalam penghayatan. Misalnya, ketika saya menghayati bunyi dari biola Alma—saya tengah membayangkan dicaci maki oleh seseorang—yang menimbulkan sensasi pedih dalam dada saya. Maka, makna bunyi dari sebuah instrumen bisa demikian berbeda setelah melewati benak pendengar—tergantung situasi subjek saat mendengarkan bunyi.
Dengan demikian, Alma melalui bunyi telah menghasilkan interpretasi tak terbatas—dalam musik yang ‘bisu’ dalam hal ini absennya lirik—kita didorong jauh menyelami diri secara intensif. Dan menemukan kepingan momen-momen yang jarang kita sadari. Lebih jauh, kita semacam mendapatkan terjemahan dari kepedihan-kepedihan yang sebelumnya tidak bisa kita bahasakan.
Indra Kresna Wicaksana, S.Pd. Lahir di Bandung, 11 April 1999. Pernah belajar ilmu Pendidikan Sejarah di Universitas Siliwangi. Meminati kajian seputar: Sejarah Kolonialisme, Filsafat, Sastra dan Kebudayaan. Mengelola @kuskarah dan @ohara_post.
Twitter @indrakw_ , Instagram @indrakw___