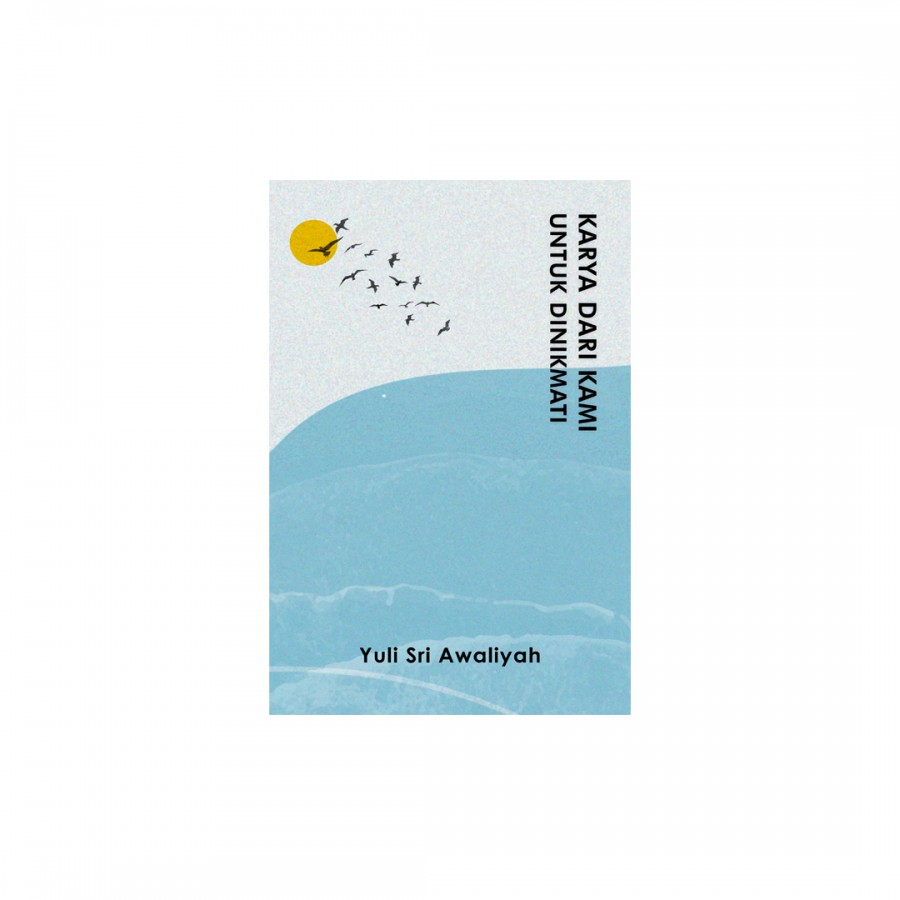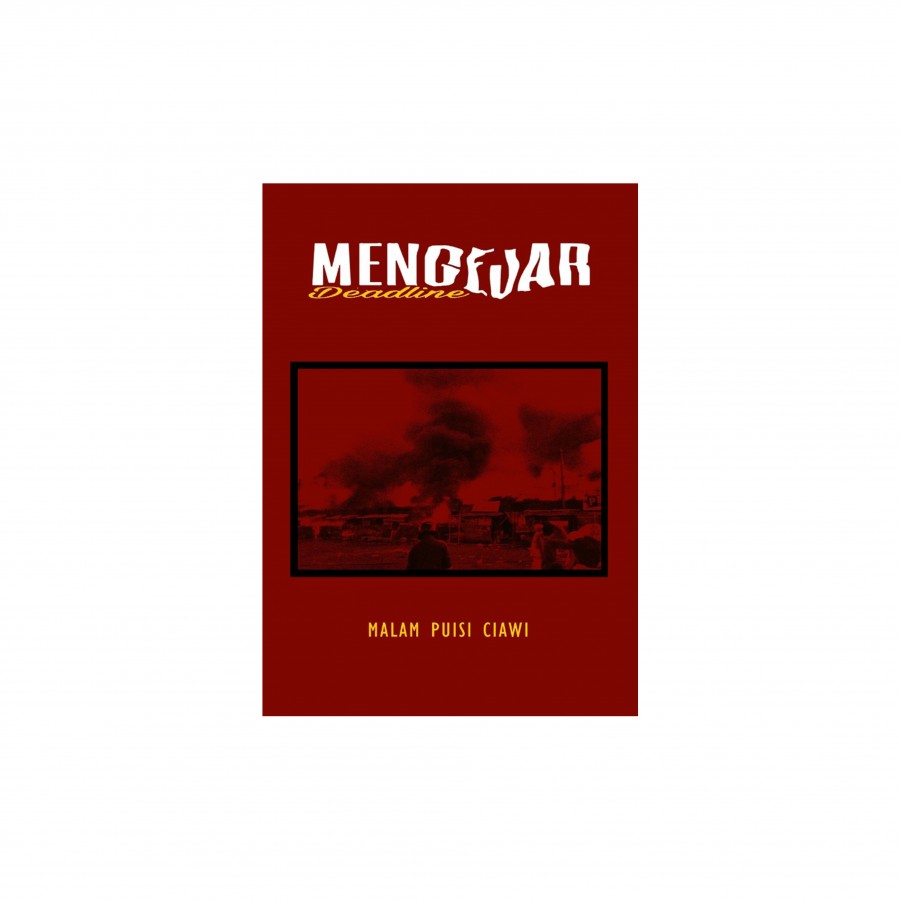Di tengah hiruk pikuk modernitas, kita sering kali terperangkap dalam kesibukan yang memaksa kita menjauh dari diri kita sendiri. Teknologi yang semakin mendominasi, tuntutan ekonomi yang tak pernah berhenti, dan tekanan sosial yang terus mendorong kecepatan hidup membuat kita semakin teralienasi, tidak hanya dari lingkungan kita, tetapi juga dari eksistensi kita yang paling mendasar.
Kehidupan urban dengan segala kecanggihannya mengikis koneksi manusia dengan alam, menciptakan jurang antara diri kita dengan tempat kita berasal. Alam bukan lagi hanya sekadar ruang fisik yang dipenuhi dengan pepohonan, gunung, sungai, dan lautan. Ia adalah tempat bagi kita untuk menelusuri kembali makna eksistensi, tempat untuk merenungi keberadaan kita dalam dunia yang lebih luas. Konsep eco-existentialism berangkat dari gagasan yang mengatakan bahwa alam liar merupakan ruang di mana manusia dapat menemukan kembali dirinya, baik secara fisik maupun spiritual, melalui refleksi yang mendalam.
Filsuf eksistensialis, seperti Jean-Paul Sartre dan Martin Heidegger, mengajukan ide bahwa manusia adalah makhluk yang terlempar ke dunia tanpa tujuan pasti, tetapi memiliki kebebasan untuk menciptakan makna dari eksistensinya sendiri. Melalui pengalaman mendalam di alam, manusia sering kali dihadapkan pada refleksi eksistensial tentang makna hidup, kematian, dan keberadaannya di dunia.
Penemuan Diri melalui Keheningan dan Keindahan Alam Liar
Alam sering kali menjadi cermin bagi refleksi diri. Dalam keheningan yang ditawarkan oleh alam liar, manusia akan dihadapkan pada diri mereka sendiri tanpa adanya sedikit pun gangguan. Pengalaman seperti itu tentu memberikan ruang bagi manusia untuk merenung dan menelaah dirinya secara mendalam.
Ketika seseorang berdiri di hadapan pegunungan yang megah, atau terbenam dalam hutan yang sepi, ia sering kali merasakan pengalaman eksistensial yang menggugah—sebuah momen di mana ia terpisah dari hiruk pikuk modernitas dan kembali ke inti eksistensinya.
Keheningan alam menjadi medium yang ideal untuk kontemplasi. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Rachel Kaplan & Stephen Kaplan pada 1989 dalam The Experience of Nature : A Psychological Perspective mengungkapkan bahwa lingkungan alami mampu memberikan kesempatan bagi manusia untuk memulihkan perhatian yang terkuras oleh kehidupan perkotaan, membuka pintu bagi refleksi diri yang lebih dalam. Maka, alam bukan sekadar tempat, tetapi juga sebuah ruang psikologis yang memungkinkan manusia merenungkan keberadaan dan makna hidupnya.
Penemuan diri melalui alam bukanlah hal yang baru. Tradisi ini telah dikenal dalam berbagai budaya dan tradisi spiritual, seperti retret di biara-biara, perjalanan ziarah ke gunung-gunung suci, atau bahkan perjalanan penemuan diri yang dilakukan oleh para filsuf. Alam liar, melalui keheningannya memang menawarkan ruang untuk refleksi yang lebih jernih, tanpa gangguan dari dunia luar.
Ada pun, alam juga mencerminkan ketidakkekalan hidup. Siklus hidup dan mati yang terjadi secara alami di alam—dari tumbuhnya pepohonan hingga layunya bunga—mengajarkan manusia tentang keterbatasan hidup. Ketika kita menyadari betapa rapuhnya kita di hadapan kekuatan alam yang tak mungkin terhindarkan, kita akan dipaksa untuk merenung lebih dalam tentang siapa kita dan apa yang benar-benar penting dalam hidup ini.
Alam menjadi guru yang tak terucapkan, sebuah refleksi dari kompleksitas eksistensial manusia. Ia menawarkan kebijaksanaan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain.
Keterasingan dalam Kehidupan Modern
Teknologi yang mendominasi kehidupan kita sehari-hari sering kali menyebabkan alienasi, perasaan keterasingan yang menimbulkan kehampaan eksistensial. Karl Marx berbicara tentang alienasi dalam konteks pekerja yang terasing dari hasil karyanya, sementara dalam konteks modern, alienasi juga terjadi karena manusia semakin menjauh dari alam. Alienasi ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mental dan spiritual.
Manusia modern terjebak dalam lingkaran rutinitas yang membuatnya terputus dari lingkungan alamnya. Dengan kondisi ini, kembalinya manusia ke alam liar menawarkan peluang untuk pemulihan. Alam, dengan kesederhanaannya, mengundang kita untuk merasakan kembali keterhubungan yang selama ini hilang. Keterhubungan ini menjadi langkah awal untuk mengatasi alienasi eksistensial.
Sebuah penelitian oleh Louv (2008) menunjukkan bahwa hilangnya kontak manusia dengan alam yang disebut sebagai nature-deficit disorder, telah memengaruhi kesejahteraan mental manusia. Ketika manusia terlalu lama hidup dalam lingkungan yang didominasi oleh teknologi dan urbanisasi, ia kehilangan kemampuan untuk merasakan keterhubungan dengan dunia di sekitarnya. Proses kembali ke alam bukan hanya menyegarkan fisik, tetapi juga menyembuhkan mental dan spiritual. Di alam liar, manusia kembali menjadi bagian dari ekosistem yang lebih besar, di mana ia tidak lagi merasa terisolasi.
Antara Ketakutan dan Kekaguman Di Alam Liar Sebagai Refleksi Eksistensi
Alam liar sering kali menimbulkan perasaan sublim—campuran antara ketakutan dan kekaguman—ketika manusia dihadapkan pada kekuatan alam yang tak terduga. Pengalaman sublim ini adalah salah satu cara di mana manusia merenungkan eksistensinya di dunia.
Pengalaman sublim ini berakar pada gagasan filsuf Edmund Burke yang memperkenalkan konsep sublime sebagai perpaduan antara ketakutan dan kekaguman yang melampaui logika manusia. Perasaan tersebut muncul ketika seseorang dihadapkan pada fenomena alam yang luar biasa, seperti badai, gunung yang menjulang, atau lautan luas yang bergejolak. Dalam momen ini, manusia menyadari betapa kecil dan tak berdayanya dirinya di hadapan alam semesta yang tak terukur.
Salah satu contoh klasik dari pengalaman sublim ini bisa ditemukan dalam karya Romantic poets seperti Wordsworth dan Shelley, yang menulis tentang perasaan mereka ketika berada di alam liar. Mereka merasa diliputi oleh perasaan kagum sekaligus takut ketika berhadapan dengan pemandangan yang melampaui kapasitas manusia untuk memahaminya. Pengalamannya memaksa manusia untuk merenungkan kembali keterbatasannya, bukan hanya sebagai makhluk yang fana, tetapi juga sebagai bagian kecil dari alam yang lebih besar.
Perasaan sublim ini juga memunculkan kesadaran mendalam tentang ketidakberdayaan manusia di hadapan alam, tetapi pada saat yang sama, itu juga memicu rasa takjub akan keindahan dan kekuatan alam itu sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Immanuel Kant dalam Critique of Judgment, pengalaman sublim tidak hanya mengingatkan kita pada keterbatasan fisik kita, tetapi juga membuka jalan bagi refleksi tentang makna keberadaan kita dalam cakupan yang lebih luas.
Ketika kita menghadapi kekuatan alam yang tidak bisa dikendalikan—badai yang menghancurkan, gunung berapi yang meletus, atau ombak yang besar—kita dipaksa untuk menerima kenyataan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari kita.
Memahami Mortalitas Ekosistem yang Lebih Luas
Salah satu elemen kunci dari filsafat eksistensialisme adalah kesadaran akan kematian. Menurut Martin Heidegger, manusia adalah satu-satunya makhluk yang menyadari kematiannya sendiri, dan kesadaran ini sangat penting untuk memahami makna hidup. Alam liar, dengan siklus kehidupan dan kematiannya yang jelas, menawarkan pengalaman yang unik untuk merenungkan mortalitas.
Di alam, kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan bagian alami dari siklus kehidupan. Pohon-pohon yang tumbang, hewan-hewan yang mati, atau daun-daun yang gugur, semuanya menunjukkan bahwa kematian adalah bagian dari aliran kehidupan yang lebih besar. Ketika manusia menyaksikan siklus ini, ia dipaksa untuk merenungkan posisinya dalam ekosistem yang luas ini.
Siklus alam ini sering kali memberikan perspektif yang berbeda tentang kematian dibandingkan dengan pandangan manusia modern, yang cenderung menghindari pembicaraan tentang kematian atau melihatnya sebagai sesuatu yang tragis. Alam mengajarkan bahwa kematian adalah bagian tak terpisahkan dari keberadaan. Siklus hidup-mati di alam menunjukkan bahwa setiap kematian menciptakan ruang bagi kehidupan baru, sebuah pemahaman yang sering kali sulit diterima dalam kehidupan urban yang steril dan terpisah dari alam.
Dalam pengalaman eksistensial di alam liar, manusia tidak hanya merenungkan kematiannya sendiri, tetapi juga memahami bahwa ia adalah bagian dari siklus yang lebih luas. Alam memperjelas bahwa meskipun kita hanya hidup dalam rentang waktu yang terbatas, namun kita adalah bagian dari proses yang terus berlanjut.
Dengan merenungkan kematian dalam struktur ekosistem yang lebih besar, manusia dapat mencapai penerimaan yang lebih dalam tentang kehidupannya sendiri. Kesadaran akan keterbatasan ini tidak mengarah pada pesimisme, melainkan pada pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya setiap momen yang kita miliki.
Mengembangkan Konsep Heideggerian tentang Being
Dalam filsafat Heidegger, konsep 'being' atau Dasein adalah tentang bagaimana manusia berada di dunia dengan cara yang otentik. Heidegger menekankan pentingnya "being-in-the-world" sebagai cara manusia menghubungkan dirinya dengan dunia yang lebih besar. Alam liar memberikan peluang unik untuk mengalami konsep ini secara nyata, di mana manusia tidak hanya ada, tetapi benar-benar berada di dalam dunia yang alami.
Pengalaman di alam liar memungkinkan manusia untuk merasakan eksistensinya secara lebih mendalam dan otentik. Nantinya manusia bukan lagi hanya sekadar sebagai subjek yang mengamati dunia, tetapi sebagai bagian dari dunia itu sendiri. Ia terlibat langsung dengan alam, merasakan angin, mendengar suara sungai, dan menyaksikan matahari terbenam, semuanya sebagai bagian dari keberadaannya yang lebih luas.
Heidegger percaya bahwa dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering kali terjebak dalam kesibukan dan rutinitas yang membuatnya terasing dari dirinya sendiri.
Di alam, manusia tidak lagi merasa sebagai entitas yang terpisah dari dunia, tetapi sebagai bagian dari jaringan kehidupan yang lebih besar. Pengalaman ini membawa pada refleksi yang lebih mendalam tentang eksistensi dan bagaimana kita bisa berada di dunia dengan cara yang lebih otentik. Melalui interaksi langsung dengan alam, manusia dapat mempraktikkan "being-in-the-world" dengan cara yang lebih mendalam dan sejati.
Banyak tradisi spiritual, seperti Taoisme dan Zen Buddhisme yang menekankan pentingnya alam sebagai tempat untuk menemukan kedamaian batin dan keterhubungan yang mendalam dengan diri sendiri.
Ada banyak ketersediaan ruang di mana manusia dapat mencapai bentuk kontemplasi yang lebih maksimal, bukan hanya sebagai refleksi terhadap dunia di luar dirinya, tetapi juga sebagai sarana untuk merenungkan keberadaan diri. Di tengah kesunyian alam, manusia dihadapkan pada realitas yang sederhana namun penuh makna: angin yang berhembus, pepohonan yang bergoyang, atau suara air yang mengalir. Ini semua menjadi alat mediasi bagi pikiran manusia untuk merenungkan hidup dan maknanya.
Proses meditasi di alam akan membantu manusia untuk melepaskan diri dari hiruk-pikuk kehidupan modern yang penuh distraksi.
Transendensi yang dialami di alam liar bukan hanya tentang melarikan diri dari kehidupan sehari-hari, tetapi tentang menemukan dimensi baru dari keberadaan kita. Alam menawarkan kemungkinan bagi manusia untuk mengatasi batasan-batasan dirinya dan mencapai pemahaman yang lebih luas tentang makna hidup dan hubungannya dengan alam semesta. Dalam keadaan ini, manusia merasa bahwa dirinya adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih luas, dan lebih bermakna daripada sekadar kehidupan sehari-hari yang terbatas.
Fatih Hayatul Azhar, seorang mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan yang hobi menulis dan memakan pisang. Instagram: @fateh.hayatul