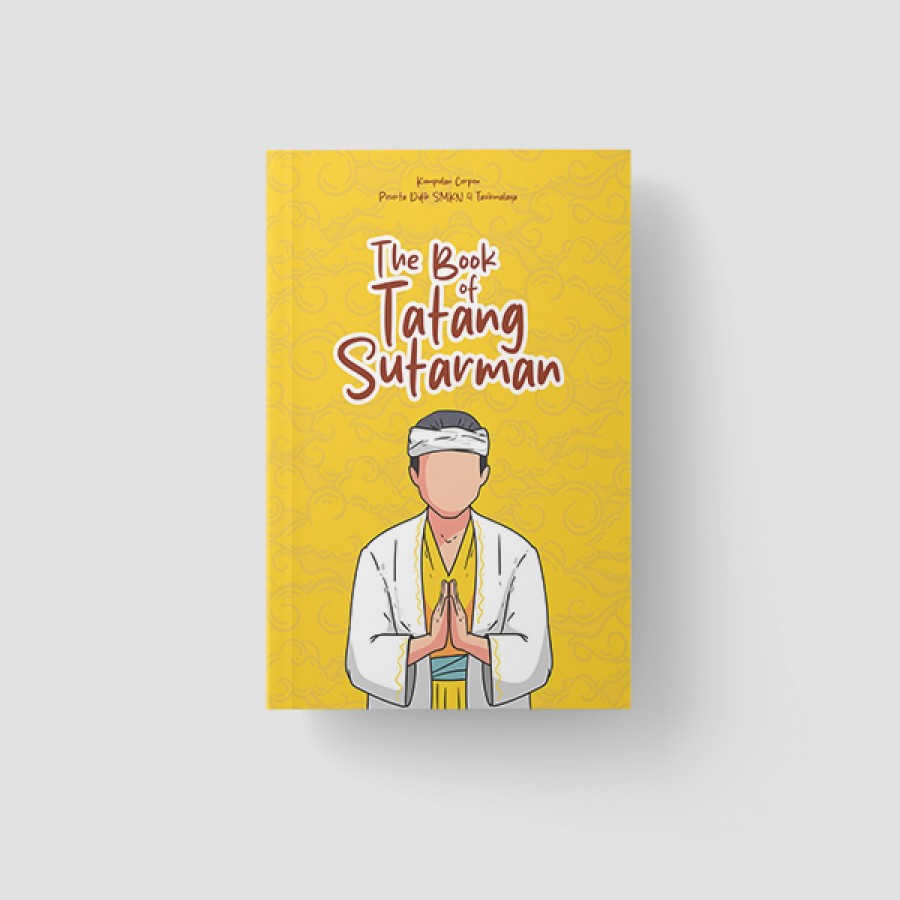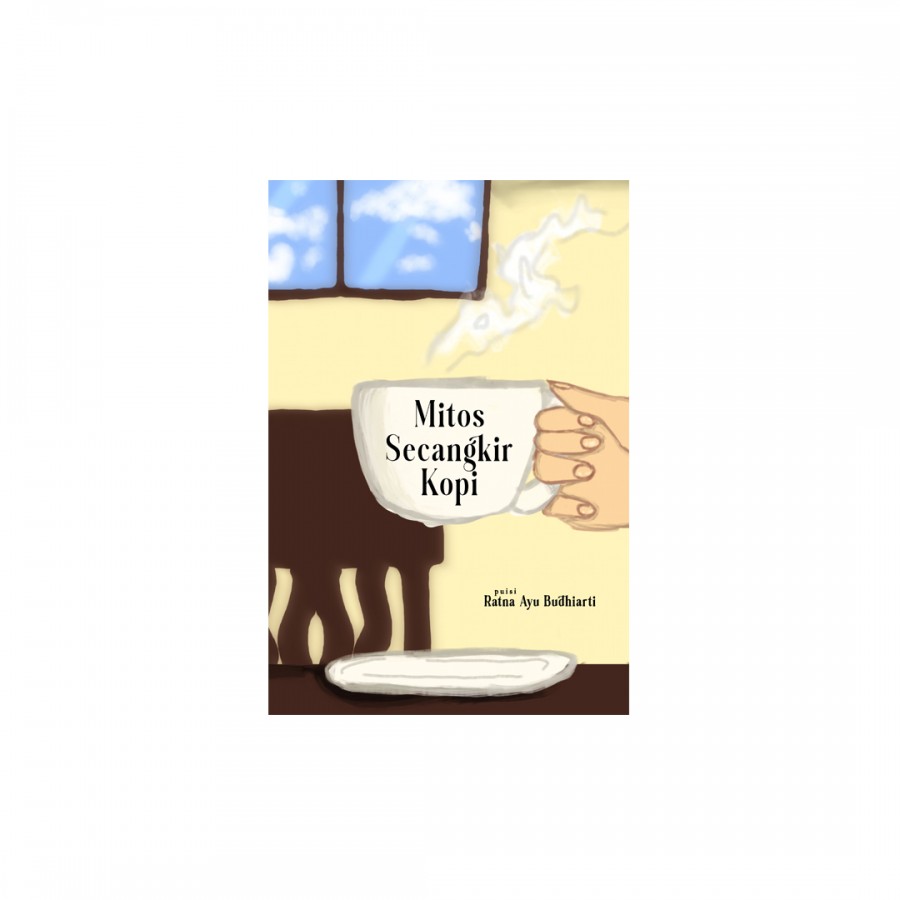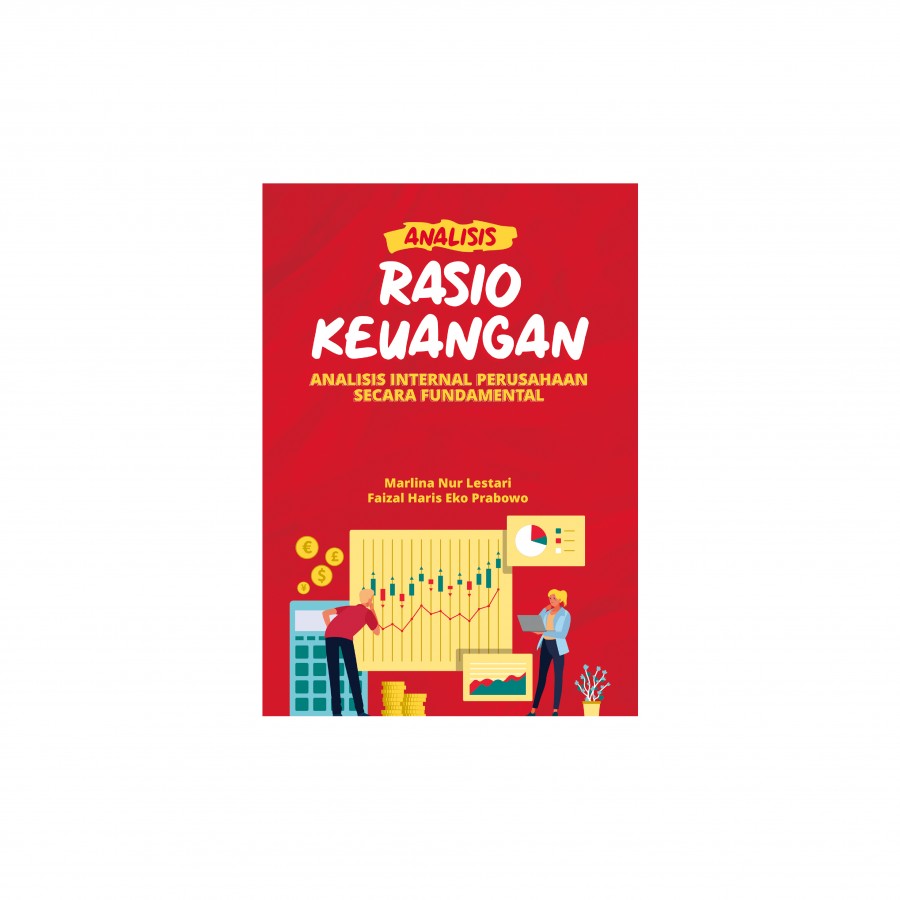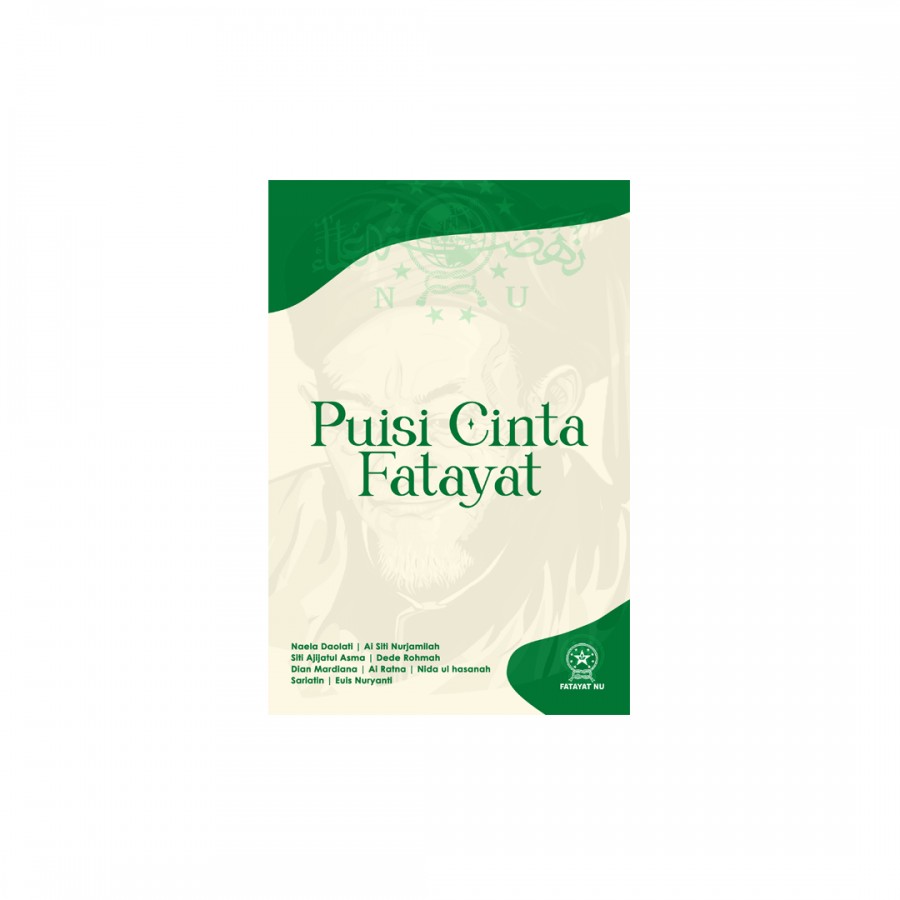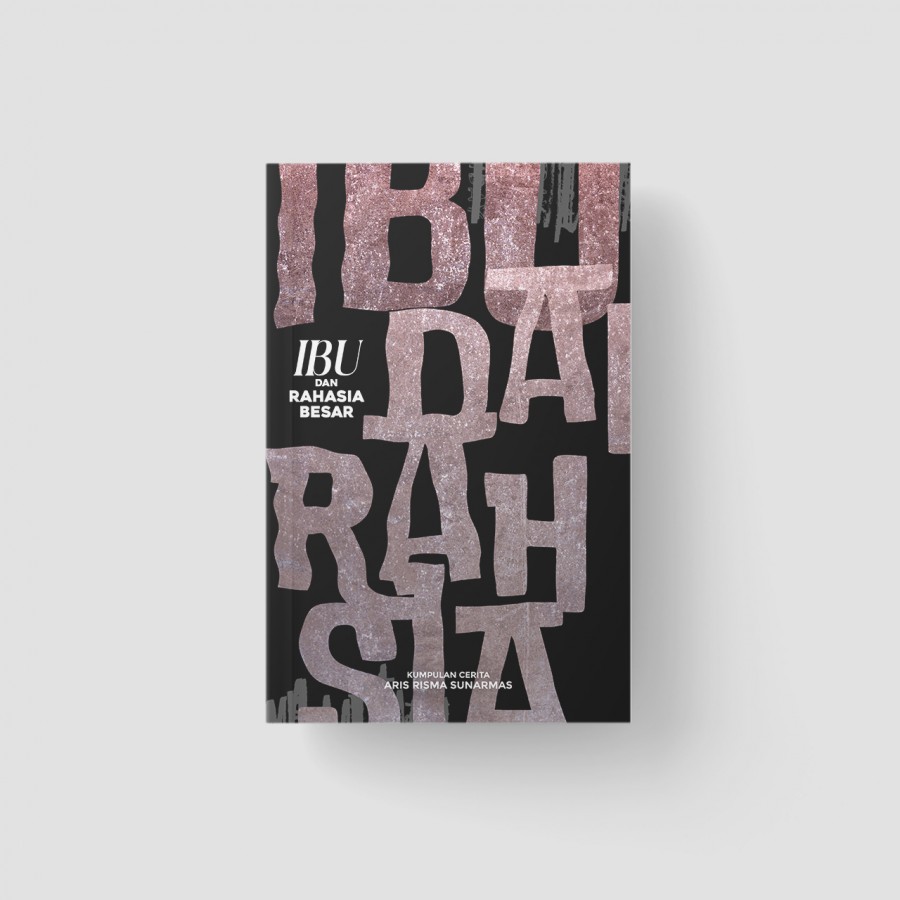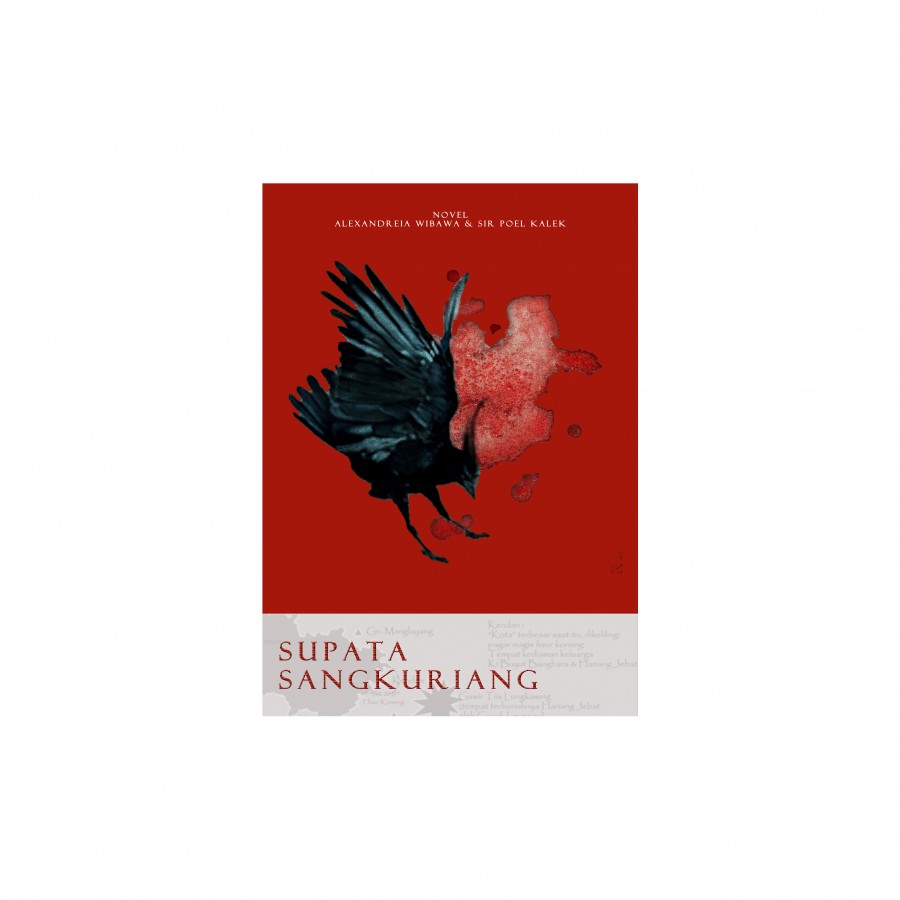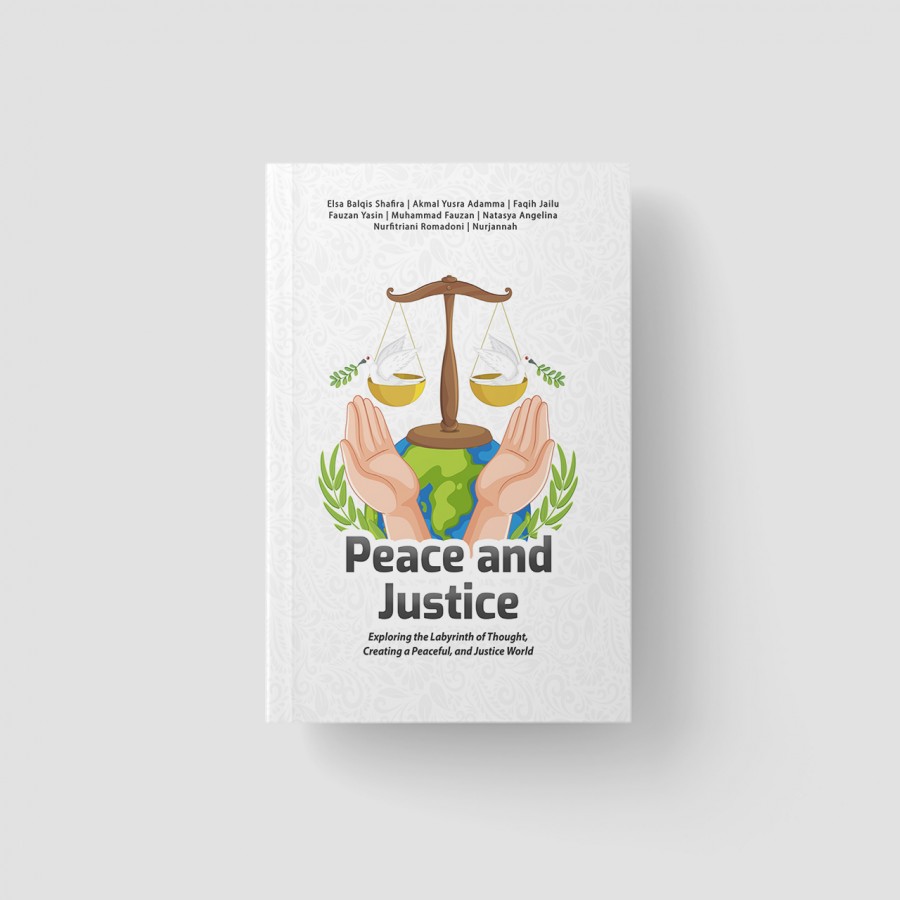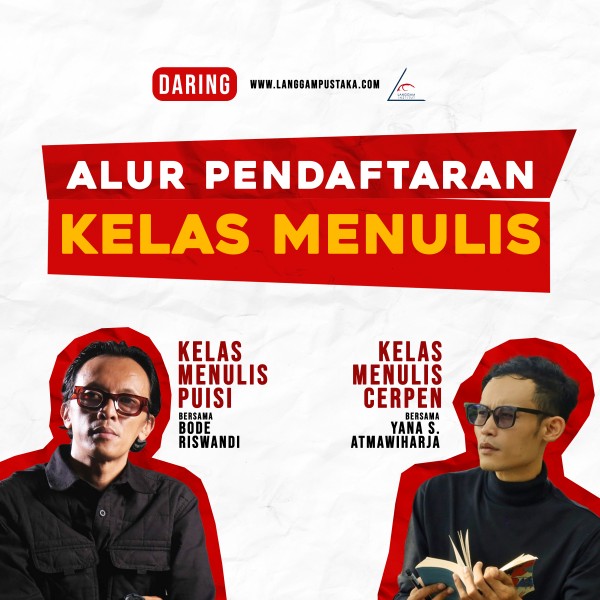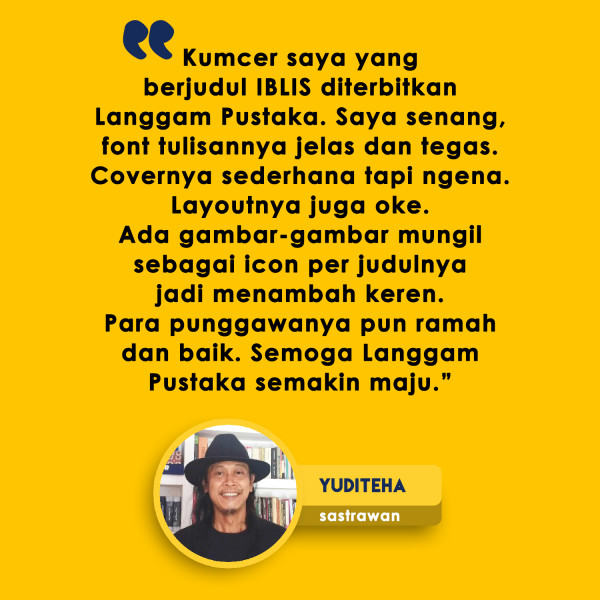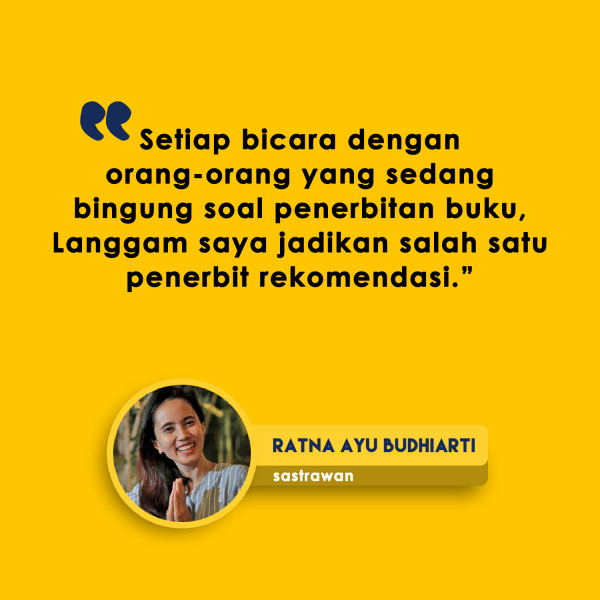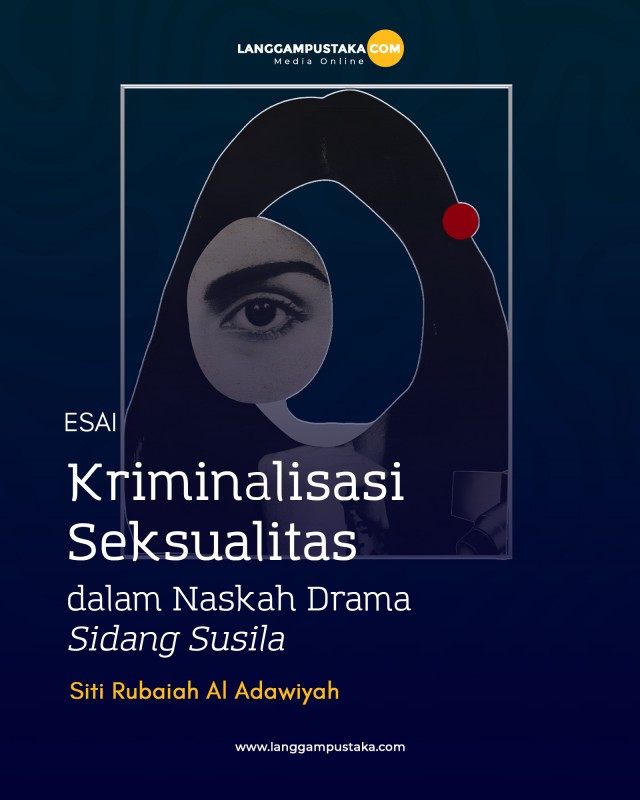
SETIAP waktu, kehidupan manusia terus berjalan dan menghasilkan berbagai persoalan baik antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, maupun manusia dengan Tuhan. Persoalan yang terjadi antara manusia dengan manusia lainnya merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari dinamika sosial di masyarakat. Interaksi yang dilakukan dalam masyarakat sering kali menimbulkan berbagai permasalahan yang berkisar pada perbedaan pendapat, perselisihan, konflik terkait berbagai aspek kehidupan sosial. Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi akibat dari adanya ketidakadilan, diskriminasi, kepentingan kekuasaan, serta berbagai hal lainnya.
Sastra menjadi ruang untuk mengkritik permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Dengan demikian, sastra bukan hanya sebagai hiburan namun juga memiliki peran penting sebagai alat kritik terhadap ketidaksesuaian yang terjadi dalam kehidupan sosial. Salah satu karya sastra yang sering digunakan untuk melakukan kritik secara tidak langsung yaitu drama.
Sastra menjadi ruang untuk mengkritik permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Karya sastra adalah bentuk karya yang secara langsung dan hakiki berhubungan dengan manusia (Ratna, 2004 hal.334). Dengan demikian, sastra bukan hanya sebagai hiburan namun juga memiliki peran penting sebagai alat kritik terhadap ketidaksesuaian yang terjadi dalam kehidupan sosial. Salah satu karya sastra yang sering digunakan untuk melakukan kritik secara tidak langsung yaitu drama. Penulisan drama tidak hanya untuk menceritakan suatu kisah yang secara artistik dan imajinatif dibaca, tetapi juga harus dipertunjukkan melalui gerak dan perilaku yang ditonton secara bersama (Hasanudin, 1996 hal.1).
Naskah drama Sidang Susila mengisahkan seorang penjual balon bernama Susila yang ditangkap paksa saat razia moral. Ia ditangkap akibat dituduh melakukan tindakan pornografi yaitu dengan melakukan tarian erotis bersama penari tayub, ia juga dituduh menjual barang-barang yang berkaitan dengan pornografi dengan tuduhan bahwa balon yang dijualnya akan menimbulkan fantasi liar bagi anak-anak. Dalam naskah drama ini, terdapat isu utama yang ingin disampaikan yaitu berupa kritik terhadap RUU Antipornografi dan Antipornoaksi pada tahun 2008 yang dianggap membatasi hak asasi masyarakat terutama dalam hal seksualitas.
Pemerintah seakan mengawasi tubuh dan seksualitas masyarakat melalui peraturan yang dirancangnya. Tubuh dan seksualitas seharusnya menjadi ranah pribadi masing-masing individu, namun akibat adanya rancangan undang-undang tersebut membuat masyarakat kehilangan kebebasan berekspresi dan hak asasinya. Naskah drama ini ditulis oleh Agus Noor yang mengembangkan karya Ayu Utami. Ayu Utami merupakan penulis yang banyak membahas isu terkait agama dan seks. Karya novel pertamanya berjudul “Saman” yang terbit pada tahun 1998. Sedangkan, Agus Noor merupakan seorang penulis puisi dan prosa. Ia juga dikenal sebagai penulis naskah drama yang terkenal gaya parodi yang cenderung satir.
Agus Noor bersama dengan Ayu Utami menuliskan naskah drama Sidang Susila sebagai bentuk kritik terhadap persoalan sosial yang terjadi yaitu adanya RUU Antipornografi dan Antipornoaksi yang dianggap sebagai sebuah kekonyolan dalam pembuatan hukum tersebut. RUU ini memang mendapatkan banyak pertentangan dari berbagai pihak masyarakat. Eksploitasi yang berlebihan atas seksualitas, harus ditentangi. Tetapi, bukan berarti harus membuat undang-undang yang ingin mengatur moral dan akhlak secara luas, seperti yang tercantum dalam RUU Pornografi Indonesia.
Penyebaran pornografi harus diatur, tetapi lebih berfokus pada kontrol penyebaran materi tersebut daripada mencoba mengatur moral dan etika secara langsung. Bab I Pasal 1 tentang Ketentuan Umum pada draf terakhir RUU Pornografi menyebutkan, pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. Definisi tersebut memperlihatkan kurangnya batasan yang jelas terhadap apa yang dianggap sebagai "materi seksualitas", sehingga definisi yang luas tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dan penyalahgunaan.
Konflik yang terdapat pada naskah drama Sidang Susila terjadi antara penguasa dengan masyarakat. Penguasa melakukan tindakan yang memanfaatkan kekuasaannya untuk mengatur masyarakat sesuai kehendak yang dianggap baik oleh mereka. Kekuasaan bukanlah sebuah struktur yang berada di atas segalanya, kekuasaan memiliki keberadaan dan fungsi yang berasal dari lapisan terbawah masyarakat, seperti dalam keluarga, institusi, dan berbagai bentuk lainnya dalam bentuk relasi kuasa (Michel Foucault, 1997 hal.116).
Relasi kuasa dipergunakan untuk mengontrol kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu terkait tubuh dan seksualitas. Dalam kaitannya, hubungan kekuasaan dengan seksualitas dapat dikatakan sebagai bio-power. Bio-power mengacu pada praktik kekuasaan modern yang diarahkan pada populasi dan tubuh individu, dengan tujuan mengatur dan mengendalikan kehidupan. Seksualitas menjadi domain kunci di mana bio-power diterapkan, karena melalui regulasi seksualitas, kekuasaan dapat mempengaruhi aspek-aspek mendasar dari kehidupan manusia, seperti kelahiran, kesehatan, dan kematian (Foucault, 1976).
Dalam drama Sidang Susila, terdapat beberapa tindakan yang menyudutkan Susila. Misalnya ketika ia ditangkap dan kemudian diinterogasi dengan pertanyaan-pertanyaan manipulatif yang mengharuskan Susila mengakui tuduhan tersebut. Para petugas yang menangani Susila melakukan tindakan kontrol represif terhadap tubuh dan perilaku individu melalui tindakan menyudutkan Susila dalam melakukan interogasi. Hal ini sejalan dengan teori bio-power Foucault, di mana negara dan institusi berkuasa mengontrol kehidupan individu, termasuk dalam hal seksualitas.
Di pengadilan, kriminalisasi seksualitas semakin terlihat. Hakim dan Jaksa merendahkan Susila dengan komentar vulgar, menegaskan bahwa tubuhnya adalah "sumber penyakit moral." Mereka berusaha menjustifikasi tindakan represif dengan hukum yang menormalkan kontrol terhadap seksualitas. Bahkan, Jaksa mengaitkan mainan anak-anak dengan pornografi untuk membangun narasi bahwa Susila berbahaya bagi masyarakat.
Akhir drama semakin menegaskan represifitas kekuasaan. Hakim memutuskan hukuman berat bagi Susila dan memerintahkan penghapusan segala bentuk ekspresi seksualitas. Keputusan ini mencerminkan penerapan bio-power dalam menindas kebebasan individu atas tubuh dan seksualitas mereka.
Seperti yang terdapat pada penutup naskah berikut.
SUARA HAKIM DI PENGERAS SUARA: Sidang Susila dengan ini memutuskan bahwa pesakitan akan menerima hukuman seberat-beratnya. Dan untuk menghindari hal-hal yang bisa berkembang dikemudian hari, maka Sidang Susila ini juga menetapkan, bahwa segala macam kata-kata, ucapan, tulisan, gambar, rekaman dan semua bentuk kelamin yang ada di muka bumi ini harus segera dihapuskan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya….
Epilog dari naskah drama Sidang Susila menggambarkan bagaimana kriminalisasi seksualitas yang diterapkan oleh adanya bio-power menghapuskan segala bentuk ekspresi seksualitas. Penegasan suara Hakim menjelaskan bahwa hilangnya kebebasan individu dalam melakukan ekspresi seksualitas. Teori bio-power yang dikemukakan oleh Michel Foucault menyoroti bagaimana kekuasaan negara dan institusi mempengaruhi dan mengatur kehidupan individu melalui kontrol terhadap tubuh dan perilaku. Dalam epilog ini, keputusan Sidang Susila untuk menghapuskan segala bentuk ekspresi seksualitas mencerminkan penerapan kekuasaan bio-power dalam mengendalikan dan menindas seksualitas individu.
Dengan demikian, naskah drama Sidang Susila menjadi bentuk kritik terhadap upaya penguasa dalam mengontrol moralitas masyarakat melalui regulasi yang represif. Drama ini menyoroti bagaimana hukum yang dibuat dengan tujuan menjaga moralitas justru dapat mengekang kebebasan individu dan merampas hak asasi manusia.
Melalui penggambaran peristiwa dalam Sidang Susila, Agus Noor tidak hanya mempertanyakan keberadaan RUU Antipornografi dan Antipornoaksi, tetapi juga menunjukkan bagaimana kekuasaan negara dapat menyusup ke dalam aspek-aspek pribadi kehidupan warganya. Pemanfaatan teori bio-power yang dikemukakan oleh Michel Foucault memperjelas bahwa kekuasaan tidak hanya hadir dalam bentuk kekuatan fisik atau militer, tetapi juga dalam bentuk regulasi yang mengontrol tubuh dan seksualitas. Hal ini menciptakan suatu bentuk dominasi yang tidak kasat mata, di mana masyarakat dipaksa untuk tunduk pada aturan yang mengikat ekspresi dan identitas mereka.
Referensi
Farhat, F. (2023). Relasi Kuasa di dalam Naskah Sidang Susila karya Ayu Utami dan Agus Noor. Jurnal Edukasi Khatulistiwa Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. 6 (1).
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Pornografi
https://naskahdrama-rps.blogspot.com/
Pramesthi, E. A., Sutanto, E., & Waslam. (2023). Masalah Sosial dalam Novel Penyalin Cahaya karya Lucia Priandarini: Pendekatan Sosiologi Sastra. Jurnal Bastra. 8 (2). ISSN: 2503-3875.
The History of Sexuality, Volume I: An Introduction. New York, NY: Pantheon Books.
Umam, K. (2019). DOR dan Drama Keadilan (Analisis Sosiologi Sastra). Jurnal NUSA,14 (4).
Siti Rubaiah Al Adawiyah merupakan mahasiswi. Beberapa karyanya sudah dimuat dalam media cetak maupun media online. Ia bisa dihubungi melalui akun instagramnya: @strubaaiiah.