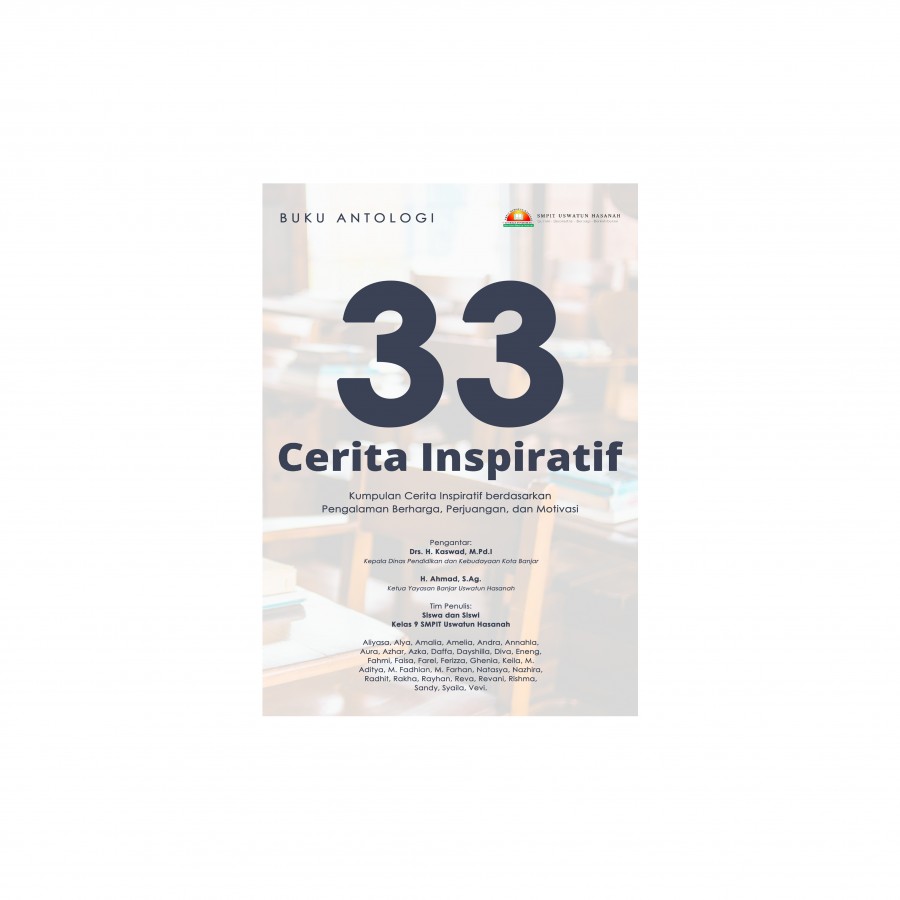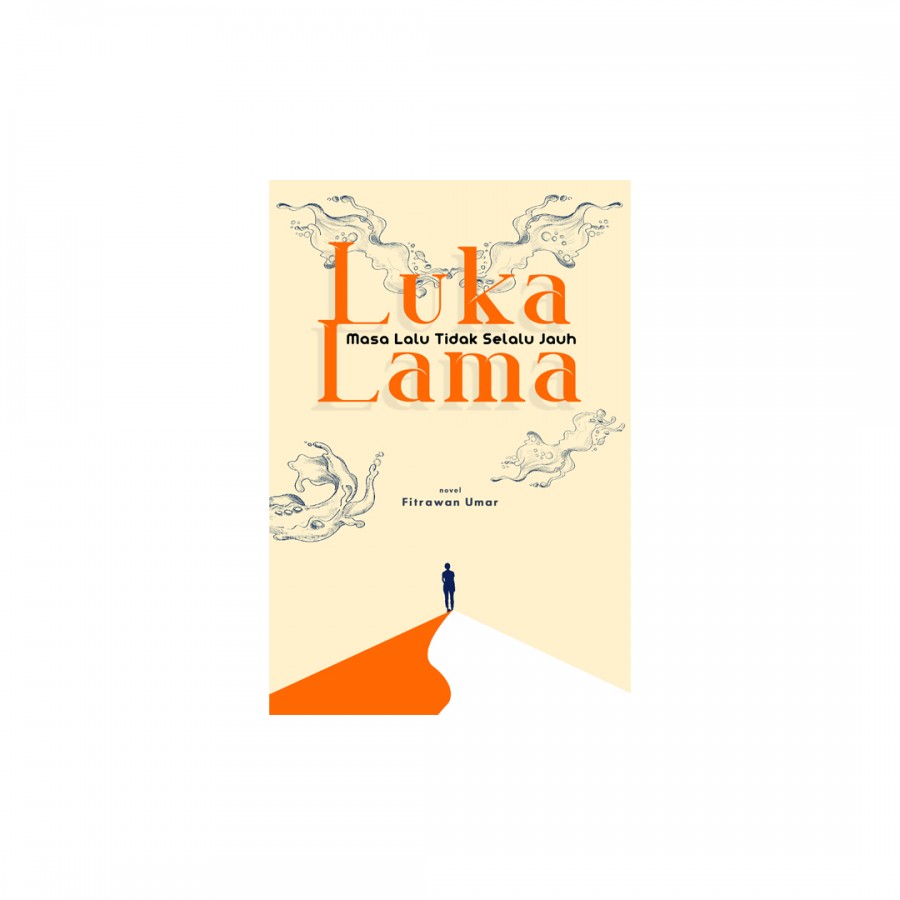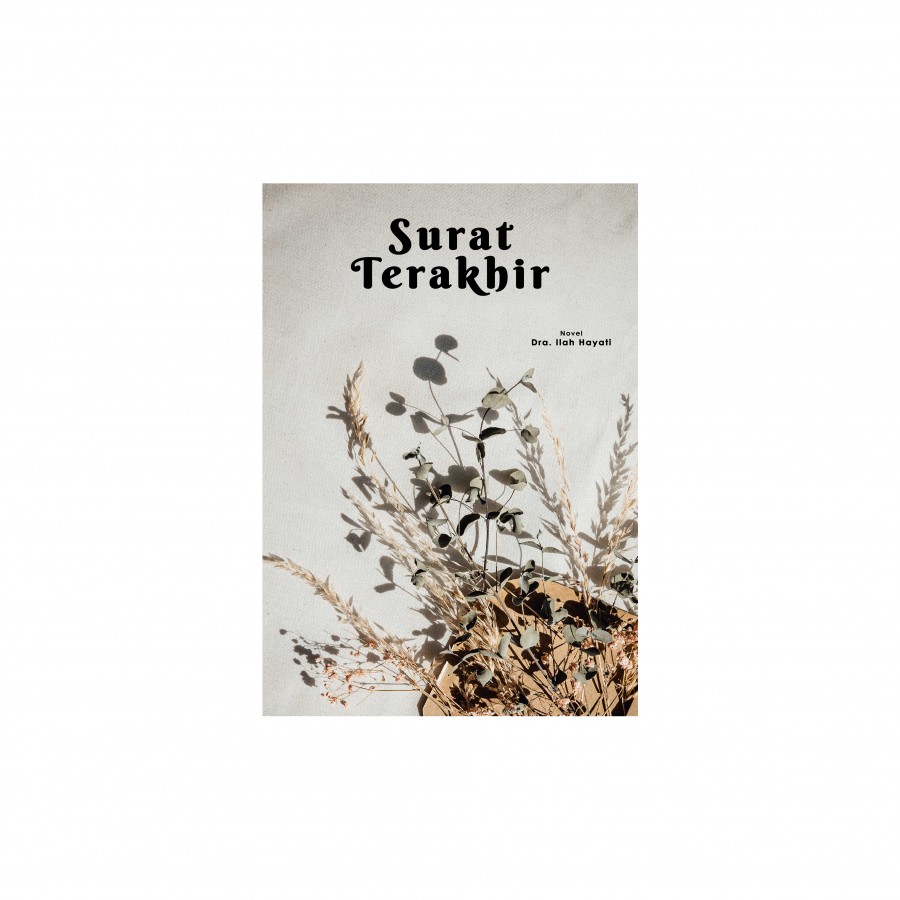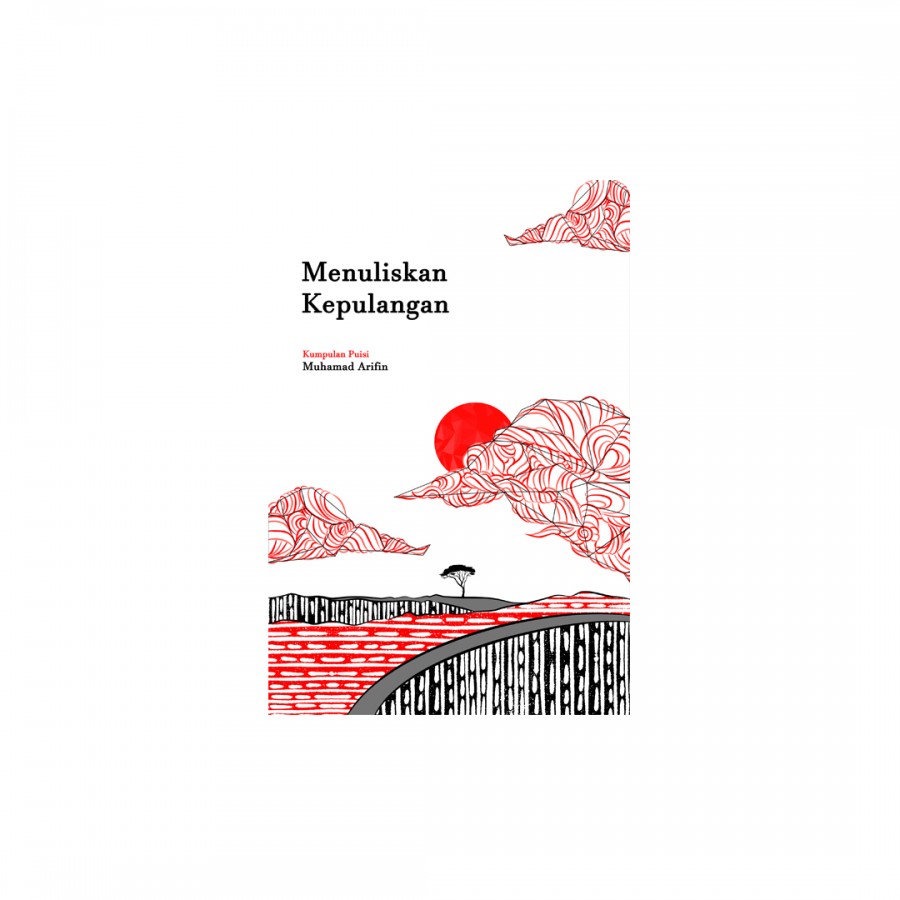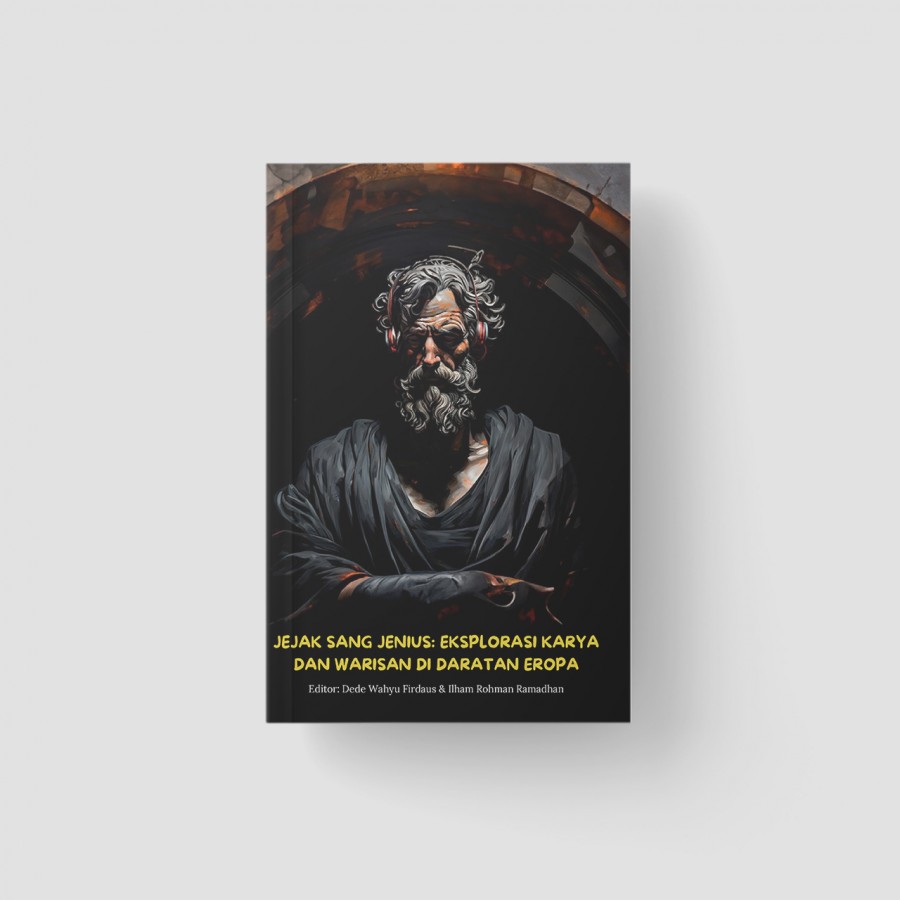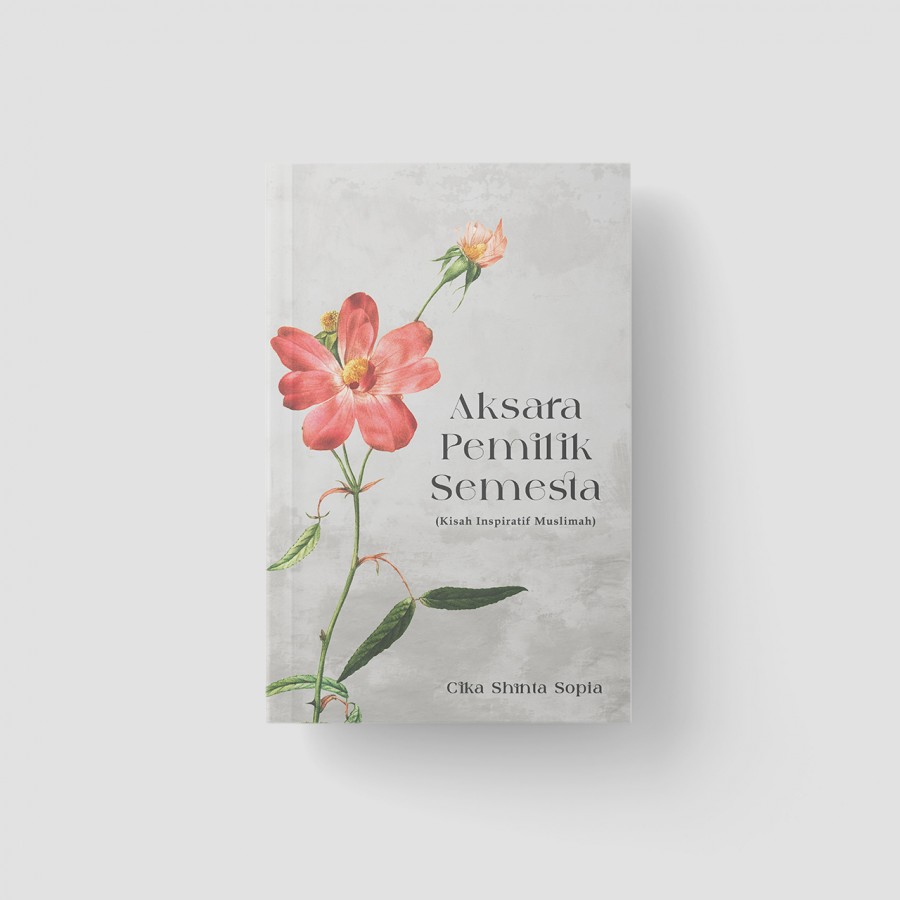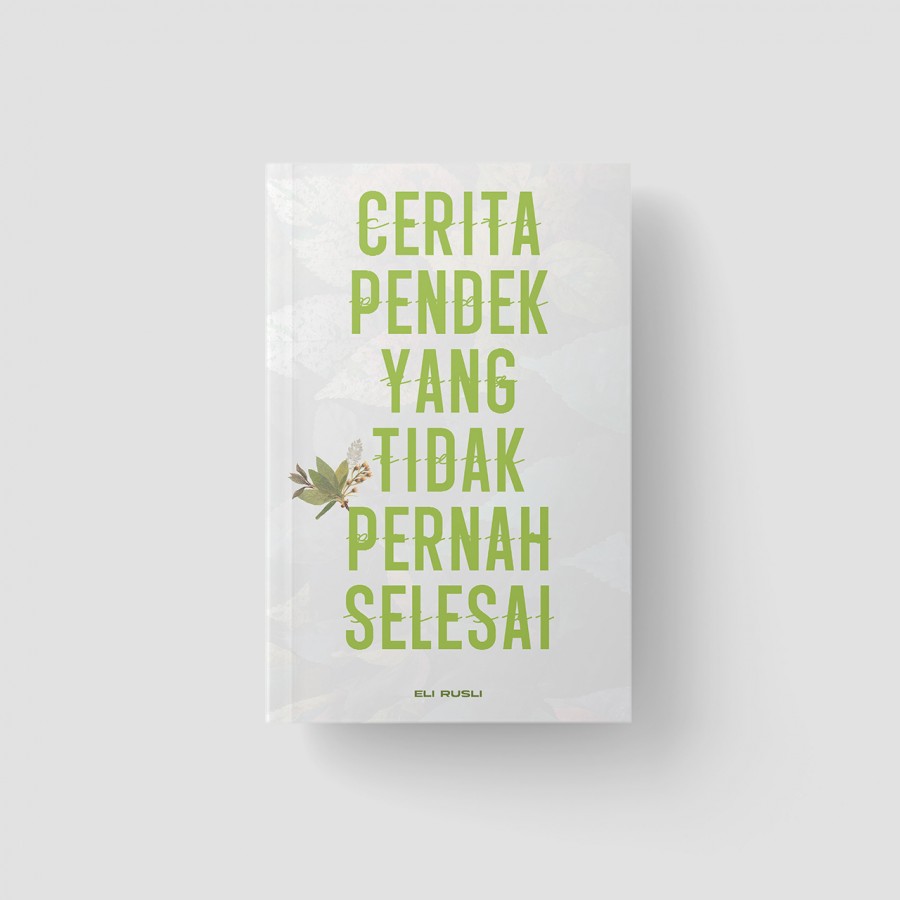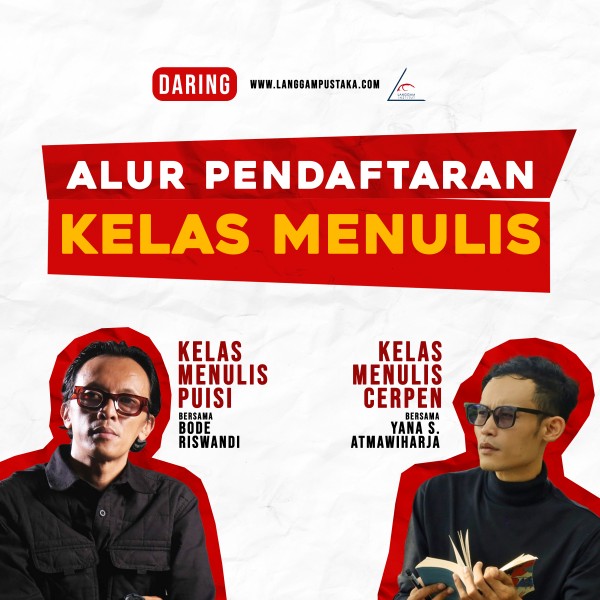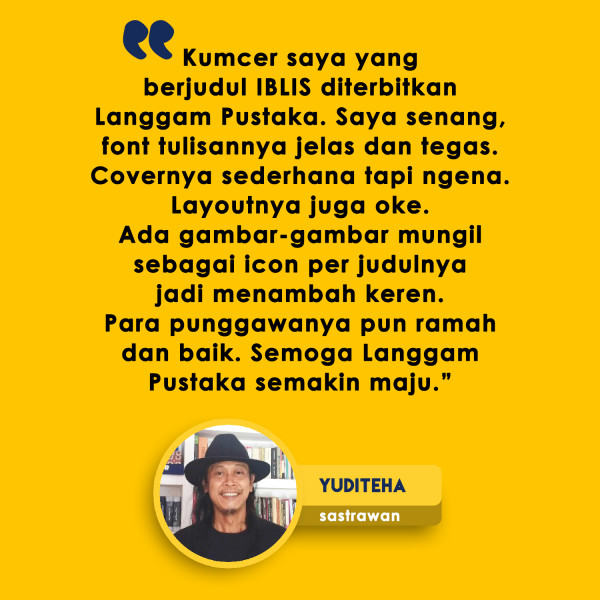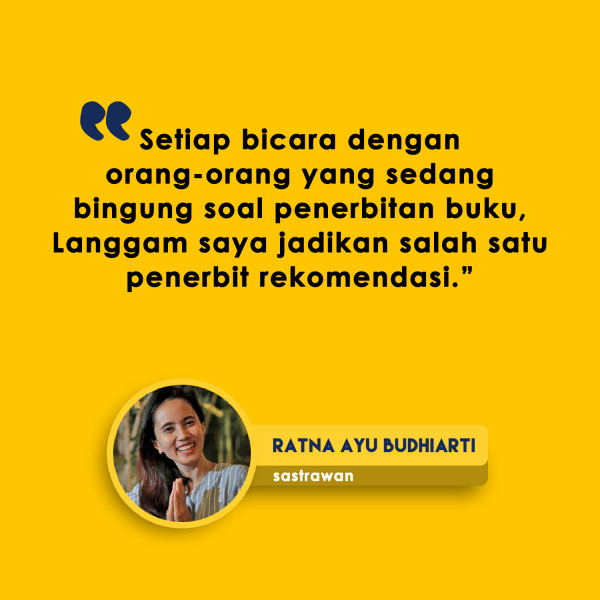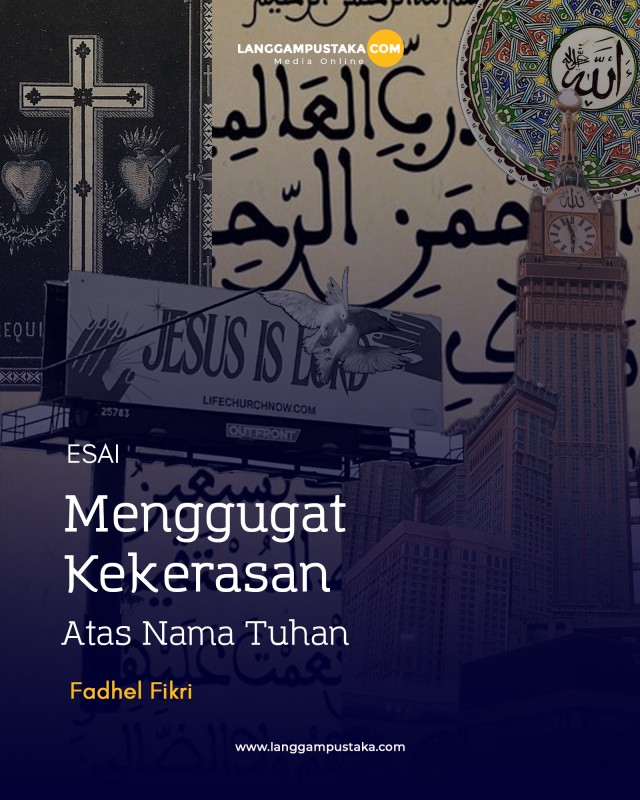
Seusai menyelami Fields of Blood: Religion and the History Violence karya Karen Armstrong, hati saya dipenuhi kegelisahan. Bayangkan, sejarah panjang agama dan kekerasan dibentangkan begitu gamblang di hadapan mata! Tak ayal, pertanyaan pun menyeruak di benak: Masak sih, Tuhan yang Maha Pengasih tega merestui pertumpahan darah? Aneh, 'kan?
Pertanyaan ini bukan basa-basi belaka, melainkan paradoks yang, menurut saya, menghantui peradaban manusia. Di satu sisi, agama mengajarkan kasih sayang, welas asih, dan kedamaian. Di sisi lain, kenyataannya, kekerasan justru kerap kali dibungkus atas nama agama. Rasanya seperti ada missing link yang terputus antara idealitas agama dan realitas sosial.
Paradoks ini, sejujurnya, membuat saya teringat akan konsep alienasi Feuerbach. Manusia menciptakan Tuhan sebagai proyeksi keinginan dan harapan, tapi pada akhirnya Tuhan justru menjadi sosok asing yang berseberangan dengan manusia. Agama, yang seharusnya membebaskan, malah jadi alat penindasan dan pembenaran atas kekerasan. Ironis, bukan?
Seharusnya agama menjadi penyejuk di tengah kerasnya kehidupan, bukannya malah menjadi senjata yang melukai hati nurani. Lantas, bagaimana kita bisa mendamaikan ajaran cinta kasih dalam agama dengan realitas kekerasan yang terjadi atas nama agama? Apakah ada yang salah dengan cara kita memahami agama, atau memang ada inherent violence dalam agama itu sendiri? Mungkinkah kekerasan ini adalah sebuah necessary evil, sebuah harga yang harus dibayar demi mempertahankan kemurnian doktrin agama?
Oleh karena itu, artikel ini saya hadirkan sebagai bentuk protes terhadap kekerasan yang mengatasnamakan Tuhan. Melalui tulisan ini, saya ingin membedah paradoks tersebut dan mengajak pembaca untuk kembali merenungkan hakikat agama yang sebenarnya, yakni ajaran cinta kasih yang humanis, serta mencari jalan keluar dari lingkaran setan kekerasan atas nama agama. Saya ingin mengajak pembaca untuk tidak hanya menjadi pengamat pasif, tetapi juga menjadi agen perubahan yang aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia.
Akar Historis Kekerasan atas Nama Agama
Menilik kembali sejarah, kita akan mendapati bahwa peradaban manusia dipenuhi catatan konflik dan peperangan yang dipicu oleh sentimen agama. Perang Salib, konflik di Timur Tengah, inquisisi Spanyol, penaklukan benua Amerika oleh orang-orang Eropa, dan berbagai persekusi terhadap kaum minoritas adalah segelintir bukti bagaimana agama kerap dijadikan tameng untuk berbuat kekerasan. Seolah-olah sejarah agama adalah sejarah pertumpahan darah.
Salah satu biang keladi, menurut saya, adalah penafsiran kitab suci yang bias dan rentan dimanfaatkan demi kepentingan politik. Agama seharusnya menjadi sumber moral dan etika, namun ketika dipolitisasi, ia kehilangan kesuciannya dan beralih fungsi menjadi alat legitimasi kekerasan.
Seperti kata Karl Marx, agama adalah candu masyarakat. Ia membius manusia dengan ilusi surga, sementara di dunia nyata, ketidakadilan merajalela. Ketika agama berselingkuh dengan politik, maka ia pun akan tercemar dan kehilangan otentitasnya. Ia menjadi budak dari kekuasaan duniawi.
William T. Cavanaugh, seorang sejarawan Amerika, dalam bukunya The Myth of Religious Violence, dengan lugas memaparkan bagaimana agama sering kali dijadikan kambing hitam atas berbagai konflik. Di Barat, contohnya, agama kerap dituding sebagai penyebab utama perang-perang besar dalam sejarah.
Padahal, jika ditelisik lebih lanjut, ada banyak faktor lain yang saling berkaitan, seperti perebutan sumber daya alam dan kekuasaan politik. Namun, stereotip negatif terhadap agama begitu kuat, sehingga ia terus-menerus menjadi sasaran tembak atas dosa kekerasan umat manusia. Agama dihakimi tanpa pengadilan yang adil. Ia dipaksa menanggung beban yang bukan miliknya.
Di sisi lain, ada juga gerakan atau tokoh agama yang menyerukan perdamaian dan toleransi. Mahatma Gandhi, misalnya, adalah sosok yang gigih memperjuangkan kemerdekaan India dengan gerakan tanpa kekerasan. Pemikiran Gandhi yang berakar pada Hinduisme dan ajaran Yesus menjadi bukti nyata bahwa agama bisa menjadi inspirasi perdamaian.
Sayangnya, tokoh seperti Gandhi sering dianggap anomali, pengecualian dari aturan umum yang menyatakan bahwa agama dan kekerasan bagai dua sisi mata uang. Benarkah demikian? Apakah agama memang ditakdirkan untuk selalu beriringan dengan kekerasan? Apakah kita terlalu pesimis dalam melihat potensi perdamaian yang dimiliki oleh agama?
Psikologi Kekerasan Religius
Selain faktor historis dan politis, ada pula faktor psikologis yang, menurut saya, mendorong seseorang melakukan kekerasan atas nama agama. Psikolog Amerika, Philip Zimbardo, dalam bukunya The Lucifer Effect, menjelaskan bahwa dalam situasi tertentu, orang normal sekalipun bisa terdorong untuk melakukan kekerasan. Lingkungan dan situasi sosial, menurut Zimbardo, dapat mengubah perilaku seseorang secara drastis. Eksperimen penjara Stanford yang dilakukan oleh Zimbardo menunjukkan bahwa kekuasaan dan otoritas dapat mentransformasi individu yang baik hati menjadi tiran yang kejam.
Fanatisme, hasrat untuk mengontrol, dan rasa terancam adalah beberapa pemicu yang dapat memperkuat kecenderungan ini. Identitas kelompok dan doktrin eksklusif juga dapat memperkeruh suasana, karena individu merasa kelompoknyalah satu-satunya yang paling benar.
Di tengah masyarakat yang semakin terpecah belah, identitas kelompok menjadi begitu penting, dan agama sering kali menjadi perekat yang menyatukan individu dalam sebuah kelompok. Namun, identitas kelompok yang eksklusif juga bisa menjadi sumber perpecahan dan konflik. Seperti kata psikolog sosial Henri Tajfel,
“Identitas sosial adalah pedang bermata dua. Ia bisa menjadi sumber kekuatan dan solidaritas, tapi juga bisa menjadi sumber kebencian dan kekerasan.”
Dalam kajian psikologi sosial, fenomena ini disebut in-group bias dan out-group homogeneity. Individu cenderung menilai positif anggota kelompoknya sendiri (in-group) dan negatif terhadap anggota kelompok lain (out-group).
Hal itu dapat memicu intoleransi dan diskriminasi, yang pada akhirnya berujung pada kekerasan. Dengan menciptakan kita dan mereka, manusia membangun sebuah tembok pemisah yang menghalangi terciptanya dialog dan empati. Kita lupa bahwa di balik setiap mereka ada seorang manusia yang memiliki perasaan dan martabat yang sama dengan kita.
Lebih jauh lagi, pendekatan psikoanalisis Lacan bisa memberi perspektif tambahan. Kekerasan, menurut Lacan, adalah manifestasi hasrat manusia yang tak terpuaskan. Individu yang merasa terasing dan terisolasi di tengah masyarakat modern akan mencari identitas dan makna dalam kelompok agama. Namun, ketika kelompok agama itu justru mengajarkan kebencian dan permusuhan terhadap kelompok lain, maka kekerasan pun menjadi pelampiasan hasrat terpendam.
Dengan kata lain, kekerasan atas nama agama adalah bentuk neurosis kolektif, cara individu mengatasi kecemasan dan ketidakpastian eksistensial. Kekerasan menjadi sebuah symptom dari ketidakmampuan manusia dalam menghadapi realitas yang kompleks. Ia adalah sebuah jalan pintas yang menawarkan solusi instan namun semu.
Menggugat Kekerasan, Merangkul Kemanusiaan
Untuk memberantas kekerasan atas nama Tuhan, diperlukan usaha bersama dari berbagai pihak. Dialog antar agama dan pendidikan yang mengajarkan toleransi dan pluralisme adalah langkah penting yang harus terus digalakkan.
Tokoh agama dan pemimpin masyarakat juga punya peran vital dalam mempromosikan perdamaian dan menentang kekerasan. Kita harus menciptakan ruang publik yang inklusif, di mana setiap orang dapat bebas mengekspresikan keyakinan dan pandangannya tanpa rasa takut. Kita harus membangun jembatan komunikasi antar umat beragama, sehingga saling pengertian dan penghargaan dapat terwujud.
Manusia itu makhluk yang rumit. Kekerasan bukanlah bawaan lahir, melainkan konstruksi sosial yang bisa dibentuk dan diubah. Karena itu, saya optimis, melalui pendidikan dan dialog yang berkelanjutan, manusia bisa belajar untuk merangkul perdamaian dan kemanusiaan. Kita harus ajarkan generasi mendatang bahwa agama adalah tentang cinta kasih, bukan kebencian dan kekerasan.
Kita harus ajarkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, bukan Tuhan yang haus darah. Kita harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal sejak dini, sehingga anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang menjunjung tinggi perdamaian dan toleransi. Kita harus menciptakan sebuah dunia di mana setiap anak dapat tumbuh kembang dengan penuh cinta dan kebebasan.
Namun, optimisme ini harus dibarengi dengan kesadaran kritis terhadap berbagai tantangan. Tantangan terbesar adalah adanya kekuatan politik dan ekonomi yang terus-menerus memelihara konflik dan kekerasan demi kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, kita harus terus bersuara melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan, baik yang dilakukan atas nama agama maupun ideologi lainnya.
Kita tidak boleh diam dan menerima kekerasan sebagai takdir. Kita harus terus berjuang demi terciptanya dunia yang lebih baik, dunia yang dipenuhi cinta kasih, perdamaian, dan keadilan. Kita harus berani mengambil risiko dan berkorban demi mewujudkan impian tersebut. Kita harus menjadi garam dan terang dunia, yang menerangi kegelapan dan memberi rasa pada kehidupan.
Pada akhirnya saya melihat, kekerasan atas nama agama adalah penyimpangan dari nilai-nilai luhur agama itu sendiri. Agama seharusnya menginspirasi terciptanya perdamaian dan harmoni. Sudah saatnya kita tolak segala bentuk kekerasan atas nama Tuhan dan merangkul nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Kita harus mengingat bahwa semua manusia adalah saudara, tanpa memandang agama, suku, ras, ataupun golongan.
Daftar Pustaka
• Armstrong, K. (2014). Fields of Blood: Religion and the History Violence. The Bodley Head.
• Cavanaugh, W. T. (2009). The Myth of Religious Violence. Oxford University Press.
• Zimbardo, P. (2007). The Lucifer Effect. Random House.
Fadhel Fikri, Co-Founder di Sophia Insitute dan pegiat filsafat dan Sains. Dan pembisnis di Sabda Literasi Palu