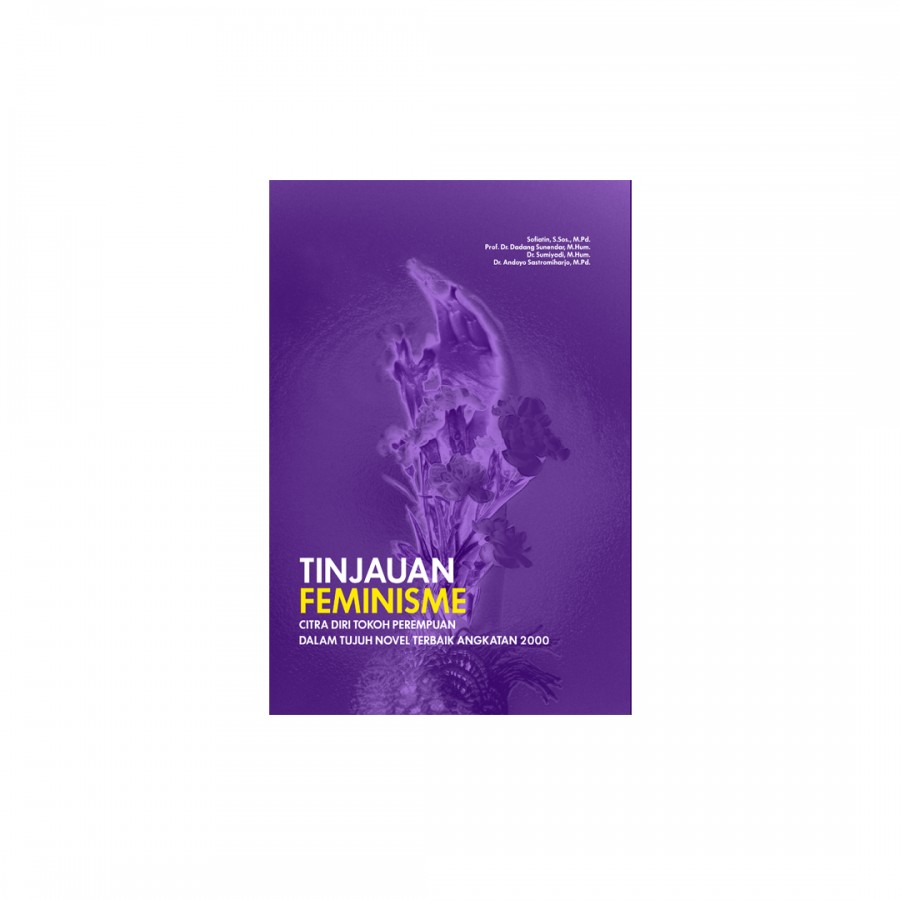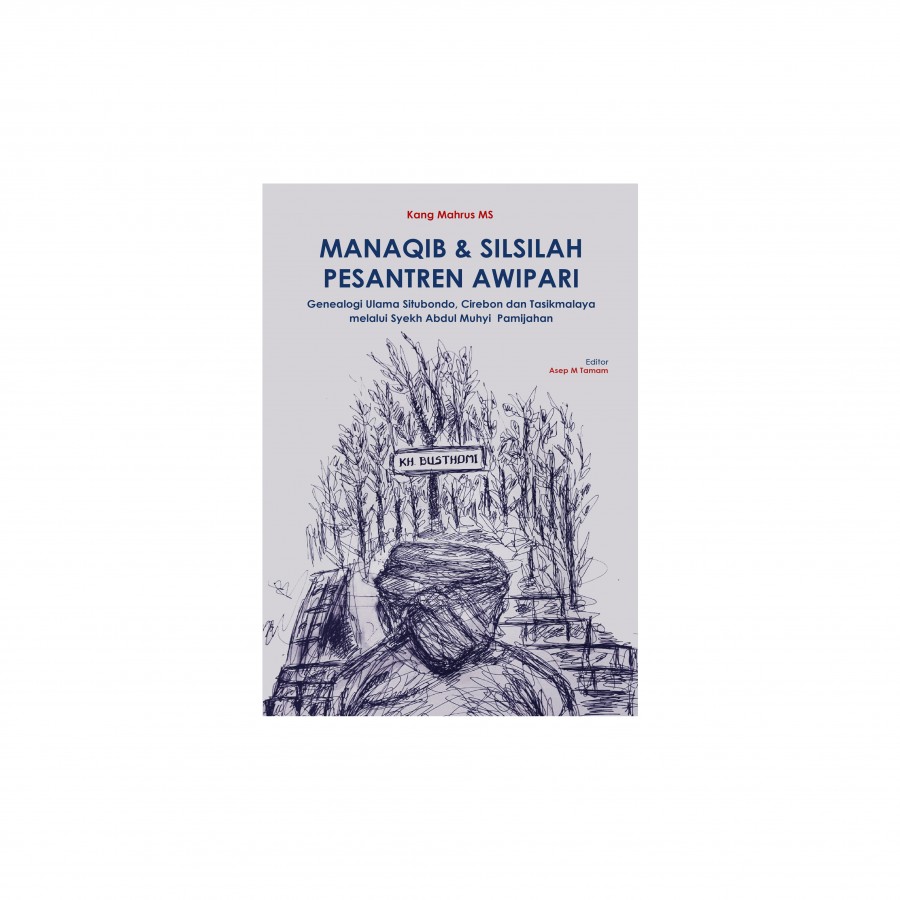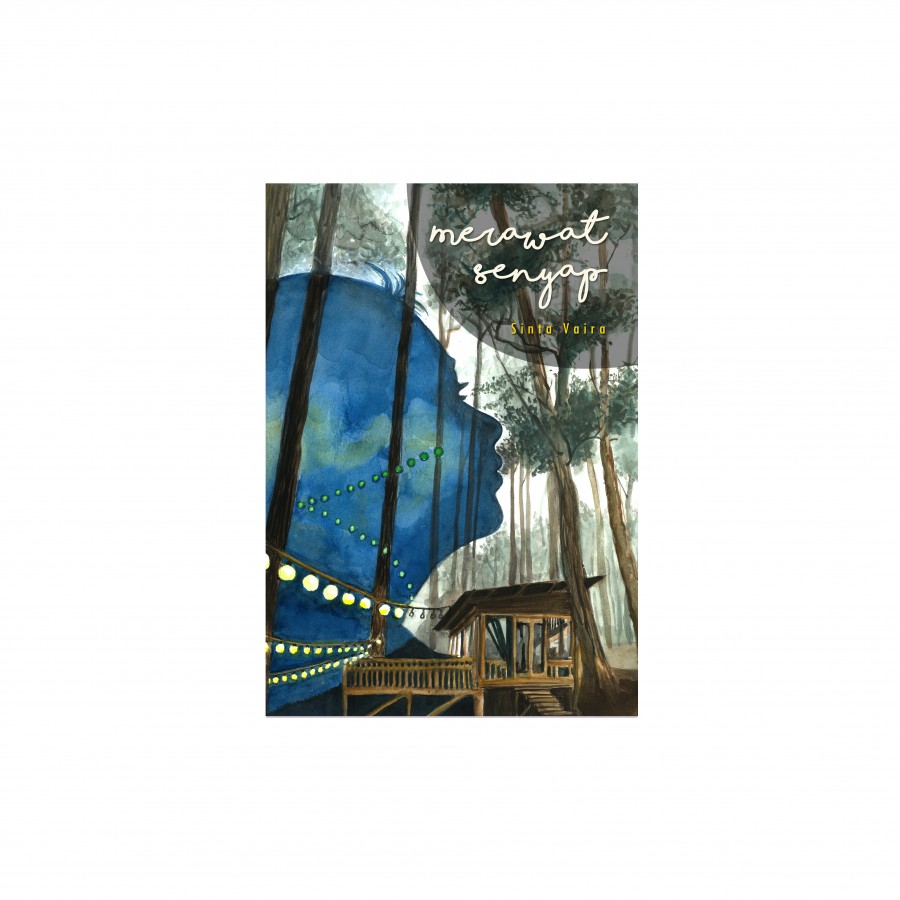Penyebaran Agama dan Akulturasi Budaya di Indonesia
Sebagai wilayah dengan masyarakat majemuk, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang mengakar dalam kehidupan masyarakatnya. Munculnya kebudayaan tersebut tentunya tak lepas dari tujuh unsur budaya yang diungkapkan Koentjoroningrat, di antaranya bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi dan keagamaan, serta kesenian. Berkenaan dengan sistem religi dan keagamaan, masyarakat Indonesia sangat kental dengan sistem animisme-dinamisme. Merupakan sistem kepercayaan terhadap ruh-ruh nenek moyang serta kekuatan gaib dari benda-benda yang dianggap keramat. Animisme-dinamisme menjadi kepercayaan yang dianut masyarakat purbakala di Indonesia.
Seiring berjalannya waktu, agama Hindu-Budha mulai masuk ke Indonesia sekitar abad pertama melalui jalur perdagangan dari India. Pada saat itu, masyarakat Indonesia yang sebelumnya percaya pada sistem animisme-dinamisme mulai memeluk agama Hindu-Budha. Sistem kebudayaan masyarakat Indonesia pun mengalami pergeseran atau perubahan mengikuti pola ajaran yang mereka anut. Sekitar abad ke-12 M Islam masuk ke Indonesia yang dibawa oleh para pedagang. Terdapat dua versi teori berkenaan dengan siapa yang membawa Islam ke Indonesia. Teori pertama mengatakan bahwa pedagang muslim Gujarat, India-lah yang membawa Islam ke Indonesia, sedangkan teori kedua menyatakan bahwa pedagang dari Arab yang memulai dakwah dan penyebaran Islam di Indonesia.
Masuknya Islam ke Indonesia sebagai agama yang tidak mengenal kasta menjadi alasan penduduk untuk memeluk agama Islam. Selain itu, Islam dianggap menyebarkan ajarannya dengan cara damai, bahkan dipadukan dengan pendekatan melalui praktik kebudayaan penduduk setempat. Maka tak sedikit kebudayaan Hindu, Budha, maupun lokal yang diakulturasikan dengan ajaran agama Islam tanpa menghilangkan nilai-nilai kemuliaan kebudayaan aslinya.
Tradisi Ngabungbang sebagai Sebuah Akulturasi
Mengutip informasi dari laman Warisan Budaya Takbenda Kemdikbud, ngabungbang merupakan suatu tradisi masyarakat Sunda dengan beraktivitas di malam hari, di bawah bulan purnama pada tanggal 14 bulan Mulud. Masyarakat Sunda sendiri mengenalnya dengan istilah “caang bulan opat belas”. Atau dapat diartikan sebagai aktivitas diam di luar rumah dan tidak tidur selama semalam suntuk.
Pada mulanya, tradisi ngabungbang ditujukan sebagai ritual penghormatan kepada leluhur. Mengutip dari berbagai sumber, tradisi ini dipelopori oleh tokoh yakni Mama H. Hasan di Jawa Barat. Pada malam tanggal 14 Maulid, Mama H. Hasan melakukan aktivitas begadang, kemudian berendam di mata air Cikahuripan. Beliau berpesan pada malam tersebut agar berendam, lalu membuat sesaji berupa tembakau dan daun jagung.
Penulis berasumsi bahwa tradisi tersebut merupakan salah satu bentuk akulturasi antara kepercayaan atau agama yang percaya pada ruh leluhur dengan kebudayaan agama Islam. Mengingat pada sumber lain, disebutkan bahwa ngabungbang dilakukan pada malam 12 Robiul ‘Awal yang bertepatan dengan lahirnya Nabi Muhammad saw. Selain itu, pada perkembangan, tradisi ini dianggap sebagai suatu kemusyrikan, sebab dalam Islam tidak mengenal tradisi penyembahan terhadap ruh leluhur.
Setelah dianggap sebagai tradisi musyrik, maka terjadi perubahan pada praktik dan tujuan tradisi ngabungbang. Ngabungbang lebih ditujukan sebagai aktivitas penyucian diri dengan pembersihan dan perawatan bumi. Pembacaan doa dan penyiraman tanaman di sekitar mata air Cikahuripan yang disertai hiburan kesenian rakyat menjadi wujud perubahan tradisi ngabungbang.
Aktivitas Pencegahan Teluh
Tradisi ngabungbang yang lahir di masyarakat Sunda Jawa Barat, turut menyebar ke daerah Jawa Tengah. Masyarakat yang turut melakukan tradisi ngabungbang adalah sebagian dari mereka yang tinggal di daerah Kabupaten Brebes perbatasan Jawa Barat. Kebudayaan Sunda memang bukan hal yang asing bagi masyarakat perbatasan tersebut. Kesehariannya, masyarakat menggunakan bahasa Sunda (menyebutnya Sunda kasar) dalam berinteraksi antar sesamanya. Bahkan pada acara-acara seperti pernikahan dan syukuran pun sangat kental dengan kebudayaan Sunda.
Tradisi ngabungbang dalam masyarakat Brebes, sejatinya masih terdapat sebagian korelasi dengan ngabungbang yang berkembang di Jawa Barat. Kesamaannya terletak pada aktivitas di malam hari, serta sebagai penolakan bala. Ngabungbang dalam tradisi mereka, merupakan kegiatan begadang yang dilakukan di rumah seseorang yang baru saja melahirkan. Tujuan diadakannya kegiatan tersebut adalah menjaga bayi dari serangan teluh yang mengincar atau nyokcrok bayi di malam hari. Praktik pesugihan teluh tersebut konon masih marak terjadi. Tak jarang jika ada bayi meninggal tiba-tiba tanpa diagnosa medis, masyarakat akan berasumsi bahwa bayi tersebut telah di-cokcrok teluh.
Masyarakat percaya, teluh akan berkeliaran dan terbang di sekitar rumah tempat bayi baru lahir sepanjang malam. Maka, setiap malam harus ada yang berjaga dan mengawasi supaya teluh tidak berani muncul dan mendekat. Tak ada ritual-ritual tertentu dalam aktivitas tersebut. Biasanya, aktivitas diisi dengan main kartu, play station, menonton, mendengarkan radio, atau hanya ngobrol-ngobrol saja. Aktivitas tersebut akan berlangsung sekitar satu bulan bahkan lebih.
Alih-alih sebagai praktik religius keagamaan, ngabungbang bagi masyarakat Brebes cenderung menjadi praktik sosial dalam menjaga hubungan antar kerabat dan tetangga demi menjaga jabang bayi agar selamat dari serangan bala. Tentu sudah jauh bergeser dari tradisi ngabungbang sebelumnya. Hal-hal akulturatif tersebut menunjukkan bahwa tradisi memang tak pernah lepas dari proses perkembangan dan pergeseran atau perubahan baik dari sisi makna maupun praktiknya.
Azis Fahrul Roji, pernah menempuh perjalanan kepenulisan di Tasikmalaya. Kini aktif menulis puisi dan artikel. Beberapa tulisan terbit di media daring maupun antologi bersama.