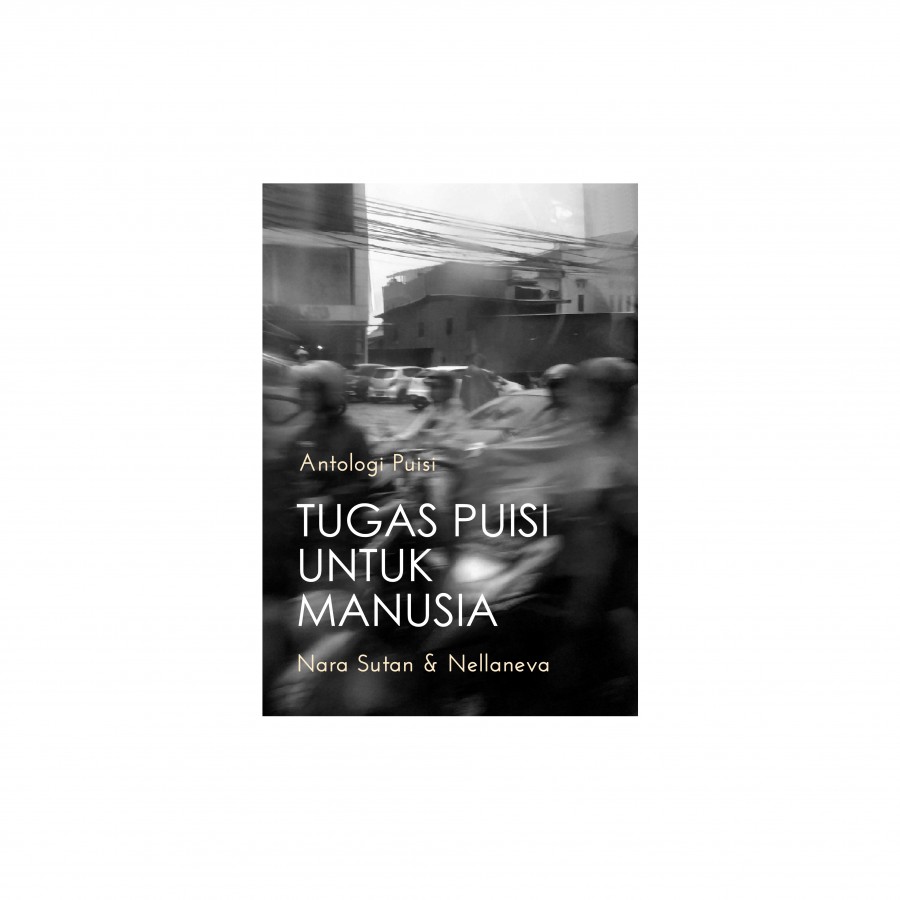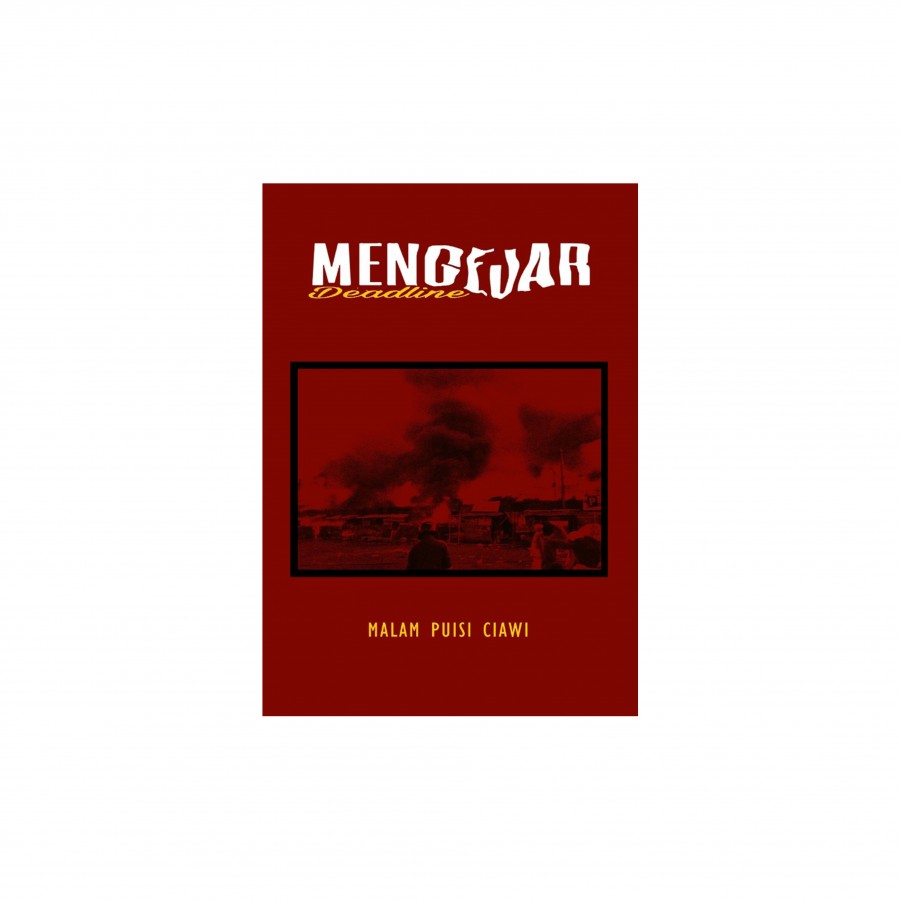“Geus nyambungan acan ka Mang Tarman?”
“Naon, ngawinkeun?”
“Enya. Koh budak na nu kahiji ek kawin panan”
“Mani ngaleut we nu hajat. Sambunganeun Teu eureun!”
Kira-kira, di kampung halaman penulis, itulah ilustrasi percakapan yang paling sering terdengar ketika musim hajatan mulai tiba. Entah kalau di daerah lain. Namun setidaknya, di wilayah Kabupaten Tasikmalaya bagian selatan, percakapan demikian sudah semacam menjadi percakapan menjelang musim hujan atau kemarau, kedatangannya akan jadi bahan perbincangan di sawah, kebun, warung kopi, pos ronda, bahkan Masjid dan Musala.
Penulis sendiri memaknai hajatan sebagai sebuah tradisi yang sudah mengakar dalam sebuah tatanan masyarakat tertentu di beberapa wilayah Jawa Barat, dilangsungkan secara turun temurun dan dilakukan oleh sebuah keluarga menjelang momen-momen besar dan penting yang menyangkut salah satu anggota keluarganya, seperti menjelang pernikahan, khitanan, dan sebagainya. Ketika berlangsungnya hajatan, tentu terdapat perbedaan-perbedaan yang menjadi keunikan tersendiri di masing-masing wilayah, dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan setempat. Salah satunya adalah bagaimana terciptanya tradisi nyambungan.
Secara sederhana, nyambungan berasal dari kata sambung yang memiliki arti menghubungkan. Jika dikaitkan dengan konteks hajatan, tentu tujuan dari nyambungan adalah menyambungkan kembali sillaturahmi antara saudara, kerabat, maupun tetangga dan kenalan dengan Shohibul Hajat, sebutan untuk orang atau keluarga yang melangsungkan hajatan. Awalnya, hampir seluruh masyarakat yang mengenal konsep nyambungan akan mendatangi rumah Shohibul Hajat dengan membawa baskom yang berisi beras dan tutumpang. Tutumpang sendiri adalah beragam jenis makanan masak atau bahan baku mentah yang dimaksudkan sebagai sumbangan dari para tamu, juga sebagai bentuk ikut serta dalam rasa suka cita keluarga yang tengah melangsungkan hajatan. Baskom yang tadi dibawa oleh tamu pada saat pulang akan diisi kembali oleh makanan matang beserta lalawuhnya. Masyarakat sunda pasti familiar betul dengan lalawuh khas hajatan, ada Ranginang, opak, wajit, bolu, kiripik cau, dan sebagainya. Sampai titik ini, nyambungan masih murni dianggap hanya sebatas hubungan “menyumbang-sillaturahmi”
Seiring perkembangan waktu, ikut berkembang pula konsep hajatan yang membuatnya semakin beragam. Penulis ambil contoh di kampung halaman penulis sendiri yang terletak di wilayah Kabupaten Tasikmalaya bagian selatan. Terkaan penulis, ada sebuah masa di mana membawa masakan atau bahan baku mentah yang disumbangkan kepada Shohibul Hajat dirasa sudah tak terlalu penting karena berbagai faktor. Sumbangan para saudara, kerabat, atau tetangga pun mulai beralih bentuk menjadi amplop dengan nominal uang tertentu. Walaupun masih banyak yang tak hanya memberi amplop saja. Ada juga yang masih membawa seekor ayam hidup, sekarung padi, bahan-bahan sayuran, atau yang paling ekstrim adalah satu set sound system untuk hajatan tiga hari dan sekelompok grup musik dangdut untuk hiburan.
Bicara tentang sound system, memang di beberapa daerah dan tradisi, hajatan tanpa kehadirannya ibarat sayur tanpa garam. Kurang bebeledagan dan senyap. Mungkin saja, awalnya, sebab hajatan adalah simbol dari rasa suka cita, kebahagaiaan, maka haruslah dikabarkan kepada khalayak agar mereka turut serta mengirimkan doanya. Jika Shohibul Hajat melangsungkan hajatan nya selama tiga hari, maka selama itu pula satu set sound system akan terus berdendang, menggemakan gendang telinga orang hampir satu desa.
Dari sisi teknis penyelenggaraan, konsep nyambungan juga terus mendapatkan inovasi-inovasinya. Paling mendasar, setiap saudara, kerabat, dan tetangga yang datang untuk nyambungan, panitia khusus sudah disiapkan untuk mencatat satu per satu apa saja yang tamu bawa, mulai dari nama sang tamu, berapa nominal rupiah di dalam amplopnya, dari mana alamat lengkapnya, dan apalagi yang mereka sumbangkan. Data itu akan secara lengkap tersedia dalam sebuah buku catatan yang tak bisa sembarangan diakses siapa pun sebelum hajatan resmi selesai.
Entah siapa yang memulai awalnya. Konsep nyambungan yang tadinya murni sebagai bentuk sumbangan kepada Shohibul Hajat mulai berubah bentuk menjadi arisan akbar bagi sebuah Dusun, bahkan Desa. Tergantung sejauh apa nama Shohibul Hajat itu dikenal oleh masyarakat. Bagaimana maksudnya? Begini, ada semacam aturan tidak tertulis yang sudah kadung melekat di tengah masyarakat tersebut bahwa misal ada seorang kerabat yang nyambungan berupa uang dua ratus ribu rupiah beserta seekor ayam jago berbobot tiga kilogram, maka ia harus mengembalikan uang dengan minimal nominal yang sama dan seekor ayam jago yang juga minimal berbobot sama pada saat sang kerabat itu melangsungkan hajatan di lain waktu. Maka dari itu, muncul kembali istilah baru, yakni istilah naur, dalam bahasa Indonesia berarti mengganti. Jika begitu, maka benar bahwa konsep nyambungan yang awalnya adalah sumbangan, telah bergeser menjadi hutang.
Berangkat dari latar belakang itulah, ilustrasi percakapan yang penulis buat di awal catatan ini malah bernada sumbang dan sinis, alih-alih bersuka cita ketika ada saudara, kerabat, atau tetangga akan melaksanakan hajatan. Sebab, nyambungan sudah kehilangan fitrahnya sebagai salah satu mempererat Sillaturahmi antar saudara, kerabat, maupun tetangga. Nyambungan tak lebih dari sekadar transaksi piutang, arisan, yang kedatangannya akan menjadi persoalan.
Agus Salim Maolana