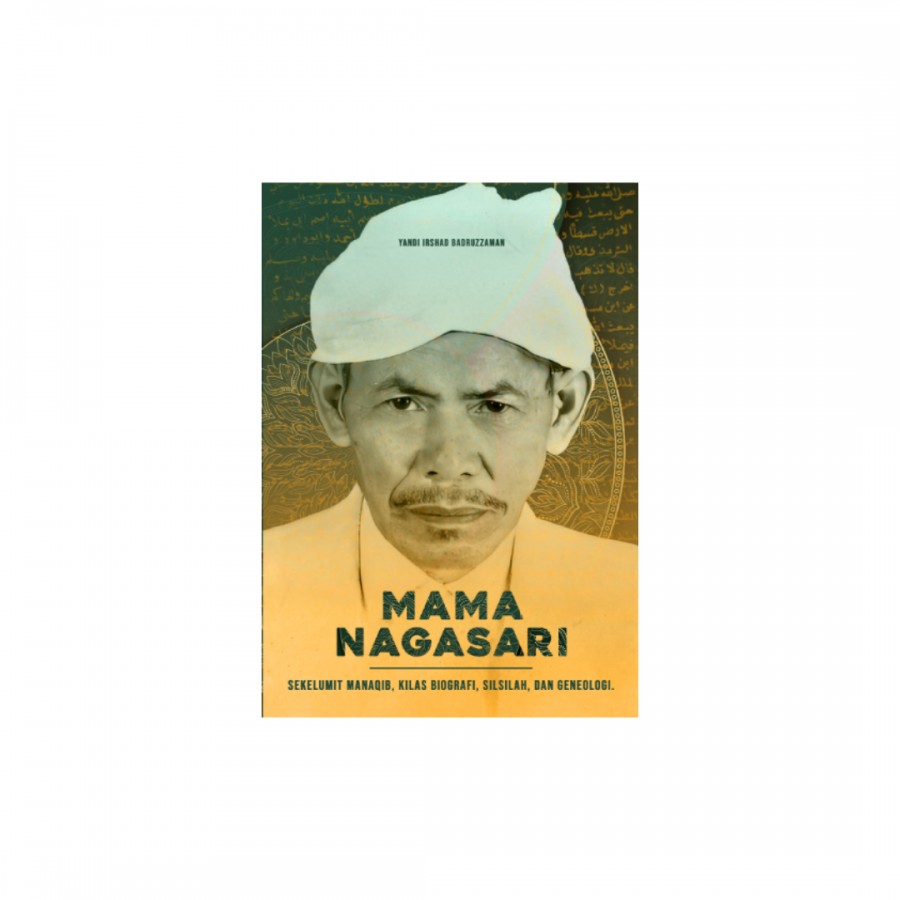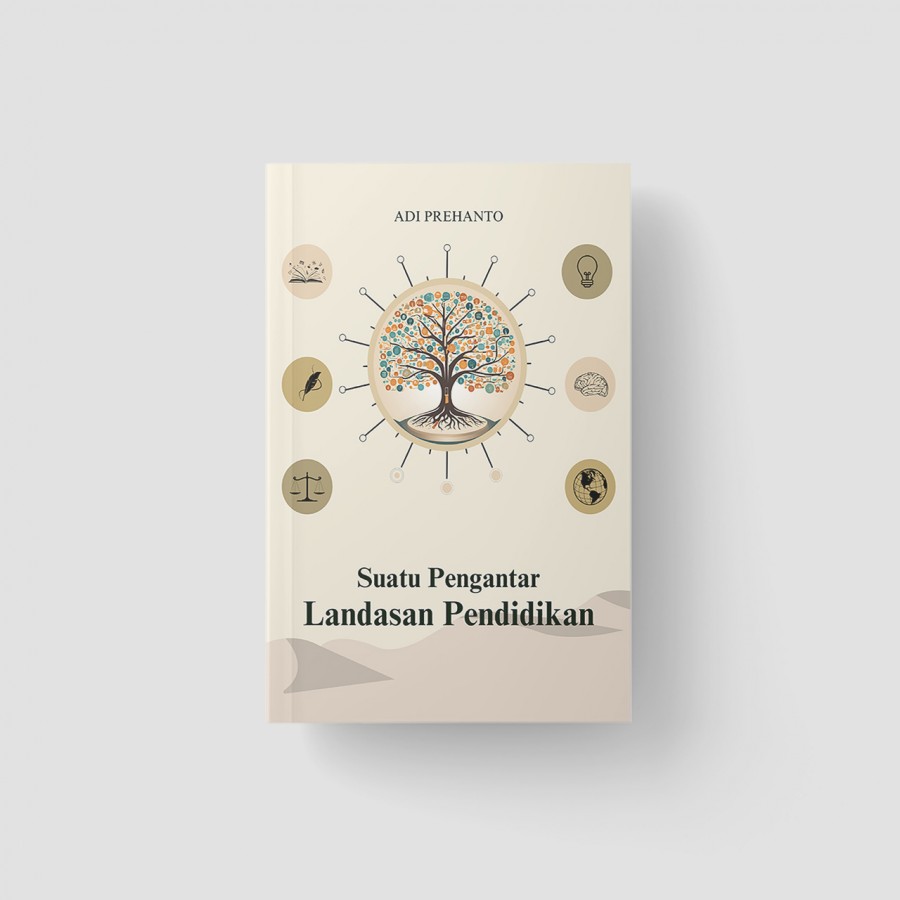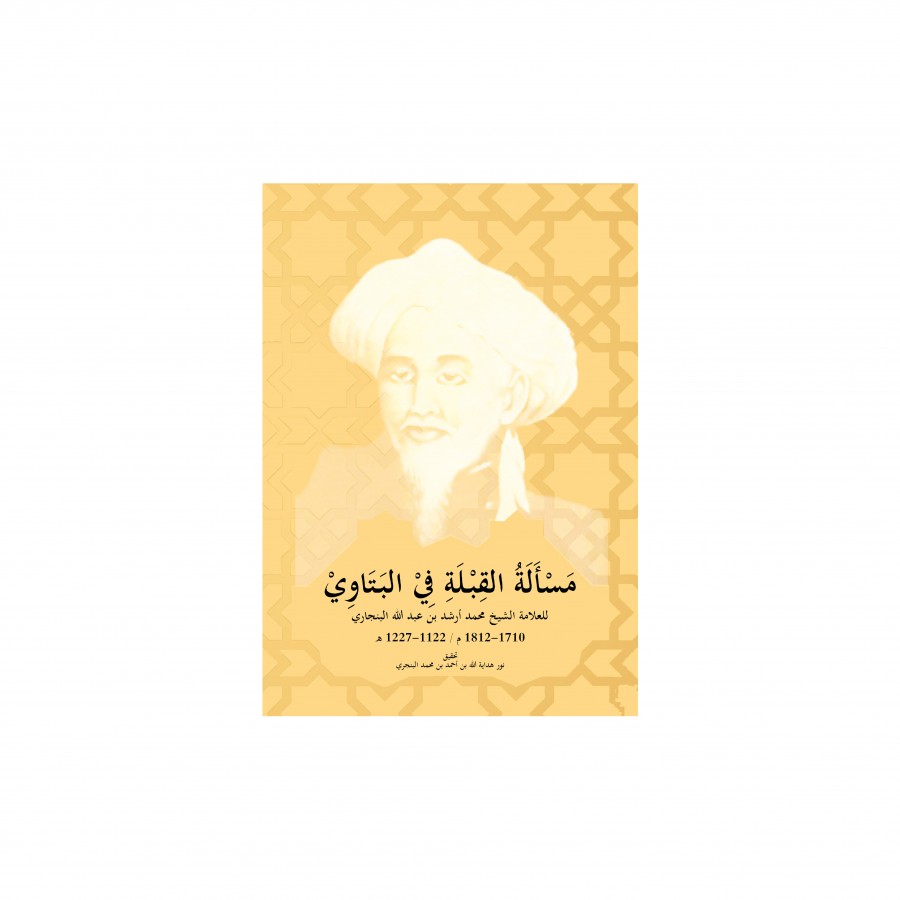Heidegger dalam ketegangan situasi hidup privat dan publiknya, di Pegunungan Black Forest (Jerman Selatan), di pedalaman Schwarzwald, wilayah bernama Todtnauberg, pada 1923 ia mendirikan satu gubuk dari kayu, menyebutnya sebagai "die Hütte" (Pondok). Di tempat ini Heidegger sering menyendiri bersama istrinya dan hidup dengan disiplin yang ketat. Berjarak dengan pelbagai rutinitas mekanis, bahkan tukang pos tak diperbolehkan mengebel pondoknya, melainkan langsung memasukkan surat ke kotak suratnya.
Selama bertahun-tahun, Heidegger mengerjakan banyak tulisannya yang paling terkenal “Being and Time” (1927) di pondok ini, mulai dari ceramah awalnya hingga teks terakhirnya yang penuh teka-teki. Dia mengklaim adanya keintiman intelektual dan emosional dengan bangunan dan lingkungan di sekitarnya, “Lanskap mengekspresikan dirinya melalui dirinya, hampir tanpa pengaruh apa pun”. Dalam Heidegger's Hut (Pondok Heidegger), Adam Sharr mengeksplorasi hubungan intens Heidegger dengan tempat, alam, dan orang.
Pondok Heidegger telah menjadi objek daya tarik mengenai dimensi fenomenologinya ‘Ada menampakkan dirinya’ yang berarti kita tidak memaksakan penafsiran-penafsiran kita begitu saja, melainkan membuka diri pada ‘Ada’ sebagai fenomena, membiarkan Ada terlihat (Sehenlassen). Misalnya, seseorang yang datang dari kota, mengunjungi sebuah daerah bentangan alam, seperti melihat pepohonan, gunung, sawah, sungai yang jarang dilihatnya—seakan-akan melihat semuanya itu pertama kali dalam hidupnya.
Penyelidikan arsitek Sharr mengenai Pondok Heidegger tentang “tempat tinggal” dan “tempat”—mengingatkan kita, dalam mendekati tulisan-tulisan Heidegger, penting untuk mempertimbangkan keadaan di mana sang filsuf, sebagaimana ia sendiri katakan, merasa "diangkut" ke dalam karya "miliknya" sebagai tempat konfrontasi heroik antara filsuf dan eksistensi; sebagai pelarian kaum borjuis kecil dari romantisme yang salah arah; sebagai tempat yang dibayangi oleh fasisme; atau sebagai bangunan kecil yang biasa-biasa saja. Mengingat keterlibatannya yang meresahkan dengan rezim Nazi pada awal tahun 1930-an.
Sebuah Pondok di Kaki Gunung Galunggung
Dalam beberapa kesempatan, saya sering mengunjungi tempat ini bersama beberapa kawan atau bahkan dengan seseorang—namun kali ini saya pergi sendirian. Di musim hujan yang bisu, saya berangkat dari tengah kota yang riak menuju ke tepian belantara kota—pergi ke sebuah tempat yang sunyi, jauh dari kebisingan dan kengerian bahasa tutur manusia. Sebelum tepat berada di batas antara pemukiman menuju gerbang nyanyi sunyi, saya kerap disambut dengan sentuhan lembut dari angin, suara serangga-serangga yang bergema, dan suara air mengalir dengan jelas—di momen ini timbul semacam getaran yang barangkali bahasa tidak bisa menjangkaunya—yang kadang kala dibersamai dengan berdirinya bulu kuduk. Bukan merasakan resonansi kehadiran entitas makhluk metafisik, melainkan persentuhan intim antara saya dengan alam.
Ketika saya mulai berjalan menuju jalan setapak dan sisi sebelah kanan jurang, saya dihadirkan perasaan yang ngilu, namun menyejukkan. Luapan gelisah dari rutinitas yang mekanis dan perasaan asing—menyatu dalam getir tubuh saya. Asing pada sesuatu yang sebelumnya saya pahami dan terlempar pada kondisi yang saya tidak kenali. Di situasi demikian, sosok Heidegger muncul dalam benak saya—bersamaan dengan satu kata khasnya yang pertama kali hadir ialah “keterlemparan” (Geworfenheit) situasi di mana Dasein (manusia) terlempar begitu saja ke dalam dunia ini. Begitu saja tanpa tahu dari mana dan mau ke mana.
Menurut Heidegger, itulah yang disebut “faktisitas” (Faktizität), kenyataan bahwa kita ada di dunia ini bersifat niscaya—pasti; tidak boleh tidak. Kita tak pernah ditanya lebih dahulu mau atau tidak hidup di dunia ini, juga kita tidak diberitahu ke mana harus bergerak di dunia ini. Kemudian, saya menemukan kalimat yang senada dalam esainya Goenawan Mohamad “debu, duka, dsb.” mengatakan, “Kita tak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita—dan terutama pada diri mereka yang menanggungkan kebengisan dan nasib buruk—jika kita simpulkan bahwa manusia memang terlontar ke dunia tanpa rencana, tanpa hikmah, tanpa alasan. Kita akan berada dalam absurditas yang galau.
Manakala, saat menyusuri jalan yang hanya cukup untuk dua kaki, saya menghadap pandangan ke depan dengan hati-hati, terdiam sejenak melihat hamparan pohon-pohon yang menyegarkan mata dan tebing mengerikan di samping kiri saya, terlihat di hadapan mata menjulang tinggi sebuah Gunung—seperti menyapa dengan melambai senyuman, pertanda saya sudah dekat dengan Pondok Heidegger—Tentu ini bukan di Jerman, melainkan di bawah kaki Gunung Galunggung—terdapat sebuah Pondok atau mungkin kata yang lebih akrab dengan telinga kita "Gubuk" yang berdiri tegap sendirian di tengah belantara gunung, di sisinya tebing menjulang tinggi yang suatu waktu siap meruntuhkannya, seakan ia telah bersedia menanggung segala terkaman nasib dengan sunyi.
Seperti dalam kumpulan puisi “Tonggeret” (2020) Acep Zamzam Noor, Lemburawi: “Sebuah gunung/ Menjadi titik sunyi/ Di bawah langit/ Ladang bertangga-tangga/ Hijau segarkan mata”. Bagi saya dalam dua bait pertamanya, penyair seperti terputus dari konsensus sosial, terberai dari ikatan kolektivitas, ia mendapati dirinya dalam kesendirian yang total—merujuk objek ‘gunung’ sebagai titik sunyi dan menandai krisis batin yang mengiringi kelahiran subjek individual dari retakan modernitas. Barangkali kita di situasi tertentu sering kali melarikan diri sejenak pada sebuah tempat yang jauh dari bayang-bayang kehidupan kita yang banal dan pelik, mungkin juga kita tak mendapati telinga yang bersedia mendengarkan sanubari yang memilukan—akhirnya kita diseret pada titik kesunyian—demikian juga seperti yang Chairil Anwar katakan “Nasib adalah kesunyian masing-masing”.
Setibanya di pintu masuk Pondok itu, saya tak menemukan Heidegger, melainkan Hannah Arendt seorang diri duduk di sela pintu dan memasang wajah yang seolah berkata "selamat datang". Dan saya sudah mengira, bukan saya satu-satunya yang datang kesini, sering kali ada beberapa orang dari luar daerah mengunjungi ke tempat ini hanya untuk sekedar membasuh tubuh dan batinnya di rendaman air panas—persis berada di samping Pondok.
Di momen ini, ketika tubuh menyelami air panas, ketika pakaian-pakaian telah dilepaskan, ketika tanggungan nasib-nasib yang berat itu diletakkan, semua bayangannya itu seakan menguap sedikit demi sedikit—seolah narasi-narasi besar ‘konstruksi sosial’ dari kesepakatan masyarakat modern—yang menjunjung tinggi kemapanan material, standar kesuksesan, dan hal-hal pelik kehidupan kita terlepas sementara dari tubuh. Serupa dengan kisah “Metamorfosis” milik Kafka dalam alegori Gregor Samsa—lekat kaitannya dengan situasi hidup manusia modern yang terasing, teralienasi, dan tak mengenal dirinya sendiri. Gregor, seperti masing-masing dari kita, hanyalah sekrup-sekrup kecil yang menyusun mesin raksasa kapitalisme. Laku hidup kita sebatas ditentukan untuk mencapai tujuan di luar keinginan kita. Bahkan mungkin kita tidak pernah dilihat sebagai manusia, melainkan sebatas komoditas yang bisa dicampakkan sewaktu-waktu saat tak lagi dibutuhkan.
Ketika aliran air panas keluar dari selongsong bambu-bambu dan menyerap melalui kulit, saya merasakan alam bersentuhan mesra dengan tubuh saya tanpa kata-kata, membasuh dari debu-debu, dan menjernihkan tubuh dan jiwa saya dari noda-noda khianat dan keruwetan dunia. Kadang kala di saat seperti ini, sering muncul bayang-bayang rutinitas yang belum tuntas, meski hadir dengan jeda terbata-bata, kemudian perlahan mulai menghilang ditepis oleh desiran angin—lalu saya mencerna dengan kemampuan terbatas, bahwa alam mungkin bisa menampakkan sisi persona feminimnya—yang penuh kasih sayang, jika kita juga membukakan diri pada alam dengan telanjang—menanggalkan semua sifat-sifat angkuh ‘hegemoni’ kita pada alam yang demikian sering kali melukainya, bahkan melindas alam dengan semena-mena, barangkali alam juga memiliki perasaan emosional—tanpa kita sadari.
Pandangan ini juga dibenci oleh Heidegger, alam hanya dilihat sebagai sumber daya untuk diperas habis demi kepentingan beberapa pihak semata. Pada akhirnya, kita hanya mampu menangkap satu ungkapan dari alam—ungkapan sebatas fungsi (Funktion). Sementara ungkapan-ungkapan alam lainnya tak lagi bisa kita sadari. Di titik ini saya membayangkan Pondok Heidegger ini menghadapi kemungkinan tragis—apa yang akan terjadi jika tempat ini ditemukan oleh tangan-tangan serakah? Kita barangkali tak bisa lagi membaur intim dengan alam, meski hanya sesaat dan sekedar bersinggah—tetapi membuat kita kerasan (betah) di dalamnya.
Heidegger melalui Prof. Budi Hardiman dalam “Heidegger dan Mistik Keseharian” (2020) mengatakan, “Dasein, tak pernah, juga pertama-tama tak pernah ada di dalam ruang. Dasein—dalam arti harfiah—menduduki ruang.” Dia tidak ‘terletak’ di suatu tempat, melainkan ‘memukimi’ suatu tempat. Karena itu kata ‘di dalam’ bagi Dasein berarti ‘bermukim’ (wohnen), ‘percaya’ (vertraut-mit) atau ‘kerasan’. Kita tidak tergeletak di dalam dunia, karna ‘tergeletak’ hanya tepat dipakai untuk benda-benda (Zeug)—melainkan terlempar di dalam dunia dan kerasan di dalamnya.
Manusia ‘terlempar’ ke dalam dunia ini. Pemuka agama dan orang-orang yang pandangannya mengandung kerangka teologis, akan protes dengan tesis ini, karena agama jelas memberi tahu bahwa manusia berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada-Nya. Tetapi menurut Heidegger, kesadaran religius ini harus ditangguhkan dulu. Bukankah semua ini hasil sosialisasi sejak kecil? Bagaimana jika sosialisasi ini tak ada? Kita sungguh-sungguh tak ditanyai lebih dahulu apakah mau dilahirkan di dunia ini.
Agama—meskipun sangat holistis dan mendalam—hanyalah salah satu cara memahami keterlemparan, tetapi faktisitas tetap, bahwa kita ‘ada begitu saja’. Jadi, menurut Heidegger keterlemparan itu sendiri lebih primordial daripada cara-cara memahaminya. Kita tentu boleh mempersoalkan pandangan Heidegger ini. “Keterlemparan” mengandung asumsi tentang tempat sebelumnya. Misalnya, bola terlempar dari tangan. Jadi, kita selalu bisa bertanya: “Terlempar dari mana?” Jika demikian, tentu ada asal dari keterlemparan itu. Tidakkah dengan demikian faktisitas bukan kata akhir? Masih ada ruang untuk penjelasan bagi asal Dasein, meski hal itu tidak ingin dimasuki oleh Heidegger.
Ketika saya hanyut dalam lamunan dimensi ‘alam pikiran’ Heidegger dan membiarkan tubuh saya tenggelam dalam kasih sayang alam melalui air panas—disadarkan oleh Matahari yang mulai terbenam di belakang Gunung Galunggung—saya harus bergegas pulang dan kembali memerankan Sisiphus. Meski tubuh saya letih—dalam perjalanan pulang menyusuri jalan setapak dan turunan yang terjal, sekurang-kurangnya saya mendapati semacam energi mengalir ke dalam tubuh. Alam membiarkan secercah dari bagian dirinya tersimpan dalam tubuh saya.
Tasikmalaya, 29 Januari 2024
Indra Kresna Wicaksana, Bandung, 11 April 1999. Pernah belajar ilmu Pendidikan Sejarah di Universitas Siliwangi. Meminati kajian seputar: Sejarah Kolonialisme, Filsafat, Sastra dan Kebudayaan. Mengelola @kuskarah dan @ohara_post
Heidegger dalam ketegangan situasi hidup privat dan publiknya, di Pegunungan Black Forest (Jerman Selatan), di pedalaman Schwarzwald, wilayah bernama Todtnauberg, pada 1923 ia mendirikan satu gubuk dari kayu, menyebutnya sebagai "die Hütte" (Pondok). Di tempat ini Heidegger sering menyendiri bersama istrinya dan hidup dengan disiplin yang ketat. Berjarak dengan pelbagai rutinitas mekanis, bahkan tukang pos tak diperbolehkan mengebel pondoknya, melainkan langsung memasukkan surat ke kotak suratnya.
Selama bertahun-tahun, Heidegger mengerjakan banyak tulisannya yang paling terkenal “Being and Time” (1927) di pondok ini, mulai dari ceramah awalnya hingga teks terakhirnya yang penuh teka-teki. Dia mengklaim adanya keintiman intelektual dan emosional dengan bangunan dan lingkungan di sekitarnya, “Lanskap mengekspresikan dirinya melalui dirinya, hampir tanpa pengaruh apa pun”. Dalam Heidegger's Hut (Pondok Heidegger), Adam Sharr mengeksplorasi hubungan intens Heidegger dengan tempat, alam, dan orang.
Pondok Heidegger telah menjadi objek daya tarik mengenai dimensi fenomenologinya ‘Ada menampakkan dirinya’ yang berarti kita tidak memaksakan penafsiran-penafsiran kita begitu saja, melainkan membuka diri pada ‘Ada’ sebagai fenomena, membiarkan Ada terlihat (Sehenlassen). Misalnya, seseorang yang datang dari kota, mengunjungi sebuah daerah bentangan alam, seperti melihat pepohonan, gunung, sawah, sungai yang jarang dilihatnya—seakan-akan melihat semuanya itu pertama kali dalam hidupnya.
Penyelidikan arsitek Sharr mengenai Pondok Heidegger tentang “tempat tinggal” dan “tempat”—mengingatkan kita, dalam mendekati tulisan-tulisan Heidegger, penting untuk mempertimbangkan keadaan di mana sang filsuf, sebagaimana ia sendiri katakan, merasa "diangkut" ke dalam karya "miliknya" sebagai tempat konfrontasi heroik antara filsuf dan eksistensi; sebagai pelarian kaum borjuis kecil dari romantisme yang salah arah; sebagai tempat yang dibayangi oleh fasisme; atau sebagai bangunan kecil yang biasa-biasa saja. Mengingat keterlibatannya yang meresahkan dengan rezim Nazi pada awal tahun 1930-an.
Sebuah Pondok di Kaki Gunung Galunggung
Dalam beberapa kesempatan, saya sering mengunjungi tempat ini bersama beberapa kawan atau bahkan dengan seseorang—namun kali ini saya pergi sendirian. Di musim hujan yang bisu, saya berangkat dari tengah kota yang riak menuju ke tepian belantara kota—pergi ke sebuah tempat yang sunyi, jauh dari kebisingan dan kengerian bahasa tutur manusia. Sebelum tepat berada di batas antara pemukiman menuju gerbang nyanyi sunyi, saya kerap disambut dengan sentuhan lembut dari angin, suara serangga-serangga yang bergema, dan suara air mengalir dengan jelas—di momen ini timbul semacam getaran yang barangkali bahasa tidak bisa menjangkaunya—yang kadang kala dibersamai dengan berdirinya bulu kuduk. Bukan merasakan resonansi kehadiran entitas makhluk metafisik, melainkan persentuhan intim antara saya dengan alam.
Ketika saya mulai berjalan menuju jalan setapak dan sisi sebelah kanan jurang, saya dihadirkan perasaan yang ngilu, namun menyejukkan. Luapan gelisah dari rutinitas yang mekanis dan perasaan asing—menyatu dalam getir tubuh saya. Asing pada sesuatu yang sebelumnya saya pahami dan terlempar pada kondisi yang saya tidak kenali. Di situasi demikian, sosok Heidegger muncul dalam benak saya—bersamaan dengan satu kata khasnya yang pertama kali hadir ialah “keterlemparan” (Geworfenheit) situasi di mana Dasein (manusia) terlempar begitu saja ke dalam dunia ini. Begitu saja tanpa tahu dari mana dan mau ke mana.
Menurut Heidegger, itulah yang disebut “faktisitas” (Faktizität), kenyataan bahwa kita ada di dunia ini bersifat niscaya—pasti; tidak boleh tidak. Kita tak pernah ditanya lebih dahulu mau atau tidak hidup di dunia ini, juga kita tidak diberitahu ke mana harus bergerak di dunia ini. Kemudian, saya menemukan kalimat yang senada dalam esainya Goenawan Mohamad “debu, duka, dsb.” mengatakan, “Kita tak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita—dan terutama pada diri mereka yang menanggungkan kebengisan dan nasib buruk—jika kita simpulkan bahwa manusia memang terlontar ke dunia tanpa rencana, tanpa hikmah, tanpa alasan. Kita akan berada dalam absurditas yang galau.
Manakala, saat menyusuri jalan yang hanya cukup untuk dua kaki, saya menghadap pandangan ke depan dengan hati-hati, terdiam sejenak melihat hamparan pohon-pohon yang menyegarkan mata dan tebing mengerikan di samping kiri saya, terlihat di hadapan mata menjulang tinggi sebuah Gunung—seperti menyapa dengan melambai senyuman, pertanda saya sudah dekat dengan Pondok Heidegger—Tentu ini bukan di Jerman, melainkan di bawah kaki Gunung Galunggung—terdapat sebuah Pondok atau mungkin kata yang lebih akrab dengan telinga kita "Gubuk" yang berdiri tegap sendirian di tengah belantara gunung, di sisinya tebing menjulang tinggi yang suatu waktu siap meruntuhkannya, seakan ia telah bersedia menanggung segala terkaman nasib dengan sunyi.
Seperti dalam kumpulan puisi “Tonggeret” (2020) Acep Zamzam Noor, Lemburawi: “Sebuah gunung/ Menjadi titik sunyi/ Di bawah langit/ Ladang bertangga-tangga/ Hijau segarkan mata”. Bagi saya dalam dua bait pertamanya, penyair seperti terputus dari konsensus sosial, terberai dari ikatan kolektivitas, ia mendapati dirinya dalam kesendirian yang total—merujuk objek ‘gunung’ sebagai titik sunyi dan menandai krisis batin yang mengiringi kelahiran subjek individual dari retakan modernitas. Barangkali kita di situasi tertentu sering kali melarikan diri sejenak pada sebuah tempat yang jauh dari bayang-bayang kehidupan kita yang banal dan pelik, mungkin juga kita tak mendapati telinga yang bersedia mendengarkan sanubari yang memilukan—akhirnya kita diseret pada titik kesunyian—demikian juga seperti yang Chairil Anwar katakan “Nasib adalah kesunyian masing-masing”.
Setibanya di pintu masuk Pondok itu, saya tak menemukan Heidegger, melainkan Hannah Arendt seorang diri duduk di sela pintu dan memasang wajah yang seolah berkata "selamat datang". Dan saya sudah mengira, bukan saya satu-satunya yang datang kesini, sering kali ada beberapa orang dari luar daerah mengunjungi ke tempat ini hanya untuk sekedar membasuh tubuh dan batinnya di rendaman air panas—persis berada di samping Pondok.
Di momen ini, ketika tubuh menyelami air panas, ketika pakaian-pakaian telah dilepaskan, ketika tanggungan nasib-nasib yang berat itu diletakkan, semua bayangannya itu seakan menguap sedikit demi sedikit—seolah narasi-narasi besar ‘konstruksi sosial’ dari kesepakatan masyarakat modern—yang menjunjung tinggi kemapanan material, standar kesuksesan, dan hal-hal pelik kehidupan kita terlepas sementara dari tubuh. Serupa dengan kisah “Metamorfosis” milik Kafka dalam alegori Gregor Samsa—lekat kaitannya dengan situasi hidup manusia modern yang terasing, teralienasi, dan tak mengenal dirinya sendiri. Gregor, seperti masing-masing dari kita, hanyalah sekrup-sekrup kecil yang menyusun mesin raksasa kapitalisme. Laku hidup kita sebatas ditentukan untuk mencapai tujuan di luar keinginan kita. Bahkan mungkin kita tidak pernah dilihat sebagai manusia, melainkan sebatas komoditas yang bisa dicampakkan sewaktu-waktu saat tak lagi dibutuhkan.
Ketika aliran air panas keluar dari selongsong bambu-bambu dan menyerap melalui kulit, saya merasakan alam bersentuhan mesra dengan tubuh saya tanpa kata-kata, membasuh dari debu-debu, dan menjernihkan tubuh dan jiwa saya dari noda-noda khianat dan keruwetan dunia. Kadang kala di saat seperti ini, sering muncul bayang-bayang rutinitas yang belum tuntas, meski hadir dengan jeda terbata-bata, kemudian perlahan mulai menghilang ditepis oleh desiran angin—lalu saya mencerna dengan kemampuan terbatas, bahwa alam mungkin bisa menampakkan sisi persona feminimnya—yang penuh kasih sayang, jika kita juga membukakan diri pada alam dengan telanjang—menanggalkan semua sifat-sifat angkuh ‘hegemoni’ kita pada alam yang demikian sering kali melukainya, bahkan melindas alam dengan semena-mena, barangkali alam juga memiliki perasaan emosional—tanpa kita sadari.
Pandangan ini juga dibenci oleh Heidegger, alam hanya dilihat sebagai sumber daya untuk diperas habis demi kepentingan beberapa pihak semata. Pada akhirnya, kita hanya mampu menangkap satu ungkapan dari alam—ungkapan sebatas fungsi (Funktion). Sementara ungkapan-ungkapan alam lainnya tak lagi bisa kita sadari. Di titik ini saya membayangkan Pondok Heidegger ini menghadapi kemungkinan tragis—apa yang akan terjadi jika tempat ini ditemukan oleh tangan-tangan serakah? Kita barangkali tak bisa lagi membaur intim dengan alam, meski hanya sesaat dan sekedar bersinggah—tetapi membuat kita kerasan (betah) di dalamnya.
Heidegger melalui Prof. Budi Hardiman dalam “Heidegger dan Mistik Keseharian” (2020) mengatakan, “Dasein, tak pernah, juga pertama-tama tak pernah ada di dalam ruang. Dasein—dalam arti harfiah—menduduki ruang.” Dia tidak ‘terletak’ di suatu tempat, melainkan ‘memukimi’ suatu tempat. Karena itu kata ‘di dalam’ bagi Dasein berarti ‘bermukim’ (wohnen), ‘percaya’ (vertraut-mit) atau ‘kerasan’. Kita tidak tergeletak di dalam dunia, karna ‘tergeletak’ hanya tepat dipakai untuk benda-benda (Zeug)—melainkan terlempar di dalam dunia dan kerasan di dalamnya.
Manusia ‘terlempar’ ke dalam dunia ini. Pemuka agama dan orang-orang yang pandangannya mengandung kerangka teologis, akan protes dengan tesis ini, karena agama jelas memberi tahu bahwa manusia berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada-Nya. Tetapi menurut Heidegger, kesadaran religius ini harus ditangguhkan dulu. Bukankah semua ini hasil sosialisasi sejak kecil? Bagaimana jika sosialisasi ini tak ada? Kita sungguh-sungguh tak ditanyai lebih dahulu apakah mau dilahirkan di dunia ini.
Agama—meskipun sangat holistis dan mendalam—hanyalah salah satu cara memahami keterlemparan, tetapi faktisitas tetap, bahwa kita ‘ada begitu saja’. Jadi, menurut Heidegger keterlemparan itu sendiri lebih primordial daripada cara-cara memahaminya. Kita tentu boleh mempersoalkan pandangan Heidegger ini. “Keterlemparan” mengandung asumsi tentang tempat sebelumnya. Misalnya, bola terlempar dari tangan. Jadi, kita selalu bisa bertanya: “Terlempar dari mana?” Jika demikian, tentu ada asal dari keterlemparan itu. Tidakkah dengan demikian faktisitas bukan kata akhir? Masih ada ruang untuk penjelasan bagi asal Dasein, meski hal itu tidak ingin dimasuki oleh Heidegger.
Ketika saya hanyut dalam lamunan dimensi ‘alam pikiran’ Heidegger dan membiarkan tubuh saya tenggelam dalam kasih sayang alam melalui air panas—disadarkan oleh Matahari yang mulai terbenam di belakang Gunung Galunggung—saya harus bergegas pulang dan kembali memerankan Sisiphus. Meski tubuh saya letih—dalam perjalanan pulang menyusuri jalan setapak dan turunan yang terjal, sekurang-kurangnya saya mendapati semacam energi mengalir ke dalam tubuh. Alam membiarkan secercah dari bagian dirinya tersimpan dalam tubuh saya.
Tasikmalaya, 29 Januari 2024
Indra Kresna Wicaksana, Bandung, 11 April 1999. Pernah belajar ilmu Pendidikan Sejarah di Universitas Siliwangi. Meminati kajian seputar: Sejarah Kolonialisme, Filsafat, Sastra dan Kebudayaan. Mengelola @kuskarah dan @ohara_post
Heidegger dalam ketegangan situasi hidup privat dan publiknya, di Pegunungan Black Forest (Jerman Selatan), di pedalaman Schwarzwald, wilayah bernama Todtnauberg, pada 1923 ia mendirikan satu gubuk dari kayu, menyebutnya sebagai "die Hütte" (Pondok). Di tempat ini Heidegger sering menyendiri bersama istrinya dan hidup dengan disiplin yang ketat. Berjarak dengan pelbagai rutinitas mekanis, bahkan tukang pos tak diperbolehkan mengebel pondoknya, melainkan langsung memasukkan surat ke kotak suratnya.
Selama bertahun-tahun, Heidegger mengerjakan banyak tulisannya yang paling terkenal “Being and Time” (1927) di pondok ini, mulai dari ceramah awalnya hingga teks terakhirnya yang penuh teka-teki. Dia mengklaim adanya keintiman intelektual dan emosional dengan bangunan dan lingkungan di sekitarnya, “Lanskap mengekspresikan dirinya melalui dirinya, hampir tanpa pengaruh apa pun”. Dalam Heidegger's Hut (Pondok Heidegger), Adam Sharr mengeksplorasi hubungan intens Heidegger dengan tempat, alam, dan orang.
Pondok Heidegger telah menjadi objek daya tarik mengenai dimensi fenomenologinya ‘Ada menampakkan dirinya’ yang berarti kita tidak memaksakan penafsiran-penafsiran kita begitu saja, melainkan membuka diri pada ‘Ada’ sebagai fenomena, membiarkan Ada terlihat (Sehenlassen). Misalnya, seseorang yang datang dari kota, mengunjungi sebuah daerah bentangan alam, seperti melihat pepohonan, gunung, sawah, sungai yang jarang dilihatnya—seakan-akan melihat semuanya itu pertama kali dalam hidupnya.
Penyelidikan arsitek Sharr mengenai Pondok Heidegger tentang “tempat tinggal” dan “tempat”—mengingatkan kita, dalam mendekati tulisan-tulisan Heidegger, penting untuk mempertimbangkan keadaan di mana sang filsuf, sebagaimana ia sendiri katakan, merasa "diangkut" ke dalam karya "miliknya" sebagai tempat konfrontasi heroik antara filsuf dan eksistensi; sebagai pelarian kaum borjuis kecil dari romantisme yang salah arah; sebagai tempat yang dibayangi oleh fasisme; atau sebagai bangunan kecil yang biasa-biasa saja. Mengingat keterlibatannya yang meresahkan dengan rezim Nazi pada awal tahun 1930-an.
Sebuah Pondok di Kaki Gunung Galunggung
Dalam beberapa kesempatan, saya sering mengunjungi tempat ini bersama beberapa kawan atau bahkan dengan seseorang—namun kali ini saya pergi sendirian. Di musim hujan yang bisu, saya berangkat dari tengah kota yang riak menuju ke tepian belantara kota—pergi ke sebuah tempat yang sunyi, jauh dari kebisingan dan kengerian bahasa tutur manusia. Sebelum tepat berada di batas antara pemukiman menuju gerbang nyanyi sunyi, saya kerap disambut dengan sentuhan lembut dari angin, suara serangga-serangga yang bergema, dan suara air mengalir dengan jelas—di momen ini timbul semacam getaran yang barangkali bahasa tidak bisa menjangkaunya—yang kadang kala dibersamai dengan berdirinya bulu kuduk. Bukan merasakan resonansi kehadiran entitas makhluk metafisik, melainkan persentuhan intim antara saya dengan alam.
Ketika saya mulai berjalan menuju jalan setapak dan sisi sebelah kanan jurang, saya dihadirkan perasaan yang ngilu, namun menyejukkan. Luapan gelisah dari rutinitas yang mekanis dan perasaan asing—menyatu dalam getir tubuh saya. Asing pada sesuatu yang sebelumnya saya pahami dan terlempar pada kondisi yang saya tidak kenali. Di situasi demikian, sosok Heidegger muncul dalam benak saya—bersamaan dengan satu kata khasnya yang pertama kali hadir ialah “keterlemparan” (Geworfenheit) situasi di mana Dasein (manusia) terlempar begitu saja ke dalam dunia ini. Begitu saja tanpa tahu dari mana dan mau ke mana.
Menurut Heidegger, itulah yang disebut “faktisitas” (Faktizität), kenyataan bahwa kita ada di dunia ini bersifat niscaya—pasti; tidak boleh tidak. Kita tak pernah ditanya lebih dahulu mau atau tidak hidup di dunia ini, juga kita tidak diberitahu ke mana harus bergerak di dunia ini. Kemudian, saya menemukan kalimat yang senada dalam esainya Goenawan Mohamad “debu, duka, dsb.” mengatakan, “Kita tak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita—dan terutama pada diri mereka yang menanggungkan kebengisan dan nasib buruk—jika kita simpulkan bahwa manusia memang terlontar ke dunia tanpa rencana, tanpa hikmah, tanpa alasan. Kita akan berada dalam absurditas yang galau.
Manakala, saat menyusuri jalan yang hanya cukup untuk dua kaki, saya menghadap pandangan ke depan dengan hati-hati, terdiam sejenak melihat hamparan pohon-pohon yang menyegarkan mata dan tebing mengerikan di samping kiri saya, terlihat di hadapan mata menjulang tinggi sebuah Gunung—seperti menyapa dengan melambai senyuman, pertanda saya sudah dekat dengan Pondok Heidegger—Tentu ini bukan di Jerman, melainkan di bawah kaki Gunung Galunggung—terdapat sebuah Pondok atau mungkin kata yang lebih akrab dengan telinga kita "Gubuk" yang berdiri tegap sendirian di tengah belantara gunung, di sisinya tebing menjulang tinggi yang suatu waktu siap meruntuhkannya, seakan ia telah bersedia menanggung segala terkaman nasib dengan sunyi.
Seperti dalam kumpulan puisi “Tonggeret” (2020) Acep Zamzam Noor, Lemburawi: “Sebuah gunung/ Menjadi titik sunyi/ Di bawah langit/ Ladang bertangga-tangga/ Hijau segarkan mata”. Bagi saya dalam dua bait pertamanya, penyair seperti terputus dari konsensus sosial, terberai dari ikatan kolektivitas, ia mendapati dirinya dalam kesendirian yang total—merujuk objek ‘gunung’ sebagai titik sunyi dan menandai krisis batin yang mengiringi kelahiran subjek individual dari retakan modernitas. Barangkali kita di situasi tertentu sering kali melarikan diri sejenak pada sebuah tempat yang jauh dari bayang-bayang kehidupan kita yang banal dan pelik, mungkin juga kita tak mendapati telinga yang bersedia mendengarkan sanubari yang memilukan—akhirnya kita diseret pada titik kesunyian—demikian juga seperti yang Chairil Anwar katakan “Nasib adalah kesunyian masing-masing”.
Setibanya di pintu masuk Pondok itu, saya tak menemukan Heidegger, melainkan Hannah Arendt seorang diri duduk di sela pintu dan memasang wajah yang seolah berkata "selamat datang". Dan saya sudah mengira, bukan saya satu-satunya yang datang kesini, sering kali ada beberapa orang dari luar daerah mengunjungi ke tempat ini hanya untuk sekedar membasuh tubuh dan batinnya di rendaman air panas—persis berada di samping Pondok.
Di momen ini, ketika tubuh menyelami air panas, ketika pakaian-pakaian telah dilepaskan, ketika tanggungan nasib-nasib yang berat itu diletakkan, semua bayangannya itu seakan menguap sedikit demi sedikit—seolah narasi-narasi besar ‘konstruksi sosial’ dari kesepakatan masyarakat modern—yang menjunjung tinggi kemapanan material, standar kesuksesan, dan hal-hal pelik kehidupan kita terlepas sementara dari tubuh. Serupa dengan kisah “Metamorfosis” milik Kafka dalam alegori Gregor Samsa—lekat kaitannya dengan situasi hidup manusia modern yang terasing, teralienasi, dan tak mengenal dirinya sendiri. Gregor, seperti masing-masing dari kita, hanyalah sekrup-sekrup kecil yang menyusun mesin raksasa kapitalisme. Laku hidup kita sebatas ditentukan untuk mencapai tujuan di luar keinginan kita. Bahkan mungkin kita tidak pernah dilihat sebagai manusia, melainkan sebatas komoditas yang bisa dicampakkan sewaktu-waktu saat tak lagi dibutuhkan.
Ketika aliran air panas keluar dari selongsong bambu-bambu dan menyerap melalui kulit, saya merasakan alam bersentuhan mesra dengan tubuh saya tanpa kata-kata, membasuh dari debu-debu, dan menjernihkan tubuh dan jiwa saya dari noda-noda khianat dan keruwetan dunia. Kadang kala di saat seperti ini, sering muncul bayang-bayang rutinitas yang belum tuntas, meski hadir dengan jeda terbata-bata, kemudian perlahan mulai menghilang ditepis oleh desiran angin—lalu saya mencerna dengan kemampuan terbatas, bahwa alam mungkin bisa menampakkan sisi persona feminimnya—yang penuh kasih sayang, jika kita juga membukakan diri pada alam dengan telanjang—menanggalkan semua sifat-sifat angkuh ‘hegemoni’ kita pada alam yang demikian sering kali melukainya, bahkan melindas alam dengan semena-mena, barangkali alam juga memiliki perasaan emosional—tanpa kita sadari.
Pandangan ini juga dibenci oleh Heidegger, alam hanya dilihat sebagai sumber daya untuk diperas habis demi kepentingan beberapa pihak semata. Pada akhirnya, kita hanya mampu menangkap satu ungkapan dari alam—ungkapan sebatas fungsi (Funktion). Sementara ungkapan-ungkapan alam lainnya tak lagi bisa kita sadari. Di titik ini saya membayangkan Pondok Heidegger ini menghadapi kemungkinan tragis—apa yang akan terjadi jika tempat ini ditemukan oleh tangan-tangan serakah? Kita barangkali tak bisa lagi membaur intim dengan alam, meski hanya sesaat dan sekedar bersinggah—tetapi membuat kita kerasan (betah) di dalamnya.
Heidegger melalui Prof. Budi Hardiman dalam “Heidegger dan Mistik Keseharian” (2020) mengatakan, “Dasein, tak pernah, juga pertama-tama tak pernah ada di dalam ruang. Dasein—dalam arti harfiah—menduduki ruang.” Dia tidak ‘terletak’ di suatu tempat, melainkan ‘memukimi’ suatu tempat. Karena itu kata ‘di dalam’ bagi Dasein berarti ‘bermukim’ (wohnen), ‘percaya’ (vertraut-mit) atau ‘kerasan’. Kita tidak tergeletak di dalam dunia, karna ‘tergeletak’ hanya tepat dipakai untuk benda-benda (Zeug)—melainkan terlempar di dalam dunia dan kerasan di dalamnya.
Manusia ‘terlempar’ ke dalam dunia ini. Pemuka agama dan orang-orang yang pandangannya mengandung kerangka teologis, akan protes dengan tesis ini, karena agama jelas memberi tahu bahwa manusia berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada-Nya. Tetapi menurut Heidegger, kesadaran religius ini harus ditangguhkan dulu. Bukankah semua ini hasil sosialisasi sejak kecil? Bagaimana jika sosialisasi ini tak ada? Kita sungguh-sungguh tak ditanyai lebih dahulu apakah mau dilahirkan di dunia ini.
Agama—meskipun sangat holistis dan mendalam—hanyalah salah satu cara memahami keterlemparan, tetapi faktisitas tetap, bahwa kita ‘ada begitu saja’. Jadi, menurut Heidegger keterlemparan itu sendiri lebih primordial daripada cara-cara memahaminya. Kita tentu boleh mempersoalkan pandangan Heidegger ini. “Keterlemparan” mengandung asumsi tentang tempat sebelumnya. Misalnya, bola terlempar dari tangan. Jadi, kita selalu bisa bertanya: “Terlempar dari mana?” Jika demikian, tentu ada asal dari keterlemparan itu. Tidakkah dengan demikian faktisitas bukan kata akhir? Masih ada ruang untuk penjelasan bagi asal Dasein, meski hal itu tidak ingin dimasuki oleh Heidegger.
Ketika saya hanyut dalam lamunan dimensi ‘alam pikiran’ Heidegger dan membiarkan tubuh saya tenggelam dalam kasih sayang alam melalui air panas—disadarkan oleh Matahari yang mulai terbenam di belakang Gunung Galunggung—saya harus bergegas pulang dan kembali memerankan Sisiphus. Meski tubuh saya letih—dalam perjalanan pulang menyusuri jalan setapak dan turunan yang terjal, sekurang-kurangnya saya mendapati semacam energi mengalir ke dalam tubuh. Alam membiarkan secercah dari bagian dirinya tersimpan dalam tubuh saya.
Tasikmalaya, 29 Januari 2024
Indra Kresna Wicaksana, Bandung, 11 April 1999. Pernah belajar ilmu Pendidikan Sejarah di Universitas Siliwangi. Meminati kajian seputar: Sejarah Kolonialisme, Filsafat, Sastra dan Kebudayaan. Mengelola @kuskarah dan @ohara_post