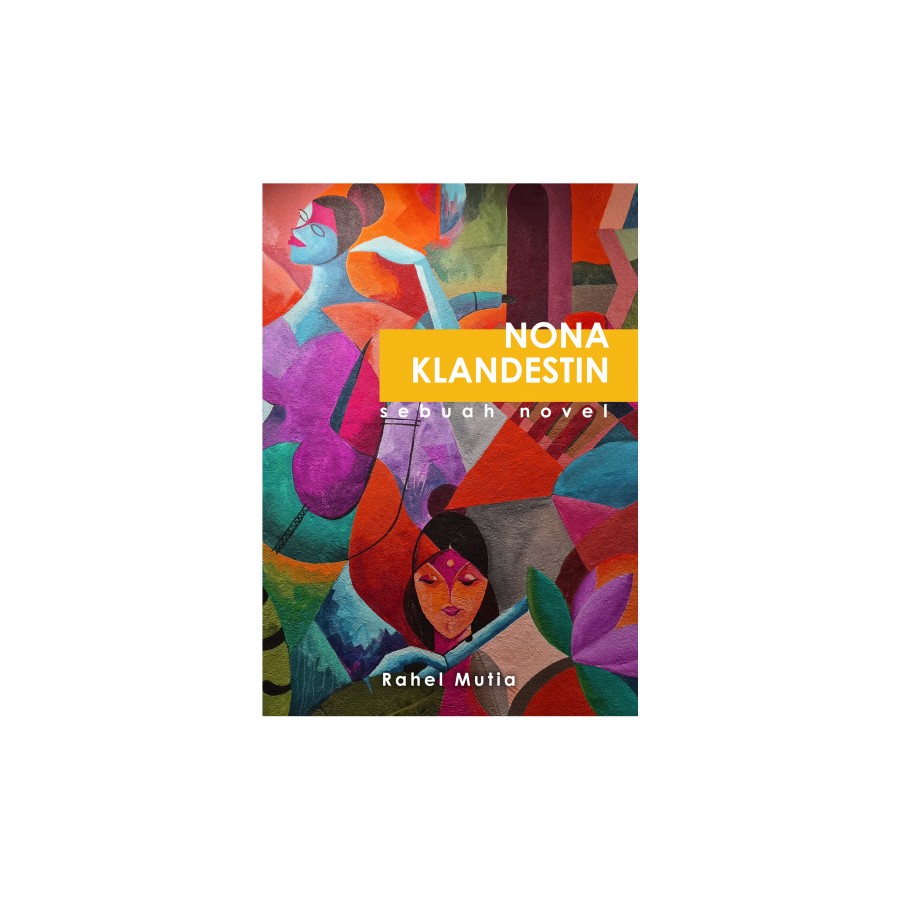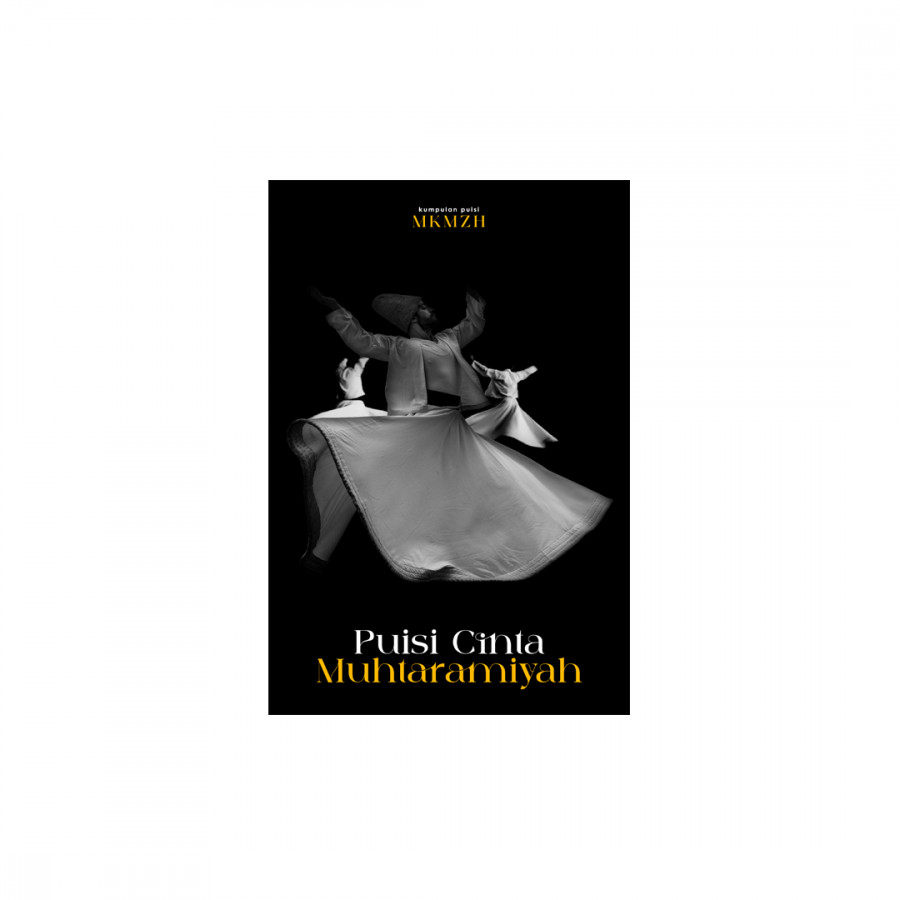Pada masa silam, orang-orang di Nusantara menyadari betul bahwa penyematan sebuah nama terhadap suatu objek yang dalam hal ini adalah tempat menjadi hal yang tak bisa dianggap remeh. Hal itu tentu didasari oleh kepercayaan, budaya, serta letak geografis masyarakat yang mendiaminya. Kemudian, menjadi penting bagaimana bahasa hadir sebagai media dari proses penamaan ini. Bahasa dan kebudayaan memiliki hubungan dan saling memengaruhi satu sama lain. Keterkaitan itulah yang kemudian oleh Nababan (1993:82) dibagi menjadi dua prinsip, yakni prinsip Filogenetik yang memandang bahasa sebagai bagian dari kebudayaan dan Ontogenetik yang mengkaji kebudayaan melalui bahasa.
Pengaruh kebudayaan bangsa Indonesia terhadap penamaan suatu tempat secara umum tercermin berdasarkan letak geografis wilayah Nusantara yang terdiri dari tiga aspek strategis, yakni aspek agraris, aspek maritim, dan aspek flora-fauna. Sederhananya, kita tak akan kesulitan menemukan nama daerah-daerah di tiap kota atau kabupaten di Indonesia yang menggunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan tiga aspek strategis di atas, seperti Desa Ngendut yang berasal dari kata Endhut (lumpur) di mana penamaan desa ini berdasarkan tekstur tanahnya yang keras, Desa Ngrandu yang memiliki kata dasar Randu, merujuk pada pohon randu yang banyak tumbuh di wilayah desa tersebut, dan lain sebagagainya. Penamaan-penamaan ini sudah jauh lebih awal digunakan sebelum akhirnya banyak nama tempat yang namanya diubah menggunakan nama tokoh-tokoh besar bangsa.
Mengerucut ke peta sebaran wilayah Jawa Barat dan Banten, kita akan mudah menemukan nama-nama daerah yang juga merujuk pada tiga aspek yang sudah dikemukakan di atas. Mulai dari Sawah lega, Cikijing, Lebak, Datar petir, Datar kupa, dan sebagainya. Kesemua nama itu lekat kaitannya dengan unsur agraris, maritim, bahkan flora dan fauna. Belum lagi masyarakat sunda, entah disepakati atau tidak, punya takaran kelakarnya sendiri. Mereka bisa berguyon tentang apa pun. Maka hampir di seluruh wilayah masyarakat Sunda, dikenal istilah Cawokah; senang berguyon tentang hal yang berkaitan dengan masalah berahi.
Nampaknya, Cawokah yang merupakan bagian dari praktik berbahasa masyarakat Sunda ini menjalar juga hingga pada proses pembentukan nama tempat di berbagai daerah yang mereka tempati. Sependek hasil observasi penulis, ada beberapa nama tempat yang mungkin jika dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia, akan terkesan vulgar dan membuat pendengarnya tersenyum sinis. Sebut saja Pasir Ewe Randa yang berada di Kampung Datarpetir, Desa Toblongan, Bojongasih, kabupaten Tasikmalaya. Pasir Ewe Randa adalah sebuah bukit rimbun yang memiliki ketinggian sekitar 500-700 mdpl. Berada tepat di punggungan Gunung Gariawas, membuat bukit ini menjadi sebuah ekosistem lengkap bagi berbagai macam hewan dan tumbuhan. Selain itu, terdapat juga beberapa mata air yang dimanfaatkan oleh warga sekitar guna dikonsumsi, mengairi saluran irigasi, pusat pengairan empang, dan jenis-jenis kebutuhan lainnya. Bukan juga tanpa pemilik, sebab beberapa luas Pasir Ewe Randa telah menjadi kebun yang dimiliki oleh beberapa warga sekitar dan ditanami beberapa jenis sayuran dan buah-buahan. Kalau kemarau tiba, lalu laju angin lebih besar dan cepat dari biasanya, puncak Pasir Ewe Randa akan dipadati oleh para lelaki setengah baya yang membawa Kolecer; kincir angin berbahan bambu. Mereka akan mengikat Kolecer andalan mereka di pohon yang dirasa cukup kuat untuk menopang batang Kolecer dan ketika baling-balingnya diterpa angin. Kalau cuaca sedang bersahabat, suara dari Kolecer akan menggelegar, membuat musim kemarau bernyanyi.
Sebenarnya, Pasir Ewe Randa akan menjadi kajian menarik bagi bidang sosiolinguistik, toponimi, maupun onomastika yang menjadi senjata bagi pengkajian awal mula proses penciptaan suatu nama. Sebab, sebagaimana pemuda yang harus mengenali dirinya, termasuk mengenali lingkungan asalnya, memahami sekaligus memaknai asal usul, bentuk, nilai-nilai falsafah yang terpendam dari proses pembentukan nama objek tersebut. Dengan begitu, bukan semata sisi vulgarnya yang menjadi sorot utama, tapi khazanah dan perbendaharaan pengetahuan pun akan bertambah, tanpa mengganggu apa yang sudah menjadi kepercayaan masyarakat sekitar. Lebih jauh, bukan tidak mungkin Pasir Ewe Randa akan melalui proses komodifikasi dan mendatangkan keuntungan ekonomis apabila dikelola dengan menggunakan kacamata kreatif. Jika saja pemerintah setempat peka atas aset luar biasa yang dimilikinya. Atau, selamanya Pasir Ewe Randa hanya akan menjadi sebuah nama guyon yang tak pernah ditelusuri, membuatnya kehilangan makna dan nilai-nilainya tak pernah muncul ke permukaan sebagai falsafah hidup.