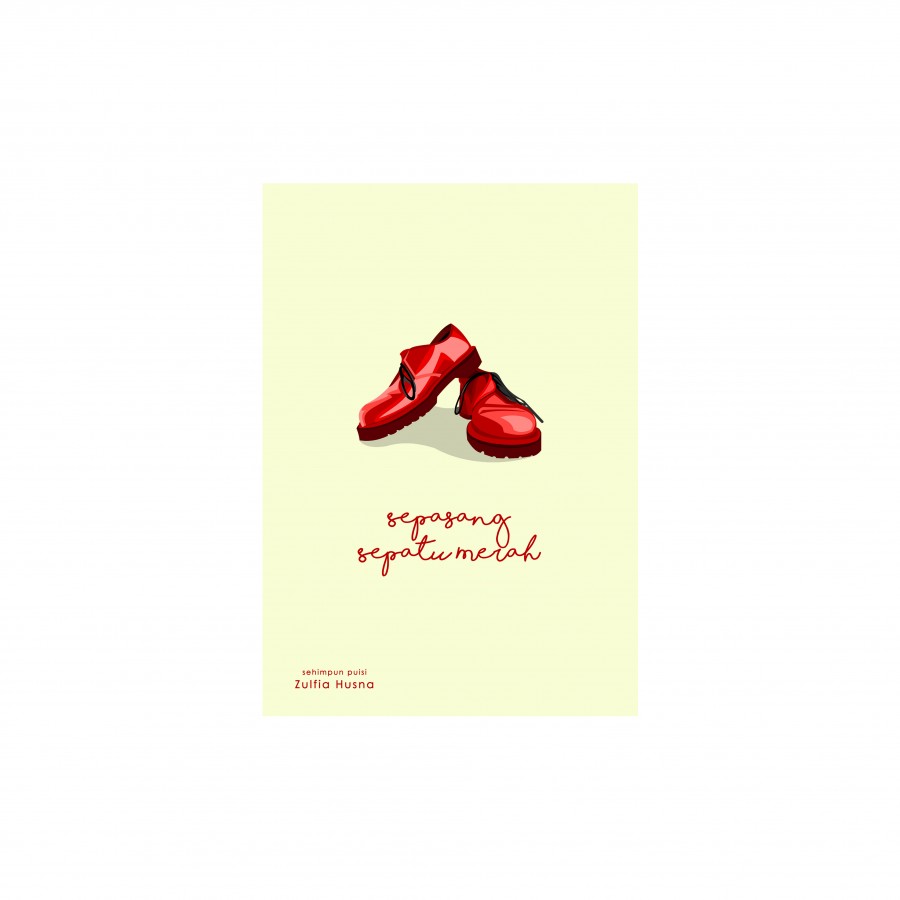-3971.jpg)
Beberapa waktu lalu, sekitar bulan Juni 2022, muncul sebuah artikel yang memuat pandangan Bapak Dodon mengenai perpustakaan yang dimuat di Kabar Cirebon tanggal 14 Juni 2022. Tepatnya, pandangan itu merespons program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan yang “Menargetkan pembangunan gedung perpustakaan sebanyak 100 unit pada tahun 2023.” Meskipun dalam respons tersebut dikatakan bahwa sampai tahun 2021 baru bisa dibangun sampai 41 unit saja. Respons itu, yang juga menyampaikan kritik, memandang bahwa pembangunan ini “Dinilai percuma saja,” dan kemudian menyarankan penyediaan internet berlangganan bagi seluruh sekolah yang penggunaannya harus dalam pengawasan guru. Beberapa waktu kemudian, ada tanggapan atas artikel tersebut yang ditulis oleh D. Ipung Kusmawi, dimuat di Kabar Cirebon tanggal 20 Juni 2022. Pandangan yang disampaikan di sana menanggapi argumen bahwa perpustakaan tidak lagi relevan, “Tidak keren dan kurang modern,” dengan mengungkapkan bahwa perpustakaan tetap mampu menghdirkan suasana yang tidak hanya berupa pertukaran informasi, melainkan lebih dari itu, dan tidak bisa sepenuhnya diganti oleh perangkat digital atau internet.
Secara garis besar, dan mudah-mudahan saya tidak keliru, artikel pertama meminta efisiensi, yakni dengan cara memperbanyak penyediaan sarana internet bagi sekolah-sekolah (Meski saya tidak menemukan saran teknis-operasional dari artikel tersebut terkait saran ini) alih-alih membangun banyak gedung perpustakaan yang dianggap “tidak efisien”. Sementara artikel kedua menyarankan suatu refleksi, yakni bahwa perpustakaan, yang berdiri sebagai suatu konstruksi bangunan tempat buku-buku fisik tersedia, tetap menyembulkan “iklim emosional” yang tipikal, yang dianggap tidak dapat tergantikan oleh kehadiran internet.
Ada semacam ambivalen, dan topik ini memancing minat saya untuk ikut menyampaikan respons, meski dapat dibilang terlambat. Untuk itu saya memohon permaklumannya.
Bertolak dari sini, saya mulai penasaran: Seberapa penting problem perpustakaan untuk diperbincangkan dengan serius dewasa ini? Terus terang, saya tertarik untuk memasuki arena diskursus ini, meski saya tidak akan menyentuh ihwal “program-politik” yang menempel dalam topik dalam artikel pertama, karena saya tidak memiliki kapasitas di wilayah itu.
Pertama-tama, saya hendak melibatkan diri bukan untuk membela atau menyerang perspektif yang mana pun, melainkan sekadar berupaya untuk memberi tawaran jeda, yang mudah-mudahan reflektif, dalam proses awal membincang ihwal perpustakaan ini. Saya hanya akan menawarkan jeda itu dengan isi yang saya kira sederhana: merenungkan kembali definisi perpustakaan. Apabila nanti tulisan ini cenderung teoretis dan dipenuhi rigiditas yang membuat pembaca lelah, saya (kembali) memohon permaklumannya.
Dari beberapa literatur yang saya baca, sekurang-kurangnya saya menemukan tiga definisi mengenai perpustakaan, yaitu perpustakaan sebagai bangunan, perpustakaan sebagai unit kerja, dan perpustakaan sebagai bahan pustaka. Ketiga definisi itu dapat kita ulas di sini untuk mengenali lebih jauh mengenai apa sebenarnya arti atau makna perpustakaan itu sendiri.
Definisi pertama saya coba rujuk dari buku Pengantar Ilmu Perpustakaan (2003). Di sana dikatakan bahwa perpustakaan adalah “suatu ruangan, bagian dari gedung/bangunan, atau gedung itu sendiri, yang berisi buku-buku koleksi, yang disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga mudah dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk pembaca”.
Eksistensi perpustakaan sebagai suatu “ruangan” fisik, tentu saja perlahan-lahan mengalami semacam dekorporealisasi. Artinya, eksistensi fisik barangkali sudah tidak lagi bisa mengimbangi kecepatan tuntutan informasi dan komunikasi dalam era komunikasi digital. Dalam hal ini saya sependapat dengan artikel pertama, bahwa koneksi internet yang memadai memang jauh lebih diperlukan secara instrumental. Hal ini mungkin muncul dari paradigma manusia dewasa ini yang akan mengerutkan dahi kalau harus pergi ke perpustakaan sekadar untuk, misalnya, mencari tahu biografi Soekarno dari buku padahal ia bisa browsing di gawai yang ia genggam. Artinya, eksistensi perpustakaan sebagai suatu bangunan korporeal, yang fisik atawa nyata, ternyata berada di tepi jurang.
Namun meski demikian, perpustakaan sebagai gedung bisa juga dianggap keliru dari sudut tertentu. Karena suatu gedung, suatu ruang, hanya akan bisa memiliki fungsi tertentu (dalam konteks ini fungsi ke-perpustakaan-an) apabila ia memiliki mekanisme kerja yang berorientasi ke arah sana. Tentu di sini perlu adanya semacam unit kerja atau institusi. Saya hendak memerkuat pandangan ini dengan definisi kedua yang mengacu pada Miburga et al dalam buku Membina Perpustakaan Sekolah (1991) yang menyatakan perpustakaan sebagai “suatu unit kerja yang berupa tempat menyimpan koleksi bahan pustaka yang diatur secara sistematis dengan cara tertentu untuk digunakan secara berkesinambungan oleh pemakainya sebagai sumber informasi”.
Meski definisi di atas berkata “yang berupa tempat menyimpan koleksi bahan pustaka,” saya justru lebih menekankan pada “unit kerja” yang diasosiasikan dengan tempat itu. Selanjutnya ketika berbicara tentang unit kerja, tentu perlu adanya operator yang menggerakkan roda operasi bahan-bahan kepustakaan hingga dapat diakses para pemakainya. Ini tentu tugas utama dari keberadaan unit kerja, yakni untuk memastikan apa yang ia kelola dapat diakses. Namun, lagi-lagi, keberadaan mesin pencari di gawai dapat menghadirkan unit kerja yang jauh lebih tangkas, cepat, dan dapat diakses 24 jam. Orang-orang tentu akan lebih “dimanjakan” dengan layanan yang luar biasa mudah ini. Namun demikian, dekorporealisasi semacam ini benar-benar berpotensi mereduksi kemanusiaan yang lahir dari komunikasi secara langsung, dan bukan telepresen. Berbagai emosi dapat dibangun dan hadir di sana. Internet tidak menyediakan nuansa (setidaknya secara primer) yang dapat menciptakan afek pada perasaan manusia.
Apabila kita mulai berbicara perpustakaan dengan definisi ketiga yang saya kemukakan, yakni perpustakaan sebagai bahan-bahan pustaka itu sendiri, maka kita akan berbicara mengenai informasi. Namun sebelum lebih jauh, saya hendak memerkuat pandangan ini dengan mengacu pada International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), yang menyatakan bahwa “perpustakaan merupakan kumpulan bahan tercertak dan non-tercertak dan/atau sumber informasi dalam komputer yang tersusun secara sistematis untuk kepentingan pemakai”.
Perpustakaan yang berisi bahan pustaka fisik, dalam pandangan ini, hanyalah merupakan satu bagian dari banyak bagian bahan pustaka. Dapat kita cermati bahwa bahan pustaka tak melulu tercetak, ia ada pula dalam bentuk non-cetak. Artinya, ia dapat berupa data “dalam komputer”.
Dewasa ini, dalam internet, kita dapat membayangkan mesin pencari itu sudah seperti “ruang perpustakaan maya” yang berisi begitu banyak bahan pustaka non-cetak. Kita dapat mengakses begitu banyak informasi. Saking banyaknya informasi di sana, kita nyaris tidak akan kekurangan bahan pustaka—meski tentu tetap akan ada kekurangan karena tidak semua tulisan cetak berkesempatan didigitalisasi.
Apabila dicermati, fakta bahwa ada begitu banyak bahan pustaka di internet mengindikasikan kemungkinan penyaringan yang tidak ketat, apalagi yang ditulis dalam platform yang tanpa filter sama sekali. Koleksi bahan pustaka di internet tentu tidak semuanya memiliki mutu yang tinggi, atau setidaknya memadai, serta “aman”. Penggunaannya pada akhirnya tetap memerlukan unit kerja yang terampil dan, tentu saja, manusiawi—sesuatu yang tidak dapat disediakan oleh unit kerja algoritmis.
Saya kira ulasan ringkas mengenai tiga definisi perpustakaan di atas cukup, tetapi sejauh saya mencermatinya, ketiga definisi itu tidak lebih daripada sekadar preferensi dan/atau instrumen. Ketiganya (bangunan, unit kerja, dan bahan pustaka) ada untuk menunjang sesuatu, yang saya kira dapat kita sepakati sebagai sejenis esensi dari perpustakaan yang melampaui tiga definisi material yang kita ulas sebelumnya.
Esensi inilah yang juga dapat dikatakan sebagai tujuan, sebagai visi, sehingga perpustakaan ada dan (harus) dibangun dan beroperasi. Namun untuk melacak esensi itu, saya hendak menelusuri kembali terminologi dasar dari perpustakaan, yang mudah-mudahan bukan menjadi konstruksi argumen “cocoklogikal” semata.
Dalam kepala saya mengambang suatu dorongan untuk menelusuri istilah perpustakaan, yang hendak saya acu dalam bahasa Inggrisnya. Saya mengandaikan perpustakaan, "library", memiliki kedekatan dengan kata "liberty", yang berarti kebebasan. Dalam bahasa Spanyol sendiri, libro/a memiliki arti buku. Namun bila kita bayangkan hubungan perpustakaan dan kebebasan itu cukup sulit ditangkap secara sederhana apabila konsep perpustakaan yang umum diterima masyarakat adalah sebatas bangunan yang berisi buku. Namun sejauh saya renungkan, ternyata secara esensial perpustakaan yang berisi buku, yang maka dari itu berarti gudang informasi dan/atau ilmu pengetahuan, memiliki kedekatan dengan prinsip enlightment, yang mana dalam sejarah Pencerahan memiliki makna “pembebasan dari zaman kegelapan”, alias suatu zaman di mana ilmu pengetahuan tidak berkembang.
Secara struktural, kita dapat pula melihat bahwa ketidaksetaraan, dominasi, serta alienasi lahir dari kelemahan dalam negosiasi wacana, yang faktor utamanya adalah karena adanya ketimpangan dominasi informasi dan/atau ilmu pengetahuan serta pembebanan makna dalam politik bahasa. Mengutip Francis Bacon, “knowledge is power”, yang maka dari itu, orang-orang tanpa pengetahuan rentan dikuasai, ditindas, diperbudak.
Dari uraian tersebut, saya mengandaikan bahwa perpustakaan, sebagai definisi keempat, merupakan sebuah instrumen emansipasi. Prinsip emansipasi ini secara sederhana dapat dimaknai sebagai pembebasan dari kondisi yang menindas, menguasai, memperbudak. Tentu konsep perbudakan ini bukan seperti “kerja paksa” dan sejenisnya, melainkan, misalnya, perbudakan oleh informasi bias, katankanlah hoax yang mengacaukan toleransi horizontal dan kejernihan membaca realitas, perbudakan dalam keringnya rutinitas hidup, perbudakan dalam kemiskinan struktural, perbudakaan menjadi konsumen sepanjang hayat untuk membeli kebutuhan manipulatif, dan lain-lain. Daftar ini masih dapat diisi sebanyak mungkin. Namun konsep “perbudakan” ini dapat dibincangkan lebih lanjut dalam ruang yang lain.
Apa yang hendak saya katakan adalah, perpustakaan tidak dapat dimaknai sebatas sebuah konstruksi, atau unit kerja, atau bahan pustaka itu sendiri. Ketiga komponen ini sama sekali tidak ada gunanya apabila tadi, pihak yang bertanggung jawab menjalankan fungsi perpustakaan tidak dapat menghubungkannya dengan publik, yang pada gilirannya tidak dapat mengaktualisasikan informasi yang hendak dikomunikasikan.
Pada akhirnya, meskipun ribuan gedung perpustakaan megah dibangun, kualitas institusi pengelola perpustakaan begitu prima, serta bahan-bahan pustaka yang tersedia memiliki mutu yang begitu diperlukan untuk memakmurkan umat manusia, ia tidak memiliki arti apa pun apabila ia tidak dapat memperluas cakrawala berpikir masyarakat yang terhimpit secara struktural maupun oleh kesempitan pikirannya sendiri sehingga tidak dapat menjadi manusia yang merdeka—khususnya dari ketidaktahuan, juga kebodohan. Namun secara teknis, untuk mengupayakan perpustakaan sebagai instrumen emansipasi, maka diperlukan sejenis "tindak lanjut" dari komunikasi masyarakat (pembaca) dan pihak yang bertanggung jawab menjalankan fungsi perpustakaan tersebut—dalam hal ini tentu korespondensi dari pihak lain yang berkaitan diperlukan—yakni pembentukkan ruang publik yang diskursif, dengan catatan tidak terpapar wabah seremonialisme.
Artinya, ketika suatu bahan pustaka telah dikonsumsi, ia perlu untuk dibicarakan ulang, dikaji lebih lanjut, didiskusikan melalui proses interkonektivitas. Artinya, suatu teks yang dipahami satu orang semestinya dikomunikasikan dengan orang lain yang memahami teks yang berbeda, yang maka dari itu memungkinkan munculnya intertekstualitas.
Dari situ kemudian konten bacaan secara perlahan dapat menubuh pada kesadaran kolektif, yang memungkinkan munculnya semacam rekonstruksi pola sosial dan keterbukaan untuk berkorespondensi dalam menangani berbagai problem empiris.
Tentu saja, sebagai penutup, statement akhir saya begitu ambigu serta tidak memberikan saran teknis-operasional yang rinci (karena untuk bagian ini memerlukan diskusi lebih lanjut), tetapi yang saya kehendaki dari tulisan ini, sebagaimana yang sudah saya tulis di pembukaan, adalah sekadar berupaya untuk memberikan semacam tawaran jeda, yang mudah-mudahan reflektif, dalam proses membicang ihwal perpustakaan. Tentunya, tulisan ini mengharapkan respons lain untuk mengelaborasi tema “perpustakaan” yang meletup dan mudah-mudahan tidak segera tenggelam ke palung ingatan yang tak tersentuh cahaya.
(15 September 2022)
Candrika Adhiyasa, menulis puisi, novel, cerita pendek, esai. Meminati filsafat (khususnya eksistensialisme dan fenomenologi) dan cultural studies. Pernah belajar ilmu lingkungan di Universitas Gadjah Mada. Instagram @candrimen. No. Kontak: 0821-2006-6009 (WA)