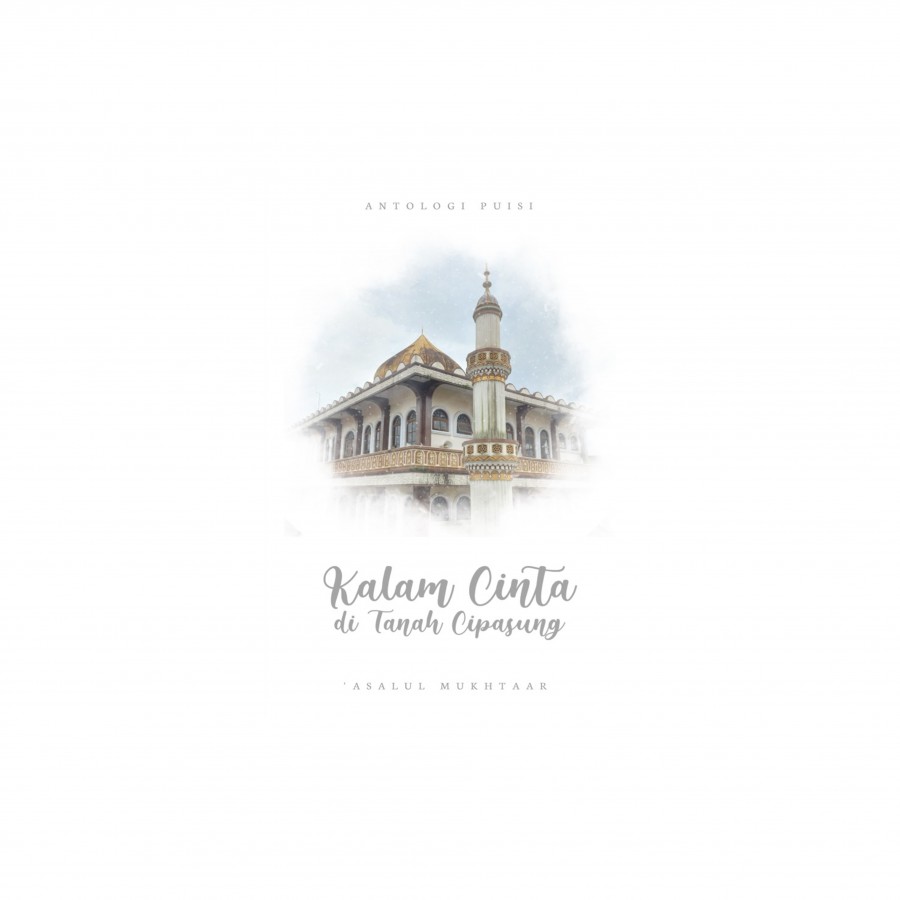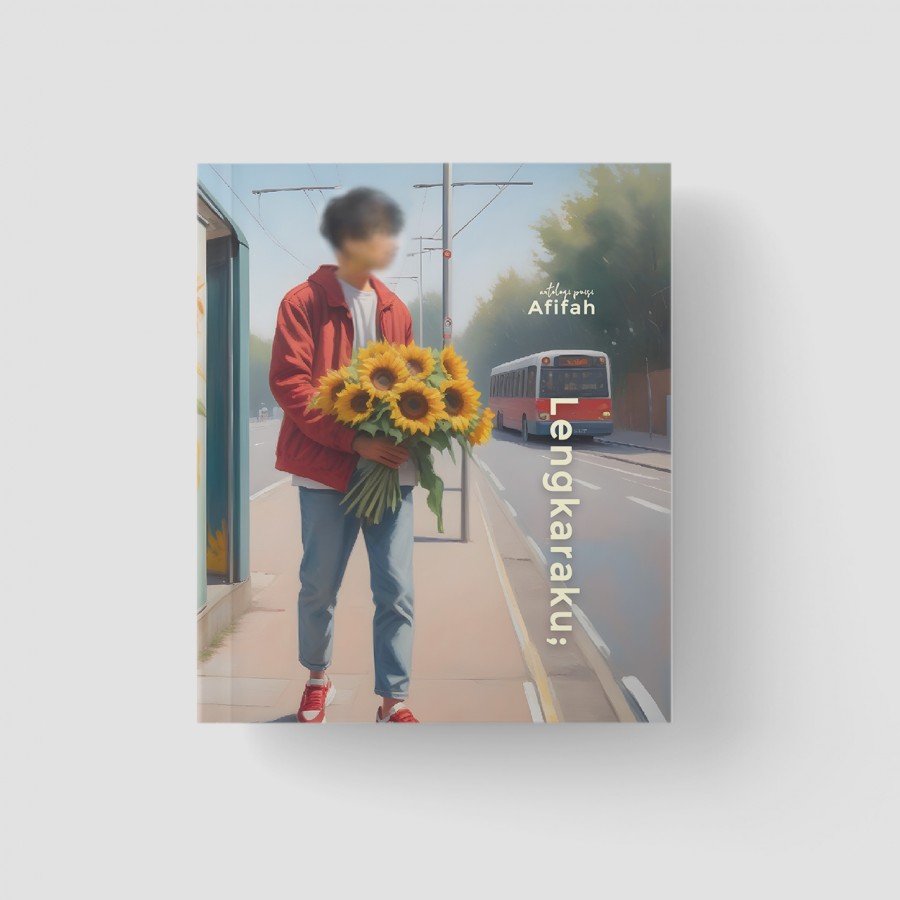Ketika negara Indonesia merdeka bulan Agustus 1945, usaha untuk menentukan cara praktik kultural mewujudkan kebangsaan Indonesia yang ideal telah diupayakan dua puluhan tahun sebelumnya. “Kebudayaan Indonesia” telah menjadi isu perdebatan di kalangan intelektual sejak tahun 1930-an, ketika seniman dan kaum terpelajar yang saat itu dipenuhi ‘deru nasionalis’ tampak menyeruak dalam serangkaian polemik kebudayaan yang tak henti-hentinya mengajukan sifat dan arah kebudayaan nasional melalui tulisan dalam majalah Pujangga Baru.
Perdebatan budaya tahun 1930-an dipicu oleh tulisan Sutan Takdir Alisjahbana mengenai kebudayaan baru, “Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru”, Polemik Kebudayaan. Menurut Takdir, kebudayaan baru perlu memutus tradisi masa lalu yang “feodal” dan “spiritualis” menuju ke arah dengan menitikberatkan pada nilai-nilai Barat yang berpangkal “modernitas”. Persoalan itu dipolarisasi dengan istilah kebudayaan pra-Indonesia dan Indonesia modern. Suatu pernyataan sikap tentang kebebasan kreatif dan universal tentang seni sebab landasan pijaknya adalah individualisme dan Internasionalisme dalam bidang kesenian.
Takdir melalui Mihardja mengatakan, “Saya berkeyakinan, dalam kebudayaan Indonesia sekarang ini akan terdapat sebagian besar elementer Barat, elementer yang dinamis. Dan sekarang ini tiba waktunya kita mengarahkan mata kita ke Barat” Pendapat Takdir itu mendapat tanggapan dari Sanusi Pane dan juga Poerbajaraka. Dari sinilah Lekra meretas jejak asal-usulnya sebagai reaksi terhadap pandangan Sutan Takdir—dan respons terhadap hilangnya semangat revolusioner saat “kesepakatan budaya” antara Indonesia yang baru dengan Belanda sebagai bagian dari Perjanjian Meja Bundar di Den Haag pada bulan November 1949.
Dibentuknya Lekra pada 17 Agustus 1950, yang berdiri sekitar enam bulan setelah terbitnya Surat Kepercayaan Gelanggang. Digagas oleh D.N. Aidit, Njoto, M.S. Ashar, A.S. Dharta. Hal ini kemudian diperkuat oleh tokoh-tokoh lain yang kemudian muncul sebagai Anggota Lekra—seperti yang dikatakan Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan, dalam “Lekra Tak Membakar Buku”, orang-orang seperti Henk Ngantung Sudharnoto, Herman Arjuno, Bakri Siregar, Bujung Saleh, Joebaar Ajoeb, Agam Wispi, Utuy Tatang Sontani, dan lain-lain. Sitor Situmorang dan Pramoedya Ananta Toer termasuk di dalamnya.
Dalam laporan Tempo, “Lekra dan Geger 1965”, awalnya, kata Yahaya Ismail, aktivitas kebudayaan Lekra diwadahi dalam lembaga-lembaga kreatif, yang meliputi lembaga seni rupa, film, sastra, dan seni drama. “Untuk melicinkan perjalanan organisasi, setiap cabang Lekra mempunyai seorang wakil yang duduk dalam pimpinan pusat.” Menurut Amarzan, Joebaar pernah bercerita kepadanya bahwa Lekra didirikan mula-mula sebagai sebuah lembaga semacam LP3ES (Lembaga penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial). Jadi, dia tidak bercabang-cabang, makanya dipilih lembaga.
Lekra dibentuk saat situasi negara yang baru berdiri, ditekan untuk menghadapi kondisi ketegangan perdebatan-perdebatan mengenai identitas kebudayaan yang saat itu sedang panas-panasnya—Lekra mengemukakan untuk bekerja khusus di lapangan kesenian dan kebudayaan, dengan realisme sosialis sebagai dasar kreatif seni dan kesusastraan mereka. Dalam Mukadimah Lekra yang telah direvisi, Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan menambahkan, tugas dan kedudukan Rakyat dipertegas, “Rakyat adalah satu-satunya pencipta kebudayaan, dan bahwa pembangunan kebudayaan Indonesia-baru hanya dapat dilakukan oleh Rakyat. Lekra berpendapat bahwa secara tegas berpihak pada Rakyat, adalah satu-satunya jalan bagi seniman-seniman, sarjana-sarjana maupun pekerja kebudayaan lainnya, untuk mencapai hasil-hasil yang tahan uji dan tahan waktu”. Dengan sikap dan tapisan itulah Lekra mengembangkan daya jangkaunya ke masyarakat luas.
Kebudayaan menurut Lekra, harus berbasis pada kerakyatan. Artinya, kebudayaan dan seni yang dimaksudkan untuk kesetaraan rakyat dan menghilangkan kesan persaingan kelas dalam menciptakan karya seni. Menjadi “kerakyatan” kemudian berarti berbagi komitmen emosional untuk Indonesia yang merdeka dan berdikari, yang terbentuk dari masyarakat secara holistis, termasuk masyarakat petani dan buruh yang berdasarkan keadilan dan melawan kebudayaan anti rakyat dari peninggalan kolonialisme yang mengandung sifat feodal dan imperialis. Tujuan itu dapat diperoleh melalui jalur revolusi.
Dalam slogan-slogan berkeseniannya, Lekra menggunakan konsep 1-5-1. Simbol ini menempatkan politik sebagai panglima sebagai asas dan basis dari lima kombinasi kerja dan turun ke bawah. Politik sebagai komando—yang dalam hal ini dimaksudkan sebagai komando dari partai (PKI), di mana Lekra dan PKI memang memiliki hubungan seperjuangan erat. Di sana ada politik, ideologi, filsafat seni, arah kepemimpinan, serta metode kerja dalam mencipta karya-karya kreatif di bidang kebudayaan. Sekaligus menjadikan realisme sosialis sebagai militansi untuk lebih tegap dalam menegakkan keadilan merata, untuk maju, untuk melawan dan menentang penindasan.
Lekra menjadikan realisme sosialis sebagai landasan penciptaan seni dan sastra. Realisme sosialis diadaptasi dari Sutan Sjahrir pada tahun 1938 seperti yang tertulis pada peringatan 5 tahun Pujangga Baru. Dwi Susanto dalam, “Lekra, Lesbumi, Manifes Kebudayaan: Sejarah Sastra Indonesia Periode 1950-1965” menambahkan, Realisme sosialis sendiri awalnya muncul di Uni Soviet sekitar abad 20. Peristiwa yang melatarbelakangi lahirnya realisme sosialis itu adalah usaha menentang pemerintah dalam peristiwa Minggu Berdarah 22 Januari 1905. Maxim Gorky yang bertugas sebagai pengelola Bolsjewik (Hidup Baru) yang berada dalam kendali Lenin.
Pramoedya Ananta Toer dalam, “Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia” menganggap Lenin sebagai pemantik lebih lanjut api sosialisme yang kekuatan kultural ataupun kesastraan harus bertujuan untuk mendukung perjuangan sosialisme. Maka, kegiatan sastra harus menjadi bagian dari kepentingan umum kaum ploletariat, menjadi roda dan sekrup kesatuan besar mekanisme sosial-demokratik, digerakkan oleh seluruh barisan depan kelas pekerja yang berkesadaran politik. Berdasarkan rumusan itu, Lekra harus mampu mewujudkan nilai-nilai realisme sosialis—sastrawan Lekra harus mengabdi pada rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat atas dasar “seni untuk rakyat” dan menjadikan politik sebagai panglima.
Dalam hal ini, Lekra menolak dengan tegas semboyan l’art pour l’art atau seni untuk seni. Semboyan ini tak lebih merupakan hasil khas masyarakat borjuis-kapitalis yang merasa takut terhadap pengaruh besar yang muncul dari para seniman dalam perjuangan rakyat. Rumusan ini kemudian senada dengan Eka Kurniawan dalam, “Pramoedya Ananta Toer, Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia, Masyarakat borjuis-kapitalis dengan semboyannya itu, bermaksud meletakkan seniman di menara gading yang gemerlap, dan dipisahkan dari masyarakat. Di kemudian hari, semboyan ini lahir dari musuh alaminya Lekra—"Manifes Kebudayaan" dengan Humanisme Universal.
Semboyan dari Manikebu atas “seni untuk seni” ini tidak lain daripada sifatnya yang meng-partikularkan diri dari masyarakat—seolah-olah rakyat seperti buruh dan tani tidak diberikan ruang—bahkan tidak layak berbicara mengenai seni dan sastra. Pram dengan sinis mengatakan bahwa humanisme universal sesungguhnya hanyalah baju baru bagi l’art pour l’art—cita-cita Angkatan 45 sama gagalnya dengan revolusi itu sendiri, yang sama sekali tidak memberikan keadilan sosial dan perubahan menyeluruh bagi rakyat Indonesia—ia tidak mampu melakukan penghayatan-penghayatan baru. Ia macet, karena perkembangan sosial lebih cepat maju.
Dalam pandangan Lekra, kebudayaan bukan hanya tidak bisa dilepaskan dari masyarakat, tapi juga dari politik. Bahkan sesungguhnya kebudayaan merupakan bagian dari politik. Sastra sebagai suatu bidang kebudayaan, karenanya juga bagian dari politik. Ini sejalan dengan pandangan realisme sosialis yang dianut oleh Lu Hsun, bahwa sastra sesungguhnya merupakan alat dari politik. Sastra merupakan bentuk lain dari propaganda.
Pram berpendapat bahwa pembedaan antara sastra sosialis dan sastra realisme sosialis adalah sama perlunya dengan pembedaan antara sosialisme utopis dan sosialisme ilmiah. Karena itu, menurutnya sastra realisme sosialis selamanya punya warna dan amanat politik yang tegas, militan, kentara, tak perlu malu-malu kucing atau sembunyi-sembunyi. Juga merupakan kesatuan integral dengan perjuangan umat manusia dalam menghancurkan penindasan dan pengisapan atas rakyat pekerja, yakni buruh tani, serta menghalau imperialisme dan kolonialisme. Pram mencontohkan Mas Marco Katodikromo sebagai pengarang realisme sosialis pertama dalam khazanah sastra Indonesia.
Sebagai sebuah usaha yang bersifat pergerakan dan revolusioner, kelompok Lekra ini tidak hanya menerbitkan karya sastra sebagai perpanjangan dari ideologinya. Namun, bersinergi dengan melakukan berbagai strategi. Salah satunya mendirikan Yayasan Pembaruan dan Komisi Penerjemahan. Kedua badan ini bertujuan memberikan edukasi dan literasi tentang ajaran Marxisme. Mereka melakukan terjemahan karya-karya sastra asing—sebagai contohnya adalah terjemahan Ibunda dari Maxim Gorky dan Kisah Manusia Sedjati dari Boris Polewoi. Dengan menerbitkan buku-buku itu, Lekra didukung oleh Partai Komunis Indonesia .
Foulcher mengatakan bahwa Lekra dalam puisi-puisinya—yang berhubungan dengan kenyataan sosial di Indonesia sering kali ada nada militansi dan agresi, terutama ketika ekspresinya dipusatkan pada isu nasional tertentu. Contoh yang terkenal adalah “Matinya Seorang Petani” karya Agam Wispi, sebuah puisi yang ditulis pada bulan September 1954 sebagai respons atas kematian akibat penggusuran penghuni liar dari tanah perkebunan milik pemerintah di Sumatera Utara. Puisi ini diperuntukkan menjadi karya klasik Lekra.
Untuk mendukung konsep kesusastraannya, Lekra harus memiliki saluran pendukungnya, dalam bidang publikasi. Melalui organisasi kebudayaan, Lekra membutuhkan satu organ media untuk menginformasikan agar bahan bacaannya dapat terbaca oleh masyarakat. Menurut Dwi Susanto, Media yang condong ke arah PKI ketika itu adalah Harian Rakyat, Zaman Baru, dan Bintang Timur. Harian Rakyat banyak menerbitkan puisi-puisi dari para seniman atau sastrawan intelektual Lekra. Hal serupa juga dilakukan oleh Bintang Timur yang menerbitkan karya-karya dari pengarang yang condong pada Lekra. Bintang Timur memiliki satu rubrik yang bernama Lentera. Setelah Pramoedya keluar dari tahanan dan sejak 16 Maret 1962, ia menjadi redaktur rubrik Lentera.
Lentera kemudian menjadi media utama yang mempublikasikan tulisan-tulisan (baik fiksi maupun esai) Pramoedya. Akan tetapi, yang paling penting, melalui Lentera itu pula Pram memulai polemik-polemiknya yang gencar. Hal ini kemudian menyeret Pram dalam perang kebudayaan (atau prahara budaya) antara Lekra dengan musuh-musuh politiknya—seperti anggota-anggota Manikebu dengan pendirian ‘humanisme universal’. Pada awalnya menurut Eka Kurniawan—polemik berlangsung antara Lentera yang diasuh Pram dengan majalah Sastra yang dipimpin H.B. Jassin. Serangan gencar Pram dan Lentera mulai berlanjut dengan judul Yang Harus dibabat dan Harus Dibangun. Kecaman dan serangan dari Pram ini ditujukan terutama kepada seniman-seniman di majalah Sastra yang merupakan sastrawan-sastrawan “tak berpartai”.
Sikap tak berpartai itu menurut Goenawan Mohamad dalam, “Peristiwa ‘Manikebu’: Kesusastraan Indonesia dan Politik di Tahun 1960-an, antara lain muncul dari kata-kata H.B. Jassin sendiri yang menulis: “Kami tidak masuk partai kiri atau kanan, itu bukan berarti bahwa kami tidak punya pendirian, tapi karena baik partai kiri dan kanan ada kekurangan-kekurangannya yang harus tetap kami hadapi secara kritis.” Pandangan itu, di awal ’60-an, memang bisa dianggap tidak bijaksana, dan akan terjerumus ke dalam tuduhan “anti Manipol”. Pada masa-masa seperti itu, ketika suhu politik merupakan pilihan yang wajar. Karena itu, tidak mengherankan jika muncul banyak Lembaga kebudayaan yang berafiliasi ke partai politik. Seperti halnya, Lekra (PKI), LKN (PNI), Lesbumi (NU) serta lain sebagainya.
Di masa-masa semacam itu, agaknya penolakan Lekra terhadap humanisme universal semakin keras. Di sini harus ditegaskan, bukan berarti Lekra menolak humanisme: yang ditolak Lekra adalah humanisme yang abstrak, yang menamakan dirinya universal. Pram dengan nada tegas mengatakan, Humanisme yang diterima seharusnya humanisme yang konkret dan berpihak pada pekerja, buruh, dan tani. Dengan kata lain, diistilahkan sebagai humanisme proletar.