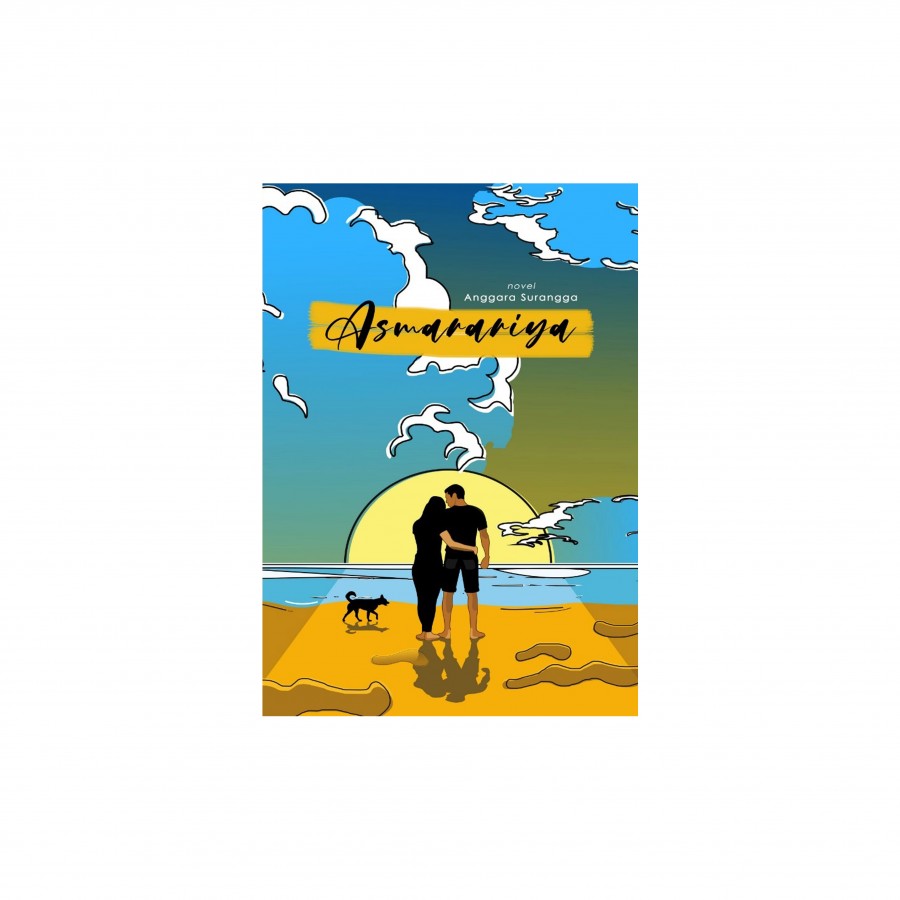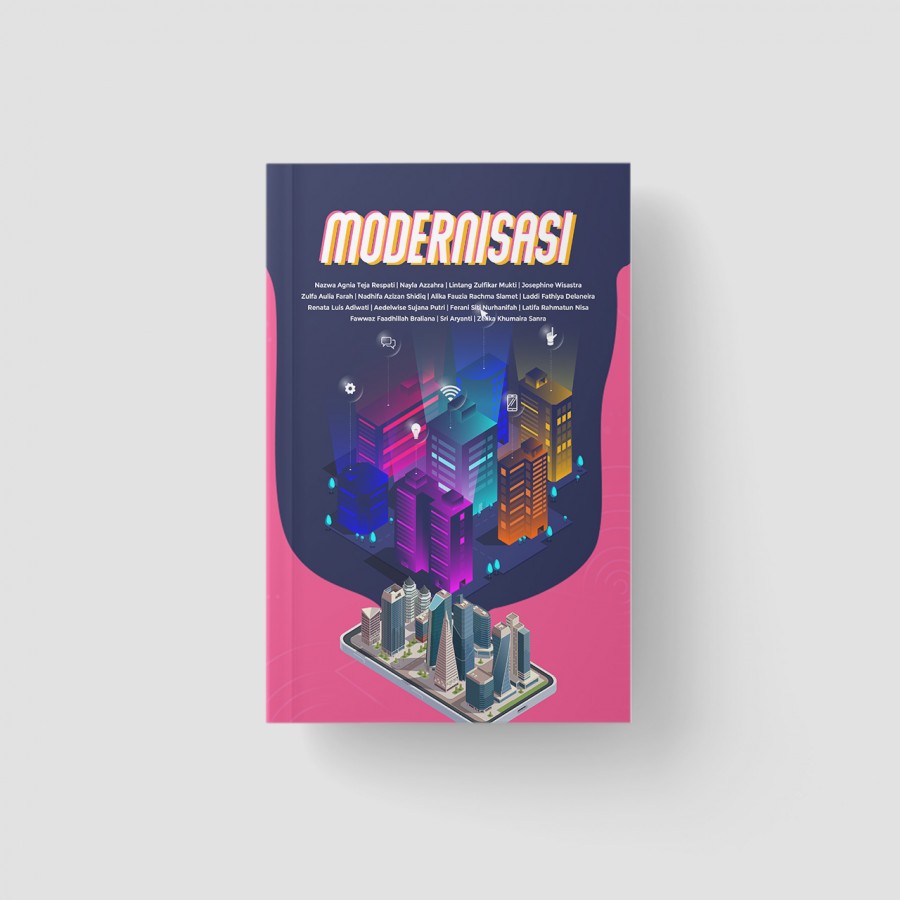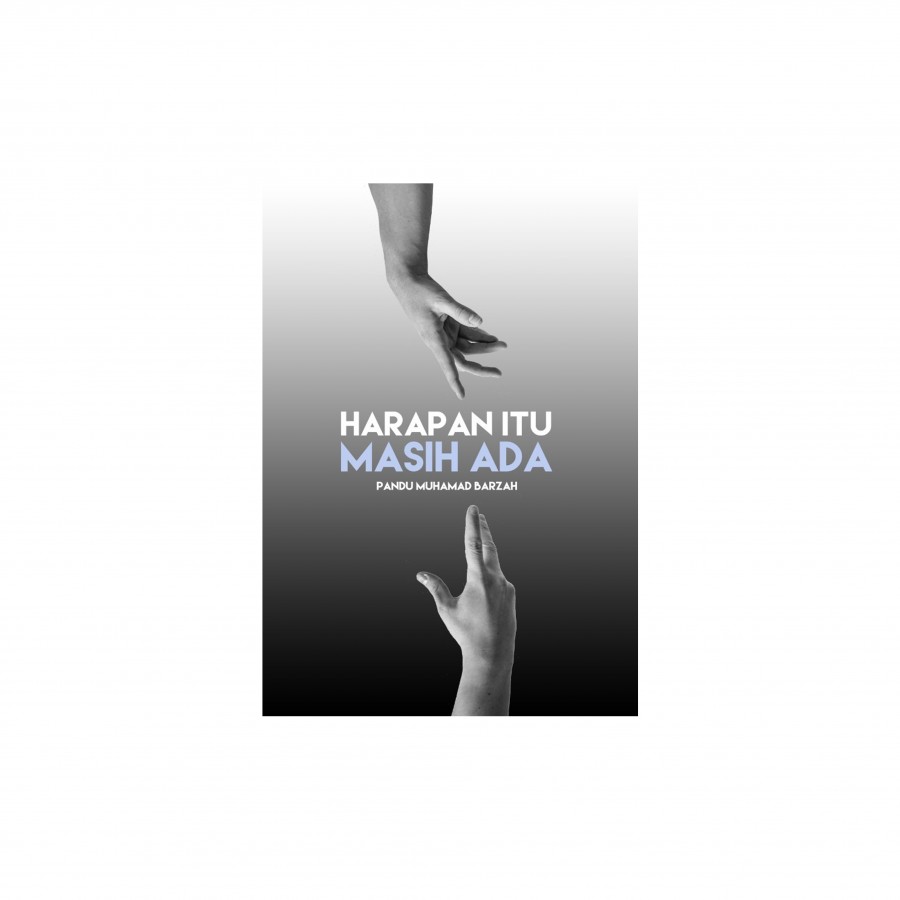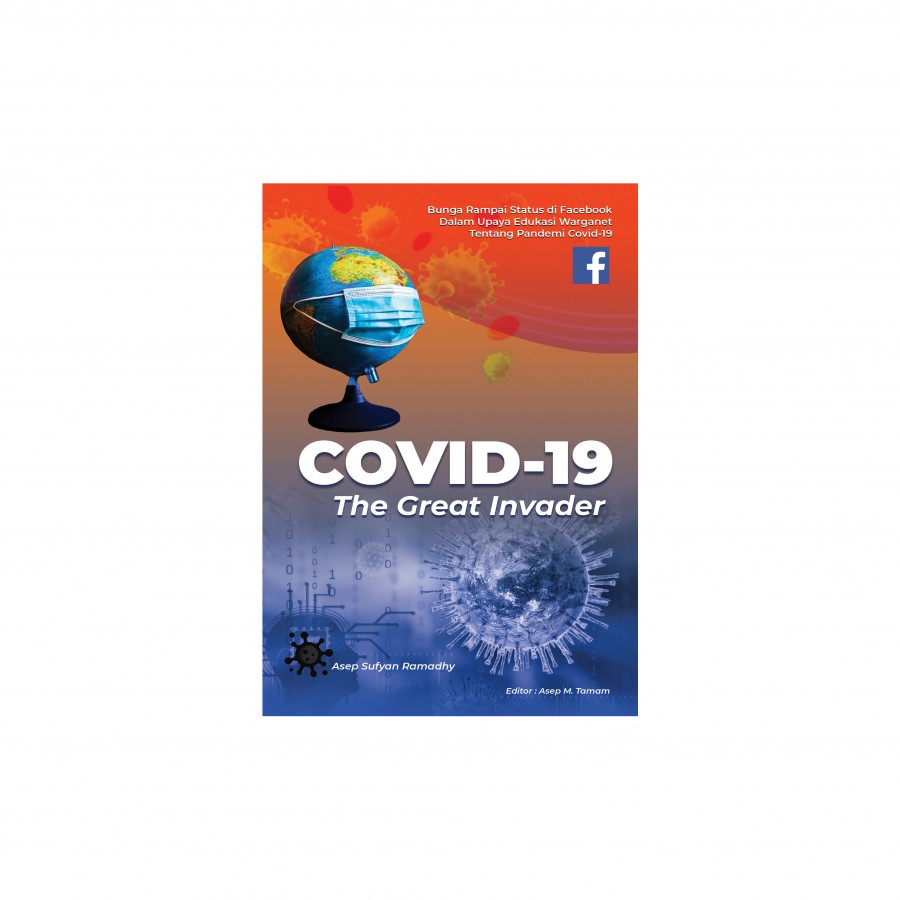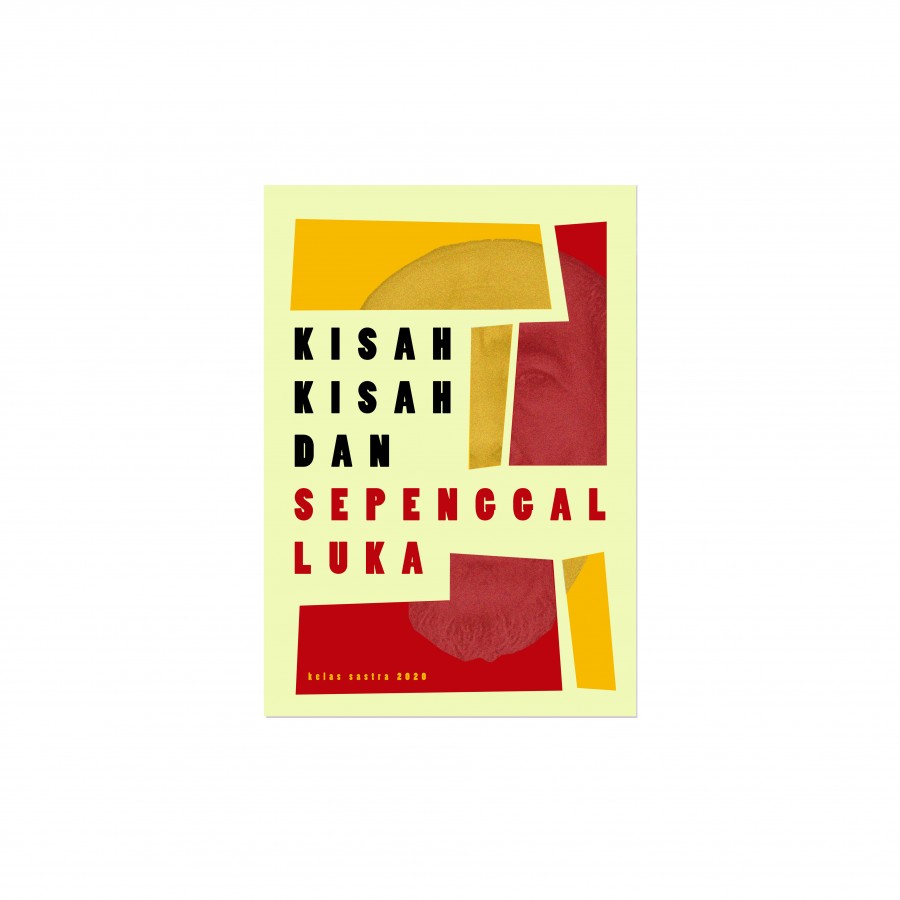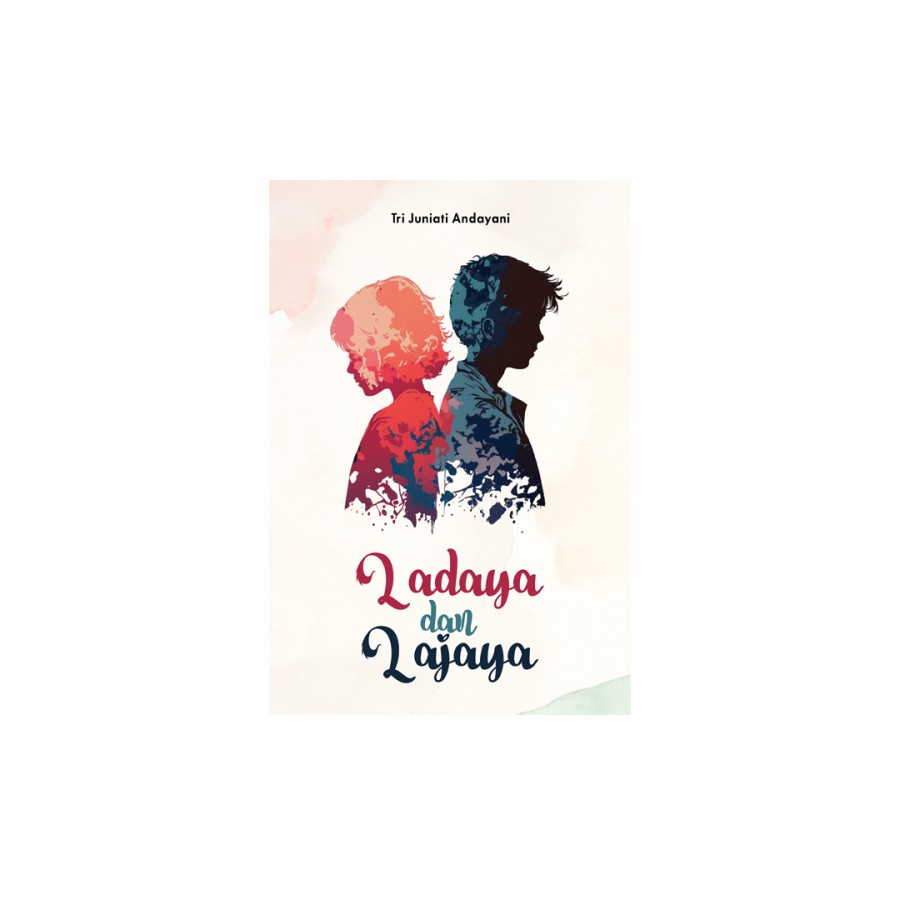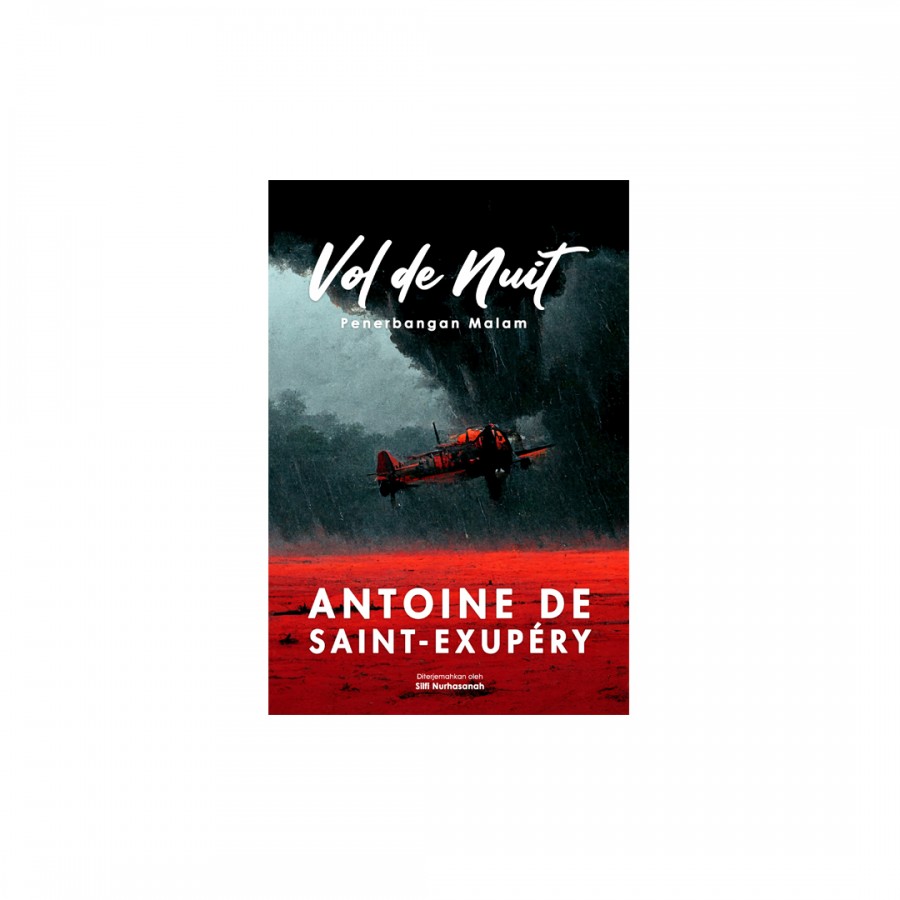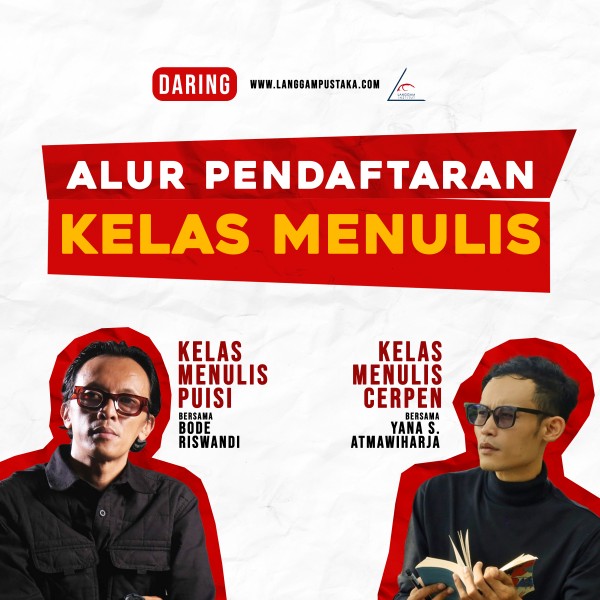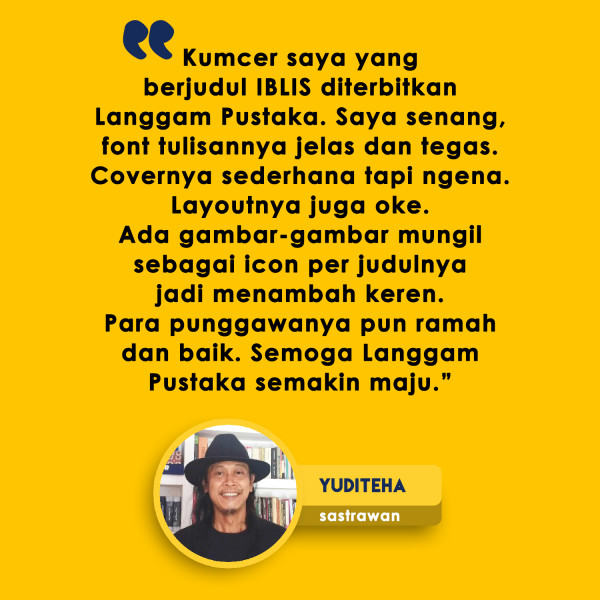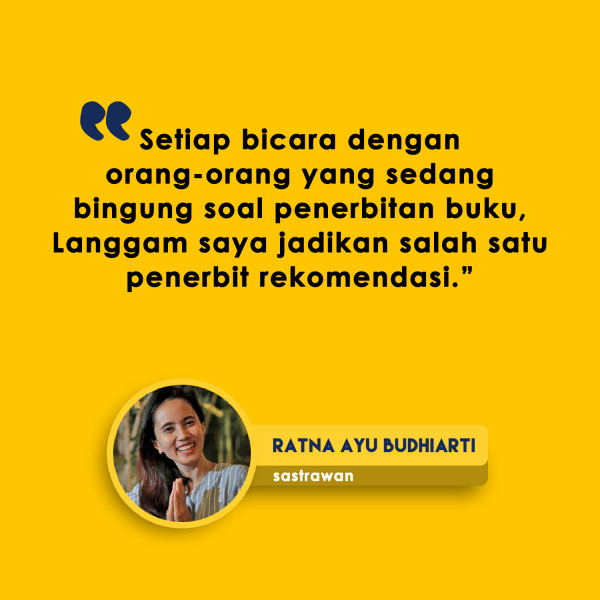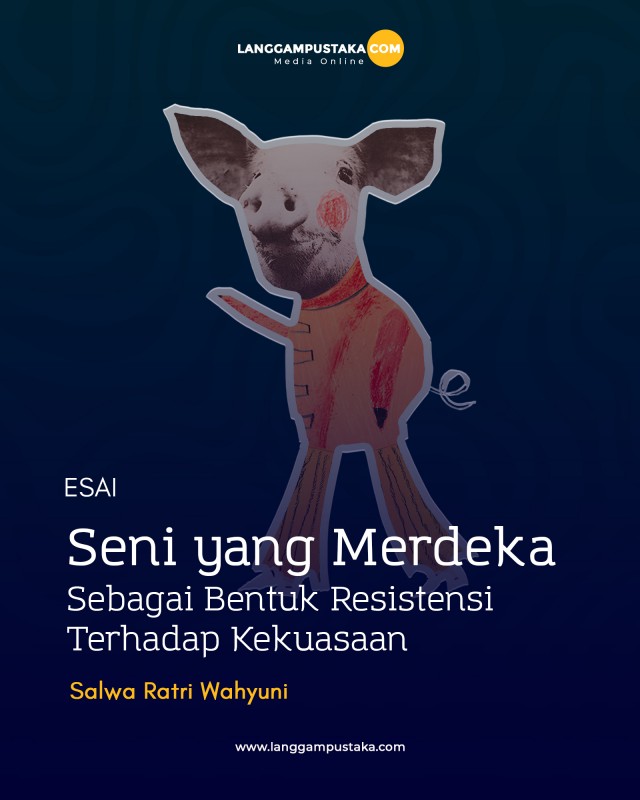
“Seni adalah kebohongan yang membuat kita menyadari kebenaran.”
– Pablo Picasso
SENI sebagai bentuk ekspresi kebebasan terkadang dapat memicu perubahan sosial dan politik. Pada beberapa kasus, karya seni juga kerap dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan dan stabilitas sosial. Katakanlah, seorang pelukis menciptakan lukisan, seorang musisi menulis lagu, dan seorang sutradara teater menyiapkan pementasan. Lantas apa yang menjadikan mereka begitu berbahaya? Mengapa sebuah karya dapat dianggap meresahkan? Tulisan ini akan membahas bagaimana karya seni dapat dianggap sebagai ancaman melalui analisis representasi Stuart Hall.
Seiring dengan perkembangan zaman, seni merupakan bagian dari ruang perlawanan. Pablo Picasso melukis Guernica sebagai protes atas kebrutalan perang saudara Spanyol (1936-1939). W.S Rendra menyuarakan rakyat kecil melalui teaternya. Seni telah menjadi cerminan masyarakat dan kekuasaan yang mengaturnya. Namun, di era rezim baru ini kebebasan dalam berkesenian kembali memunculkan polemik. Fenomena “Neo Orba” muncul sebagai istilah sensor terhadap kebebasan berkesenian dan pembungkaman kritik. Jika merunut ke belakang, kepemimpinan Soeharto merupakan salah satu rezim yang paling ketat dalam mengatur bagaimana seni boleh berkembang. Seniman yang berani menyuarakan kritik kerap berakhir di bui, diasingkan, atau bahkan "menghilang." Kini, setelah lebih dari dua dekade reformasi, situasi serupa kembali terjadi.
Pameran lukisan karya Yos Suprapto dibatalkan, Lukisan Tikus Garuda karya Rokhyat diturunkan, lagu band Sukatani yang berjudul Bayar Bayar Bayar dihapus, dan teater Wawancara dengan Mulyono dibredel. Inilah yang disebut oleh banyak orang sebagai Neo Orba—mirip dengan pola yang terjadi pada era Orde Baru.
Seni bukan sekadar bentuk ekspresi, tetapi juga alat representasi. Dalam kacamata representasi teori, seperti yang dijelaskan oleh Stuart Hall, seni memiliki kekuatan untuk membentuk dan menantang makna yang diterima dalam masyarakat. Representasi dalam seni tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga menciptakan realitas baru yang dapat mengguncang struktur kekuasaan yang sudah mapan. Lebih jelasnya, Menurut Hall (2005: 18-20), representasi adalah kemampuan untuk menggambarkan atau membayangkan. Representasi menjadi penting mengingat budaya selalu dibentuk melalui makna dan bahasa, dalam hal ini, bahasa adalah salah satu wujud simbol atau salah satu bentuk representasi.
Hall (1997: 15) membagi representasi ke dalam tiga bentuk; (1) Representasi reflektif, (2) Representasi intensional, dan (3) Representasi konstruksionis. Representasi reflektif adalah bahasa atau berbagai simbol yang mencerminkan makna. Representasi intensional adalah bagaimana bahasa atau simbol mengejawantahkan maksud pribadi sang penutur. Sementara representasi konstruksionis adalah bagaimana makna dikonstruksi kembali ‘dalam’ dan ‘melalui’ bahasa.
Menurut Stuart Hall, makna tidak pernah bersifat tunggal. Sebuah gambar bisa memiliki makna yang berbeda tergantung pada siapa yang melihatnya. Ketika seniman menggambarkan realitas dengan cara yang berbeda dari versi resmi penguasa, mereka sedang menantang narasi dominan. Mereka menciptakan wacana tandingan yang dapat mengubah cara masyarakat melihat dunia. Dan inilah yang ditakuti oleh penguasa—seni tak hanya menciptakan estetika baru melainkan juga membuka ruang kesadaran baru bagi masyarakat. Bayangkan sebuah lagu bisa membakar semangat perlawanan, maka hegemoni penguasa mulai retak, legitimasi kekuasaan mereka mulai goyah.
Pada Desember 2024, pameran tunggal Yos Suprapto di Galeri Nasional Jakarta menjadi perbincangan panas. Pameran bertajuk "Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan" memuat karya-karya yang mengkritik kondisi sosial dan politik. Lukisan-lukisan seperti "Konoha I dan Konoha II," "Banteng Merah," "Dua Orang Sedang Makan," dan "Raja Sedang Duduk" dianggap bermuatan politik dan vulgar. Akibatnya Yos Suprapto menurunkan tujuh lukisannya pada Senin, 23 Desember 2024. Dan menurunkan tiga puluh lukisan lainnya pada hari berikutnya.
Keputusan ini memicu perdebatan luas tentang kebebasan berekspresi dan batas sensor seni. Dalam perspektif teori representasi, seni tidak hanya berfungsi sebagai refleksi realitas, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk dan menantang makna dominan dalam masyarakat. Ketika negara turun tangan untuk mengontrol makna yang diciptakan oleh seniman, maka yang terjadi bukan sekadar sensor, tetapi upaya hegemonik untuk mengendalikan wacana publik.
Kasus serupa terjadi pada lukisan "Tikus Garuda" karya Rokhyat yang juga mengalami sensor. Lukisan yang semula dipamerkan di ruang pameran Badri Gallery di kota Banjarmasin ini diturunkan karena alasan faktor keamanan. Lukisan ini menampilkan sosok Garuda dengan kepala tikus mengenakan dasi, sementara di bagian ekornya, terlihat buntut tikus yang menggantung di antara kedua kakinya. Cakar Garuda mencengkeram tulang dengan tulisan "aneka tunggal." Karya ini jelas merupakan kritik terhadap kondisi bangsa, khususnya terkait dengan praktik korupsi yang menggerogoti negara. Sebuah refleksi ironis terhadap kondisi bangsa.
Dalam konteks teori representasi, simbol memiliki makna yang terus berubah tergantung pada siapa yang menginterpretasikannya. Pemerintah ingin mempertahankan makna Garuda sebagai simbol nasionalisme yang sakral, sementara seniman melihatnya sebagai media untuk menyampaikan kritik terhadap kondisi negara. Ketika kritik ini dibungkam, itu menunjukkan bahwa penguasa tidak hanya ingin mengontrol politik dan ekonomi, tetapi juga makna dan interpretasi publik.
Tak hanya seni visual, musik pun tak luput dari sensor. Duo punk rock Sukatani dari Purbalingga, Jawa Tengah, merilis lagu "Bayar, Bayar, Bayar" yang mengkritik praktik korupsi dalam institusi kepolisian Indonesia. Liriknya menyoroti isu suap dalam layanan publik seperti pembuatan SIM dan pembebasan tahanan. Lagu ini mendapatkan perhatian luas dan menjadi populer di kalangan mahasiswa yang memprotes kebijakan pemerintah. Namun, pada 20 Februari 2025, Sukatani merilis video permintaan maaf kepada institusi kepolisian dan meminta penggemar untuk menghapus lagu tersebut dari koleksi mereka, memicu perdebatan mengenai kebebasan berekspresi di Indonesia.
Dalam konteks teori representasi Stuart Hall, lagu "Bayar, Bayar, Bayar" dapat dilihat sebagai upaya untuk memproduksi dan menyebarkan makna mengenai korupsi dalam institusi kepolisian melalui medium musik. Menurut Hall, representasi adalah proses di mana makna diproduksi dan dipertukarkan di antara anggota masyarakat menggunakan bahasa atau simbol-simbol lainnya.
Kasus lain juga terjadi pada seni teater. Pada 15 Februari pementasan teater "Wawancara dengan Mulyono" di ISBI Bandung gagal terlaksana. Penyebab hal ini ialah tempat acara yang tidak bisa diakses karena pintunya digembok. Rektor ISBI Bandung, Retno Dwimarwati, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga kondusifitas lingkungan akademik dan mencegah kegiatan yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) serta kepentingan politik praktis di lingkungan kampus.
Dalam perspektif teori representasi Stuart Hall, kasus ini mencerminkan bagaimana makna suatu teks atau karya seni tidak bersifat tetap, melainkan dapat dikonstruksi dan ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai pihak. Rektorat ISBI, sebagai institusi dengan otoritas, memproduksi makna bahwa pementasan ini berbahaya atau bermuatan politis, sehingga perlu dilarang demi menjaga stabilitas kampus. Sementara itu, Teater Payung Hitam dan para pendukungnya memiliki tafsir yang berbeda, melihat pementasan ini sebagai bentuk ekspresi kritis terhadap realitas sosial. Perbedaan interpretasi ini menunjukkan bagaimana representasi suatu karya dapat menjadi arena negosiasi makna, di mana kekuasaan berperan dalam menentukan narasi dominan dan membatasi wacana-wacana alternatif.
Dalam teori representasi Stuart Hall, makna tidak bersifat tetap, melainkan dinegosiasikan oleh berbagai pihak. Negara, dalam hal ini, berusaha menegaskan interpretasi tunggal terhadap sejarah dan perlawanan aktivis dengan melarang karya-karya yang menawarkan perspektif alternatif. Ini merupakan bentuk kontrol atas narasi sejarah agar hanya versi resmi yang tetap hidup dalam benak masyarakat.
Fenomena pembungkaman seni ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang memasuki fase "New Orba" di mana kontrol terhadap ekspresi kembali diperketat, meskipun dibungkus dengan retorika demokrasi. Sensor tidak lagi dilakukan secara terang-terangan seperti di masa Orde Baru, melainkan dengan cara yang lebih halus. Seni seharusnya menjadi ruang bagi kebebasan berekspresi dan refleksi kritis terhadap kondisi sosial. Ketika negara mulai takut pada seni, itu adalah tanda bahwa mereka takut pada suara rakyat.
Salwa Ratri Wahyuni, Lahir di Rengat 14 Juni 2005, saat ini merupakan mahasiswa Sastra Indonesia dan bergiat di Labor Kepenulisan Kreatif FIB UNAND. Penulis dapat disapa melalui akun Instagram @waa.tashi