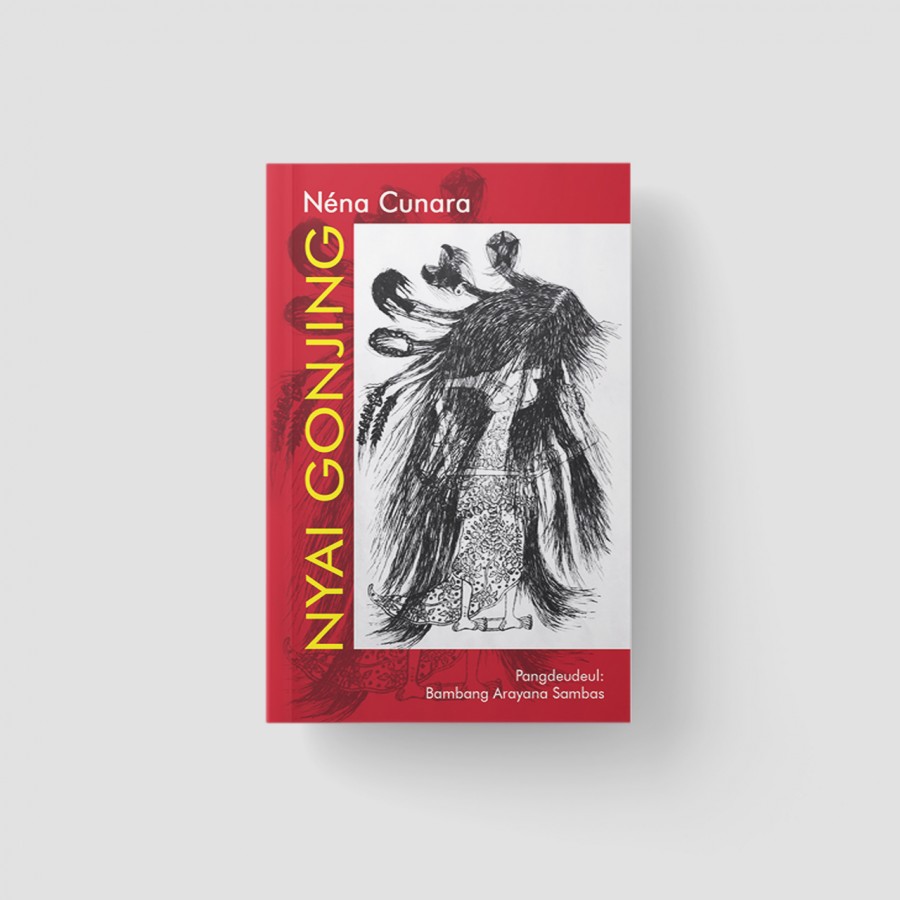Beberapa waktu lalu kita dihadapkan pada pilihan, oposisi, kawan-lawan, atau pihak netral. Demokrasi memang membuat bingung. Ada anak memilih roti, emak memilih masak, bapak memilih bekerja. Memang demokrasi selain juga menemukan kebebasan hak pilih, juga menganjurkan untuk meng “iya” kan memilih. Apalagi menjelang pemilihan pilpres dan perwakilan rakyat. Baliho dipasang di ujung jalan-jalan, disematkan antara pagar tembok sekolah, di internet muncul iklan pilpres kembali. Anak-anak bahkan yang belum cukup umur bisa menentukan pilihan mereka sejak dini, “ini presidenku”. Semakin tampak nyata demokrasi dari sejak dini.
Demokrasi adalah jalan manusia menentukan suatu pilihan, bekerja-atau berada dalam zona nyaman. Manusia berpikir dengan segala oportunisnya, zaman reformasi masih terus didengungkan. Memang apa yang akan kita reformasi? Pembangunan, ideologi, Pancasila, atau mungkin reformasi nasib yang kian hari makin parah dan terpuruk. Jika kita tarik kembali zaman Lincoln berkuasa, presiden yang tak muluk-muluk janji dan berpidato, tapi menggaungkan suara demokrasi sebagai tameng, lalu dipilih oleh rakyat kulit hitam maupun ras kulit putih. Kulit putih memang sudah menghegemoni Amerika secara budaya dan politik. Melalui media-media sosial, lagu pop, buku, majalah, ras kulit putih memang berdominasi dalam hegemoni kebudayaan.
Akan tetapi Lincoln meretakkan semua itu dengan menyatukan ras putih-ras hitam, bagi Lincoln, manusia tidak dipandang melalui ras tapi melalui persamaan hak asasi. Demokrasi adalah sosialis-humanisme yang mengakar kuat pada setiap bangsa, secara universal. Baik secara otonom, sosialis-humanisme adalah jalan menghargai nyawa seseorang. Perbudakan mesti dihapuskan. Seperti penderitaan ras hitam Amerika yang diperbudak ras putih selama bertahun-tahun. Jepang yang memperbudak ras pribumi selama 3,5 tahun.
Sosialis-humanis kian kali dihadapkan pada perdebatan sengit. Antara gimmick atau ngaco itu sudah jadi hal biasa. Bukan berarti kita harus terhanyut dalam gelombang zaman edan. Seperti yang dikatakan Ronggowarsito, “manungso zaman akhir, yen ra edan ra melu keduman”. Manusia zaman akhir kalau tidak ikut gila (politik maupun trend) ya pasti tidak kebahagiaan. Perkataan pujangga Surakarta ini di dukung dengan ucapan masyarakat yang sekan mengiyakan hadirnya zaman edan, “wong edan kui bebas”. Orang gila itu bebas sekehendak maunya, mau berbuat apa-apa. Apalagi kalau didukung kekuatan militer dan senjata. Pasti semakin tambah edan, karena tidak ada lawan ketika berhadapan dengan moncong senjata. Pasti ujung dari musuh militer adalah maut.
Saat zaman Jaya Baya, raja dari kediri itu sudah meramakan, “pasar ilang ramene, kali ilang kedunge”. Pasar hilang keramaiannya, diganti dengan pasar kapitalis di mal-mal yang serba mewah dan jauh dari kata jorok. Sungai hilang arah, arah dalam arti kita sendiri manusia sudah hilang kendali diri, “adigang-adigung”, kepada jabatan dan kepada rakyat. Rakyat seakan hanya “merem-melek” menyaksikan zaman berubah dan berganti. Dihiasi dengan pesta-pesta demokrasi yang sebenarnya merugikan ekonomi “rakyat cilik”.
Sosialis yang dihadapkan Bung Karno pada kita adalah sosialis gotong-royong. Orang saling bahu-membahu membantu pembangunan, menyokong meratanya pendidikan. Walaupun masih banyak anak tidak mendapatkan akses pendidikan. Masih terbelakangnya pendidikan di desa-desa terpencil. Jika kembali ke unit desa, maka gotong-royong adalah tradisi setahun sekali tiap musim panen, pesta rakyat di mana rakyat saling membersihkan got, menyapu jalan, memperbaiki gapura, bagi-bagi hasil panen. Seakan telah lupa bahwa banyak dari anak mereka belum mendapatkan pendidikan. Jalan pengetahuan masih sempit dan terkonyong-konyong masuk dalam lumbung padi semata.
Pesta demokrasi di Indonesia memang “edan”, siapa yang punya banyak duit dia punya kuasa. Pemilihan dewan perwakilan rakyat diharuskan bermodalkan uang minimal satu milyar. Jual tanah, jual mobil, “asset” berharga sekalian, lalu tiap kepala rumah dikasih tiga puluh ribu. Rakyat seakan tersugesti, yang uangnya banyak, pasti peduli pada rakyat, walaupun dipenuhi pencitraan dan program kerja yang ngawur. Kita memang humanis, tapi humanis ngawur, kita memang sosialis, tapi sosialis rendahan.
Seperti ueforia nonton timnas main piala Asia, suara dukungan berjuta rakyat mengaum bersatu memenuhi stadion, tapi setelah satu setengah jam selesai, mereka kembali ke jalan individual. Persatuan dan kesatuan hanya satu setengah jam berlangsung, keadilan sosial hanya saat usai puasa selama sebulan. Kemanakah sosialis-humanis?
Muhammad Lutfi, menyelesaikan S1 Sastra Indonesia di UNS, menyelesaikan S2 Pendidikan Bahasa Indonesia di UNNES. Bergiat dalam GMDI dan Rumput Sastra. Buku yang ditulis dan diterbitkannya: ASUH, ELEGI, LORONG, PELAUT, BERLAYAR, TAKA, SENJA, BUNGA DALAM AIR.