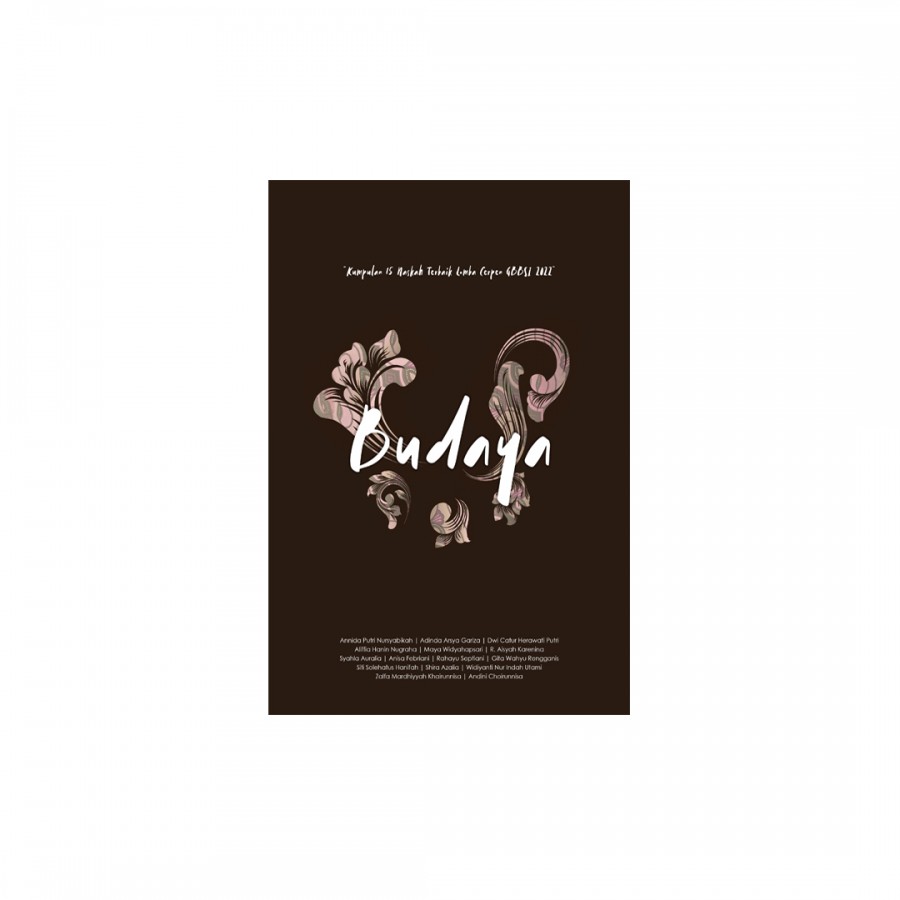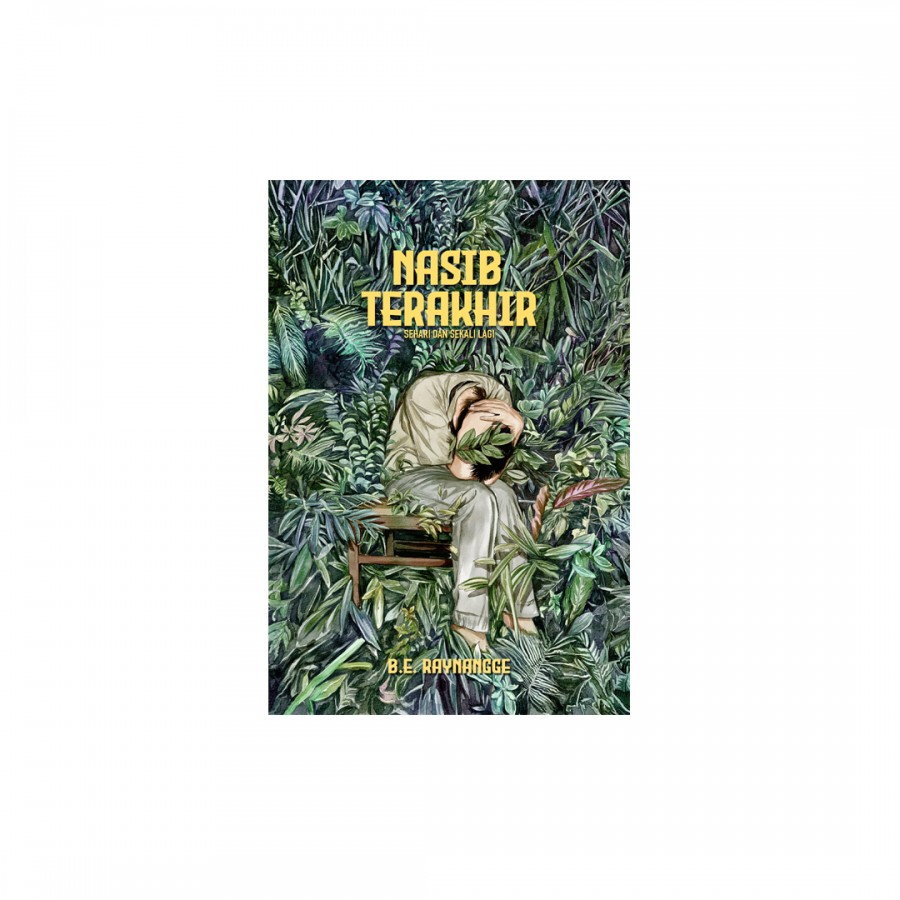Film berjudul Vina: Sebelum 7 Hari garapan sutradara Anggy Umbara dan rumah produksi Dee Company yang sebelumnya dijadwalkan naik layar pada tanggal 9 Mei 2024 akhirnya tayang sehari lebih cepat, yakni tanggal 8 Mei 2024 di seluruh jaringan bioskop Indonesia. Film ini diangkat dari kisah nyata, yakni tragedi pembunuhan terhadap dua orang remaja bernama Vina Dewi Arsita dan Eky Rudiana asal Cirebon pada tahun 2016 silam. Vina dan Eky merupakan sepasang kekasih yang meninggal akibat kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok geng motor. Pedihnya, 11 anggota geng motor ini juga melakukan aksi biadabnya dengan memerkosa Vina secara bergilir, sebelum akhirnya membunuh dua remaja tersebut.
Dari kabar yang beredar luas kala itu, 16 hari pasca dimakamkan, arwah Vina diberitakan memasuki tubuh seorang sahabatnya yang bernama Linda dan menceritakan seluruh kronologi kejadian mengenaskan yang membuat ia dan kekasihnya harus meninggal dunia. Singkat cerita, dari kejadian itulah misteri kematian Vina dan Eky perlahan terkuak hingga ditetapkanlah 11 anggota geng motor tersebut menjadi tersangka.
8 tahun semenjak tragedi memilukan itu terjadi, Film berjudul Vina: Sebelum 7 Hari resmi tayang di layar bioskop tanah air. Dalam tiga hari penayangan sampai tanggal 10 Mei, film ini sudah meraup sebanyak 1.194.268 penonton. Tentu bukan capaian yang main-main. Pasalnya, terhitung hingga awal bulan Mei 2024, baru ada enam film Indonesia yang mampu mencatatkan diri sebagai film peraih lebih dari 1 juta penonton. Jadi, film berjudul Vina: Sebelum 7 Hari resmi menjadi film ke-tujuh yang meraih lebih dari 1 juta penonton. Namun, sedikit ada yang mengganjal rasanya jika menengok kembali bagaimana latar belakang kisah nyata di dalam film ini jika harus disandingkan dengan keberhasilan dan capaian besar filmnya.
Satu pertanyaan besar dalam konteks tayangnya film berjudul Vina: Sebelum 7 Hari ini adalah sejauh mana film yang mengangkat kisah nyata terkait praktik kekerasan dapat dibatasi dan dapat diterima. Di luar lingkup film sebagai karya sinema dan karya visual, aspek norma dan empati seharusnya merupakan benteng awal untuk pembatasan produksi film yang diangkat dari kisah nyata, dari mana pun sudut pandangnya diambil.
Jawaban atas pertanyaan di atas tentu akan mengarah kepada diskusi yang penting tentang etika dan tanggung jawab dalam penggambaran kekerasan –terhadap perempuan— dalam film yang didasarkan pada kisah nyata. Meskipun film memiliki kebebasan artistik untuk mengangkat berbagai tema, termasuk kekerasan terhadap perempuan, ada beberapa pertimbangan penting yang harus diperhatikan. Saya menimbang beberapa arah diskusi atas pertanyaan di atas dengan objektif dan berusaha lugas.
Pertama, film yang mengangkat kisah nyata tentang kekerasan –baik terhadap perempuan maupun laki-laki— harus bertumpu pula pada pemahaman sensitif terhadap pengalaman korban. Ini termasuk memahami dampak emosional, fisik, dan psikologis dari kekerasan tersebut. Ketika atribut kisah nyata ini dipindahalihkan ke dalam film, maka jelas dari sudut pandang mana film akan berbicara dan menentukan keberpihakannya secara konkret. Dengan bertumpu pada ini, maka bias di dalam film akan terhindarkan.
Kedua, penting untuk menghormati privasi dan keamanan korban. Film harus menghindari mengidentifikasi secara langsung korban kekerasan, kecuali jika ada izin dan dukungan yang jelas dari korban atau keluarga mereka. Dalam konteks kasus Vina, dua korban yang meninggal dunia diidentifikasi secara langsung di dalam film, walaupun pihak rumah produksi dan sutradara menyatakan telah mendapat persetujuan dari pihak keluarga untuk mengangkat kembali kisah anggota keluarganya ke dalam film layar lebar. Hal ini akan kembali mengerucut pada pertanyaan dan diskusi lain, yakni apakah keluarga korban memiliki kapasitas pengetahuan untuk menimbang baik buruk dan akibat dari tayangnya film ini secara lebih luas?
Ketiga, dalam pernyataannya beberapa waktu lalu, Anggy Umbara selaku sutradara film berjudul Vina: Sebelum 7 Hari menjelaskan bahwa tujuannya mengangkat kembali kisah tragis ini tak lain tak bukan adalah sebagai upaya menuntaskan kasus kekerasan ini. “Ya kita kan kisah nyatanya seperti itu, kita dari true story dan menurut saya film ini penting untuk diangkat lagi, kasusnya diusut lagi, karena memang belum selesai.” Tegasnya dalam salah satu kesempatan kepada awak media. Hal tersebut berkenaan dengan fakta bahwa film yang mengangkat kisah nyata tentang kekerasan harus memiliki tujuan yang jelas untuk mendidik penonton tentang masalah ini dan meningkatkan kesadaran tentang dampaknya dalam masyarakat. Namun lagi-lagi, frasa mendidik penonton akan menimbulkan bias lain. Sederhananya, bukankah fakta bahwa kasus kematian Vina adalah salah satu kasus viral di tahun 2016 menjadi latar belakang diproduksinya film ini. Bagi industri, Viral adalah cuan yang diembel-embeli empati dan edukasi bagi penonton. Tentu bukan hanya saya yang mengarah ke hal tersebut, bukan? Bicara Industri, maka kita akan menemukan fakta tentang kekuatan kapital yang bermain dua kaki di sana. Saya akan bahas setelah ini.
Keempat, film yang memutuskan untuk bercerita dengan dalih keadilan harus memberikan ruang untuk menggambarkan perjuangan korban kekerasan, serta upaya untuk memperjuangkan keadilan dan pemulihan. Ini bisa menjadi sumber inspirasi dan pemberdayaan bagi mereka yang mengalami kekerasan serupa. Hasil konkret dari upaya untuk memperjuangkan keadilan dan pemulihan bukan semata terletak pada komentar penonton selepas keluar dari bioskop, melainkan lahirnya Raising Awarness bagi masyarakat supaya benar-benar menjauhi tindakan kekerasan. Namun, apakah film Vina: Sebelum 7 Hari dan Anggy Umbara benar-benar konsen terhadap upaya peningkatan kesadaran atau hanya mengeksploitasi kisah tragis dari Vina? Pada akhirnya, film yang mengangkat kisah nyata tentang kekerasan harus bertanggung jawab secara moral dan etis. Mereka memiliki potensi besar untuk memengaruhi persepsi masyarakat tentang masalah ini, sehingga harus dihadapi dengan sensitivitas dan kehati-hatian yang tinggi.
Jika kembali ke belakang, satu fakta yang cukup mencuri perhatian adalah bahwa pengungkapan kasus kematian Vina dan Eky justru dibongkar secara kronologis oleh arwah Vina sendiri yang diceritakan merasuki tubuh sahabatnya bernama Linda. Sejak kejadian kerasukan tersebut, pengusutan kasus ini semakin viral dan dikonsumsi khalayak ramai. Dalam konteks film, film horor di Indonesia telah menjadi subjek penelitian yang menarik bagi para akademisi dan peneliti, terutama karena film horor memiliki pengaruh yang signifikan dalam budaya populer dan industri perfilman Indonesia. Terlebih, film-film horor Indonesia sedikit banyaknya dialih wahanakan dari budaya urban legend yang melekat dalam kepercayaan masyarakat Indonesia, termasuk praktik kerasukan itu sendiri.
Kedekatan masyarakat Indonesia dengan kejadian kerasukannya sahabat Vina tersebut diamini dan disambut baik oleh industri film horor. Selain tak perlu mengonstruksi ide baru, modal besar telah mereka dapat dengan cuma-cuma, viral. Seperti yang telah saya singgung di atas, dalam kacamata industri, viral adalah jaminan cuan yang diembel-embeli empati dan edukasi bagi penonton. Sekadar mengunjungi keluarga korban dan ziarah ke makam korban bukanlah bentuk nyata dari keberpihakan industri film horor atas tanggung jawab Raising Awarness, apalagi upaya untuk memperjuangkan keadilan. Jauh panggang dari api.
Kabar terbaru menyebutkan, bahwa untuk menaikkan Film Vina: Sebelum 7 Hari di layar lebar, bioskop terpaksa harus menggeser beberapa film dengan genre lain yang kalah pamor. Hal ini secara tegas menyatakan bahwa Lingkaran industri melekat dan bergantung pada kekuatan kapital. Di banyak negara, termasuk Indonesia, industri bioskop didominasi oleh beberapa rantai bioskop besar yang dimiliki oleh perusahaan besar. Rantai-rantai bioskop ini memiliki kontrol yang signifikan atas distribusi film dan jaringan bioskop di berbagai kota besar, yang memberi mereka keunggulan kompetitif dalam industri. Selain itu, Beberapa perusahaan besar yang mengoperasikan rantai bioskop juga memiliki studio produksi film sendiri atau memiliki hubungan yang erat dengan studio produksi. Hal ini memberi mereka kontrol atas konten film yang diputar di bioskop dan memungkinkan mereka untuk mempengaruhi arah industri film secara keseluruhan.
Distributor film besar sering memiliki hubungan yang erat dengan rantai bioskop besar, yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan distribusi film dan menentukan film mana yang akan diputar di bioskop mana. Hal ini memberi kekuatan kapital kontrol atas akses penonton terhadap berbagai jenis film. Dalam kaitannya dengan Film Vina: Sebelum 7 Hari garapan rumah produksi Dee Company, coba saja periksa bagaimana profil Dee Company selaku rumah produksi yang dimiliki oleh Dheeraj Kalwani ini dan bagaimana mondar mandirnya nama Anggy Umbara yang keluar masuk bioskop satu tahun terakhir ini.
Sampai hari ini, saya masih belum memutuskan apakah akan pergi ke bioskop untuk menonton film Vina: Sebelum 7 Hari ini atau bersikap sebagai orang yang berkomitmen terhadap norma dan empati dalam sebuah karya film.
Agus Salim Maolana