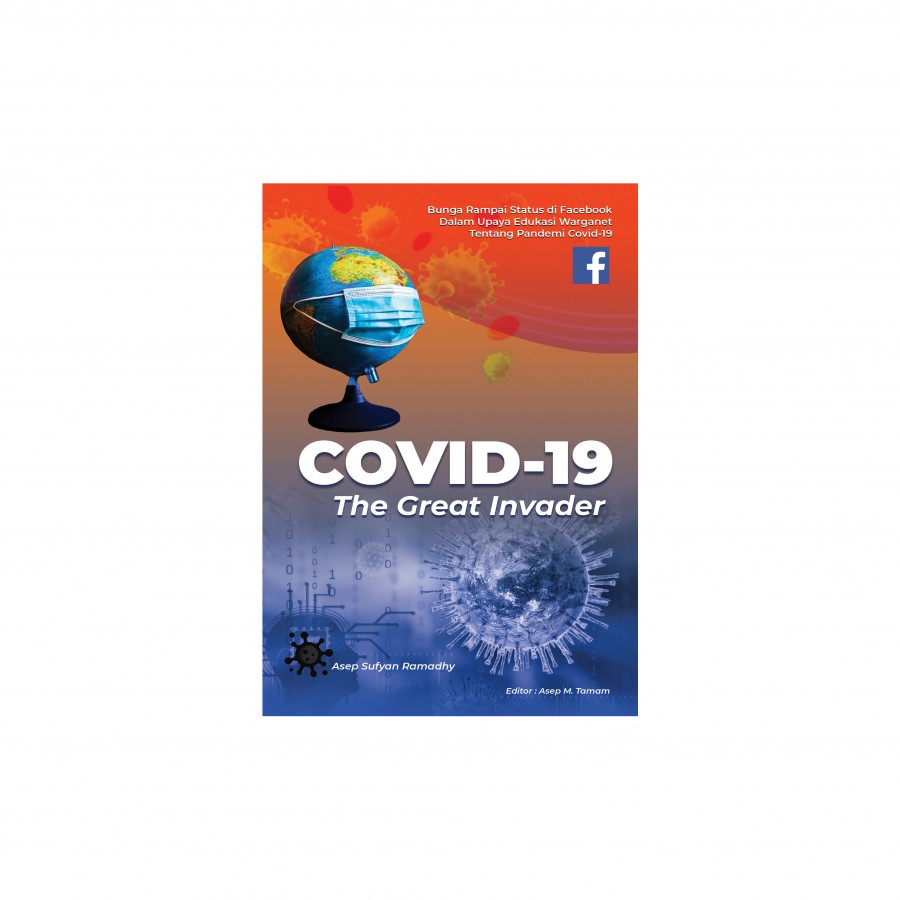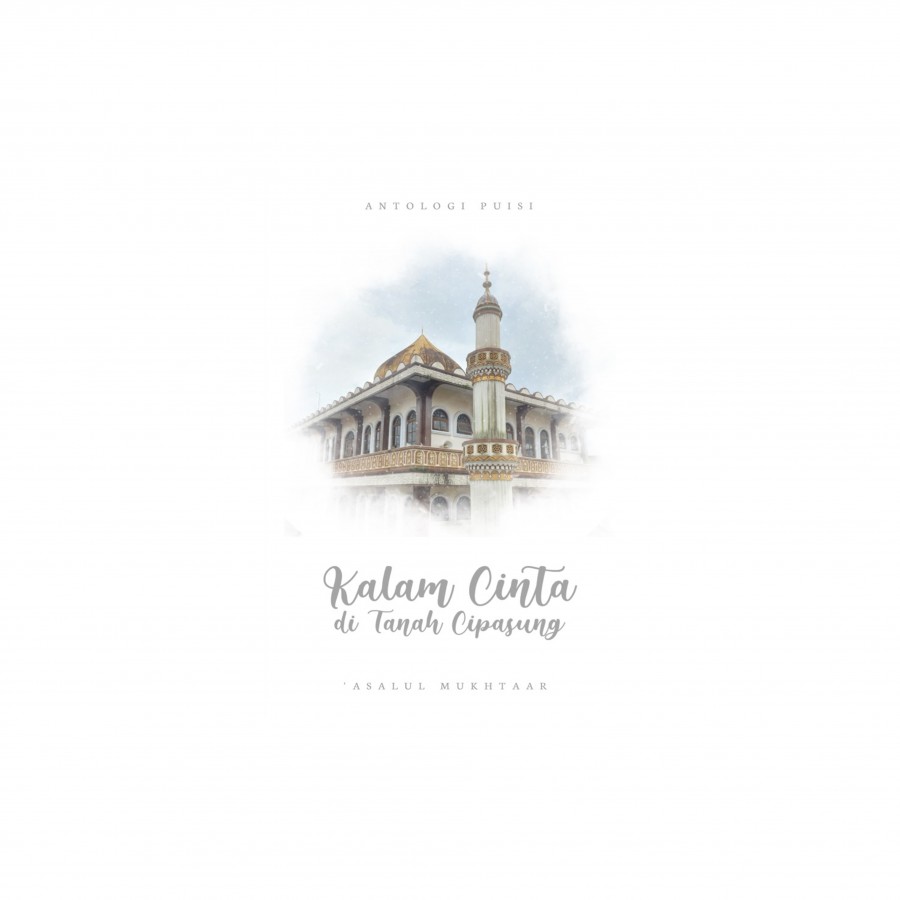.jpg)
Kain Sekolah Abang
Kata tetangga,
Dua tahun kurang, bukan jarak ideal perbedaan usia
Belum lagi menyentuh balita, abang sudah disusul tiga adiknya
Ibu menaruh hormat pada tiap kata yang diumpat
Memikul lara di tiap-tiap kaca etalase kedai lontong kami
Sementara Bapak masih menanti dengan berbagai harap; dipanggil kerja angkat oleh orang pasar
Abang mulai meninggalkan balita,
Menangis-nangis meminta disekolahkan seperti yang seusianya
Sementara, jasa tukang angkat sudah tidak lagi larat
Tangis Abang memecah, terdengar hingga kampung sebelah
Uni Sati, toke sawit kampung kami
Datang berbondong-bonding dengan kain sekolah kanak-kanak yang pudar warna
Kepunyaan sulungnya lima tahun lalu
Sebagai bukti membalas iba, kepada Bapak yang sering dipanggil kerja
Kain Sekolah Abang (2)
Bapak senang bukan kepalang
Abang bisa disekolahkan juga minggu depan
Tapi, setelah sehari sekolah, Abang bilang:
“mengapa baju abang tidak sama warnanya dengan yang lain?”
Bapak hanya membalas senyum menelan ludah,
Bapak tidak bisa bersandiwara pada anak sulungnya:
Orang suruhan hanya berhak berpakaian lusuh-lusuh
Katanya, memang begitu kodrat etika.
Di tahun kemudian,
Kain sekolah Abang yang lusuh sampai juga pada gadis kecil
Berkali-kali kucoba layangkan gugatan kepada Ibu
“Ini bukan baju perempuan, ini baju laki-laki”
Kata Ibu “tidak apa-apa, pakai saja dulu selama menunggu Bapakmu ada uang”
Namun, hingga menuntaskan pendidikan pertama, uang bapak belum juga tampak hilalnya.
Wanita Perayu Tuhan
Sudah berkali-kali busur pahit menyucuk setiap hela nafas,
Wanita paruh baya terengah-engah antara duka dan sengsara
Nasihat Bapaknya kian kemari agar jangan pernah mengemis iba,
Selain dalam tiap-tiap kepulan doa saja
Wanita paruh baya tengah mengadu pada Tuhannya,
Perkara tungku api di dapur yang tak lagi berasap
Perkara ternak ayam yang mati sia-sia digulat ular sawah
Perkara ladang warisan yang sudah tiga tahun enggan berbuah
Wanita paruh baya sedang merapal doa-doa
Doa kesembuhan,
keselamatan,
kebahagiaan
Kemudian menyisipkannya sedikit dalam ruang sunyi dan kertas kosong
Katanya, doa-doa untuk anaknya suatu masa
Sebab yang ia tau, orang tak berpunya tidak berhak menulis wasiat pusaka
Sebab kata Bapaknya, orang tak berpunya tak berhak menuliskan apa-apa selain doa
Dari Gerbong ke Gerbong
Di gerbong pertama
Wanita tua dengan garis keriput merias wajah dengan segala do’a
Merampungkannya dalam kepulan tangan berakar,
Lalu mengikatnya erat pada pundak gadis lusuh berbaju kumuh
Di gerbong kedua, bangku baris kanan
Lelaki berpakaian bagus dengan jas kulit menyilau
Saling mencontek pada do’a yang sama
Hanya saja bedanya, dititipkan pada pundak gadis frustasi yang dibekali properti
Antara deru kereta, gerbang satu dan dua serta pemisahnya
Kedua gadis saling terikat garis
Pasal rautan sengsara yang tragis
Antara deru kereta, gerbong satu dan dua serta pemisahnya
Kedua gadis saling beradu tangis
Pasal talian nasib yang bengis
Perkara
Anangkara sudah bicara pada Pandu laksana
Perkara Milara, gadis yang meminta agar segala janji dipaksa
Anangkara murka
Pandu laksana bungkam saja, sebab Milara anak seorang datuk berpunya.
Anangkara sudah bicara pada Pandu laksana
Perkara Sati si gadis bisu yang pincang adat dan tak berbudaya
Anangkara tak dapat murka
Sebab, Pandu laksana sudah bicara
bahwa Sati memang gadis yang lahir dengan kebiadaban adat nenek moyangnya
Anangkara sudah bicara pada Pandu laksana
Perkara dayang-dayang nan menggerinda tiap sudut tanah pusaka
Anangkara hanya menjawab dengan sujud pada Tuhannya.
Katanya, perkara pusaka kita diberi kuasa.
Rosidatul arifah, Mahasiswi aktif Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Bergiat di Labor Penulisan Kreatif LPK FIB Unand. Beberapa tulisannya telah dimuat dalam surat kabar dan platform digital seputar sastra daan kebudayaan. Akun media sosial : rosidatul_arifah (instagram)